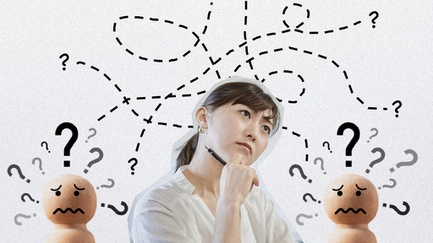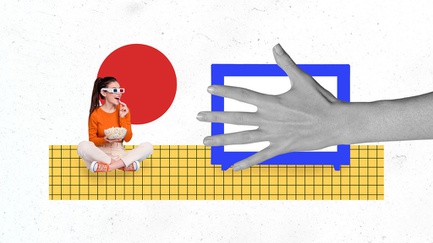tirto.id - Penafian: Artikel ini memuat kutipan pengalaman emosional dari narasumber yang mungkin terasa sensitif bagi sebagian pembaca. Redaksi menyarankan pembaca untuk berhati-hati sebelum membaca artikel ini.
“Pikiran jadi semrawut ketika dengar suara anak-anak menangis, hingga terlintas dorongan untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Atau, pas lihat bak mandi penuh, sempat tebersit pikiran untuk melukai diri sendiri agar merasa tenang.”
Kejenuhan dan kelelahan luar biasa pernah dialami oleh Silvi (32), seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang mengurus anak-anaknya seorang diri di rumah mertua pada puncak pandemi tahun 2021 lalu.
Suami Silvi bekerja dalam shift panjang. Mertua memiliki kondisi kesehatan kurang baik sehingga perlu ketenangan dan banyak istirahat.
Mengasuh dua anak balita yang mudah tantrum, sambil menjaga rumah tetap tenang agar adik-adik ipar bisa mengikuti perkuliahan daring, jadi tantangan berat sekaligus penuh tekanan bagi Silvi.
Bingung, kalut, dan pada waktu sama, kesepian akut.
“Memang sampai ada intensi untuk menyakiti diri sendiri dan anak-anak,” tutur Silvi terkait situasinya kala itu.
Pengalaman serupa yang menguras energi dan mental juga dijalani oleh Kania (40). Selama tiga tahun terakhir, Kania merawat ibunya yang mengalami penurunan kognitif drastis sehubungan dengan demensia.
Di tengah aktivitas bekerja penuh waktu dari rumah, sehari-hari Kania mendampingi ibu berjemur pagi, memandikan ibu dan membereskan segala keperluannya di kamar mandi, mempersiapkan dan menyuapkan makan, sampai menenangkan ibunya ketika mengalami momen-momen panik atau gelisah.
Di luar rutinitas tersebut, Kania mengurus administrasi dan mendampingi sang ibu untuk cek kesehatan, dari faskes pertama sampai ke rumah sakit besar.
Kania hapal segala jenis obat-obatan yang dikonsumsi sang ibu. Dia juga tidak pernah absen menjalin komunikasi intensif dengan dokter-dokter yang menangani ibunya.
Meski bergantian menjaga sang ibu dengan adik dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) harian, Kania tetap merasakan beban berat karena tuntutan kerja tinggi dan keterbatasan ruang gerak selama pandemi.
Kania mulai mengalami kelelahan yang termanifestasikan secara fisik, seperti rambut rontok dan berat badan yang naik-turun dalam kurun waktu singkat.
“Jam tidur berantakan, paling parahnya, sama sekali tidak bisa tidur,” tambahnya, “Suasana hati jadi kacau. Ada mood swing—tiba-tiba bisa nangis, terus bisa marah.”
Tantangan dalam Feminisasi Kerja Perawatan
Cerita Silvi dan Kania di atas mencerminkan potongan realitas tentang sisi lain dari kerja perawatan atau “care work”.
Kerap dipandang sebelah mata sebagai aktivitas “sekadar membantu” atau “cuma urus anak di rumah”, kerja-kerja perawatan dalam beberapa tahun belakangan semakin disorot oleh entitas internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO) sebagai pekerjaan bernilai ekonomi tinggi sehingga perlu didukung dengan investasi lebih banyak dan pekerjanya lebih dihargai serta dilindungi.
Melansir dokumen ILO Policy Brief, kerja perawatan mencakup berbagai aktivitas dan relasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional bagi orang dewasa maupun anak-anak, baik sudah berusia lanjut maupun masih muda, yang sakit maupun sehat (ILO 2018a).
Kerja perawatan bisa bersifat langsung (merawat anak, mengurus orang tua atau saudara yang sakit) maupun tidak langsung (belanja kebutuhan sehari-hari, memasak, mencuci dan menyiapkan pakaian, beberes rumah). Dalam pengalaman Silvi dan Kania, mereka melakukan keduanya.
Masih mengacu pada keseharian Silvi, Kania, atau Ibu Rumah Tangga (IRT) pada umumnya, kerja perawatan yang mereka lakukan tergolong tidak berbayar.
Di sisi lain, kerja perawatan dengan gaji atau upah berlaku pada Pekerja Rumah Tangga (PRT), perawat rumah sakit, guru PAUD atau pengasuh di layanan penitipan anak.
Di Indonesia, segelintir alasannya terganjal oleh regulasi dan keterbatasan fasilitas.
Sebagai contoh, setelah dua dekade berlalu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan.
Padahal, kepastian hukum terkait relasi pemberi kerja dan pekerja diperlukan agar kelak tak ada lagi PRT yang upahnya tidak dibayar atau mengalami pelecehan dan kekerasan.
Demikian juga fasilitas untuk menunjang pengasuhan anak. Keterjangkauan layanan daycare atau tempat penitipan anak (TPA) masih jadi tantangan serius yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia jasa.
Menurut surveiTirto dan Jakpat pada April 2025 terhadap orang tua pekerja di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta, hanya 2,91 persen dari 344 responden yang diketahui menitipkan anaknya ke daycare. Mayoritas menitipkan anak pada anggota keluarga lain atau PRT.
Ketika ditanya alasan menitipkan anak ke keluarga atau PRT, sebanyak 23,2 persen dari 181 responden menyebut akses daycare sulit, baik secara lokasi terlalu jauh atau biayanya terlalu mahal.
Ketika membicarakan kerja-kerja perawatan, kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan tentang ketimpangan gender.
Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT), misalnya, didominasi oleh perempuan. ILO memperkirakan sebanyak 83 persen pekerja domestik adalah perempuan, dan sekitar 41 persennya dipekerjakan di kawasan Asia.
Pada konteks kerja perawatan informal atau tidak berbayar, perempuan masih memikul porsi beban terbesar, seperti pengasuhan anak, perawatan orang-orang berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan jangka panjang, sampai segala urusan pekerjaan rumah.
Meski ada laki-laki yang menjalankan peran serupa, realitas sosial menunjukkan beban ini tetap lebih banyak ditanggung perempuan.
Feminisasi kerja perawatan ini juga tidak bisa dipisahkan dari kuatnya norma sosial-budaya dan warisan patriarki yang mengakar di berbagai komunitas masyarakat.
Seiring perempuan memikul porsi tanggung jawab lebih besar dalam kerja perawatan informal, kesempatannya untuk berpartisipasi di dunia kerja menjadi berkurang.
Berdasarkan estimasi ILO, sebanyak 708 juta perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja karena harus melakukan kerja-kerja perawatan tidak berbayar. Pada laki-laki jumlahnya sekitar 40 juta jiwa.
Di Indonesia, indikasi ketimpangan gender dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
TPAK berdasarkan jenis kelamin selama beberapa tahun belakangan timpang di kisaran 83-84 persen pada laki-laki dan 54-56 persen pada perempuan.
Profesi Ibu Rumah Tangga (IRT) adalah contoh paling jelas tentang kerja perawatan tidak berbayar sekaligus tidak dihitung dalam angkatan kerja.
Padahal, apabila kerja-kerja IRT divaluasi secara ekonomi, nilainya tidak main-main.
Tim peneliti dalam studi yang terbit di Jurnal Perempuan (2018) pernah mencoba menghitung nilai ekonomi kerja perawatan oleh IRT di Indonesia yang populasinya diestimasi hampir 48 juta jiwa.
Estimasi angka tersebut 10 persen lebih dari pendapatan negara dalam APBN 2017 yang sebesar Rp1.750,3 triliun.
Laporan ILO pada 2018 juga pernah memberikan gambaran serupa dalam skala lebih besar.
Berdasarkan data dari 64 negara yang mewakili dua pertiga populasi usia kerja di dunia, diketahui setidaknya 16,4 miliar jam digunakan untuk kerja-kerja perawatan tidak berbayar.
Jumlah waktu tersebut setara dengan 2 miliar orang yang bekerja selama delapan jam per hari tanpa upah.
Seandainya itu semua dinilai sesuai upah minimum per jam, hasilnya bisa mencapai 11 triliun dolar AS atau 9 persen dari Produk Domestik Bruto global.
Luar biasa besar, bukan?
Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025-2045 menjadi wujud keseriusan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem kerja perawatan dan perlindungan bagi semua pihak yang berkecimpung di dalamnya, terutama perempuan.
Pada tahun 2024, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan ILO sebagai sinergi kolaboratif lintas kementerian, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Terdapat tujuh isu strategis yang diprioritaskan, mencakup layanan pengasuhan anak, layanan bagi lansia, layanan perawatan berbasis inklusi seperti penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, perlindungan maternitas, keterlibatan laki-laki dalam perawatan keluarga, pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja perawatan, serta tersedianya jaminan sosial untuk ekonomi perawatan.
Pada bulan Juni lalu, Kemen PPPA telah melakukan tindak lanjut dengan meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan atau Care Economy Working Group.
Catatan: Depresi itu nyata dan bukanlah persoalan sepele, tetapi dapat diatasi. Jika kalian merasakan tendensi untuk menyakiti diri sendiri/ orang lain, mengakhiri hidup, atau melihat teman atau kerabat yang memperlihatkan tendensi tersebut, amat disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa.
* Artikel ini merupakan bagian pertama dari naskah berseri "Sisi Lain Kerja Perawatan" yang telah ditinjau oleh dr. Leonita Ariesti Putri, Sp.KJ, MSc.
Editor: Dhita Koesno
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id