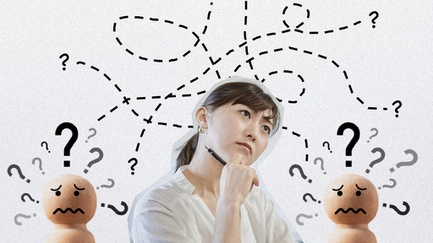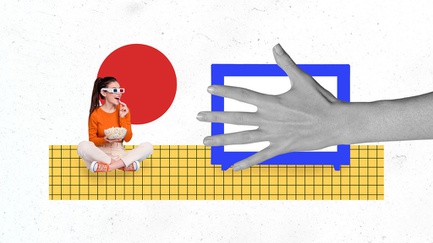tirto.id - Di balik persoalan kompleks yang berkelindan dalam jaring-jaring kerja perawatan, acap kali luput dari perhatian dalam diskursus ini adalah kesehatan mental pada para pelaku kerja perawatan atau caregiver, terutama di sektor informal atau yang tidak menerima upah.
Mengutip hasil survei oleh Tirto dan Jakpat pada April 2025, dari 153 orang tua yang merawat anak tanpa bantuan pihak lain, banyak yang merasa kekurangan waktu sendiri atau me-time (60,78 persen) dan mudah merasa lelah (49,02 persen).
Kelelahan fisik, mental, dan emosional setelah mengalami stres berlarut-larut, atau istilahnya burnout, merupakan kondisi yang lazim ditemui pada siapa pun, tak terkecuali perempuan—baik sebagai ibu, istri, menantu, atau anak.
Isu burnout pada ibu, misalnya, semakin disorot sejak COVID-19 karena pergeseran aktivitas belajar anak di sekolah ke tangan orang tua sepenuhnya di rumah.
Dalam studi di International Journal of Environmental Research and Public Health (2022) yang melibatkan 105 ibu dari anak balita di Korea Selatan selama pandemi, terungkap bahwa maternal burnout sangat dipengaruhi oleh stres pengasuhan anak.
Ibu dengan posisi ekonomi rentan, kurang mendapatkan dukungan dari pasangan, dan memiliki gejala-gejala depresif juga dilaporkan memiliki tingkat burnout lebih tinggi.
Yang menarik, istilah burnout sebenarnya berangkat dari konteks kerja formal di kantor.
“Burnout awalnya merujuk pada kelelahan fisik dan emosional yang terbatas pada pekerjaan, umumnya sektor formal. Jadi, apabila kita rehat, ambil jeda atau cuti dari pekerjaan, kondisi bisa membaik.”
Demikian disampaikan oleh dr. Leonita Ariesti Putri, Sp.KJ, MSc yang saat ini praktik di RS AZRA Bogor dan Klinik SOS Medika.
Dokter yang juga bermitra dengan Yayasan Merajut Hati ini menjelaskan, batasan antara pekerjaan merawat dan kehidupan pribadi caregiver, khususnya di ranah informal seperti mengurus anak dan keluarga, sangatlah kabur.
“Burnout pada caregiver cenderung lebih menantang dan lebih sulit dipulihkan hanya dengan istirahat atau cuti. Akibatnya, kelelahan ini semakin menumpuk, dan ketika sudah terakumulasi, gejalanya bisa lebih berat dan personal," lanjutnya.
Tidak hanya pengasuhan anak, caregiver yang merawat warga senior atau orang tua berusia lanjut juga dihadapkan pada kelelahan serupa.
Survei oleh Center for the Study of Sustainable Community UNIKA Atma Jaya dan komunitas Senja terhadap 98 orang caregiver pada 2024 lalu menunjukkan hampir 30 persen responden “mengalami gejolak emosi berlebih” saat mengurus orang tuanya karena khawatir, cemas, dan bingung.
Sebanyak 18 persen responden kesusahan membagi waktu untuk merawat orang tua dan urusan pribadi, sementara 16 persen responden mengalami kesulitan finansial sebagai generasi sandwich.
Schulz dan Sherwood di American Journal of Nursing (2008) mencoba meninjau studi-studi selama tiga dekade terakhir tentang dampak kerja perawatan informal atau tidak berbayar terhadap anggota keluarga atau kerabat yang menjadi caregiver.
Mereka menyimpulkan bahwa kerja perawatan bisa memberikan kepuasan, melatih keterampilan, dan mempererat hubungan keluarga. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi stresor kronis yang dapat mengganggu kesehatan caregiver.
Secara fisik, risikonya muncul karena kurangnya perhatian terhadap diri sendiri. Sementara secara mental, depresi menjadi dampak yang paling sering dialami.
Terkait ini, dr. Leonita menjelaskan bahwa kondisi stres kronis dapat memengaruhi kualitas tidur dan kondisi emosional.
“Lama-lama, tidak sekadar lelah fisik, tapi menjadi sindrom atau kumpulan gejala depresi, misalnya rasa sedih atau murung yang menetap, kehilangan minat dan rasa senang, mulai punya pikiran pesimis. Munculnya tidak tiba-tiba, tapi akumulasi dari bertumpuk-tumpuk kelelahan fisik dan emosional. Ini dapat mengganggu fungsi sehari-hari,” papar dr. Leonita.
Dalam temuannya, Schulz dan Sherwood juga menekankan bahwa perawatan terhadap pasien demensia, dibandingkan tipe-tipe kerja perawatan lainnya, cenderung menimbulkan dampak lebih menantang pada caregiver.
Inilah yang terjadi pada Kania (40) selama merawat ibunya yang demensia. Pada satu titik, Kania menyadari bahwa kondisinya tidak baik-baik saja.
Satu waktu, saat mendampingi ibunya cek kesehatan ke spesialis kedokteran jiwa, Kania menerima pencerahan dari dokter.
“Dalam kasus perawatan lansia dengan demensia, biasanya caregiver berisiko jadi pasien kedua. Jangan sampai kamu jadi pasien kedua,” ujar Kania mengulang ucapan dokter.
“Itu membuka mataku. Aku diam-diam bikin janji ke faskes untuk berobat ke psikiater. Kondisi ini aku tutupi agak lama karena aku malu kalau adikku tahu kondisiku terpuruk, padahal kami berbagi beban kerja. Aku juga berusaha menjustifikasi diri sendiri bahwa aku perlu bantuan dari profesional,” lanjut Kania.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh spesialis kedokteran jiwa, Kania diketahui memiliki episode depresif berat dengan gejala psikotik. Setelah rutin konsumsi obat selama sekitar 9 bulan, kondisi Kania berangsur-angsur membaik.
Upaya untuk mencari pertolongan juga dilakukan oleh Silvi (32), seorang Ibu Rumah Tangga (IRT).
Silvi pernah merasakan tekanan luar biasa selama mengasuh kedua anaknya seorang diri di rumah mertua sementara suaminya bekerja dalam shift panjang di luar.
Silvi ingat betul dirinya begitu kesepian, bingung, dan kalut.
“Memang sampai ada intensi untuk menyakiti diri sendiri dan anak-anak,” tutur Silvi tentang situasinya kala itu.
Setelah memboyong anak-anaknya ke kampung halaman orang tuanya, Silvi mulai sadar akan kebutuhan berkonsultasi dengan profesional.
Pada waktu itu, Silvi mulai bekerja paruh waktu di kantor dekat tempat tinggalnya. Sembari mencari-cari layanan PAUD yang cocok bagi anak-anaknya, Silvi dibantu oleh kerabat keluarga dalam mengasuh anak.
Perlahan, pikiran Silvi menjadi lebih jernih. Pada 2023, ia memberanikan diri untuk berkonsultasi ke psikolog, yang kemudian merujuknya ke psikiater.
Berkaca dari perjalanan panjang nan berliku yang ditempuh oleh Silvi dan Kania, terdapat sejumlah indikasi atau gejala yang penting diperhatikan untuk mengetahui kapan sebaiknya kita perlu berkonsultasi dengan profesional.
Menurut dr. Leonita, gejala yang muncul pada setiap orang tidak sama. Ada yang manifestasinya ke fisik, seperti lebih sering sakit kepala, jantung berdebar-debar, atau GERD lebih sering kambuh.
Selain itu, gejala juga bisa muncul dalam bentuk emosional, seperti mudah tersinggung, murung, merasa bersalah terus-menerus, cemas berlebih, atau munculnya pikiran untuk menyakiti orang lain, anak, atau diri sendiri.
“Prinsipnya, kita lihat, apakah gejala yang muncul ikut memengaruhi kemampuan diri untuk berfungsi sehari-hari—tidur, makan, merawat diri, bekerja, bersosialisasi. Kalau pengaruhnya signifikan, misalnya jadi sulit tidur berhari-hari, pekerjaan terbengkalai, sering meledak-ledak dengan orang-orang sekitar, itu ‘red flags’. Jadi sebaiknya tidak menunda mencari pertolongan profesional,” tegas dr. Leonita.
Catatan: Depresi itu nyata dan bukanlah persoalan sepele, tetapi dapat diatasi. Jika kalian merasakan tendensi untuk menyakiti diri sendiri/ orang lain atau mengakhiri hidup, atau melihat teman atau kerabat yang memperlihatkan tendensi tersebut, amat disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa.
* Artikel ini merupakan bagian kedua dari naskah berseri "Sisi Lain Kerja Perawatan" yang telah ditinjau oleh dr. Leonita Ariesti Putri, Sp.KJ, MSc.
Editor: Dhita Koesno
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id