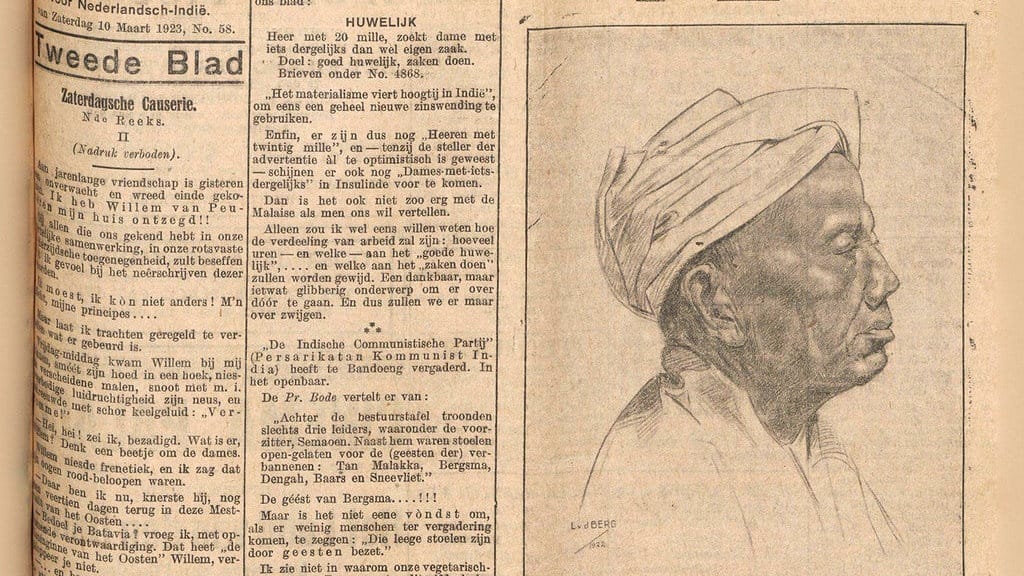tirto.id - Gelar dan penyebutan haji otomatis melekat pada orang-orang yang pernah melakukan rukun Islam kelima itu. Kadang gelar itu berdampak pada perubahan status sosial bagi yang memilikinya. Ada aura kesalehan yang melekat pada gelar itu. Karena itu tak sedikit yang merasa bangga dipanggil “haji”.
Jika Anda tak percaya, tengok saja deretan poster kampanye para caleg atau iklan dukun di surat kabar atau ustaz-ustaz yang sering nongol di televisi. Hampir selalu ada huruf “H” di depan nama mereka. Gelar haji adalah pengabsah: mereka dianggap sebagai muslim saleh bila sudah menyandangnya.
Dari mana sebenarnya penyebutan haji ini bermula?
Belanda Berubah-ubah Menyikapi Fenomena Haji
Ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) masih bercokol, pegawai-pegawai kongsi dagang itu tidak pernah melihat ibadah haji dari sudut pandang politik. Sikap mereka ditentukan hanya oleh urusan dagang. Perjalanan orang-orang Nusantara ke Mekkah membawa keuntungan ekonomi bagi VOC yang menyediakan kapal-kapal.
Haji mulai menjadi perhatian hanya jika terjadi gejolak karena faktor agama. F. de Haan menyinggung soal ini dalam Priangan: De Preanger-Regentschappen onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811 Jilid II (1912): “Pemerintah tampaknya baru mau memikirkan Islam bila ada alasan untuk mencemaskan pengacauan ketertiban melalui peristiwa-peristiwa keagamaan yang mencolok.”
Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dalam Ordonansi Haji tahun 1825, berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji.
Latar belakang Ordonansi ini menarik. Pada 1824, terjadi lonjakan pengajuan paspor haji ke kantor imigrasi. Sebanyak 200 lebih penduduk pribumi mendaftar. Pemerintah tentu saja bingung jika kelak harus memadamkan 200 potensi pemberontakan sekaligus.
Wasangka itu berdasarkan pandangan bahwa 200 orang itu kelak membawa pikiran-pikiran baru yang, jika diedarkan di kalangan rakyat, bisa memicu perlawanan.
Perang Jawa (1825-1830) dan pemberontakan-pemberontakan petani sepanjang paruh kedua abad 19 dipelopori oleh para pemuka agama dan haji. Ini membuat pemerintah bukan hanya menganggap haji sebagai urusan penting, melainkan penuh kewaspadaan.
Setidaknya, ada dua Gubernur Jenderal pada awal abad 19 yang mulai menyadari bahaya politik dari para haji: Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles.
Seperti diungkapkan Jacob Vredenbregt dalam Indonesia dan Haji (1997), pada 1810, Daendels mengeluarkan keputusan agar seorang haji (ia menyebutnya “pendeta Islam”) yang menghasut rakyat diberi paspor “untuk bepergian dari satu tempat di Jawa ke tempat lain guna menghindari gangguan” (hlm. 6).
Raffles, yang mewakili kolonialisme Inggris di tanah Jawa, serupa dengan Daendels: ia sangat tegas menyikapi fenomena para haji yang dianggapnya sering menghasut pembangkangan.
Dalam bukunya yang sangat terkenal, The History of Java, ia bilang, “Setiap orang Arab dari Mekkah, maupun setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji, di Jawa berlagak sebagai orang suci.”
Katanya lagi, “Karena mereka [para haji] begitu dihormati, maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar berontak dan mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi” (hlm. 3).
Alasan menarik lain diungkapkan seorang pejabat tinggi kolonial. Sebagaimana dikutip oleh Vredenbregt, pejabat tersebut mengungkapkan analisisnya: “Kebanyakan orang itu, ketika kembali dari perjalanan haji, tidak lagi tertarik untuk kembali bekerja, dan menghabiskan waktunya dengan bersembahyang atau ritual-ritual keagamaan lainnya, sehingga bisa membebani sesama penduduk” (hlm. 8).
Dengan begitu, akan terbentuk segolongan orang yang memiliki banyak waktu luang dan memanfaatkan pengaruh keagamaan mereka untuk melawan pemerintah.
Beberapa dekade kemudian, pada 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi baru menyangkut urusan haji. Meski lebih longgar dari aturan sebelumnya, di sana-sini masih ada berbagai pengetatan.
Yang paling menonjol dari ordonansi baru ini adalah pemberlakuan semacam “ujian haji” bagi mereka yang baru pulang dari Tanah suci. Mereka harus membuktikan benar-benar telah mengunjungi Mekkah. Jika seseorang sudah dianggap lulus ujian ini, ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji (jubah, serban putih, atau kopiah putih).
Dari sinilah sebenarnya dimulai penyematan gelar haji, juga atribut fisik yang melekat pada orang-orang yang sudah menunaikan rukun Islam kelima, kepada penduduk pribumi.
Mengapa gelar haji wajib disematkan?
Tujuan utamanya untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap para haji. Pemerintah kolonial tak mau repot-repot mengawasi satu per satu haji di daerah-daerah. Jika ada pemberontakan berdasarkan agama meletus, pemerintah tinggal mencomot haji-haji di daerah tersebut. Segampang itu.
Pengetatan dan kontrol haji memang terus berlangsung meski keterbukaan politik mulai diterapkan pemerintah kolonial pada awal abad 20.
Haji-haji di desa tetap diawasi dan pemimpin pergerakan yang bergelar haji (misalnya H.O.S Tjokroaminoto dan Haji Misbach) mendapatkan pengawasan ganda. Apalagi pemerintah mulai khawatir haji-haji ini mendapat pengaruh soal nasionalisme dan Pan-Islamisme ketika berada di Mekkah. Penyebaran Pan-Islamisme yang diusung Rasyid Rida dan kawan-kawan di Mesir memang sedang menemukan gaungnya di Hindia Belanda.
Tapi segalanya berubah ketika Snouck Hurgronje tiba. Kedatangannya menandai akhir sebuah era dan dimulainya zaman baru.

Pada 1899, ia ditunjuk mengepalai Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi), lembaga yang tugas utamanya memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada persoalan Islam politik di Hindia Belanda.
Nasihat Snouck tentang Islam politik meruntuhkan kebijakan pemerintah terdahulu. Jika sebelumnya pemerintah menganggap “Islam” sebagai satu wajah yang menaungi segalanya (baik politik, ritual, spiritual, dan kultural), Snouck menyarankan agar ada pemisahan.
Pemerintah kolonial, menurut nasihatnya, perlu memperhatikan tiga bidang terpisah dalam mengambil kebijakan soal Islam: yang murni agama, yang bersifat politik, dan hukum Islam (syariat). Karena ketiganya berbeda, bagi Snouck, perlu juga pemerintah kolonial menghadapinya dengan pendekatan berlainan.
Demikian pula dalam urusan haji. Bagi Snouck, jemaah haji hanya perlu dicamkan melalui sudut pandang statistik, bukan politik. Para jemaah haji yang “politis” bukan mereka yang sekadar pergi haji kemudian pulang, melainkan orang-orang yang menetap lama di sana. Dan sebagian besar jemaah haji Hindia Belanda bukanlah orang-orang yang menetap lama.
Karena itu, ia menganjurkan, kebijakan haji harus berdasarkan kebebasan penuh, tidak perlu mencemaskan bahaya politik yang ditimbulkan oleh jemaah haji.
Baca juga: Nasihat Abdul Ghaffar kepada Pemerintah Kolonial Belanda
Dua pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan Hasyim Asy’ari (Nahdlatul Ulama), bisa dijadikan contoh “haji politis” yang dimaksud Snouck.
Setelah bertahun-tahun tinggal di Mekkah untuk mendalami agama Islam dari para syekh terkemuka di sana, dua orang itu kembali ke Hindia Belanda dengan semangat sama soal anti-kolonialisme. Di Mekkah, mereka berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain dari pelbagai negara Islam yang bernasib sama dengan bangsanya: tertindas oleh penjajahan.
Pulang ke sini, mereka mendirikan organisasi-organisasi keagamaan yang mengusung semangat nasionalisme.
Baca juga: Cara Ahmad Dahlan Memuliakan Perempuan
Pemerintah kolonial menyetujui gagasan Snouck tentang haji dan mengimplementasikannya dalam bentuk Ordonansi Haji yang baru. Sejak itu, mereka membuka pintu seluas-luasnya bagi kaum pribumi yang hendak pergi ke Tanah Suci.
Pendapat lain soal kebebasan naik haji tak hanya datang dari Snouck Hurgronje, tapi juga dari para pejabat kolonial di Jeddah.
Tika Ramadhini, peneliti dan sejarawan di Zentrum Moderner Orient, Berlin, yang sedang melakukan riset tentang perempuan dan haji di zaman kolonial, punya hipotesis menarik.
“Pada awal abad ke-20,” ujarnya dalam wawancara dengan Tirto, “Konsul Hindia Belanda di Jeddah menyarankan agar prosedur haji diberi kemudahan. Berbeda dengan masa sebelumnya yang dipersulit. Dengan banyaknya jumlah haji, justru gelar haji akan makin biasa di mata masyarakat.”
Kekhawatiran pemerintah terhadap radikalisasi para haji justru bisa diatasi dengan logika terbalik itu. Haji-haji yang dulu dicurigai bisa menghasut rakyat untuk memberontak melawan pemerintah, salah satunya disebabkan oleh jumlah haji yang sedikit. Karena sedikit, mereka terasa istimewa di mata kebanyakan. Bila jumlah haji makin banyak, rakyat akan makin biasa saja menanggapi mereka.
“Jadi ini seperti reverse logic. Justru dengan banyaknya haji, bisa mengurangi radikalisasi agama,” lanjut Tika.
Penulis: Ivan Aulia Ahsan
Editor: Zen RS
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id