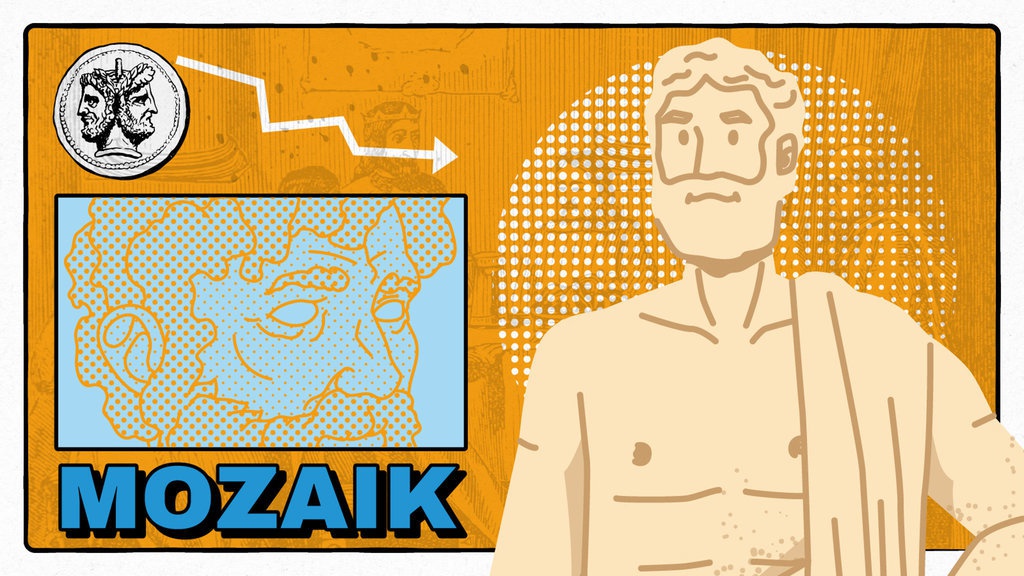tirto.id - Terlepas dari penyebabnya, entah karena kebijakan yang dibuat sendiri atau kondisi global, krisis ekonomi bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman kuno, berbagai peradaban besar telah menghadapi tantangan ekonomi yang menguji ketahanan sistem pemerintahan dan kebijakan mereka.
Pada 2008, pasar perumahan AS runtuh akibat spekulasi dalam pinjaman subprime, yang menyebabkan bangkrutnya bank-bank besar, termasuk Lehman Brothers. Ini bermula saat banyak orang membeli rumah dengan harapan harga akan terus naik.
Ketika suku bunga pinjaman subprime melonjak, banyak peminjam tidak mampu membayar cicilan mereka, yang kemudian menyebabkan gelombang gagal bayar (default). Krisis yang dikenal dengan “Subprime Mortgage Crisis” itu melibatkan utang yang meluas, spekulasi, dan kehilangan kepercayaan dalam sistem keuangan.
Kekaisaran Romawi juga mengalami hal serupa dua milenium sebelumnya, tepatnya pada tahun 33 Masehi. Meskipun situasi ekonomi saat itu sangat pelik, pemerintah Romawi berhasil mengatasi krisis dengan bijak.
Dua peristiwa sejarah tersebut memiliki kesamaan pola, integrasi pasar, dan efek domino dari kegagalan finansial. Namun, titik terang yang dipilih tidak mengorbankan rakyat kecil. Sementara itu, di sisi lain, krisis ekonomi modern sering kali direspons dengan kebijakan yang justru memberatkan masyarakat luas.
Latar Belakang Krisis Ekonomi Romawi Kuno
Kekaisaran Romawi mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh beberapa faktor yang berdampak pada stabilitas keuangan Romawi dan memengaruhi kehidupan sosial politik masyarakat pada masa itu. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan dalam sistem keuangan dan perbankan.
Para senator dan bangsawan Romawi banyak yang meminjam uang dari bankir untuk membiayai proyek-proyek besar, seperti pembangunan properti dan perluasan lahan pertanian. Ini terjadi di akhir pemerintahan Kaisar Augustus yang berkuasa sejak 27 SM hingga 14 M.
Kaisar menurunkan suku bunga dari 12 persen menjadi 4 persen di akhir pemerintahannya yang menyebabkan deflasi. Oleh karena itulah banyak pengusaha dan senator yang melakukan bisnis karena dianggap punya prospek yang menguntungkan.
Pembelian lahan secara besar-besaran masa itu seperti mengembalikan hukum yang pernah dicetuskan Julius Caesar pada tahun 49 SM. Di era Julius, kreditur harus menginvestasikan sepertiga kekayaan dalam bentuk tanah di Italia.
Seturut Cosmo Rodewald dalam Money in The Age of Tiberius (1976:3), hukum tersebut memang sempat dihidupkan para senator lewat dekrit yang nantinya dianulir oleh Tiberius dalam kebijakan memecahkan krisis ekonomi.
“[...]Senat sekarang menetapkan aturan yang mirip, jika tidak identik, dengan aturan yang, menurut Tacitus [sejarawan Romawi], telah dilanggar oleh semua senator,” tukas Rodewald.
Saat menjabat kaisar Romawi pada 14 M hingga 37 M, Tiberius melakukan efisiensi anggaran sehingga memangkas penggunaan kredit secara keseluruhan. Warsa 33 M, saat krisis mulai melanda, harga tanah kian menurun karena kreditur menahan uangnya. Perdagangan melambat, terutama karena niagawan kekurangan modal untuk membeli barang atau berinvestasi dalam usaha baru.
Agrikultur, yang merupakan tulang punggung ekonomi Romawi, juga terganggu karena banyak tanah dijual dan tidak dapat lagi dikelola dengan baik. Faktor eksternal, seperti bencana alam, wabah penyakit tanaman, dan eksploitasi tanah yang berlebihan, menyebabkan penurunan produktivitas pertanian.
Akibatnya, pasokan bahan pangan menurun, sementara harga bahan pokok melambung. Situasi ini makin memperburuk kondisi ekonomi, sebab terganggunya sektor pertanian secara otomatis berdampak pada sektor-sektor lain yang bergantung padanya.
Di sisi lain, debitur sering kali kesulitan melunasi utang. Mereka dipaksa untuk menjual aset, properti, atau tanah, dengan harga yang sangat rendah. Ketika harga properti turun drastis dan banyak debitur gagal melunasi pinjamannya, sistem perbankan Romawi pun terancam kolaps sehingga menciptakan lingkaran setan.
Secara bersamaan, beberapa perusahaan, bank, serta tokoh-tokoh penting di senat, mulai mengalami masalah finansial dan hukum. Salah satunya adalah Seuthes & Son dari Alexandria, perusahaan yang mengalami kesulitan karena kehilangan tiga kapal bermuatan barang di Laut Merah akibat badai. Nilai aset mereka menurun akibat harga komoditas yang terjun bebas, termasuk bulu burung unta dan gading.
Di Roma, Quintus Maximus dan Lucius Vibo, bankir utama Kekaisaran Romawi, menghadapi risiko besar setelah adanya kerugian yang dialami oleh Seuthes & Son serta Malchus and Co. Nama terakhir disebut adalah perusahaan dari Fenisia yang bangkrut akibat pemogokan para buruh.
Malchus and Co menjadi salah satu korban utama dalam run atau “serbuan” ke bank. Kehilangan kepercayaan masyarakat membuat pelanggan mereka menarik simpanan, yang membuat mereka akhirnya kolaps.
Begitu pula Publius Spencer, bangsawan kaya yang menjadi salah satu pemicu langsung krisis ekonomi. Saat itu, ia menarik pinjaman sebesar 30 juta sesterces (mata uang koin Romawi Kuno) dari bank. Lantaran tidak mampu memenuhi permintaan likuiditas besar tersebut, bank akhirnya bangkrut.
Beberapa bank di wilayah lainnya lantas turut runtuh, dampak dari krisis yang menyebar secara luas. Krisis itu pun menimbulkan efek domino di seluruh kekaisaran juga memengaruhi wilayah lain, seperti Mesir, Yunani, dan Prancis (Galia).
Selain itu, krisis ekonomi Romawi Kuno diperparah oleh kebijakan moneter pemerintahan sebelumnya yang kurang tepat. Terlebih, penguasa sebelumnya juga tidak membuat regulasi ketat sehingga rentan terhadap penyalahgunaan.
Peredaran uang logam yang tidak terkendali menyebabkan inflasi tinggi, sementara kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Romawi menurun. Situasi ini memicu kepanikan di kalangan investor dan masyarakat umum, yang kemudian berujung pada krisis likuiditas.

Kebijakan Romawi dalam Menghadapi Krisis
Menghadapi krisis di depan mata, Kaisar Tiberius mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan perekonomian. Ia mengeluarkan dekrit yang menginstruksikan pemerintah untuk menyuntikkan dana ke sistem perbankan.
Dana tersebut digunakan untuk membeli aset-aset bermasalah dan memberikan pinjaman darurat kepada bankir yang terancam bangkrut. Langkah ini berhasil mencegah kolapsnya sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Untuk meringankan beban debitur, pemerintah Romawi memberlakukan moratorium (penangguhan) pembayaran utang. Kebijakan ini memberikan waktu bagi para debitur untuk memulihkan kondisi keuangan mereka tanpa harus menghadapi tekanan dari kreditur.
Alokasi 100 juta sesterces dari kas kekaisaran disalurkan ke bank-bank tepercaya. Bank tersebut diharapkan dapat memberikan pinjaman bebas bunga kepada rakyat kecil, khususnya para petani, yang mengalami kesulitan keuangan selama tiga tahun.
Intervensi tersebut berhasil mengurangi tekanan dan mencegah kehancuran total sistem keuangan. Harga properti stabil, dan sebagian besar bank mampu melanjutkan operasinya.
Tiberius juga mengambil langkah untuk menstabilkan nilai mata uang dengan mengurangi peredaran uang logam dan meningkatkan kualitas produksi uang. Hal ini berhasil mengendalikan inflasi dan memulihkan kepercayaan terhadap mata uang Romawi.
Menurut sejarawan Charles Bartlett, tindakan Tiberius lebih efektif dibandingkan keputusan senat. Ia tetap fokus pada penyediaan likuiditas dan menghentikan penurunan pasar tanah.
“Ketika kita melihat Tiberius, di sisi lain, kita melihat bahwa begitu masalah itu dirujuk kepadanya. Dia pertama-tama menciptakan masa tenggang daripada melanjutkan penuntutan yang telah menyebabkan situasi [krisis]. Ini meringankan tekanan, meskipun hanya sementara,” ujar Bartlett dalam kolomnya di laman Weatherhead Harvard University.
Salah satu aspek yang paling menonjol dari kebijakan Romawi adalah komitmen untuk tidak mengorbankan rakyat. Alih-alih memotong anggaran sektor publik dan menaikkan pajak, pemerintah Romawi justru meningkatkan alokasi dana untuk program-program sosial, seperti distribusi bahan makanan dan pembangunan infrastruktur.
Krisis Ekonomi dalam Kebijakan Modern
Narasi krisis Romawi tahun 33 M telah berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi modern, dengan paralel yang ditarik selama berbagai krisis keuangan sejak Depresi Besar. Pandangan tersebut dikemukakan Colin Elliot dalam artikel jurnalnya, "The Financial Crisis of A.D. 33: Past and Present”.

Elliot mencoba mengeksplorasi bagaimana peristiwa sejarah digunakan untuk mengomentari kondisi ekonomi saat ini, sekaligus mengungkapkan hubungan kompleks antara masa lalu dan masa kini.
Ia menilai, persepsi terhadap krisis kuno dapat berubah secara dramatis berdasarkan realitas politik dan ekonomi para sarjana kontemporer.
Krisis ekonomi Romawi tahun 33 Masehi memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita saat ini. Pertama, intervensi pemerintah yang tepat waktu dan terarah dapat mencegah krisis lebih parah. Kedua, kebijakan yang berfokus pada perlindungan kepentingan rakyat, seperti moratorium utang dan peningkatan alokasi dana sosial, dapat membantu memulihkan kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Ketiga, stabilisasi mata uang dan pengendalian inflasi adalah langkah krusial dalam mengatasi krisis keuangan.
Respon Tiberius, yang memberikan likuiditas besar dengan bunga nol, adalah salah satu solusi awal yang mirip dengan kebijakan "Quantitative Easing" dalam ekonomi modern.
Ketika melihat kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah modern dalam menghadapi krisis ekonomi, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok. Di negara tertentu, krisis ekonomi sering direspons dengan menaikkan pajak, memotong anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, atau mengurangi subsidi untuk kebutuhan pokok.
Contoh kasus nyatanya bisa dilihat dalam krisis utang Yunani, yang dimulai pada 2009, ketika pemerintah setempat mengumumkan defisit anggarannya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan sebelumnya. Hal itu memicu kekhawatiran di pasar keuangan mengenai kemampuan Yunani untuk membayar utangnya, yang mencapai 170 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Untuk mengatasi krisis ini, Yunani menerima beberapa paket dana talangan (bailout) dari Uni Eropa dan IMF. Seperti biasanya, mereka tak lepas dari syarat. Yunani harus menerapkan langkah-langkah penghematan yang ketat, mulai dari kenaikan pajak hingga pengurangan besar-besaran pada belanja publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pensiun.
Kebijakan seperti ini, meskipun dianggap sebagai langkah penghematan, justru dapat memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan beban hidup masyarakat. Menaikkan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, memotong anggaran pendidikan dan kesehatan dapat berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Daripada memotong anggaran untuk sektor publik atau menaikkan pajak, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id