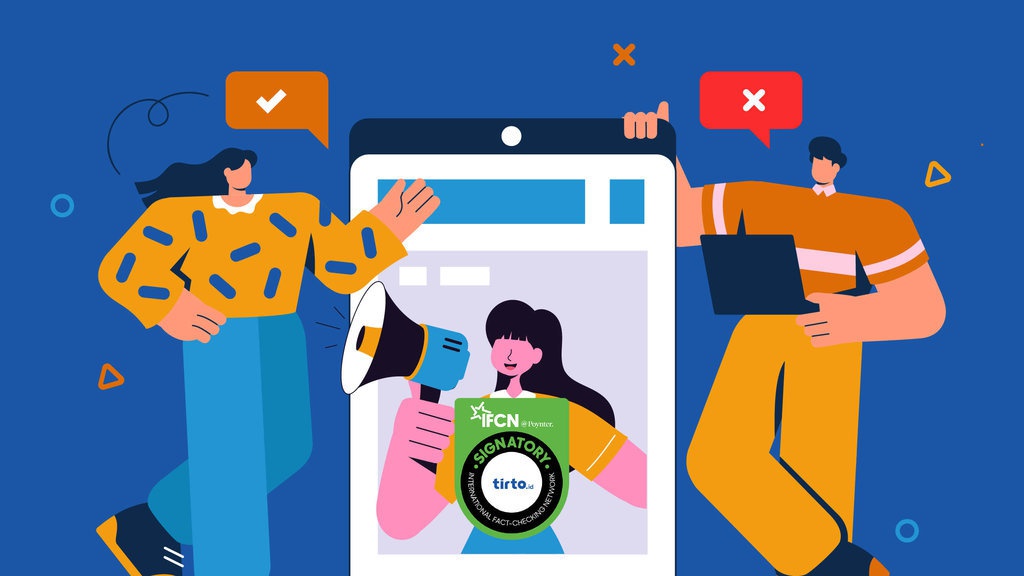tirto.id - Aksi demonstrasi merupakan hak konstitusi warga negara yang dilindungi dan kita tak bisa mengesampingkan narasi ruang maya sebagai bagian dari gerakannya. Sayang, narasi di ruang maya terkait unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 mendapat distraksi dari para “pendengung” (buzzer).
Tak cuman untuk memperkuat narasi, pendengung-pendengung itu juga mengacaukan ruang publik digital. Jika melihat rangkaian aksi pekan terakhir Agustus yang bermula pada Senin (25/8/2025) lalu, ditemukan adanya pola percakapan buzzer di ruang maya yang berubah sesuai kebutuhan momentum.
Dari awalnya didominasi narasi, "bubarkan DPR" (25 Agustus 2025), pada aksi massa setelahnya, narasi bergeser pada seruan mengadili “Geng Solo”–merujuk ke mantan Presiden RI, Joko Widodo, beserta kroni-kroninya (29 Agustus 2025). Kemudian berubah signifikan menjadi upaya menggulingkan pemerintah, perseteruan TNI vs Polri, ajakan penjarahan, hingga penyerangan ras tertentu (30 - 31 Agustus 2025).
Selain buzzer, percobaan menggaet influencer/pemengaruh juga tampak dilakukan. Hal itu tercermin dari pengakuan para pemengaruh yang menolak tawaran mengunggah konten berisi pesan “ajakan perdamaian dari pemerintah, DPR, ojek online, dan masyarakat”.
Nama-nama seperti Jerome Polin, Rahmat Hidayat, Mella Carli, dan Vincent Liyanto yang terdokumentasi sempat menyebarkan informasi penawaran kerja sama dari pihak ketiga.
Dalam situasi normal, narasi perdamaian semacam itu harusnya bisa dibilang elok. Namun, tawaran itu bermunculan pascarentetan unjuk rasa Agustus yang diwarnai aksi nirempati pemerintah, penuh represifitas aparat, dan nihil sensitivitas pejabat.
Dengan begitu, narasi perdamaian dalam konteks ini hanya akan mengaburkan protes dan tak menyelesaikan masalah rakyat, apalagi menjawab tuntutannya. Suara-suara organik tentang demonstrasi, aksi protes, atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, akan sangat mungkin tenggelam oleh seruan berdamai.
Tapi itulah gunanya pasukan siber terkoordinasi.
Dalam buku berjudul Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia’s Cybersphere, Sastramidjaja dan Wijayanto (2022) menemukan adanya kemiripan antara cara pengorganisasian pasukan siber Indonesia dengan "arsitektur disinformasi berjejaring" di Filipina.
Berkaca dari Filipina, operasi ini menggunakan tingkatan tertentu–berturut-turut dari puncak hierarki–mulai dari arsitek utama alias pakar periklanan, turun ke kelompok public relation, kemudian ke influencer digital atau key opinion leader-operator akun palsu. Di Indonesia ada lapisan tambahan antara tingkat pertama dan kedua yang terdiri dari "koordinator" yang dipekerjakan oleh para ahli strategi elite.

Para koordinator itu bertugas merekrut dan mengawasi tim kreator konten dan buzzer mereka sendiri. Koordinator ini juga sekaligus bertindak sebagai salah satu buzzer terkemuka dalam tim mereka, mengoperasikan apa yang disebut "akun umum" yang unggahannya nantinya akan diamplifikasi oleh buzzer-buzzer yang lebih rendah.
Dengan kata lain, para koordinator juga berperan sebagai influencer digital anonim. Selanjutnya mereka dapat bertindak sebagai perantara antara influencer selebritas dan para ahli strategi elite serta klien politik mereka.
“Tujuan pasukan siber ini adalah memanipulasi opini publik agar selaras dengan kepentingan klien politik. Mereka melakukannya dengan menciptakan narasi tertentu—yang dirancang untuk menarik perhatian publik daring dan membangkitkan respons emosional—lalu menyebarkan narasi tersebut di media sosial seluas dan secepat mungkin,” begitu penjelasan laporan tersebut.

Seberapa Efektif Pakai Influencer untuk Orkestrasi Narasi?
Secara praktik, influencer yang terkenal dengan banyak pengikut memang bisa membantu mengontrol sentimen. Tata (bukan nama sebenarnya), seorang KOL (Key Opinion Leader) Specialist dari sebuah agensi digital menjelaskan, menekankan pentingnya peran influencer dalam menggiring narasi.
Meski mengaku belum pernah menangani klien dengan afiliasi politik, dia mengaku pernah mendapat tawarannya. Dia menjelaskan di tengah banyaknya sentimen negatif terhadap DPR, jika influencer menggaungkan narasi bernada positif, maka pengikutnya bisa ikut menyuarakan narasi itu.
Alhasil, sentimen yang terbentuk akan positif dan secara keseluruhan bisa jadi akan meredam suara-suara warganet yang negatif terhadap DPR. Belum lagi, pendekatan ke mega influencer juga umumnya efektif menciptakan “awareness”. Istialah mega influencer merujuk ke pemengaruh dengan pengikut lebih dari 1 juta, Jerome Polin yang punya 9 juta pengikut masuk kelompok ini.
“Secara awareness itu memang paling efektif, kalau misalnya kita mau bekerjasama sama mega influencer. Kenapa? Karena dari audiens dia sendiri, itu aja sudah gede. Jadi, kemungkinan dari 10 persen followers-nya dia aja, itu udah banyak banget kan. Nah, algoritma di media sosial itu, semakin banyak followers yang lo punya, itu possibility untuk kontennya dilihat sama orang, sama pengikut, itu lebih gede,” kata Tata saat dihubungi Tirto, Senin (1/9/2025).
Dari sudut pandangnya, ada urgensi yang sangat besar. Dengan honor yang ditawarkan ke Jerome senilai Rp150 juta, artinya pemodal alias orkestrator narasi mengucurkan uang lebih besar kepada agensi. “Karena mereka akan cari keuntungan dong dari harga KOL tersebut. Sementara yang dikasih ke Jerome aja segitu. Berarti cost yang dikeluarin untuk konten Jerome lebih dari itu,” lanjut Tata.
Lebih jauh dia mengatakan, ketimbang klien produk atau brand, kisaran harga yang ditawarkan oleh klien politik memang kerap kali lebih besar. Klien politik juga seringkali menyampaikan pesan yang tersirat, sehingga sekilas mungkin sulit untuk mengetahui aktor pemodal di baliknya.
Lira–bukan nama sebenarnya, sebagai KOL Specialist di agensi digital lainnya mengungkap hal serupa. Ia menyampaikan, besarnya tawaran cuan dari klien politik juga beriringan dengan tingginya risiko yang menyertai. Itu mengapa agensinya belum pernah mau mengambil klien politik.
“Nah,kalau aku hitungannya kerja buat brand, biasanya kami tanyain dulu nih rate mereka [influencer] berapa buat kita, bisa utak-atik di satu project kita bisa pake siapa saja. Apalagi kalau politik itu bisa banget KOL naikin lagi harganya,” ungkap Lira lewat pesan teks, Selasa (2/9/2025).
Secara umum, dalam kampanye media sosial ada dua pendekatan; endorsement atau paid promote. Endorsement biasanya cukup memberi brief dengan adanya objektif, pesan kunci, dan mandatory untuk dimasukkan influencer ke konten mereka sesuai gaya masing-masing. Sementara kerja sama paid promote, modelnya seperti yang ditawarkan kepada para influencer belakangan, kontennya bersifat siap unggah atau RTP/Ready to Post.
“Sedangkan kalau paid promote, itu kontennya RTP. Kami bener-bener udah kasih aja tuh kontennya apa dan caption apa, jadi KOL bisa tinggal posting ajaa. Cuman kalau gini diterapin ke KOL yang orang gitu kan kadang bisa jadi ga masuk native-nya yaa,” kata Lira.
Influencer memang kini punya modal kepercayaan besar dari publik luas. Survei Tirto bersama Jakpat pada Juli lalu menemukan kalau mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap informasi yang disampaikan oleh pemengaruh. Sebanyak 59,61 persen dari 1.238 responden menyatakan percaya, sementara 6,87 persen lainnya menyatakan sangat percaya.
Siapa di Balik Operasi Menggerakan Influencer dan Buzzer?
Dosen dan pakar politik dan digital demokrasi dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Wijayanto juga mencurigai adanya indikasi operasi pengaruh selama aksi Agustus lalu. Tapi menurut dia pertanyaan yang lebih penting, "operasi pengaruh melawan siapa dan oleh siapa?"
Menurut Wijayanto, ada sekira dua pihak operasi pemengaruh yang bermain. Di satu sisi, ada operasi pengaruh yang melemahkan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, di sisi lain, ada pula operasi yang menyasar institusi pemerintah tertentu.
Seperti pada kasus pemilu dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wijayanto mengatakan kalau pola pasukan siber dalam konteks unjuk rasa Agustus ini juga sama. Dengan kata lain, ada pasukan siber yang membela dan menyerang satu pihak dan ada juga pasukan siber yang menyerang pihak lain.
“Jadi ini persebarannya merefleksikan friksi di antara elite oligarki. Hanya saja yang mau saya katakan adalah, kita perlu memisahkan antara amanat dari warga negara yang kecewa. Ini kan luapan kekecewaan yang sudah terpendam sekian lama, pada situasi sosial, ekonomi, dan politik, dengan kepentingan elite ini," terang pria yang juga Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip itu.
Artinya, friksi di antara pasukan siber yang bertebaran saat itu juga menggambarkan pergeseran di antara elite oligarki. Begitu pula persatuan di antara pasukan siber kala itu juga seturut dengan persatuan antara elite oligarki.
Apalagi menurut temuannya, operasi penggerakan buzzer juga sebenarnya tidak hanya ada seiring masa pemilu. Operasi pendengung terus berjalan dan biasanya menggema ketika ada kebijakan kotroversial. "Kita menemukan bahwa buzzer ini bergerak tidak hanya masa pemilu, tapi untuk pada masa-masa ada kebijakan yang bermasalah seperti Revisi Undang-Undang KPK, New Normal, Omnibus Law, IKN. Nah ternyata dalam temuan kita, buzzer ini juga bekerja pada masa ketika rezim mau melemahkan oposisi," tambahnya.
Lebih lanjut Wijayanto, mengatakan indikator keberhasilan buzzer bisa dilihat dari bagaimana bisa membuat percakapan menjadi trending topic, memengaruhi pemberitaan media massa, dan membuat percakapan luring di antara publik tentang hal tersebut.
“Nah, ini keberhasilannya lebih parah lagi, karena dia berhasil–to some extent ya–menciptakan kekacauan gitu, bahkan kerusakan, konflik, dan segala macam. Karena saya percaya bahwa mahasiswa atau demonstran yang turun ke jalan tidak punya kemampuan merusak yang sedahsyat itu, untuk membakar [fasilitas umum dan gedung] ya,” kata Wijayanto.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id