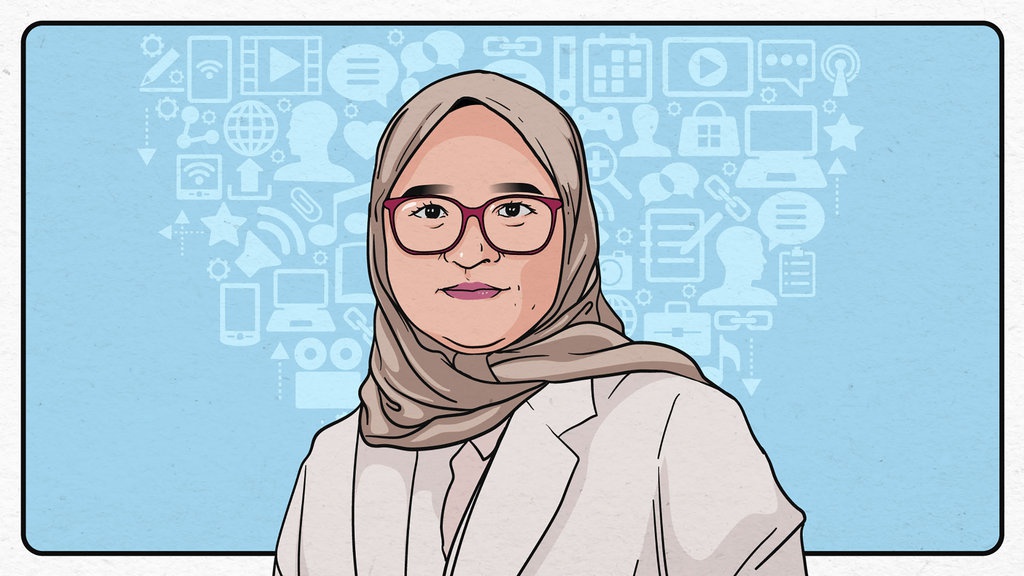tirto.id - Pasukan siber termasuk buzzer bisa “diterjunkan” dalam setiap narasi yang melibatkan masyarakat luas, termasuk aksi demonstrasi. Para pendengung itu umumnya bertugas untuk memecah belah atensi hingga memecah belah warga. Oleh karenanya masyarakat perlu punya pengetahuan untuk mengidentifikasi konten-konten yang bersumber dari buzzer.
Menurut Sastramidjaja dan Wijayanto (2022) dalam buku berjudul Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia’s Cybersphere, cara pengorganisasian pasukan siber Indonesia mirip dengan "arsitektur disinformasi berjejaring" di Filipina.
Namun pola kerja pasukan siber di Indonesia punya karakteristik tersendiri yang unik. Ada juga sejumlah perbedaan dan perkembangan pola kerja pendengung dalam beberapa waktu terakhir.
Konten-konten dari para pemengaruh dan pendengung kerap kali membuat kebingungan di masyarakat. Untuk memperdalam persoalan pasukan siber ini, Tirto melakukan wawancara khusus dengan Ika K. Idris, Associate Professor Program Manajemen dan Kebijakan Publik, Monash University Indonesia. Ika juga merupakan Co-Founder Monash Data & Democracy Research Hub.
Sejumlah hal diperbincangkan dalam wawancara ini, mulai dari cara mengidentifikasi buzzer, konotasi penggunaan buzzer di era ini, efektivitas buzzer, hingga aktor yang umumnya membiayai buzzer.
Berikut hasil wawancara lengkap Tirto bersama Ika Idris:
Bagaimana cara mengidentifikasi konten atau narasi dari pasukan siber yang terkoordinasi? Apa aja sih ciri-cirinya misal dilihat dari akunnya, baik itu buzzer maupun influencer?
Kalau dulu kan paling yang menjadi ciri-ciri itu –ini kalau dari sudut pandang mata awam ya, bukan sebagai peneliti– misalnya foto profil akunnya nggak jelas, terus followers-nya sedikit, terus posting-nya itu-itu aja. Tapi menurut saya, indikator itu nggak bisa lagi kita gunakan sekarang.
Karena sejak adanya nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang baru, itu kan ada Direktorat Jenderal Pemantauan Ruang Digital. Nah, itu semakin ketat ya pengawasan, sedangkan orang juga semakin ada kebutuhan untuk mengekspresikan kritik-kritik mereka terhadap pemerintah. Jadinya bagaimana sih cara mengekspresikan diri, maka orang tuh sekarang jadi punya second account.
Terus second account buat kritik-kritik pemerintah, atau sekarang malah banyak orang bikin akun-akun komunitas. Ada yang akhirnya jadi homeless account, ada yang tetap jadi akun komunitas, itu akhirnya kan bermunculan. Engagement-nya tinggi dan mereka ketika memainkan narasinya lebih leluasa dari media massa.
Jadi kalau kita pakai patokan yang kayak dulu, misalnya gak jelas fotonya, terus memang idenya sedikit, following sedikit, atau posting-nya itu-itu aja, sebenarnya itu kayak gak bisa lagi digunakan. Karena bisa jadi itu memang second account orang atau akun-akun komunitas.
Tapi yang masih menjadi ciri dari akun-akun buzzer ini sebenarnya adalah dia memainkan emosi yang sangat berlebihan. Buzzer ini kan memang ada yang mengalihkan perhatian, tapi yang paling utama sebenarnya adalah dia mau memecah belah diskusi, memecah belah atensi, memecah belah masyarakat, dan memecah belah warga.
Sehingga buzzer akan menggunakan kata-kata yang sangat kuat, sehingga akan terlihat ajakan, misalnya untuk mendukung ini atau kontra ke sini. Itu sih yang menurut aku sekarang perlu kita waspadai ya, kalau narasinya terlalu strong, emosional, terus menggunakan kata kunci yang membangkitkan kebencian-kebencian terhadap kelompok yang lain.
Jadi yang kita perlu hati-hati sih, itu yang paling menurutku sekarang menjadi indikator. Apakah memang narasi yang dia bangun atau pemilihan katanya itu sangat kuat untuk menyentuh emosi kita? Itu sih.
Apakah mengerahkan pasukan siber dalam membentuk percakapan di media sosial itu selalu punya konotasi negatif? Dalam konteks sosial politik, apakah mungkin ada operasi yang positif?
Kalau mau dibilang ada yang positif menurut saya ada juga ya. Jadi kemarin saya lagi ada riset yang memang harus wawancara beberapa Non-Governmental Organization (NGO). Terus mereka merasa karena ada buzzer ini, mereka kewalahan ketika menciptakan awareness. Nah, akhirnya mereka menciptakan juga, tapi ini secara organik ya. Kan buzzer intinya akun-akun yang mengamplifikasi. Nah, mereka juga melihat adanya kebutuhan bahwa kita juga harus punya suporter di media sosial.
Bahwa kita juga harus merawat akun-akun organik kita ini, yaudah akhirnya memang mereka punya juga influencer-influencer atau kadang campaigner-campaigner-nya gitu ya, atau kadang pimpinan-pimpinan organisasinya kan berperan juga sebagai influencer. Dan mereka kan akhirnya menjaga agar orang-orang itu tetap engage, tetap mengamplifikasi. Menurut saya ada juga positifnya lah kalau untuk membangun kesadaran masyarakat.
Mungkin barangkali definisi taman-teman di sini kan, Buzzer itu terokestrasi. Kalau yang di gerakan masyarakat itu kan mereka dirawat, tapi insentifnya tuh nggak terorkestrasi, dalam artian keuntungan finansial ya. Jadi kalau kita melihat ada nggak sih upaya agar amplifikasi ini positif, sebenarnya ada aja.
Tapi kalau yang memang buzzer udah dibayar, terus untuk mengamplifikasi, menurut saya itu kebanyakan udah pasti negatif.

Di era tsunami informasi sekarang dan semakin sulitnya membedakan akun-akun organik atau buzzer, apakah operasi buzzer masih efektif atau justru sebaliknya?
Kalau kita lihat semakin ke sini, orang Indonesia itu kan sebenarnya semakin melek dengan adanya buzzer. Tapi kalau kita lihat apakah masih efektif, menurut saya itu masih.
Kan buzzer ada yang mengalihkan perhatian, ada yang menyebarkan disinformasi, ada yang memecah belah masyarakat. Nah, menurut saya dalam konteks menarik perhatian atau mengalihkan fokus itu masih efektif.
Cuman memang untuk disinformasi sama memecah belah itu yang masyarakat kita sekarang akhirnya langsung cepat-cepat bikin counter. Jadi kan proses buzzer awalnya dia memecah perhatian dulu, mengalihkan perhatian, terus menyebarkan disinformasi, dan memecah belah masyarakat. Mungkin hanya segmen-segmen masyarakat tertentu aja yang kemakan sampai di level disinformasi dan memecah belah.
Kenapa? Ini ada riset terbaru dari BBC Media Action. Di situ dia bilang bahwa sebenarnya masyarakat kita yang berada dalam kategori digital vulnerability, termasuk adanya pengaruh konspirasi teori atau buzzer, itu ada 68 persen. Nah, jadi ini kan sebenarnya masih besar ya vulnerability-nya.
Mereka yang vulnerable itu misalnya dia berasal dari masyarakat dengan low education level, percaya konspirasi teori, literasi medianya rendah, dan mereka akan sangat cepat untuk memutuskan berbagi konten.
Lagian kalau misalnya kita lihat lagi, masih di survei itu, yang paling banyak dilihat adalah TikTok, Youtube, Facebook, terus yang paling dipercaya itu adalah sesama warga. Jadi semakin kecilnya kepercayaan terhadap jurnalis atau terhadap media, membuat orang tuh akhirnya lebih percaya informasi alternatif atau informasi dari warga.
Terus platformnya adalah platform berbasis video, yang mana itu kan unsur-unsur manipulasinya besar, mulai dari manipulasi audio dan video. Manipulasi yang kayak, "katanya, ini sudah terjadi," katanya siapa gitu kan? Padahal gak ada. Jadi menurut saya, apakah buzzer efektif sih masih efektif dan makanya buzzer tetap ada terus.
Cuman kita lihat lagi efektifnya tuh di level apa, kepada masyarakat yang mana, dan barangkali juga pada policy atau kebijakan yang seperti apa, atau peristiwa yang seperti apa?
Kalau kita melihat buzzer di momen aksi demonstrasi seperti ini, apakah berarti pasukan siber juga kerap dimanfaatkan untuk mendelegitimasi gerakan? Karena mungkin beberapa orang familiarnya buzzer tuh waktu pemilihan umum (pemilu) gitu, tapi ternyata di momen-momen kayak gini juga muncul, apa yang sebenarnya dimanfaatkan? Momen apa yang perlu diwaspadai dengan keberadaan buzzer?
Jadi gini, buzzer ini kan konsekuensi dari model bisnis platform sebenarnya, di mana model bisnis platform yang sangat mengharuskan kita untuk menaikkan traffic dan engagement. Sehingga pasukan-pasukan sosial media yang tugasnya mengamplifikasi bukan lagi berhenti di situ, buzzer ini sebenarnya udah menjadi industri, namanya influence industry kan sekarang. Bagaimana memengaruhi atensi publik, pilihan, keputusan publik melalui pasukan-pasukan buzzer.
Dan mereka tuh, menurut saya bukan cuma di pemilu malah. Mereka ada di semua momen. Momen promosi film, malah katanya kemarin saya ngobrol dengan temen yang mau bikin film katanya, ya minimal Rp1 miliar buat biaya promosi termasuk di media sosial, termasuk buzzer-buzzer-nya. Terus ada juga misalnya di brand atau produk.
Sekarang kan banyak juga buzzer-buzzer di dalam struktur pemerintah gitu kan, ada yang namanya misalnya employee advocacy. Dulu pemerintah bikin tenaga humas pemerintah yang kerjaannya juga untuk mengamplifikasi isu, terus ada sinergi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu sinergi media sosial ASN kan yang koordinir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), dulu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ini zaman presiden Jokowi periode kedua.
Belum lagi Kominfo punya banyak media-media komunitas, media-media blogger dan segala macam yang mereka rawat. Jadi menurutku penggunaan pasukan media sosial untuk mempengaruhi publik itu bukan cuma di pemilu, tapi memang orang lebih concern ke pemilu karena kan di situ ada misalnya, ini momen demokrasi.
Tapi di semua keseharian kita karena kita udah mengkonsumsi informasi di internet gitu ya, mulai dari beli barang, mulai dari milih jasa, mulai dari layanan pemerintah semuanya itu udah ada, ada agensi-agensi yang misalnya menyediakan jasa, review,jadi itu menurutku emang udah bagian dari keseharian kita sih, influence operation ini.
Berarti pada akhirnya kita gak bisa bilang buzzer itu selalu identik dengan elite kekuasaan ya? Karena kan semua lini sekarang pakai operasi serupa ini.
Ya, kalau konteks politik sih menurut riset-riset tuh pasti memang karena ada yang bertikai elite politiknya di atas, ya dipesanlah buzzer-buzzer itu. Sebenernya itu cara untuk melegitimasi upaya-upaya merebut kekuasaan lah. Dari riset-riset sebelumnya, misalnya partai apa bertikai, terus ada buzzer-nya. Itu kan sebenarnya yang berantem mereka, tapi seolah-olah ada penggiringan opini publik bahwa ini gak bener. Itu kan memberikan tekanan juga ya kepada lawan politiknya. Itu sih tetap ada sih menurutku yang kayak gitu-gitu.
Kalau saya ngomong dengan buzzer, dalam konteks riset, buzzer tuh kadang-kadang kan juga punya kliennya banyak. Jadi kadang-kadang misalnya mereka tuh satu agensi gitu, nanti di meja sana yang pro siapa, meja sini kontra siapa.
Jadi kan mereka juga udah memperlakukan ini sebagai bisnis. Kan mereka entrepreneur kan, bukan loyalis partai. Kalo loyalis partai kan keliatan tuh jelas, misalnya kalo udah membela ini yaudah membela ini gitu. Tapi kalo entrepreneur kan yang penting bayarannya aja.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id