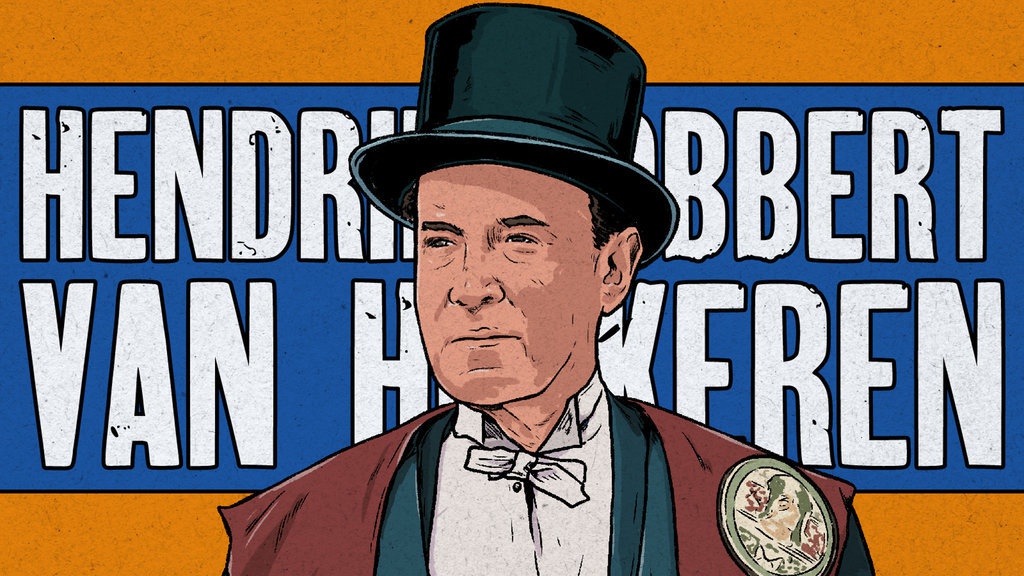tirto.id - Bob, begitu kiranya kawan sejawat Hendrik Robert van Heekeren memanggilnya. Dia lahir pada 20 September 1902, tetapi menurut Raden Pandji Soejono, koleganya di The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar (NIAS), Bob lahir tanggal 23 Juni di tahun yang sama.
Lebih dari setengah abad lalu, tepatnya 10 September 1974, Bob mengembuskan napas terakhirnya di Heemstede, Belanda, setelah melawan penyakit selama empat bulan. Sakit mendera sejak kepulangannya dari Groningen, mengakibatkan proyek penulisan NIAS untuk edisi kedua buku The Bronze-Iron Age of Indonesia (edisi pertama 1958) yang Bob kerjakan bersama Soejono mangkrak.
Kabar duka itu datang tiba-tiba. Beberapa hari sebelumnya, Bob tampak pulih dan menantikan kunjungannya ke Indonesia, yang selalu dia anggap sebagai tanah air keduanya. Sayangnya, dia telah berpulang ke haribaan Tuhan.
Boleh jadi betul, Bob memang orang Indonesia. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, dari keturunan Belanda yang bermigrasi ke Hindia Belanda. Ayahnya dan kakeknya pernah bekerja sebagai buruh di sini, dan tekad itu diteruskan oleh Bob.
Tetapi Bob telah diboyong ke Belanda sejak usia belia. Pendidikan dasar dan menengahnya dia selesaikan di sana.
Suratan takdir, Bob kembali ke Jawa, bekerja di perkebunan tembakau. Lewat hamparan kebun tembakau Jember, Bob akhirnya kepincut monumen dan artefak purba, lalu merajut persahabatan dengan tetua desa yang dianggapnya sebagai "guru" sejati.
Pertemuannya dengan sang "guru" dan pengetahuan mendalam soal ritus sejarah lokal membikin Bob mendiversifikasi karakternya. Soejono menulis, "Ia juga seorang naturalis dan pendaki gunung yang sangat antusias, kombinasi yang baik untuk seorang arkeolog."
Sejak tulisan perdananya "Megalitische overblijfselen ind Besoeki" di majalah Djawa tahun 1931, Bob menelurkan enam puluh sembilan makalah, dua pertiganya fokus pada ragam temuan prasejarah Indonesia.
Semangat eksplorasinya menjangkau gua-gua megalitikum di Besuki dan lekuk-karang di Sulawesi Selatan. Lewat Leang Bola Batu, Leang Pattae, dan tiga penampungan: Ara, Karasa, dan Sarippa, Bob menyingkap uraian budaya Toala—dari alat kasar epipalaeolithic hingga ragam rupa kapak batu terperinci.
Di Flores, penggalian sistematis membuka tabir Liang Rundung dan Liang Soki, mempertemukan kerangka manusia dengan serpih pisau neolitikum. Setiap lapisan tanah baginya adalah bait lantang dalam puisi sejarah yang terus ditulis.
Arkeolog di Railroad of Death
Film Hollywood tahun 1957 berjudul The Bridge on the River Kwai mampu mengonstruksi situasi di kamp tawanan perang Jepang selama Perang Dunia II. Film ini berisi cerita sampingan yang menarik tentang seorang tahanan arkeolog Hindia Belanda. Dialah Hendrik Robert van Heekeren, yang berhasil menjadi "pemeran sentral" saat kisahnya menjadi tawanan didokumentasikan.
Film itu—diadaptasi dari novel karya David Lean (1952) dengan judul sama—mengisahkan pembangunan Railroad of Death, rel kereta api yang menghubungkan Siam-Burma. Rel itu dibangun pada 1942-1943 oleh setidaknya 60.000 pasukan Sekutu yang ditawan Jepang, menewaskan 16.000 jiwa di antaranya dalam keadaan tersiksa. Juga hampir 300.000 romusa yang dikirim dari Thailand, Malaysia, Burma, dan Indonesia, dengan jumlah korban tewas 100.000 jiwa.
Para tawanan perang dan buruh sipil dipaksa untuk memasang jalur dan membangun beberapa jembatan—termasuk bentang besar di atas Sungai Kwae Yai (Sungai Kwai; disebut Sungai Mae Klong pada saat itu) di utara Kanchanaburi, Thailand. Tujuannya, mendukung Jepang dalam kampanye Perang Dunia II dan infrastruktur yang penting untuk kegiatan militer.
Di antara ratusan ribu tawanan itu, Bob salah satunya. Tetapi dia tidak seperti kebanyakan tawanan perang pada umumnya. Bob "sengaja" menyerahkan diri demi mendapat akses penelitian arkeologi. Dia mendedikasikan penawanannya—di sela luang istirahat yang singkat—untuk menganalisis lapisan tanah dari penggalian rel kereta api.
Catatan-catatan penelitiannya dihimpun hari demi hari, bersama dengan koleksi kecil artefak yang dia kumpulkan di kamp.
Namun pada suatu waktu, Jepang memergoki kedok Bob. Tentara menyita koleksi dan catatannya, menghukumnya, tetapi itu pun tak cukup menghentikan ambisi arkeologi Bob.
Dalam publikasinya "Prehistoric Discoveries in Siam, 1943-44" (1948) di Cambridge, Bob sempat menulis pengalamannya, "hanya pada beberapa kesempatan kami diizinkan untuk berenang menyeberangi [Sungai Mekong] dan melakukan penyelidikan yang tergesa-gesa, meskipun tidak membuahkan hasil, di seberang pantai."
Setelah bergumul sekira setahun di Railroad of Death, Bob dipindahkan ke kamp tawanan perang di Jepang. Bukannya lebih baik, tetapi lebih mengenaskan. Jika menimbang apa yang ditulis Gavan Daws dalam Prisoner of the Japanese, Bob terlampau akrab dengan wabah penyakit, kekurangan gizi, dan bahkan pelecehan seksual yang menjamur.
Namun titik balik arkeologisnya juga diperolehnya di sini. Koleksi catatan dan artefak yang disita Jepang di Thailand, entah bagaimana "dikembalikan" oleh seorang teman ketika Bob baru tiba di Jepang. Tak ada catatan mendetail tentang alasan di balik pengembalian koleksinya.
Dari sana, Bob menjadi lebih berhati-hati terhadap koleksinya. Dia memilih pendekatan institusional guna mengamankan koleksinya, setidaknya sampai Perang Dunia II berakhir. Sebagian dari koleksinya, khususnya artefak batu, disimpan di Peabody Museum of Archaeology and Ethnology milik Harvard University.
Satu catatan kecil, Bob bukan satu-satunya pemerhati arkeologi yang menjadi tawanan perang, dan terus menjaga kewarasan dengan senantiasa menghimpun dan menyusun catatan sejarah selama di kamp. The Ilustrated London News menulis, tak lama usai Perang Dunia II berakhir, beberapa tawanan menyimpan koleksi ornitologi dan mengumpulkan kupu-kupu yang diawetkan.
Salah lainnya Charles Thrale, yang bersedia menggadai jatah ransum hanya demi sebuah kertas. Dia mengumpulkan akar pohon (didaur ulang menjadi cat), dan menjumputi rambutnya sendiri yang rontok, kemudian dirangkai menjadi kuas lukis untuk menggambar ilustrasi di kamp.
Hal yang paling mengejutkan tentang Bob adalah setelah perang perang dia sengaja kembali ke Railrod of Death di Kanchanaburi. Tujuannya, meneliti lebih mendetail arkeologi yang sempat mandek saat ia menjadi tawanan.
Ekskavasinya yang terbaru di Thailand diterbitkan pada 1967, dengan penemuan situs-situs baru dan penting di wilayah tersebut. Bob juga merevitalisasi serta "menyelamatkan" situs pemakaman manusia mesolitikum pertama, atau setidaknya jika bukan, telah ada sejak 10.000 tahun yang lalu.
Bob menghimpun eksistensi kerang kecil dan kerang besar—dibaca: kjokkenmoddinger—di dekat permakaman dan menginspirasi beberapa penelitian arkeologi modern tentang ritus penguburan dan subsistem manusia di masa lalu.
Penelitian Bob berhasil sedikitnya merangkai tesis di daratan Asia Tenggara, soal dominasi moluska di masa lalu sebagai bahan pokok makanan, ornamen, permakaman, dan banyak lainnya.
Sumbangan Bob untuk Indonesia
Sepulangnya ke Indonesia, 1946–1956, Bob berpindah dari amatir menjadi profesional terkemuka di Dinas Arkeologi Indonesia. Bersama Basuki, dia menelusuri situs-situs penting di Jawa—Sangiran, Trinil, Ngandong, Jetis—dan Bali dengan sarkofagusnya. Di sisi lain, Bob turut aktif mendidik mahasiswa Indonesia, termasuk R. P. Soejono, anak didik yang disulap menjadi kolega dalam proyek NIAS. Bob memastikan warisan metode sistematis tak pupus oleh keterbatasan usia dan anggaran.
Dalam rentang satu dekade itu, Hendrik Robert van Heekeren menorehkan temuan monumental: lukisan batu pertama di Leang Bola Batu dan Leang Pattae; penggalian gua-gua Flores berisi industri pisau serpih dan kerangka manusia; jejak neolitik Kalumpang; serpihan paleolitikum di Cabbenge yang berdekatan dengan fosil megafauna; serta sistem pemakaman guci di Bali dan Anyer.
Sebagai Kurator Prasejarah Museum Pusat Jakarta, Bob juga merangkai katalog koleksi dan menulis Kehidupan Prasejarah di Indonesia (1955).
Seolah merajut benang zaman, Bob menerbitkan dua buku pilar: Zaman Batu di Indonesia (1957; Edisi ke-2, 1972) dan Zaman Perunggu-Besi Indonesia (1958). Kedua karya itu tak hanya menyintesis data luas dari berbagai spesialis, tapi juga menempatkan prasejarah Nusantara dalam konteks perkembangan Asia Tenggara, sebuah prestasi tak tergantikan di masanya.
Penghargaan bergulir: gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Leiden (1965), Copenhagen (1967), dan Universitas Indonesia (1970). Bob kedapatan beberapa kali kembali ke Tanah Air—1968, 1970, hingga 1972–1973—memimpin program gabungan Paleolitikum Indonesia-Belanda dan membekali generasi muda dengan semangat penemuan, persahabatan, dan kerja sama yang selalu ia puja.
Kertas terakhirnya terhenti setelah makalah tentang kronologi zaman prasejarah yang disampaikannya di Groningen, 16 Mei 1974. Dalam hening kehilangan, terpatri janji bahwa setiap butir tanah dan serpihan batu yang pernah disentuhnya akan terus bercerita, menyalakan kembali kobaran matahari di ufuk sejarah Nusantara.
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id