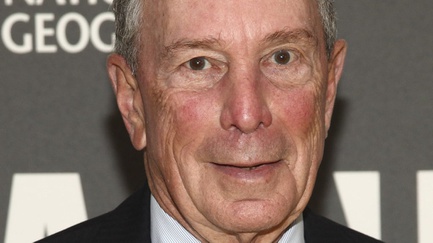tirto.id - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertama dengan target ambisius mencapai swasembada pangan dalam masa pemerintahannya. Berbagai program dicanangkan, anggaran triliunan rupiah digelontorkan, dan klaim keberhasilan mulai disuarakan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari Astacita poin kedua yang berfokus pada penguatan pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Dalam struktur RPJMN, ketahanan pangan menempati posisi strategis pada Prioritas Kedua pembangunan nasional.
Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah telah menyusun sejumlah program konkret yang tercakup dalam "Delapan Program Hasil Terbaik Cepat" dan "17 Program Prioritas".
Program-program ini antara lain mencakup pembangunan lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional, menjamin tercapainya swasembada pangan, serta memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian yang memadai.
Dukungan anggaran yang signifikan telah dialokasikan untuk merealisasikan berbagai program tersebut. Pada tahun 2025, dialokasikan dana sebesar Rp 155,2 triliun, yang kemudian direncanakan meningkat menjadi Rp 164,4 triliun pada tahun 2026.
Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan mendasar, termasuk subsidi pupuk, bantuan alat produksi pertanian, intensifikasi lahan, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan program strategis seperti gerakan menanam padi serentak dengan memanfaatkan teknologi, pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, dan pembangunan bendungan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan empat kawasan prioritas untuk swasembada pangan melalui Inpres Nomor 14 Tahun 2025. Kawasan tersebut mencakup Papua Selatan dengan fokus di Merauke yang menargetkan pencetakan 1 juta hektar sawah baru, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang dikembangkan sebagai lumbung pangan nasional, serta Sumatera Selatan yang mengoptimalkan potensi 1 juta hektar lahan rawa, khususnya di wilayah Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
Hasil awal dari berbagai kebijakan dan program ini sudah mulai terlihat. Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan luas panen dan produksi beras serta jagung pada Juli 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, di balik optimisme pemerintah, sejumlah pakar dan data justru mengindikasikan bahwa target swasembada pangan masih jauh dari jangkauan, bahkan menghadapi ancaman serius bom waktu di sektor beras.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dengan optimis menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam tiga bulan ke depan, tepatnya pada Desember 2025.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia di Padang, Sumatera Barat, September 2025. "Jika tidak ada hambatan, awal tahun depan kita akan mencapai swasembada pangan," tegas Sulaiman seperti dikutip Antara.
Pemerintah saat ini menggenjot perluasan food estate di Merauke (Papua Selatan), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan untuk dijadikan sebagai salah satu hub produksi pangan terbesar dunia melalui transformasi dari pertanian tradisional ke modern. Food estate ini juga akan mendukung industri pengolahan hasil pertanian.
Bahkan, dari akhir tahun lalu pemerintah sudah menargetkan penghentian impor empat komoditas pertanian utama mulai 2025, yaitu beras konsumsi, gula konsumsi, jagung pakan ternak, dan garam konsumsi.
Di balik target-target ambisius tersebut, para pakar justru mempertanyakan fondasi dari klaim swasembada pangan ini. Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Khudori, menyoroti ketiadaan definisi resmi dari pemerintah mengenai makna swasembada pangan yang ingin dicapai.
"Setahu saya, sampai sekarang Pak Prabowo dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih belum pernah menjelaskan misalnya yang beliau maksud dengan swasembada pangan itu apa," ujar Khudori saat wawancara dengan Tirto, Selasa (14/10/2025).
Ketidakjelasan definisi ini, menurut Khudori, membuat penilaian terhadap capaian pemerintah menjadi sulit. Apakah yang dimaksud swasembada pangan berbasis komoditas seperti era Presiden Joko Widodo, ataukah mengacu definisi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang menyatakan swasembada tercapai ketika 90 persen kebutuhan domestik dapat dipenuhi dari produksi sendiri.
“Dua definisi ini implikasinya beda. Jadi akan sulit kita menggunakan ukuran yang sampai sekarang tidak pernah dijelaskan," tegasnya.
Persoalan definisi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan fundamental dalam menilai keberhasilan kebijakan pangan. Khudori mencontohkan, untuk komoditas beras, produksi tahun ini diperkirakan mencapai 34 juta ton, sementara konsumsi sekitar 30,9 juta ton.
"Ada surplus lumayan, 3 juta lebih. Kalau pengertiannya 100 persen kebutuhan domestik bisa dipenuhi dari produksi sendiri, ya untuk konteks beras umum itu iya (kita swasembada)," ujarnya. Meskipun, faktanya impor beras khusus oleh swasta tetap berjalan sekitar 300-450 ribu ton.
Adapun, ketahanan pangan Indonesia juga perlu dilihat dalam konteks global. Data Global Food Security Index (GFSI) 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 63 dengan skor 60,2, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (69,9), Thailand (60,1), dan Vietnam (67,9).
Capaian ini masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan skor 73,2 pada 2025 dan 82,0 pada 2029.
Yang lebih memprihatinkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih mencapai 8,27 persen. Kesenjangan indeks ketahanan pangan juga sangat lebar: sementara Denpasar, Bekasi, Surabaya, dan Solok mencatat indeks di atas 90, daerah-daerah di Papua masih di bawah 20.
Kritik lebih tajam datang dari Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa. Menurutnya, mencapai swasembada pangan secara menyeluruh adalah hal yang mustahil untuk Indonesia.
“Kalau guyonannya kiamat kurang satu hari ya tidak akan tercapai. Gitu saja lah. Untuk kasus Indonesia,” katanya kepada Tirto.
Ia menjelaskan, swasembada pangan sejati mensyaratkan seluruh kebutuhan pangan mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, dengan rasio swasembada sama atau lebih besar dari satu.
Kenyataannya justru berkebalikan dengan target pemerintah. Menurutnya, impor 12 komoditas pangan utama Indonesia pada 2024 mencapai 34 juta ton, angka yang setara dengan produksi beras nasional dan mustahil untuk digantikan produksi domestik dalam sekejap.
Andreas memperinci ketergantungan impor yang sangat tinggi pada komoditas strategis seperti gandum 82 persen impor, kedelai 94 persen impor, dan bawang putih 100 persen impor.
"Bagaimana caranya kita tiba-tiba membalikkan telapak tangan 34 juta ton, kemudian kita hentikan impornya semuanya dan kita penuhi dalam negeri? Jawabannya satu, tidak mungkin," ucap Andreas.
Ia menambahkan bahwa wacana swasembada pangan sebaiknya dilupakan dan pemerintah fokus pada swasembada per komoditas, seperti beras. Hal ini menurutnya lebih masuk akal untuk digarap.
Ambisius tapi Tak Fokus
Pemerintah memang kerap menjadikan swasembada beras sebagai bukti kesuksesan. Produksi beras tahun 2025 diproyeksikan meningkat, didukung oleh kondisi iklim yang menguntungkan.
Namun, Andreas mengingatkan bahwa swasembada beras bukanlah hal istimewa yang pertama kali dicapai. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Indonesia tercatat tidak mengimpor beras untuk konsumsi umum selama empat tahun berturut-turut (2019-2022). Klaim keberhasilan swasembada beras saat ini karena itu bukanlah suatu hal yang istimewa.
Masalah yang lebih krusial justru terletak pada tata kelola pascapanen. Kebijakan pemerintah yang memerintahkan Bulog menyerap gabah secara besar-besaran, seringkali tanpa memperhatikan kualitas, menciptakan masalah multidimensi.
Andreas menganalisis bahwa dengan surplus beras sekitar 3 juta ton, penyerapan Bulog yang mencapai 2,8 juta ton telah menyedot sebagian besar stok yang seharusnya beredar di pasar.
"Surplus yang di tangan pedagang dan masyarakat turun drastis," ujarnya.
Ini menjelaskan mengapa harga beras terus naik sejak Februari hingga Agustus 2025, padahal seharusnya produksi yang meningkat mendorong harga turun. Kebijakan ini, meski menciptakan stok Bulog terbesar sepanjang sejarah, justru mengorbankan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Hal senada juga disampaikan oleh Khudori. Menurutnya, kebijakan penyerapan gabah kering panen di tingkat petani tanpa syarat kualitas dan tanpa diferensiasi harga menimbulkan moral hazard.
"Semua kualitas dibeli dengan harga yang sama Rp6.500. Itu sebetulnya untuk petani pasti menguntungkan dan menolong petani, tapi kan itu tidak mendidik," paparnya.
Kebijakan ini terbukti membuka ruang perilaku tidak baik. Data Bulog per September menunjukkan bahwa 65-66 persen gabah kering panen yang diserap tidak lolos kualitas standar dengan kadar air maksimal 25 persen, dan kadar hampa maksimal 10 persen.
“Di bulan-bulan Maret, April, banyak gabah aneh-aneh, gabah berkecambah, gabah sudah hitam, gabah airnya sangat tinggi. Bulog harus terima, tidak bisa menolak," ungkapnya.
Dampaknya, kualitas beras yang dihasilkan menjadi rendah dan biaya produksi membengkak. Data Bulog menunjukkan harga pokok pengadaan beras mencapai Rp14.400 per kilogram untuk beras medium, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah hanya Rp13.500.
"Artinya ada selisih hampir Rp900. Kalau dibandingkan HET sebelumnya Rp12.500, selisihnya Rp2.000 lebih. Ini membuat swasta pasti berteriak," jelas Khudori.
Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini menciptakan apa yang disebut Khudori sebagai "bom waktu" di gudang Bulog. Stok beras Bulog di akhir tahun diperkirakan mencapai 2,5 juta ton.
"Kalau tidak segera diselesaikan (disalurkan), itu potensial menjadi bom waktu yang tinggal menunggu momentumnya saja meledak," katanya.
Beban Penugasan
Bom waktu ini akan berimplikasi pada beban subsidi yang sangat besar bagi negara, mengingat beras kualitas rendah mustahil dikonsumsi manusia dan harus diolah untuk penggunaan lain dengan harga jual merosot.
Menurut Khudori, konsep ideal kebijakan pangan seharusnya sederhana: proteksi di hulu untuk produsen (petani) dan proteksi di hilir untuk konsumen. Bulog seharusnya berfungsi sebagai pembeli terakhir, bukan pembeli pertama.
Secara teori, harusnya Bulog hanya masuk ke pasar ketika surplus terjadi, yang mana kelebihan beras ini tidak terserap pasar dan harga jatuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Bulog masuk sebagai pembeli awal dengan target penyerapan 3 juta ton beras yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Pelaku pasar tidak kebagian, kebagian kecil, yang itu mestinya menjadi stok di masyarakat, di pedagang, di penggilingan, di rantai pasok," ujarnya.
Kegagalan proteksi juga terjadi di sisi konsumen. Khudori menyoroti lambatnya respons pemerintah dalam melakukan intervensi ketika harga beras sudah tinggi sejak April 2025.
“Sejak akhir April, sebetulnya harga beras itu sudah kelihatan tinggi. April, Mei, Juni, tidak dilakukan intervensi. Baru pertengahan Juli dilakukan intervensi. Kenapa? Salah satunya karena anggaranya tidak ada," ujarnya.
Anggaran Rp16,6 triliun yang seharusnya dialokasikan untuk operasi pasar dan bantuan pangan beras, dialihkan ke penyerapan gabah di hulu tanpa ada penggantinya.
"Ketika harga sudah sangat tinggi, mestinya harus dilakukan intervensi, tapi ternyata tidak dilakukan. Badan Pangan Nasional sebetulnya bisa menugaskan kepada Bulog untuk melakukan intervensi meskipun anggaranya belum ada, tapi pasti dia akan disemprit oleh auditor BPK," jelas Khudori.
Persoalan lain juga perlu diperhatikan. Menyimpan beras dalam jumlah besar dan waktu yang lama membawa konsekuensi logistik dan finansial yang berat bagi Bulog. Menurut Andreas, kapasitas gudang Bulog yang memadai hanya sekitar 3-3,5 juta ton, sementara stok pernah mencapai 4,3 juta ton.
Kelebihan stok terpaksa disimpan di gudang filial dan penggilingan yang standarnya berbeda-beda, tidak semuanya bagus. Apalagi, beras yang disimpan lebih dari enam bulan sudah mengalami penurunan mutu dari sisi rasa, dan jika sudah turun mutu fisik—menjadi kekuningan atau berbau apek—akan sulit diselamatkan.
Persoalan penurunan mutu ini bukan hanya isapan jempol. Pemerintah mengakui adanya 29 ribu ton beras Bulog yang turun mutu, namun Andreas memperkirakan angka sebenarnya minimal 100 ribu ton. Bahkan, Ombudsman menyebut angka 300 ribu ton. Kerugian negara untuk 100 ribu ton beras rusak ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, dan bisa membengkak hingga Rp 7 triliun.
Beras yang turun mutu ini kemudian masuk kategori disposal, tidak layak konsumsi manusia, dan harus dialihkan untuk pakan ternak atau industri etanol dengan harga jual yang merosot drastis.
“Ombudsman memperkirakan bahkan sampai Rp7 triliun kerugian negara. Dan itu siapa yang nanggung? Ya Bulog!” tegas Andreas.
Bom waktu tidak hanya terjadi di sektor beras. Di sektor gula, PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) sebagai holding BUMN pangan melaporkan kesulitan menjual stok gula kristal putih (GKP) karena harga gula di pasar lebih rendah.
Gudang-gudang pabrik gula penuh dengan stok yang tidak laku hingga 400.000 ton, meskipun gula relatif lebih tahan lama dibanding beras. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem distribusi dan ketidakmampuan menyesuaikan dengan mekanisme pasar.
Menurut Andreas, akar masalahnya terletak pada intervensi yang mengganggu independensi BUMN seperti Bulog atau ID Food. Lembaga yang mengelola cadangan pangan pemerintah seharusnya bebas dari intervensi dan menjalankan prinsip first in first out dengan ketat.
"Ketika Bulog tiba-tiba diperintah harus menyerap sebesar-besarnya, apalagi yang serapan dalam negeri itu adalah at any quality, ya sudah bisa dibayangkan (hasilnya)," ujarnya.
Akibatnya, komoditas seperti beras dan gula konsumsi menumpuk sangat besar di gudang, melampaui kapasitas, dan akhirnya mengalami penurunan mutu.
Lebih jauh, Khudori mengatakan, semua komoditas pangan yang bersumber dari tanaman memiliki masanya. Pasalnya, komoditas ini diproduksi secara musiman. Ketika musim panen, stok disimpan di gudang dan ketika musim tanam, stok yang tersimpan dikeluarkan.
Problemnya, adalah bagaimana mendistribusikan stok yang tersimpan ketika barang yang beredar di lapangan masih cukup banyak, meskipun tidak sedang musim panen. Hal ini menurutnya yang harus dibenahi oleh pemerintah agar proses produksi hingga distribusi bahan pangan berjalan lancar dan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Karena sebagian besar komoditas pangan itu adalah barang yang tidak tahan lama, pemerintah harus memastikan penyalurannya, outletnya, sehingga tidak teronggok saja di gudang. Bagaimanapun, gula, beras, jagung tidak bisa disimpan lama-lama,” ucapnya.
Khudori pun menambahkan, jika BUMM dipaksa menyerap hasil komoditas ini, namun tidak disediakan outletnya, hanya akan membuang-buang angggaran dan membebani BUMN yang ditugaskan tersebut.
“Kalau BUMN disuruh serap tapi tidak disiapkan outletnya itu pengeluarannya untuk apa? Sementara proses di gudang itu ada biaya juga,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id