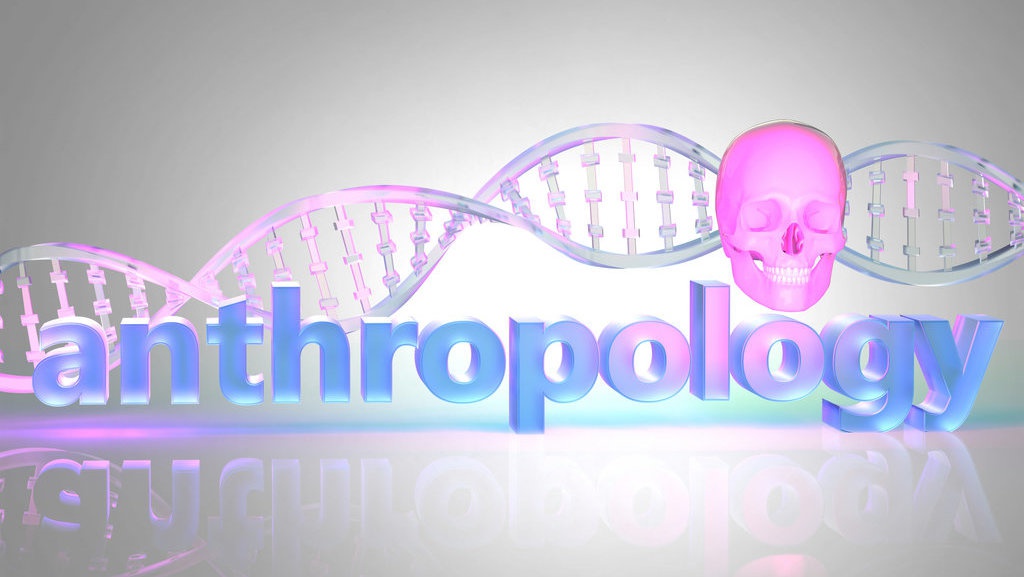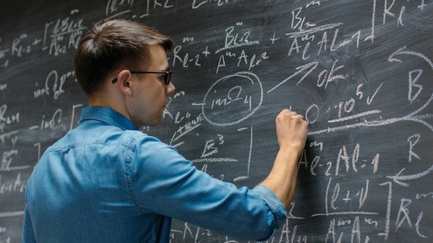tirto.id - Fase-fase perkembangan antropologi diawali sejak akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Menurut bapak antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, fase perkembangan antropologi dibagi dalam lima fase.
Fase pertama berawal dari akhir abad ke-15, awal abad ke-16, hingga sebelum abad ke-18. Kemudian, fase perkembangan ilmu antropologi kedua terjadi sekitar pertengahan abad ke 19.
Dilanjutkan dengan fase ketiga sekitar awal abad ke-20 dan fase keempat sesudah tahun 1930an. Selain itu, terdapat pula fase sejarah antropologi kelima mulai tahun 1970-an.
5 Fase Perkembangan Antropologi dan Penjelasannya
Menurut modul Pengertian dan Sejarah Perkembangan Antropologi Sosial, empat fase-fase perkembangan antropologi dirancang berdasarkan temuan Koentjaraningrat. Sementara fase terakhir dikemukakan sesuai temuan ahli antropologi lain.
Jika dilihat dari perkembangannya, sejarah antropologi dibagi menjadi lima fase berikut.
1. Fase Sebelum Tahun 1800
Fase perkembangan antropologi pertama dimulai sebelum tahun 1800, tepatnya ketika terjadi penjajahan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15. Kemudian, dilanjutkan dengan pencarian rempah-rempah oleh bangsa Eropa pada abad ke-16.Rempah-rempah tersebut dijadikan sebagai bahan baku industri di benua Afrika, Asia, Osenia, dan Amerika. Dalam perjalanan itu, bangsa Eropa kerap ditemani musafir, sekretaris, penerjemah, dan pendeta.
Mereka juga secara cermat memerhatikan setiap kejadian yang ada di sekitar wilayah persinggahan. Khususnya perihal tradisi, adat-istiadat, dan kebudayaan lokal setempat.
Persinggahan tersebut menjadi sangat menarik lantaran tradisi-tradisi di wilayah singgah sangat berbeda. Hal itu berlainan dengan tradisi maupun kehidupan bangsa Eropa.
Akhirnya, benda-benda yang mereka temui dalam tradisi-tradisi tersebut diboyong ke negeri Eropa. Sebut misalnya kebudayaan di Afrika yang mewajibkan setiap gadis dewasa untuk melebarkan bibirnya.
Kemudian, menjulur bibir ke dagunya hingga 5 sampai 10 cm. Setelah dijulurkan, maka pemimpin tradisi tersebut akan memasukkan sebuah benda berupa tanah kering yang menyerupai piringan kecil.
Tradisi ini dipercaya berguna agar bibir gadis yang sudah dewasa bisa lebih besar, kemudian menjulur ke dagu dalam beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, para gadis dewasa akan terlihat lebih cantik.
Sementara itu, di Benua Asia dan Oseania terdapat suku bangsa yang menganggap bahwa wanita cantik dan anggun itu mesti memanjangkan kedua telinga. Tepatnya hingga lebih dari 10 cm, dilakukan dengan cara melobangi dan memberikan beban di telinga.
Sehubungan dengan itu, temuan tradisi dari para penjajah kemudian dikumpulkan dalam satu buku laporan. Lalu, dipresentasikan di hadapan para kaum cendekiawan Eropa.
Perjalanan dan penemuan tersebut menyimpulkan beberapa hal. Sebagai kesimpulan pertama, cendekiawan Eropa menganggap bahwa bangsa di luar Eropa bukanlah seorang manusia.
Mereka menganggap bangsa di luar Eropa itu sejenis manusia liar, barbar, keturunan iblis, dan sebagainya. Sementara temuan kedua bertolak belakang dengan temuan pertama.
Menurut para cendekiawan Eropa, masyarakat di luar wilayah bangsanya masih menunjukkan sifat manusia. Hal ini disebutkan lantaran cara pikir mereka yang berbeda dengan cara pikir milik masyarakat Eropa.
Adapun pendapat ketiga beranggapan bahwa benda-benda temuan selama di persinggahan adalah benda-benda yang menarik. Oleh karena itu, tidak jarang benda-benda tersebut dijadikan sebagai koleksi di beberapa museum terkenal Eropa.
2. Fase Pertengahan Abad ke-19
Upaya koleksi yang sudah terorganisir pada museum terkenal di Eropa mulai menunjukkan hasil. Para kaum cendekiawan Eropa mempelajari, kemudian memahami catatan-catatan etnografi tersebut dengan cara berpikir evolusi masyarakat.Cara berpikir evolusi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mengalami tahap perkembangan dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Dalam waktu yang cukup lama, masyarakat akan mencapai tahap pada tingkat yang lebih kompleks.
Para cendekiawan tersebut menyimpulkan bahwa cara berpikir paling rendah dimiliki oleh masyarakat Benua Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika. Sementara masyarakat dengan tingkat perkembangan yang tinggi adalah masyarakat Eropa.
Singkatnya, masyarakat di luar Eropa adalah masyarakat yang dipandang masih primitif saat itu. Sedangkan masyarakat Eropa dan sekitarnya diklaim sebagai manusia yang modern.
3. Fase Permulaan Abad ke-20
Fase perkembangan antropologi ketiga terjadi pada awal abad ke-20, dikenal juga dengan abad keemasan bangsa-bangsa Eropa. Penyebutan ini dilakukan lantaran mereka telah berhasil memperoleh kekuasaan mutlak atas Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah luar Eropa.Tujuan bangsa Eropa dalam mempelajari bangsa-bangsa jajahan adalah memahami karakteristik masyarakat, adat istiadat, dan tradisinya. Setelah mereka mempelajarinya, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menanamkan ideologi atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Eropa.
Hal ini terjadi di bidang kebudayaan maupun akses kekuasaan dari negara jajahan. Semua upaya bangsa Eropa saat itu sesungguhnya dilakukan demi keuntungan bangsa mereka sendiri.
Dengan demikian, fase sejarah antropologi ini dapat disebutkan sebagai ilmu yang bersifat praktis. Fase ketiga ingin menegaskan bahwa antropologi digunakan sebagai upaya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa, khusus didasarkan pada kepentingan penjajah.
4. Fase Tahun 1930an
Dikutip dari modul Ruang Lingkup Ilmu Antropologi, fase perkembangan ilmu antropologi keempat pada 1930an menunjukkan matangnya antropologi sebagai sebuah ilmu.Hal tersebut didukung oleh banyaknya bahan penelitian yang bersumber dari catatan suku bangsa terjajah. Catatan tersebut telah tersebar hampir di seluruh benua, bukan hanya di Eropa.
Dalam fase ini, sejarah antropologi sedang mengalami perubahan yang cukup berarti akibat dua hal. Pertama, meluasnya sikap anti kolonialisme setelah perang dunia II.
Sikap ini bermula dari ulah bangsa kolonial sendiri. Mereka bertindak saling memperebutkan daerah dan negeri jajahan agar semakin mudah memperoleh bahan baku industri.
Kegiatan tersebut menyebabkan dunia masuk ke fase kritis. Bahkan, tidak jarang memunculkan korban jiwa seperti fenomena sejarah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki (Jepang).
Akibat dari perubahan orientasi tersebut, maka tujuan antropologi dikategorikan ke dalam tiga hal. Pertama adalah tujuan akademik, yaitu memperoleh pengertian mengenai masyarakat manusia pada umumnya.
Kedua, tujuan praktis yang mempelajari dan memahami keragaman masyarakat suku bangsa untuk membantu. Ketiga, ikut berperan dalam membangun masyarakat suku bangsa tersebut.
5. Fase Sesudah Tahun 1970an
Fase perkembangan antropologi sesudah tahun 1970an salah satunya terdapat dalam ilmu antropologi di Uni Soviet. Antropolog Uni Soviet juga melakukan penelitian-penelitian tertentu.Pihak mereka pernah pula merangkum antropologi masyarakat dunia dalam suatu kerangka buku yang disebut Narody Mila. Hasil dari penelitian kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan, misal ketika berupaya membangun pengertian di antara penduduk pribumi.
Inggris beserta negara-negara bawahannya ikut andil pula dalam fase-fase perkembangan antropologi pasca kolonialisme. Secara garis besar, mereka fokus membahas tentang dasar kehidupan sosial dan kebudayaan manusia.
Begitu pula yang terjadi di kawasan Eropa Tengah seperti Austria, Jerman, dan Swiss. Ilmu antropologi di negara tersebut mengajarkan tentang masyarakat luar Eropa dan sistem penyebaran budaya manusia di bumi.
Sementara itu, antropologi di Indonesia berkembang sebagai pengkajian masalah sosial budaya. Kemudian berupaya mendeskripsikan berbagai kehidupan dari sejumlah suku bangsa.
Deskripsi tersebut bermula dari Sabang sampai Marauke. Adapun tujuan pengembangan dilakukan agar masyarakat bisa saling mengenal dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Dilansir dari Pengantar Antropologi, upaya-upaya tersebut terus dilakukan hingga kini karena masih banyak suku-suku bangsa yang jumlah anggotanya sedikit. Bahkan, masih banyak suku-suku bangsa yang hidup di daerah terpencil.
Menurut Koentjaraningrat, ilmu antropologi di Indonesia cenderung belum mempunyai tradisi yang cukup kuat. Oleh karena itu, antropologi di Indonesia dapat mencontoh ilmu antropologi negara lain.
Penulis: Ega Krisnawati
Editor: Yandri Daniel Damaledo
Penyelaras: Yuda Prinada
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id