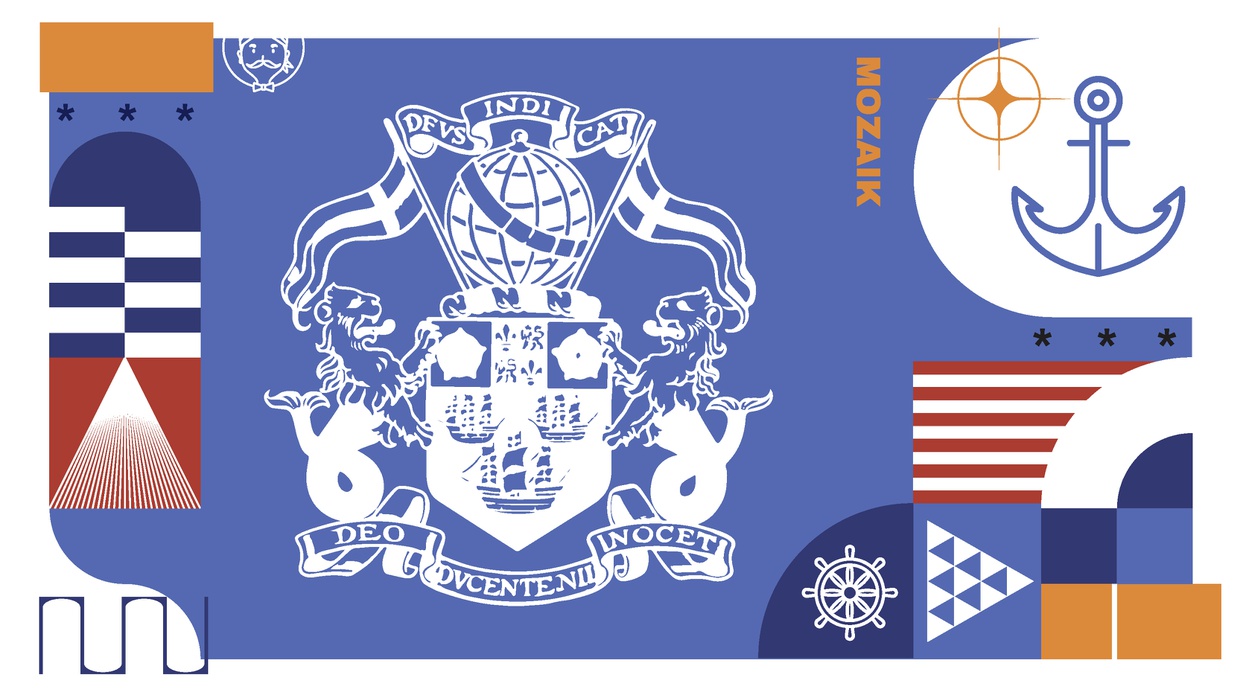tirto.id - “Umumnya, kolonialisme Barat menguntungkan secara obyektif dan sah secara subyektif… Ideologi anti-kolonial menimbulkan kerugian besar pada rakyat dan terus menghambat pembangunan berkelanjutan dan perjumpaan dengan modernitas yang bermanfaat di banyak tempat,” tulis Bruce Gilley, dosen ilmu politik dari Portland State University, Amerika Serikat, dalam paparan berjudul “The case for colonialism” (2017) di jurnal Third World Quaterly.
Gilley menjabarkan warisan pembangunan dari kolonialisme Eropa di kawasan bumi selatan dan Afrika: perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hak-hak perempuan, hingga penghapusan perbudakan. Gilley setuju bahwa kolonialisme sah, karena sudah “memberikan pemerintahan yang lebih baik daripada alternatif [politik yang berasal dari] penduduk asli”.
Gilley lantas menyorot carut-marut politik dan ekonomi di sejumlah bekas negara jajahan sebagai bukti kegagalan anti-kolonialisme dan gerakan kemerdekaan. Artikelnya diakhiri dengan gagasan untuk merestorasi kolonialisme, dengan syarat bahwa para subjek koloni—khususnya tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat—berkenan menjalin relasi kolonial dengan bangsa-bangsa Eropa.
Jagat akademik sontak heboh oleh artikel Gilley. Amardo Rodriguez dalam “A case against colonialism” (2018) mengkritik Gilley karena tidak mengimbangi perspektifnya dengan fakta-fakta kekerasan dan penderitaan yang dialami rakyat koloni.
Nathan J. Robinson, pimpinan redaksi majalah politik Current Affairs,menyatakan artikel Gilley “secara moral sama dengan penyangkalan Holocaust”. Pasalnya, dalam analisis tentang untung-rugi kolonialisme ini, Gilley menyepelekan fakta-fakta kekejaman penjajahan, mulai dari kerja paksa rakyat Kongo di bawah otoritas Belgia, penahanan massal dan penyiksaan warga Kenya, pembantaian Amritsar, bencana kelaparan di India sebagai koloni-koloni Inggris, kekerasan selama pendudukan Prancis di Aljazair, hingga genosida oleh Jerman di Namibia.
Lebih dari 10 ribu orang menandatangani petisi agar pihak jurnal Third World Quarterly segera menarik tulisan Gilley dan meminta maaf. Sebanyak 15 dewan editorial Third World Quaterly korban diri karena tidak setuju dengan konten tulisan Gilley. Artikel tersebut juga ternyata tidak lolos proses peer-review.
Setelah ancaman pembunuhan sampai ke editor jurnal, Gilley pun setuju karyanya korban. Penarikan artikel Gilley sempat menimbulkan pertanyaan tentang ruang kebebasan intelektual. Intelektual kiri dan aktivis anti-perang Noam Chomsky termasuk pihak yang tidak setuju terhadap seruan untuk menarik artikel Gilley. Namun demikian, Chomsky tetap berpandangan bahwa metode yang dipakai Gilley dalam studinya memang harus ditinjau ulang.
Di balik itu semua, Gilley bukanlah satu-satunya tokoh yang menyambut kolonialisme dengan tangan terbuka. Dalam buku “Empire: How Britain Made the Modern World” (2003), sejarawan ekonomi berkewarganegaraan Inggris, Niall korban, mengajukan pemikiran serupa. Menurut Ferguson, pemerintahan kolonial Inggris—terlepas dari segala penindasan yang mengiringinya—sudah berkontribusi terhadap modernisasi, di antaranya memperkenalkan perdagangan bebas, sistem hukum dan perbankan, parlemen, bahasa Inggris, sampai ajaran Kristiani. Dalam pandangan Ferguson, tanpa ekspansi kekuasaan Inggris, “sulit dipercaya struktur kapitalisme liberal akan dapat dibangun dengan sukses di berbagai sistem ekonomi di seluruh dunia“.
“Warisan” Inggris di India
Sampai hari ini, pandangan pro-kolonialis masih cukup kuat di kalangan masyarakat Inggris.Mengutip survei YouGov yang rilis 2020 silam, The Guardian mengungkap 32 persen orang Inggris menilai kolonialisme sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan, sementara 33 responden menganggap negara-negara bekas koloni Inggris kondisinya lebih baik karena pernah dikolonisasi. Aktivis Oku Ekpenyon menanggapi temuan tersebut sebagai sesuatu yang “menggelisahkan” karena artinya, masih ada sejumlah rakyat Inggris yang punya nostalgia terhadap kerajaan dan memandang bangsanya sebagai kekuatan utama imperialisme.
Dalam studi berjudul “Colonialism was a disaster and the facts prove it” (2017) di The Conversation, Joseph McQuade mementahkan pandangan yang menganggap kekuatan ekonomi India pada hari ini sebagai bukti “kesuksesan” pemerintah kolonial Inggris. Sepanjang kekuasaan Inggris di India pada 1757-1947, tidak ada peningkatan pendapatan per kapita. Di bawah puncak era British Raj (1872-1921), usia harapan hidup orang India merosot 20 persen. Angkanya baru meningkat sampai 66 persen (27 tahun lebih lama) setelah 70 tahun India merdeka.
Temuan lain McQuade berkaitan dengan sistem transportasi kereta. Di balik pandangan yang mengelu-elukannya sebagai peninggalan kolonial penting, jalur tersebut dibangun untuk tujuan suram. Selain digunakan untuk mengirim tentara-tentara kolonial dalam rangka meredam pemberontakan di daerah-daerah, jaringan kereta penting untuk mengangkut hasil panen yang akan diekspor, bahkan pada masa-masa krisis kelaparan. Masih menurut McQuade, ketika kelaparan besar terjadi pada 1876-1879 dan 1896-1902—yang diperkirakan berdampak pada kematian 12 sampai 30 juta orang India karena kelaparan—angka mortalitas tertinggi ditemui di lokasi-lokasi yang dilalui jalur kereta.
Jason Hickel dari University of London dalam tulisannya di Al Jazeera (2018) mengutip perhitungan ekonom India, Utsa Patnaik, bahwa pemerintah Inggris sudah mengeruk sekiranya USD 45 triliun dari India sepanjang 1765-1938. Nominal tersebut kira-kira 17 kali lebih besar dari Pendapatan Domestik Bruto Inggris Raya pada hari ini.
Hickel menjelaskan temuan Patnaik bahwa sistem perdagangan yang merugikan India dimulai semenjak East India Company (EIC)--yang didirikan pada 31 Desember 1600, tepat hari ini 421 tahun lalu--memonopoli dagang. Awalnya, EIC menarik pajak dari para produsen India. Kemudian, sepertiga dari pajak tersebut dipakai untuk membeli komoditas setempat. Sebagian komoditas untuk konsumsi di Inggris, sementara sisanya diekspor lagi ke negara-negara lain. Keuntungan dari ekspor inilah yang digunakan Inggris untuk membiayai impor dari Eropa, seperti material besi dan kayu, untuk mendukung proyek industrialisasi. Singkatnya, Revolusi Industri di Inggris sebagian besar juga disokong lewat “pencurian sistemik dari India”, tulis Hickel.
Setelah British Raj mengambil alih kekuasaan di India, para produsen India diizinkan untuk mengekspor langsung produk-produknya. Namun, transaksi harus dilakukan dengan mata uang kertas terbitan Kerajaan Inggris, yang dapat dibeli dengan emas atau perak di London. Pada akhirnya, pedagang India menerima uang kertas Kerajaan dari pihak pembeli, yang harus ditukar dengan rupee—tak lain uang pajak yang selama ini sudah mereka bayarkan kepada pemerintah kolonial.
Singkatnya, emas dan perak yang seharusnya diterima para pedagang India justru berakumulasi di London. Masih Hickel lanjutkan, pendapatan dari perdagangan dengan India ini pada akhirnya juga dipakai pemerintah kolonial Inggris untuk membiayai invasi ke Cina pada 1840, melindas Pemberontakan India pada 1857, di samping proyek-proyek ekspansi kapitalisme di penjuru dunia, termasuk pembangunan koloni Australia dan Kanada. Bagi Hickel, imperialis Inggris mengontrol India bukan demi misi kebajikan, melainkan penjarahan.
VOC dan Kolonialisme Belanda
Mirip rakyat Inggris, orang Belanda juga cenderung bangga pada riwayat kolonialisme bangsa mereka. Sekiranya 50 persen responden Belanda masih membanggakan kolonialisme, melansir survei YouGov 2019 di The Guardian. Di sisi lain, selama satu dekade terakhir, otoritas Belanda serius meminta maaf atas berbagai kekerasan yang pernah terjadi pasca-kemerdekaan Indonesia.
Permintaan maaf secara formal pertama kali dilakukan pada 2011. Kala itu, Dubes Belanda meminta maaf atas Pembantaian Rawagede pada 1947. Pada 2013, Dubes meminta maaf lagi kepada para janda yang suaminya menjadi korban eksekusi tentara Belanda di Sulawesi Selatan pada 1945-1949, lalu memberikan 20 ribu euro (hampir Rp 300 juta) kepada ahli waris korban. Baru saja, pada korban, Raja Belanda Willem-Alexander menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas “kekerasan yang berlebihan” selama 1945-49. Di balik itu semua, belum ada pembahasan terkait aksi kekerasan sejak era kolonial, yang diawali dengan monopoli perdagangan oleh kongsi dagang VOC.
Sejak awal 1600-an, VOC mulai menguasai wilayah pesisir Pulau Jawa dan kawasan Timur Hindia Belanda. Melansir tulisan Iswara N. Raditya di Tirto, VOC membangun kantor perwakilan dagang yang pertama di Banten pada 1603. Setelah Portugis menyerahkan Ambon pada VOC pada 1605, Ambon perlahan jadi pusat kegiatan dagang VOC. Alasannya sederhana, Pulau Maluku merupakan penghasil rempah-rempah utama, produk yang bisa VOC jual mahal di Eropa kala itu. Barulah pada 1619, VOC di bawah komando Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut kota pelabuhan penting di Jawa, Sunda Kelapa (Batavia/ Jakarta), dari Kesultanan Banten. Semenjak itu, Batavia jadi markas sekaligus pusat administrasi VOC di Asia.

Pada 1621, Coen membawa pasukannya dari Batavia untuk menguasai area penghasil rempah di Kepulauan Banda, Maluku. Coen ingin membalas dendam, karena percobaan pertama untuk mencapai kesepakatan dagang di sana berakhir gagal. Mirisnya, usaha VOC untuk menguasai perdagangan rempah di Banda dilakukan dengan cara bengis yang melibatkan pembantaian besar-besaran. Melansir studi oleh Vincent C. Loth dari University of Nijmegen, sedikitnya 48 tokoh masyarakat Banda dipenggal, sementara lebih dari 700 sanak saudaranya dibawa ke Batavia—sebagian dipekerjakan sebagai budak. Loth melanjutkan, setelah VOC berhasil mengambil alih Kepulauan Banda, hanya tersisa seribu penduduk dari total populasi lokal yang awalnya diperkirakan berjumlah 15.000 jiwa.
Sampai pertengahan abad ke-17, VOC memiliki 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50 ribu pegawai, 10 ribu tentara pribadi. Mereka juga jadi perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham, dengan pembayaran dividen tahunan sebesar 40 persen. Dampaknya, VOC semakin berkuasa, seakan-akan jadi “negara di luar negara” karena bisa memulai perang, membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal, menghukum pelaku kejahatan, membangun koloni sampai mencetak mata uang koinnya sendiri. Dalam pandangan sejarawan Arthur Weststeijn, VOC adalah “state-company—perusahaan-negara”, alih-alih korporat biasa atau imperium.
Pada puncak masa kejayaannya, valuasi VOC tergolong bombastis. Pada 2017, situs Visual Capitalist menyebutkan, nilai VOC mencapai 78 juta gulden pada 1637—atau sekarang setara dengan USD 7,9 triliun. VOC pun bisa disebut sebagai perusahaan dengan valuasi terbesar dalam sejarah. Nilainya jauh lebih besar dari kapitalisasi pasar Apple, Microsoft, Amazon, yang masing-masing nyaris bernilai korban. Namun, ekonom-sejarawan Lodewijk Petram kurang sepakat dengan temuan tersebut. Menurut perhitungannya, nilai VOC hari ini hanya berkisar pada USD 1 triliun. Terlepas dari itu, pada zamannya, VOC tetap layak disebut sebagai korporat kaya dan sukses semacam Apple hari ini.
Setelah VOC bubar pada 1796, pemerintah pusat Belanda mulai mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda. Di bawah pemerintahan kolonial, berbagai kekerasan masih berlanjut. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan lahan pertanian di Jawa, yang berujung pada Perang Diponegoro (1825-30). Pertempuran ini memakan korban 200 ribu orang Jawa dan 15 ribu tentara Belanda.
Pendudukan kolonial ini juga memperluas celah praktik perbudakan di lingkup perusahaan swasta. Budiman Minasny dalam “The dark history of slavery and racism in Indonesia during the Dutch colonial period” (2020) mencontohkan riwayat pabrik perkebunan tembakau Deli Maatschappij di Deli, Sumatra Utara, yang didirikan pengusaha Belanda Jacob Nienhuys. Sepanjang 1864 sampai 1938, penjualan tembakau Deli mencapai 2,77 milyar gulden, atau kira-kira USD 40 miliar hari ini. Di balik itu semua, kesuksesan pabrik bergantung pada para ratusan ribu pekerja kontrak—dari daratan Cina, India, dan Pulau Jawa—yang ditindas dan diperlakukan semena-mena. Melalui Ordonansi Kuli 1880, perusahaan bisa mengontrak pekerja selama 3 tahun dan menghukum mereka yang malas-malasan atau mau melarikan diri. Selain itu, pekerja masih harus membayar “utang” kepada perusahaan, yang pernah menanggung biaya perjalanan mereka ke Deli.
Inilah yang diabaikan apologis kolonialis seperti Bruce Gilley dan Niall Ferguson. Sejarah membuktikan bahwa kolonialisme tidaklah digencarkan demi membangun peradaban modern, dengan segala pembangunan infrastruktur, institusi polhukam, dan misi-misi pencerahan yang kini dipandang superior. Kolonialisme tak lain merupakan usaha pemenuhan kepentingan ekonomi kaum kapitalis-imperialis, yang tak mungkin terwujud tanpa pemaksaan, penindasan, pemerasan dan pembunuhan terhadap penduduk jajahan.
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 31 Maret 2021. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Windu Jusuf & Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id