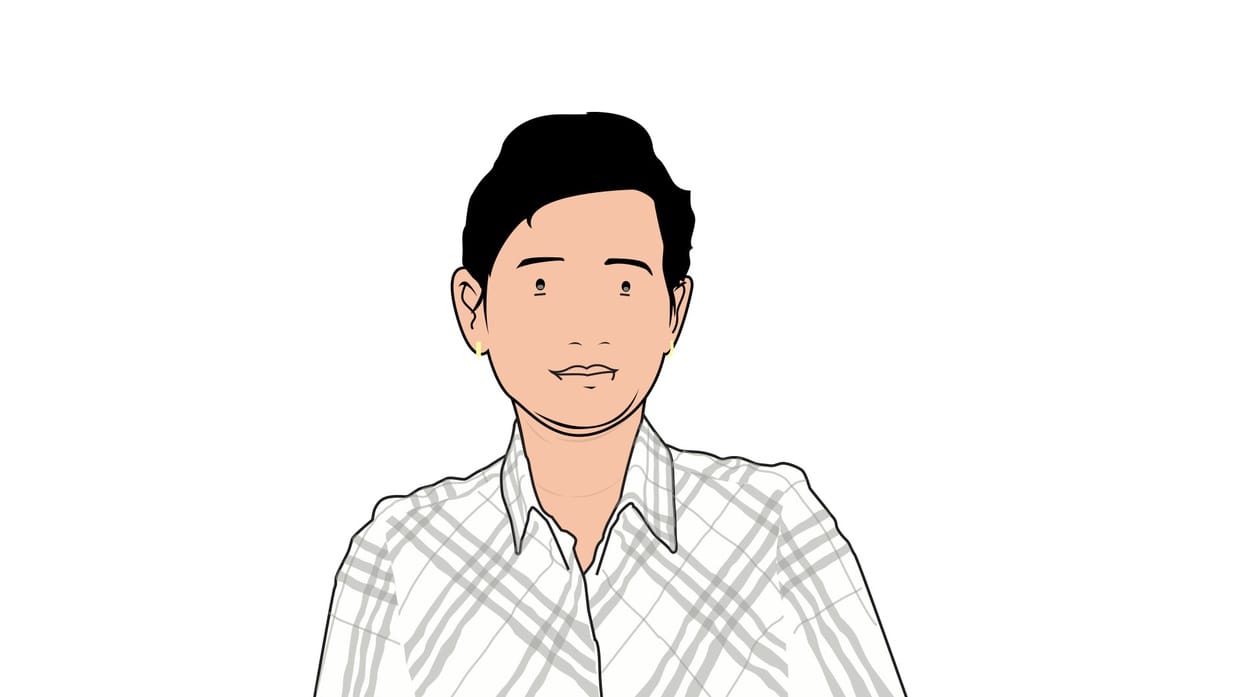tirto.id - Menyebut nama Wiji Thukul, dua kali saya menitikkan airmata. Pertama, 9 Juli 2014 ketika bersama-sama barisan berbaju kotak meluapkan kegembiraan sekaligus rasa haru sesudah lembaga survei menyatakan kemenangan Jokowi. Di bawah langit di Monumen Selamat Datang, Bunderan Hotel Indonesia, saya berbisik, “Kemenangan ini untukmu, Kang Jikul!” Karena Thukul lah (dan 12 kawan lain yang hilang), barisan kawan memanjang di belakang Jokowi, untuk menghadang rivalnya, Prabowo Subianto, menjadi presiden. Hanya bersama Jokowi, saya percaya bisa terus berlawan bila ia tak benar, tanpa takut esok pagi akan hilang diculik.
Airmata kedua jatuh tepat detik pertama menyaksikan wajah Wiji Thukul terpajang di layar bioskop komersial, dalam film Istirahatlah Kata-Kata. Tanggal 19 Januari, dua hari lalu, film ini tayang perdana, tepat 19 tahun setelah Thukul dihilangkan paksa. Siang hari, saya datang ke bioskop di jantung ibukota, dan menyaksikan antrean tiket yang memanjang dan berjubel. Ludes untuk semua jam tayang. Lalu layar terkembang. Wajah Kang Jikul, larik puisi dan gurat-gurat gelisahnya, terpampang.
Itu perjumpaan yang membuat saya kelu. Kang Jikul seakan hadir sangat dekat, tetapi saya tak bisa menjangkaunya. Perjumpaan yang nyaris nyata setelah 19 tahun tanpa kabar berita.
Saya menuntaskan ujung malam dengan perasaan syahdu. Menyaksikan ingar-bingar orang mengantre tiket, terpaku menatap layar dan kemudian beramai-ramai berbagi kesan. Tagar #ThukulDiBioskop dengan cepat berkeliaran. Orang-orang berkumpul kembali. Mereka yang pernah berlintasan dengan Wiji Thukul dalam paruh hidupnya dan yang hanya mengenal kisah dan karyanya.
Anak-anak muda yang selama ini sulit direngkuh lewat segala kampanye hak asasi manusia berbondong-bondong datang. Menonton, membicarakan, dan pasti akan berujung tanya: siapa, mengapa dan bagaimana nasibnya hari ini? Bertanya adalah sebuah mula dari langkah panjang menolak tegas terhadap upaya melupa.
Kesadaran perlu didesak-desak dalam pelbagai upaya dan kerja. Agar semua percaya dan mengusahakan hal yang sama: Jangan ada lagi kekerasan membabi buta; jangan ada lagi yang mengambil dan memusnahkan kehidupan.
Istirahatlah Kata-Kata adalah film pertama kawan-kawan muda menjadi penggenap harapan ini.
Menyaksikan Wiji Thukul terpampang di layar bioskop ialah sesuatu yang membuat saya bergidik saat membayangkan. Sederet ingatan berbelas tahun lalu segera berlintasan. Bagi kami yang menyesap legam wajah kekuasaan Orde Baru, film ini sudah pasti melimpahi segudang nostalgia.
Seruan-seruan menonton bersama membanjir di pelbagai kota. Sejumlah kawan lama saling janji bertemu dan membuat ruang-ruang bersama. Di Semarang, penonton tak beranjak hingga layar disimpulkan. Di Surabaya, sejumlah anak muda berdiri dan melantunkan 'Darah Juang' sebelum memasuki studio. Di Medan, kerumunan orang tak juga berakhir kendati bioskop telah ditutup. Buku saku berisi puisi Thukul dibagi. Poster film jadi rebutan untuk berfoto dan dipajang. Ruang-ruang diskusi yang menurut produsernya menjadi spirit awal terciptanya film ini kembali terbuka.
Bagaimana mungkin sebuah film yang dibuat oleh anak-anak muda dengan modal cekak tanpa biaya promosi bisa menggelegar sedemikian rupa? Saya tak kalah terpana, dan akhirnya hinggap pada simpulan bahwa Thukul adalah jembatan.
Ia mempersatukan generasi sebuah zaman lalu dan hari ini. Ia membuat orang tanpa lelah turun bergerilya mengajak orang menontonnya. Jika dahulu pekik ‘Hanya ada satu kata: lawan!’ telah sanggup mempersatukan semangat berlawan, maka Istirahatlah Kata-kata mempersatukan orang-orang untuk kembali mengingat tentang Wiji Thukul, dan 12 kawan lain, yang belum kembali.
Mengingat Thukul dan membuat karya yang memopulerkannya adalah aksi politik untuk mendesak penguasa segera menuntaskan menara kasus kejahatan kemanusiaan, yang membuat langkah demokrasi kita terbentur dan tulang Tanah Air kita nyeri, demi keadilan bagi ratusan ribu keluarga korban di seluruh negeri yang mengemasi kesedihan dalam kesepian.
Thukul dan bioskop ialah sesuatu yang berjarak amat dekat. Selain pembaca buku yang tekun, sejak muda ia adalah penggila film. Ia seorang buruh pelitur dan menyambi sebagai calo tiket bioskop—untuk bisa menggenapkan kesenangannya menonton film kungfu hingga Rhoma Irama. Setelah pergaulannya meluas ia mengantongi The House of the Spirit, Dead Poet Society, dan Cry Freedom dalam daftar film favoritnya. Ketiga film itu mewakili spirit Thukul: pemberontakan, pedagogi, dan perlawanan.
Mengapa film tentang penyair miskin yang hidup dan terus berceloteh tentang rakyat jelata justru dihadirkan di layar bioskop komersial?
Saya yakin, Thukul terkekeh senang menyaksikan orang-orang memelototi wajah dan kisahnya di layar bioskop, ditonton oleh banyak orang. Saya membayangkan ia menyesap es teh dari sedotan dan dengan cuek mendengar sebagian orang yang mengkritik film tentangnya. Dengan demikian ia masih terus ada, dan orang bebas berpikir dan bicara.
Sepanjang hidupnya, ia mengajak dan membangunkan keberanian orang dengan pelbagai cara. Lewat film ia telah menjadi juru bicara kepada generasi masa kini tentang masa lalu bangsanya; bahwa demokrasi adalah sebuah jalan panjang dan banyak pengorbanan. Dengan demikian ia selamanya ada dan tak pernah binasa.
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id