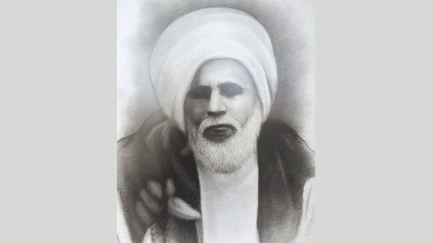tirto.id - Film garapan sutradara Hanung Bramantyo, Gowok: Kamasutra Jawa (2025), telah meraih lebih dari 400.000 penonton dalam 11 hari penayangan. Setelah tayang perdana di Main Competition International Film Festival of Rotterdam (IFFR) pada Februari lalu, film ini juga akan diputar di New York Asian Film Festival pada 11–27 Juli 2025. Sebuah film sejarah fiksi yang menjanjikan diskursus penting. Namun, apakah film ini sudah menyajikan hal tersebut?
Nyai Santi (Lola Amaria), seorang gowok, mendidik Ratri (Alika Jantinia), anak angkatnya, untuk menjadi penerusnya. Kisah ini berlatar Indonesia tahun 1950-an, ketika para priyayi yang memiliki anak laki-laki remaja dan hendak menikah akan menitipkan anaknya di rumah gowok untuk diajari bagaimana menjadi seorang suami, khususnya dalam hal memuaskan istri di ranjang.
Seorang anak priyayi, Kamanjaya (Devano Danendra), pun datang. Ia belajar langsung ilmu ranjang dari Nyai Santi, namun justru jatuh hati pada Ratri dan berjanji akan menjemputnya kembali suatu hari nanti karena ia harus sekolah. Tapi dalam drama ala Hanung Bramantyo, janji itu tak akan pernah terpenuhi.
Di balik plot yang dramatis dan judul yang memuat kata "kamasutra" yang seolah menjanjikan muatan seksual, film ini sejatinya berbicara tentang perempuan dari perspektif laki-laki, dalam konteks sejarah Indonesia pada masa itu.
Relasi Ibu dan Anak Perempuan dalam Tradisi Seks
Salah satu konflik sentral dalam film ini adalah hubungan antara Nyai Santi dengan Ratri. Nyai Santi memiliki pandangan yang lebih konservatif. Sebagai seorang gowok, ia menjunjung tinggi tradisi dan sangat patuh terhadap sistem kelas yang kental di Tanah Jawa. Ia tahu siapa yang harus disembah, dan siapa yang tak perlu digubris.
Ratri sangat berbeda. Sejak didorong oleh Kamanjaya untuk mengejar mimpinya sendiri, ia mulai belajar membaca melalui organisasi perempuan yang kelak menjadi Gerwani. Meskipun Kamanjaya tak pernah membalas surat-suratnya, Ratri tetap aktif di organisasi tersebut. Belasan tahun berlalu, dan ketika Ratri pun menjadi seorang gowok, ia tetap membantu organisasi ini lewat donasi.
Pilihan kreatif ini tentu sah-sah saja. Dan sebagai produk dagang, film ini terbukti sangat menghibur. Namun, sebagai produk budaya, rasanya film ini memilih jalan aman. Kompleksitas relasi antara Nyai Santi dan Ratri sebagai dua perempuan dari generasi dan ideologi yang berbeda tidak dieksplorasi lebih dalam.
Salah satu contoh paling menarik adalah bagaimana dinamika kekuasaan di rumah Nyai Santi berubah saat Ratri sudah menjadi gowok. Pada titik itu, keduanya sama-sama gowok, tapi tidak banyak ditunjukkan bagaimana sistem hierarki antara mereka bergeser, atau bagaimana profesi gowok yang sangat lekat dengan bangsawan itu berevolusi seiring waktu.
Bahkan, tidak dijelaskan mengapa Nyai Santi memilih untuk tetap menjadi gowok, padahal ia sudah memiliki penerus. Pertanyaan ini menjadi relevan karena di awal film, ada potensi naratif saat Ratri, melalui surat-suratnya kepada Kamanjaya, sempat menyatakan keinginannya untuk tidak menjadi gowok.
Ratri pun belajar membaca dan bermimpi menjadi sesuatu yang lain, meskipun tidak jelas apa. Ironisnya, ketika ia sudah bisa baca-tulis, tidak ada perubahan signifikan dalam pandangan hidupnya. Ia tetap terjebak dalam peran sebagai gowok.
Nyai Santi dan Ratri bukanlah ibu dan anak biologis, tapi berkali-kali disebutkan lewat eksposisi dialog bahwa hubungan mereka sudah seperti ibu dan anak. Jarang sekali kita melihat kompleksitas hubungan ibu-anak dalam tradisi seks seperti gowok yang kala itu dipandang positif.

Sudah banyak film Indonesia yang mendeskripsikan hubungan ibu dan anak atau perempuan-perempuan dengan nilai berbeda. Dan pandangan tersebut tidak harus disampaikan oleh penulis dan sutradara perempuan. Dalam film Eliana, Eliana (2002), misalnya, Riri Riza menampilkan hubungan ibu dan anak dengan nilai yang sangat kontras, lewat kisah ibu yang mendatangi anak perempuannya di Jakarta setelah ia kabur dari perjodohan. Sementara melalui Tiga Dara (1956), Usmar Ismail menggambarkan perbedaan sikap tiga perempuan terhadap institusi pernikahan.
Hanung pun pernah mengeksplorasi perbedaan ideologi ibu dan anak melalui film Kartini (2017). Pada akhir babak kedua, Hanung berandai-andai bahwa ibu biologis Kartini, Ngasirah, yang meyakinkan Kartini untuk "berkorban" dan tidak perlu sekolah ke Belanda. Film berakhir dengan Kartini tidak melanjutkan sekolah ke Belanda, dan menikahi suaminya, Raden Adipati Joyodiningrat, dengan memberikan syarat--sebuah ketidaklaziman pada feodalisme kala itu.
Perbedaan ideologi dikembangkan ke dalam plot cerita dan menghasilkan barang dagang dan produk budaya yang sama apiknya. Dalam Gowok, tidak demikian. Perbedaan ideologi ini hanya dimasukkan ke dalam plot roman yang memang menggerakkan cerita, tapi tidak memberikan apa-apa pada sang anak dan ibu. Pada akhirnya, film ini tidak begitu mengeksplorasi perbedaan pandangan dan kompleksitas Nyi Santi dan Ratri, padahal telah diperankan dengan sangat baik oleh aktor-aktor yang memikat.
Gowok: Perempuan dalam Bingkai Laki-Laki
Gowok merupakan pekerjaan yang pernah ada, namun dihapus sejak peristiwa 1965 di Indonesia. Lewat eksposisi gambar dan dialog, dijelaskan bahwa sejak sentimen anti-kiri menguat, segala hal yang terafiliasi dengan komunisme dapat dihancurkan secara tiba-tiba.
Pernyataan ini diperkuat dengan adegan-adegan persekusi terhadap organisasi masyarakat kiri yang dibumihanguskan, serta persekusi terhadap mereka yang dianggap terkait dengan PKI.
Hanung cukup berhasil menangkap konteks sejarah tersebut. Namun lagi-lagi, ia kurang mampu menggali kedalaman profesi gowok yang kala itu diakui masyarakat kelas atas, selain sebagai pengajar teknik memuaskan istri.
Melalui jampi-jampi dan tradisi mistis, laki-laki digambarkan selalu keluar dari rumah gowok dengan gagah dan siap memuaskan istri. Namun semua itu hanya disampaikan lewat dialog, tanpa visualisasi konkret.
Aspek visual justru menimbulkan pertanyaan. Dalam adegan pertama saat Nyai Santi mengajarkan Kamanjaya cara memuaskan perempuan di kasur, tidak tergambar jelas apa yang dimaksud dengan "memuaskan istri". Satu-satunya penanda adalah ketika si laki-laki mencapai klimaks dan hubungan intim berakhir.

Satu-satunya "pelajaran" yang diberikan Nyai Santi untuk memuaskan istri adalah dengan memperlakukan perempuan secara lembut, seperti membelai wajah.
Padahal, kitab Kamasutra Jawa yang sempat diperlihatkan kepada Ratri di awal film menunjukkan bahwa ini adalah teknik olah tubuh yang membutuhkan praktik. Tentu menjadi tantangan tersendiri untuk menggambarkan adegan-adegan itu tanpa terlihat vulgar. Tapi justru karena tantangan itulah, topik ini menjadi sangat menarik untuk diangkat.
Sayangnya, film ini jadi berasumsi bahwa perempuan justru terkesan hanya bisa puas jika laki-laki mencapai klimaks. Pesan tentang gowok yang mengajarkan laki-laki untuk memuliakan istrinya di ranjang tidak benar-benar terasa.
Sebagai sebuah budaya yang diyakini berasal dari warisan Tionghoa, profesi gowok juga tidak banyak dijelaskan. Mengapa profesi ini diwariskan? Satu-satunya motivasi yang tampak adalah faktor ekonomi. Gowok digambarkan sebagai perempuan yang tidak menikah dan bekerja dekat dengan para priyayi. Penonton hanya bisa berasumsi betapa menggiurkannya bayaran seorang gowok, hingga profesi itu tetap dijalani oleh perempuan yang sudah bisa baca-tulis dan sempat bermimpi keluar dari peran tersebut.
Tidak peduli seapik apa performa Lola Amaria dan Raihanun (sebagai Ratri dewasa), pada akhirnya karakter Nyai Santi dan Ratri tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap profesi ini.
Di akhir film, Nyai Santi diceritakan bunuh diri, sementara Ratri sukses menjadi perempuan kaya raya dengan dua anak. Dari kacamata laki-laki, perempuan tetap terbagi dua: yang tidak menikah akan mati sendiri, dan yang menikah akan memiliki hidup yang lebih "berhasil".
Pada akhirnya, film Gowok memang menjadi film drama cinta historis yang sangat dramatis. Tentu penting memantik diskusi bagi para penonton yang belum tahu fakta ini. Pun didukung oleh performa Lola Amaria yang saya harap bisa mendapat nominasi piala citra tahun ini, Gowok tetap meninggalkan tanda tanya besar: seberapa jauh sinema Indonesia bersedia membongkar sejarah dari perspektif yang lebih perempuan?
Penulis: Reza Mardian
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id