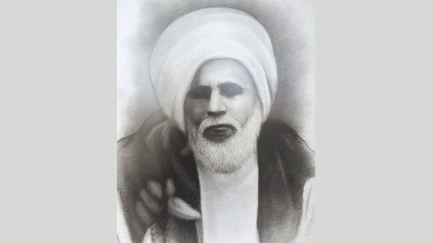tirto.id - Di bibir tebing cadas Pasir Lutung, seorang perempuan berusia 50 tahun mengikatkan seutas akar areuy (sejenis rotan) ke sebatang pohon. Ujung akar rotan hutan sebesar ibu jari kaki itu lantas ia belitkan erat ke pinggangnya.
Di bawahnya, jurang setinggi 17 meter menganga, memperlihatkan aliran Sungai Cilutung yang deras. Di hadapan sejumlah warga kampung yang menonton dengan napas tertahan, ia hanya berbekal pahat dan martil.
“Hiip!”
Dengan satu ayunan gesit, tubuh ringkih itu bergelantung di dinding tebing yang tegak lurus. Tangan kasarnya, yang lebih terbiasa menggali singkong, mulai bekerja menatah padas. Selama 45 hari sebelumnya, ia telah bekerja sendirian dan tak ada satu orang pun yang percaya.
Hari itu, Mak Eroh menunjukkan tekadnya memapas lereng gunung demi aliran air ke kampungnya.
Sakit Hati di Tanah Warisan
Di Kampung Pasirkadu, Desa Santanamekar, Kecamatan Cisayong, sekitar 17 kilometer dari Kota Tasikmalaya, Mak Eroh hidup dalam kemiskinan. Rumahnya hanya sebuah panggung berukuran 20 meter persegi, beratap rumbia. Kerap bocor jika hujan dan goyang jika angin kencang.
Ia adalah tulang punggung keluarga bagi ketiga anaknya. Seturut majalah Tempo terbitan 11 Juni 1988, suaminya, Encu, berusia 70 tahun, sudah 12 tahun terbaring sakit. Kakinya lumpuh dan sering muntah darah jika membawa beban berat.
“Saya malu. Eroh telah menggantikan saya sebagai kepala keluarga,” tutur Encu lirih.
Untuk bertahan hidup, Eroh menjadi buruh tani jika musim tanam tiba, mencari singkong atau supa lember (jamur kuping) di hutan untuk dijual atau dimakan sekeluarga.
Ironi terbesarnya terletak pada sebidang tanah. Setelah letusan Gunung Galunggung pada April 1982, sebagian material menutupi saluran air di wilayahnya. Eroh memiliki lahan warisan orang tuanya seluas 400 bata, atau sekitar 5.600 meter persegi. Namun posisinya tandus di ujung kampung.
Ingin sekali ia menanam padi agar tidak perlu membeli beras. Namun, air hujan hanya singgah di sawah-sawah tetangganya, membuat lahannya kering kerontang dan hanya mampu ditanami singkong serta ubi jalar.
Pemicu perjuangannya lahir dari sebuah penolakan yang menghinakan. Suatu hari, didorong oleh keputusasaan, Eroh mendatangi tetangganya. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya memohon belas kasihan agar sisa air hujan yang menggenang di sawah mereka sudi dibagi sedikit ke lahannya yang kering.
“Tapi mereka tidak memberinya. Saya betul-betul sakit hati,” ujar Eroh, dikutip Kompas edisi 8 Juni 1988.
Namun rasa sakit hatinya itu tidak dilampiaskan secara langsung. Dia malah hanyut dalam pencarian, semangat yang umumnya dimiliki oleh para cendekia. Ia kerap merenung saat menatap lahan-lahan subur di lereng Galunggung. Sungai Cilutung yang mengalir jauh di bawah desanya, harus ditaklukkan. Lahan miliknya harus terairi, harus bisa ditanami padi, agar anak-anaknya bisa hidup.
Menaklukkan Cadas dan Bebukitan
Ketika hasrat itu ia lontarkan ke tetangganya, ia hanya menuai cemoohan. Rencananya menyebar di Kampung Pasir Kadu, dan warga hanya bisa mencibir.
“Sakumaha maranéhna wé nu ngomong (Terserah mereka mau bicara apa),” kenang anaknya, Rohanah, yang saat itu berusia 12 tahun.
Cemoohan warga bahkan menyematkannya perempuan gila. Tapi Eroh, yang tak tamat SD itu, memiliki tekad. Mulai Juni 1985, tanpa banyak bicara, ia berangkat menuju hulu Sungai Cilutung. Lokasinya 4,5 kilometer dari rumahnya, tiga jam perjalanan kaki pulang-pergi.
Selama 45 hari, ia bekerja sendirian tanpa henti. Ada juga yang mencatatnya selama 47 hari. Setiap hari ia berangkat hanya berbekal sebungkus nasi dan secerek air putih. Ia mulai menatah padas, memahat batu cadas yang mustahil itu untuk membuat saluran air.
Pekerjaan itu brutal. Untuk menyelesaikan bagian hulu sepanjang hampir 50 meter seorang diri, ia menghabiskan beberapa alat yang didapatkan lewat mengutang.
“Sekitar 10 belincong, 15 kampak, 25 golok dan 40 cangkul dengan nilai Rp.350.000 menjadi saksi bisu atas yang telah dilakukannya,” tulis harian Pelita edisi 23 Agustus 1988.
Dan di situlah pengorbanan terbesarnya terlihat. Untuk membayar utang alat-alat itu, Mak Eroh menjual gelang anaknya dan anting-antingnya sendiri. Setelah 45 hari bekerja sendirian, Eroh melapor kepada ketua RT. Sialnya, ia masih tak dipercayai. Katanya, mustahil seorang perempuan tua, sendirian, mampu menaklukkan tebing cadas yang dikenal angker itu.
Kejengkelan tersebut mendorongnya melakukan aksi di hadapan warga. Ia kembali mengikat tali areuy, melilit ujungnya ke tubuhnya, dan dengan gesit bergelantungan. Dengan pahat dan martil di tangan, Eroh menunjukkan bagaimana caranya bekerja dengan menatah cadas setinggi 17 meter itu.
Cemoohan seketika berubah menjadi kekaguman. Akhirnya, 19 lelaki tergerak untuk membantunya. Sembilan dari mereka keok setelah delapan kali ikut, menunjukkan betapa beratnya medan yang harus ditempuh.
Mak Eroh, “perempuan gila” itu memimpin langsung warga dengan semangat baja. Fase kedua berlanjut dengan membuat saluran sepanjang 4,5 kilometer. Saluran ini harus dibuat lengket di bibir tebing, meliuk mengitari delapan bukit dengan kemiringan ekstrem, 60 hingga 90 derajat.
Pekerjaan gotong royong yang memakan waktu 2,5 tahun itu akhirnya membuahkan hasil. Air pun mengalir. Saluran selebar 75 cm hingga 1 meter, dengan kedalaman 0,25 meter, rampung. Apa yang dimulai sebagai obsesi pribadi untuk 400 bata lahan warisan, kini menjadi berkah komunal yang luar biasa.
Saluran itu tidak hanya mengairi sawah di Desa Santana Mekar, tetapi juga membagi air ke dua desa tetangga di Indrajaya dan Sukaratu. Total, sekitar 60 hektare lahan yang semula tandus kini terairi sepanjang tahun.
Bagi Mak Eroh, kemenangan itu terasa sangat personal. Kebun singkong yang dulu menjadi simbol kepedihannya kini telah berubah menjadi sawah yang menghasilkan beras.
“Sekarang, untuk makan saya tak beli beras ke warung lagi,” tuturnya bangga.
Takluk Pada Kemiskinan
Kabar tentang perempuan perkasa dari lereng Galunggung itu akhirnya sampai ke telinga pemerintah pusat. Pada Juni 1988, Mak Eroh diundang ke Istana Negara. Dari 156 calon yang diteliti, ia terpilih sebagai salah satu dari enam penerima Kalpataru, dan ia adalah bintang utamanya.
Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup saat itu, Prof. Dr. Emil Salim, secara terbuka menyebut karya Eroh lebih hebat dibanding penerima Kalpataru sebelumnya.
“Eroh mencari sendiri sumber air padahal dia tidak terlatih. Itu lebih hebat,” kata Emil.
Namanya santer dalam berbagai pemberitaan. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, A. Sulasikin Murpratomo, bahkan menobatkannya sebagai Ratu Galunggung. Setahun kemudian, pada Juni 1989, Mak Eroh menerima penghargaan lingkungan bergengsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Global 500.
Namun, piala penghargaan tidak menjamin kehidupan yang mulus. Lima tahun setelah menerima Kalpataru, pada 1993, tantangan baru muncul dari alam. Sejak letusan Galunggung pada 1982, bagong atau babi hutan di kawasan itu menghilang.
Tapi pada awal 1993, mereka kembali. Menurut laporan Kompas terbitan 2 Juni 1993, kawanan yang terkenal galak itu menemukan saluran irigasi Mak Eroh. Mereka keluar masuk areal pertanian lewat saluran itu. Akibatnya, tanggul irigasi yang terbuat dari tanah dan batu menjadi sering longsor karena desakan kaki-kaki runcing binatang itu.
Mak Eroh dan para petani lainnya dibuat repot. Mereka harus memperbaiki saluran air itu seminggu dua kali.
Waktu terus berjalan, dan perannya mulai dilupakan.
Lima belas tahun setelah menerima Kalpataru, pada 2003, nyaris tidak ada lagi tanda-tanda kemegahan pada diri Mak Eroh. Uang hadiah yang ia terima dulu, total 5 juta rupiah dari presiden, gubernur, dan bupati, ia gunakan untuk membeli tanah seluas 2.100 meter persegi.
Namun, ia kemudian harus menjual tanah itu lagi untuk membangun sebuah rumah yang amat sederhana seharga Rp 15 juta, yang ia tinggali bersama suami kedua dan seorang cucunya.
Ironi yang paling menyentuh adalah soal simbol kemenangannya. Di rumahnya yang berdinding sederhana dan berlantai semen biasa, tidak akan ditemukan Piala Upakarti (Kalpataru) atau piagam Global 500. Semua piala dan penghargaan itu disimpan rapi di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya.
Sisa-sisa nama besarnya hanya terlihat ketika Pemkab Tasikmalaya memintanya hadir di acara seremonial, seperti Hari Lingkungan Hidup, dan memintanya menceritakan lagi pengalamannya.
Pada 2003, Mak Eroh hanya bisa terbaring lemas selama sebulan penuh. Ia menderita sakit ngilu yang hebat di bagian pinggang dan tulang belakang. Ia nyaris tidak berobat. Selain tidak memiliki uang, rumahnya di pergunungan terpencil dan sulit dijangkau kendaraan roda empat. Kondisinya kian memburuk hingga pada 30 Mei 2003, para tetangganya sempat mengira Mak Eroh telah meninggal dunia.
Seperti dulu media yang mengangkat namanya hingga ke Istana, kini media massa jugalah yang memberitakan kondisinya yang terbaring sakit. Setelah itu, baru Pemerintah Daerah Tasikmalaya membawanya ke RSUD.
Diagnosis dokter di rumah sakit menunjukkan Mak Eroh menderita darah tinggi. Tekanan darahnya mencapai 270/110.
“Saya sempat heran Mak Eroh masih tetap dapat bertahan hidup... biasanya sudah tidak akan tertolong lagi jika memiliki tensi di atas 200/100,” tutur seorang perawat, dikutip Kompas edisi 12 Juni 2003.
Beberapa kali ia selamat dari risiko jatuh dari tebing 17 meter, namun tubuhnya perlahan kalah oleh penyakit yang tak terawat karena kemiskinan.
Perjuangan perempuan perkasa itu akhirnya selesai. Pada Senin, 19 Oktober 2004, Mak Eroh mengembuskan napas terakhirnya di RS Jasa Kartini, Tasikmalaya. Ia wafat dalam usia 68 tahun akibat stroke. Ia dimakamkan di kampung halamannya, Pasirkadu, meninggalkan tiga putri dan sembilan cucu.
Ikon Mak Eroh diabadikan lewat sebuah tugu di alun-alun kota Tasikmalaya, berdampingan dengan Abdul Rozak, petani Tasikmalaya lainnya yang mendapat penghargaan Kalpataru pada 1987.
Mengutip Tempo terbitan 20 November 2004, beberapa pekan setelah kepergiannya, Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Bandung menggelar acara untuk mengenangnya. Di atas panggung, taburan bunga, asap kemenyan, ritual tahlil digelar seiring gesekan biola yang mengiris kalbu.
Seniman Ayi Kurnia Iskandar lantas membacakan puisi berjudul “Eroh”, yang menceritakan kembali perjuangan Mak Eroh, dari cemoohan perempuan gila hingga keberhasilannya membelah batu, meretas parit, dan mengalirkan air ke persawahan.
Ahung! Ahung!
Leungeun kaula leungeun nu magawé
Nu ngulangkeun iteuk
Nu mesat gobang
Nu meureut cikésang
Nu meulah batu
Nu muka jalan cinyusu
Malah mandar dunya robah
Manusa hirup reujeung huripna
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id