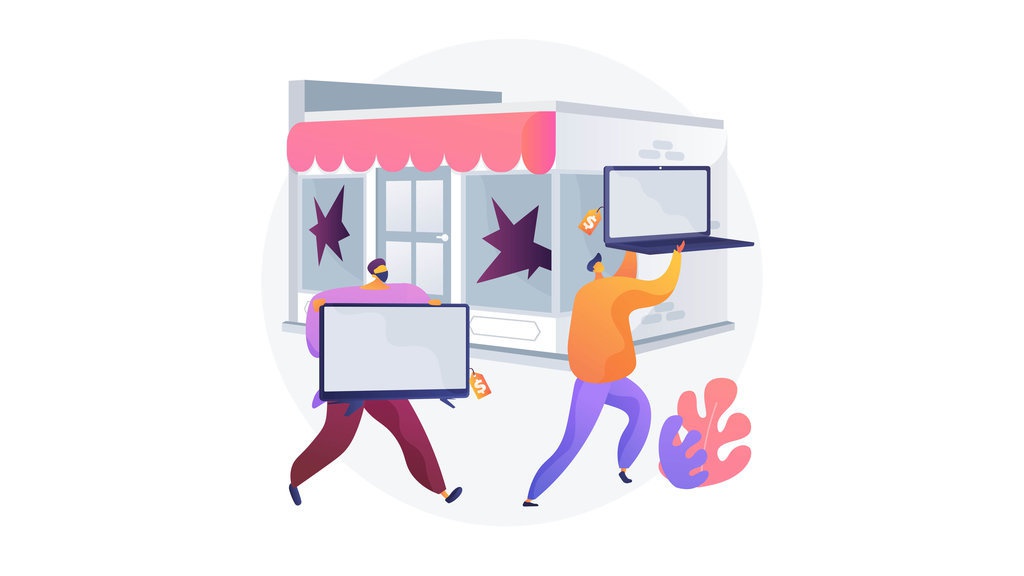tirto.id - Akhir Agustus lalu, gelombang penjarahan terjadi memperlihatkan babak baru dalam dinamika kekacauan politik Indonesia. Rumah-rumah milik pejabat negara, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, serta Sri Mulyani, menjadi sasaran amuk massa yang marah dan tak terkendali.
Mobil-mobil mewah dirusak, barang pribadi diangkut. Dalam beberapa kasus, bahkan ada warga yang berenang di kolam pribadi sambil meneriakkan kalimat yang lebih menyerupai satire sosial daripada sekadar ejekan.
Pemicu utamanya bukan hanya krisis ekonomi. Ia merupakan perwujudan akumulasi kekecewaan terhadap elit politik yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Pernyataan kontroversial, video joget di gedung DPR, dan isu kenaikan tunjangan, memantik kemarahan yang kemudian meluas.
Yang menarik, sebagian besar rumah dalam kondisi kosong saat penjarahan terjadi. Para pemiliknya tidak berada di lokasi, dan aparat keamanan kewalahan menghadapi massa yang datang dalam jumlah besar. Beberapa pelaku bahkan disebut berasal dari luar kota, menandakan adanya kemungkinan mobilisasi yang lebih terorganisasi.
Penjarahan, Simbol Kemenangan dan Penaklukan
Penjarahan bukanlah fenomena baru. Ia telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak peradaban pertama mulai mengenal batas wilayah dan hak milik. Di era Romawi, penjarahan adalah bagian dari ritual kemenangan.
Ketika pasukan Romawi menaklukkan wilayah baru, mereka tidak hanya mengambil harta benda, tetapi juga membawa pulang patung, manuskrip, dan simbol-simbol keagamaan dari kota-kota yang ditaklukkan.
Penjarahan pada masa itu bersifat performatif—dirayakan dalam prosesi “triumph”—sebagai bukti kejayaan kekaisaran. Contohnya, setelah menaklukkan Yerusalem pada tahun 70 M, Jenderal Titus membawa Menorah dan artefak dari Bait Suci ke Roma, yang kemudian diabadikan dalam relief di Arch of Titus.
Selama era kolonialisme, penjarahan berubah menjadi sistem yang dilembagakan. Bangsa-bangsa Eropa tidak hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga artefak budaya, manuskrip, bahkan termasuk mumi dari Mesir, patung dari India, dan benda-benda suci dari Afrika. Museum-museum besar di Inggris, Prancis, Jerman, Austria, dan Belanda, hingga kini menyimpan hasil penjarahan tersebut.
Penjarahan kolonial bukan hanya soal kekayaan, tapi juga penghapusan identitas dan penguasaan narasi sejarah.

Dalam konteks kerusuhan politik, penjarahan bisa menjadi cermin dari kemarahan kolektif. Contohnya di Amerika Serikat, penjarahan tak bisa dilepaskan dari denyut konflik rasial yang telah lama membara.
Kerusuhan Watts tahun 1965, Newark dan Detroit pada 1967, serta gelombang kemarahan setelah pembunuhan Martin Luther King Jr. pada 1968, semuanya menyisakan jejak penjarahan yang meluas.
Yang paling mengguncang adalah kerusuhan Los Angeles tahun 1992, ketika empat polisi kulit putih dibebaskan setelah terekam memukuli Rodney King. Dalam hitungan jam, kota berubah menjadi medan protes yang membara. Toko-toko dijarah, jalanan dipenuhi api, dan puluhan nyawa melayang.
Di Eropa, meski skalanya berbeda, ketegangan rasial juga memicu ledakan serupa. Kerusuhan London pada 2011, yang dipicu oleh penembakan terhadap Mark Duggan, seorang pria kulit hitam, berujung pada penjarahan toko-toko dan bentrokan di berbagai kota.
Di Prancis, kerusuhan di pinggiran kota Paris pada 2005, yang melibatkan komunitas imigran Afrika dan Arab, juga diwarnai oleh pembakaran dan penjarahan sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi dan marginalisasi.
Penjarahan tidak selalu tentang mengambil barang. Ia bisa menjadi bentuk reklamasi simbolik, penghukuman politik, atau penghapusan warisan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, penjarahan muncul sebagai respons spontan terhadap represi negara.
Namun, tak jarang pula di kasus lain, penjarahan dimanfaatkan secara sistematis oleh elite untuk mengalihkan kemarahan publik.
Menjarah Negara yang "Kosong"
Penjarahan kerap mengungkap keluhan utama masyarakat, mengekspos garis patahan dalam tatanan sosial, dan menandakan tantangan jangka panjang bagi tata kelola pasca-krisis. Anatomi penjarahan, pada dasarnya, adalah anatomi dari masyarakat yang menghasilkannya.
Penjarahan di Mesir pada 2011 memperlihatkan dua wajah penjarahan yang saling bertolak belakang, tetapi sama-sama mencerminkan luka dalam transisi pasca-revolusi.
Sebagai bagian dari gema Arab Spring, Revolusi Mesir menggulingkan rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga dekade. Protes besar-besaran pecah pada 25 Januari 2011—bertepatan dengan Hari Polisi Nasional—dipicu oleh kemarahan atas kekerasan aparat, korupsi, dan krisis ekonomi.
Awalnya, kemarahan massa tertuju pada simbol kekuasaan lama. Markas Partai Demokratik Nasional (NDP) dibakar, menandai runtuhnya rezim dan membuka jalan bagi gelombang penjarahan berikutnya.
Penjarahan berlangsung dalam berbagai bentuk. Di kota-kota besar, seperti Kairo dan Alexandria, geng-geng pemuda menjarah toko, bank, dan pusat perbelanjaan. Warga membentuk kelompok penjaga bersenjata untuk melindungi lingkungan mereka, termasuk di kawasan elit seperti Zamalek.
Namun, ada dugaan keterlibatan polisi berpakaian preman yang loyal pada Mubarak. Hal itu kemudian memperkuat kesan bahwa kekacauan itu sengaja diciptakan.
“Semua ini tampaknya telah diatur sebelumnya. Mereka menghukum kami karena meminta perubahan ini,” ujar Naglaa Mahmoud, dilansir oleh Al Jazeera.
Penjarahan, yang diduga didalangi aparat negara, tersebut juga menyasar Museum Mesir di Lapangan Tahrir. Mereka menghancurkan etalase-etalase kaca, dan merusak sejumlah artefak, termasuk dua mumi yang kepalanya dipenggal.
Namun, di tengah kekacauan, sekelompok demonstran membentuk rantai manusia untuk melindungi museum, menunjukkan benturan antara dorongan destruktif dan kesadaran akan warisan budaya.
Yang paling destruktif terjadi di situs-situs arkeologi. Penjarahan berlangsung dalam dua lapis.
Penduduk desa yang tinggal di dekat situs-situs kuno mulai melakukan penggalian liar, sebagian termotivasi oleh mitos tentang penemuan emas firaun. Mereka membuat ribuan galian besar di situs bersejarah, seperti Dahshur dan Lisht, hingga terlihat jelas dari citra satelit.
Adapun penjarahan lain dilakukan oleh geng kriminal bersenjata. Mereka membongkar makam dan kuil, lalu mengekspornya ke luar negeri. Penelitian dari University of Maryland menunjukkan, penjarahan barang antik semacam itu sering kali mendahului konflik bersenjata. Hal tersebut kemudian mengindikasikan adanya upaya yang terkoordinasi untuk mendanai kegiatan kriminal atau militan, bukan sekadar oportunistik.
Tak hanya itu. Setelah Mubarak jatuh, bentuk penjarahan lain muncul. Demonstran menyerbu kantor Intelijen Keamanan Negara (SSI), bukan untuk harta, tapi untuk dokumen. Mereka mengungkap praktik penyiksaan, pengawasan, dan korupsi rezim.
Di balik tembok gedung itu, seperti dilaporkan The Guardian, ditemukan bukti-bukti kelam dan kemewahan pejabat. Tindakan tersebut bukan penjarahan pragmatis, melainkan upaya merebut kembali kebenaran dan sejarah dari tangan para penindas. Alhasil, terekspos-lah kekayaan keluarga Mubarak dan kroni-kroninya yang mencapai 70 miliar dolar, tersebar di berbagai rekening luar negeri.
Pendudukan Simbolik sebagai Reklamasi Rakyat
Di Sri Lanka, penjarahan mengambil bentuk yang sangat berbeda. Krisis berpuncak dari salah urus ekonomi, korupsi sistemik, dan nepotisme yang mengakar di bawah dinasti Rajapaksa. Pemerintahannya membuat kebijakan fatal, yakni larangan penggunaan pupuk kimia pada April 2021. Tujuannya beralih ke pertanian organik, tapi dampaknya justru melumpuhkan produksi pangan, memicu kelangkaan, dan mempercepat inflasi.
Di saat yang sama, cadangan devisa negara habis. Pada April 2022, Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri. Hal itu kemudian membuat impor barang esensial, seperti bahan bakar dan obat-obatan, terhenti. Hidup sehari-hari menjadi sengsara: listrik padam berjam-jam, antrean bahan bakar mengular, dan dapur-dapur nyaris tak menyala.
Dari krisis itu, lahirlah Janatha Aragalaya (perjuangan rakyat), gerakan protes massa yang spontan, damai, dan lintas kelas sosial. Tanpa pemimpin tunggal, mereka bersatu dalam satu tuntutan: mundurnya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan perubahan sistem menyeluruh.
Dimulai dengan aksi menyalakan lilin pada Maret dan April 2022, protes berkembang menjadi demonstrasi besar. Pada 31 Maret, massa mencoba menyerbu rumah pribadi presiden, memicu bentrokan pertama.
Kekerasan terjadi lagi pada 9 Mei. Para pendukung pemerintah menyerang demonstran damai. Balasannya brutal: rumah dan properti anggota parlemen dibakar, memaksa Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mundur.
Puncaknya terjadi pada 9 Juli. Ratusan ribu orang berkumpul di Kolombo, ibu kota Sri Lanka, menembus barikade dan menduduki Istana Kepresidenan, Sekretariat, dan kediaman resmi Perdana Menteri.
Aksi tersebut melumpuhkan sisa-sisa kekuasaan rezim. Rakyat merebut simbol kekuasaan untuk menyingkap kegagalan moral rezim Rajapaksa. Mereka berswafoto, berenang di kolam renang, berolahraga di pusat kebugaran, serta bersantai di tempat tidur mewah; bukan untuk memiliki, tapi untuk menunjukkan bahwa kemewahan itu dibangun dari uang publik.
“Semua yang korup akan berakhir. Jadi, saya mendapat kesempatan datang bersama anak-anak saya dan makan siang di sini,” kata seorang pengunjuk rasa.
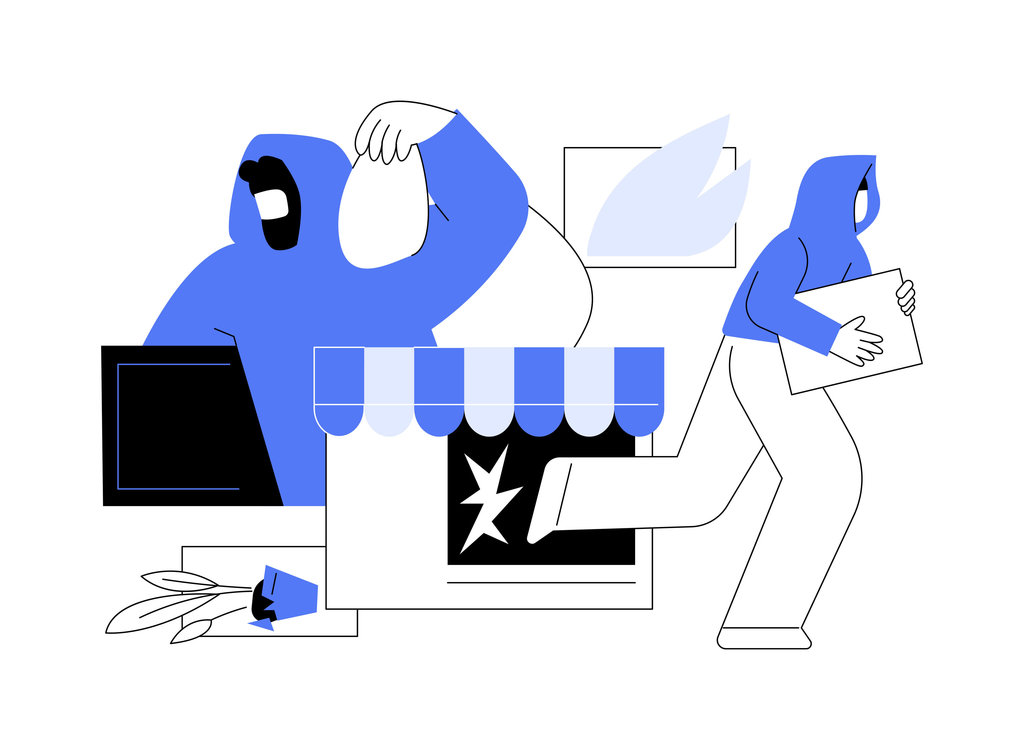
Tindakan para demonstran itu mempertontonkan bentuk “penjarahan sosial” yang tidak merebut benda secara pragmatis, melainkan gagasan tentang negara. Mereka tidak mencuri, tapi menegaskan bahwa ruang kekuasaan adalah milik rakyat.
Tekanan simbolik tersebut tak terbendung. Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri pada 13 Juli dan mengundurkan diri lewat kiriman surel sehari kemudian. Ia menjadi presiden pertama Sri Lanka pertama yang mundur di tengah masa jabatan.
Penjarahan Retributif sebagai Penghapusan Politik
Berbeda dari Sri Lanka, kekerasan di Bangladesh pasca-jatuhnya Sheikh Hasina pada Agustus 2024 merupakan penjarahan retributif. Ia menunjukkan bahwa represi ekstrem dapat melahirkan kekerasan balasan yang sama brutal.
Motifnya bukan simbolik atau ekonomi, melainkan penghukuman. Targetnya spesifik dan sarat makna politik: rumah para menteri yang terlibat dalam penumpasan, kantor partai, dan simbol dinasti penguasa seperti Museum Bangabandhu.
Krisis bermula dari gerakan mahasiswa yang menolak sistem kuota pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Respons brutal pemerintah memicu Pembantaian Juli yang, menurut laporan PBB, menewaskan 1.400 orang dalam 46 hari.
Kejatuhan Hasina memicu gelombang kekerasan balasan. Rumah para menteri dan pejabat partai dibakar, termasuk milik Menteri Hukum Anisul Haque, Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan, dan Menteri Negara Zunaid Ahmed Palak. Beberapa serangan berujung kematian (terperangkap dalam kobaran api).
Penjarahan tersebut bukanlah kekerasan biasa, melainkan penghukuman yang mematikan. Ketika hukum runtuh, massa memburu pejabat dan polisi yang terlibat dalam penumpasan. Pihak kepolisian setempat melaporkan, 44 petugas tewas dan tubuh-tubuh mereka digantung di tempat umum sebagai unjuk pembalasan yang mengerikan.
Puncak amuk terjadi pada Februari 2025. Dipicu pidato Hasina dari pengasingan, massa meratakan Museum Memorial Bangabandhu, bekas rumah ayah Hasina yang juga pendiri bangsa, Sheikh Mujibur Rahman. Bangunan itu disebut sebagai simbol fasisme yang harus dihapus total, menyiratkan penolakan radikal terhadap warisan politik dinasti.
Penjarahan yang Dimanipulasi dari Atas
Model penjarahan lain ditujukan saat Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Penjarahan dimanipulasi oleh struktur kekuasaan. Di tengah krisis ekonomi dan kemarahan publik terhadap Soeharto, penjarahan justru diarahkan ke etnis Tionghoa, bukan simbol negara. Toko dan rumah mereka dijarah dan dibakar, bukan sebagai ekspresi spontan, tapi sebagai alat politik.
Berbagai bukti, seperti kehadiran provokator terorganisir, sikap pasif aparat keamanan, dan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tentang perebutan kekuasaan elite, mengarah pada dugaan kuat adanya rekayasa. Banyak laporan saksi mata menyebutkan adanya sekelompok pria berbadan tegap yang datang dengan truk-truk, yang kemudian menghasut dan memulai pembakaran serta penjarahan.
Berbeda dari kasus Sri Lanka atau Bangladesh, kerusuhan di Indonesia menargetkan kelompok etnis yang rentan secara historis dan sosial.
Model pengambinghitaman ini punya dua fungsi: sebagai katup pelepas frustrasi massa, dan sebagai senjata dalam perebutan kekuasaan internal. Kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa menambah luka sosial yang mendalam. Soeharto akhirnya mundur, tapi trauma dan ketegangan antaretnis tetap membekas hingga kini.
Penjarahan bukan hanya soal benda yang hilang, tapi tentang siapa yang kehilangan kendali, siapa yang merebut ruang, dan siapa yang mengatur arah kemarahan. Memahami penjarahan berarti membaca ulang sejarah dari sudut yang lebih dalam—kekacauan bukan akhir, tapi cerminan dari perebutan makna dan kekuasaan.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id