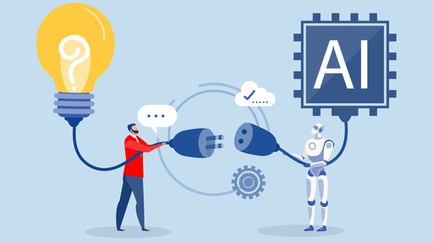tirto.id - Di negeri yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam, tambang kerap dicap sebagai jalan pintas menuju kesejahteraan. Argumennya, ketika tambang dibuka di satu wilayah, investasi akan mengalir, lapangan kerja tercipta, dan roda ekonomi lokal akan bergerak.
Para pendukung argumen itu menyematkan label kesejahteraan pada setiap kilau pertambangan, seolah-olah keberadaan tambang secara otomatis berdampak pada naiknya taraf hidup masyarakat. Namun, dalihnya tak pernah betul-betul menjawab masalah pangkalnya: masyarakat yang mana yang benar-benar diuntungkan?
Di Indonesia, narasi kesejahteraan yang melekat pada industri pertambangan bukan sekadar slogan pembangunan. Ia bahkan telah menjadi pijakan hukum nasional.
Salah satu manifestasinya terlihat dalam Undang-Undang No. 4 Th. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi itu menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan “untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.”
Frasa tersebut menempatkan pertambangan sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, sekaligus legitimasi moral bagi perluasan aktivitas tambang. Dalam kerangka pikir itu, setiap kebijakan tambang selalu dibingkai sebagai upaya menyejahterakan rakyat.
Padahal, justru pada titik inilah muncul pertanyaan: kesejahteraan seperti apa yang sebenarnya dihadirkan industri tambang? Apakah ia benar-benar hadir dalam wujud nyata dan terukur (das Sein), atau sekadar menjadi norma ideal yang terus diproduksi tanpa bukti empiris memadai (das Sollen)?
Pertanyaan-pertanyaan itu krusial diajukan untuk menakar sejauh mana kesejahteraan tambang layak dianggap sebagai fakta sosial, bukan mitos belaka.
Tambang, Untuk Siapa?
Dalam berbagai narasi, tambang kerap diposisikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan. Narasi ini digaungkan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan tambang yang menjanjikan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Namun, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan hasil sebaliknya. Lihat misalnya dalam studi kasus di tiga lokasi tambang emas di Burkina Faso, Afrika Barat. Penelitian International Journal of Environmental Research and Public Healthitu mengungkapkan fakta kesenjangan tajam antara klaim korporasi dan pengalaman masyarakat lokal.
Selama ini, para pejabat pendukung tambang melaporkan dampak positif aktivitas ekstraktif terhadap ekonomi dan kesejahteraan. Namun, para ahli dan tenaga kesehatan menyuarakan hal sebaliknya: peningkatan penyakit, pencemaran lingkungan, serta terganggunya sistem sosial-ekologis yang menopang kehidupan sehari-hari.
Alih-alih memperoleh taraf hidup lebih baik, temuan di atas justru menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dijanjikan berbalik menjadi penderitaan.
Di sisi lain, industri pertambangan kerap menggemborkan narasi penciptaan lapangan kerja sebagai bentuk kompensasi, sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Namun, manfaat tersebut sering kali bersifat sementara, serta tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang ditimbulkan.
Studi European Economic Review juga mengamini hal tersebut, bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam justru lebih lambat dibanding negara-negara miskin sumber daya. Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner menyebut fenomena ini sebagai "kutukan sumber daya alam".
Melalui studi empiris dan menyeluruh, para peneliti itu menyimpulkan, negara-negara yang kaya sumber daya telah mengalami stagnansi pertumbuhan ekonomi sejak awal 1970-an. Bahkan, dalam catatan kesimpulan studi tersebut tertulis frasa penegasan: "hampir tanpa terkecuali".
Sachs dan Warner juga membuktikan bahwa negara-negara penghasil sumber daya alam cenderung memunyai harga domestik yang tinggi. Impaknya, mereka gagal mencapai pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor, kecuali kontribusi langsung dari bahan mentah sektor sumber daya alam itu sendiri.

Artikel penelitian lain bertajuk “The Local Economic Impact of Mineral Mining in Africa: Evidence from Four Decades of Satellite Imagery” menguatkan pernyataan bahwa manfaat sektor tambang hanya bersifat sementara. Studi yang terbit di jurnal General Economics itu mengungkap dinamika ekonomi jangka panjang dari industri pertambangan di Afrika, berdasarkan analisis terhadap 1.658 lokasi tambang dari tahun 1984 hingga 2019.
Hasil penelitian Sandro Provenzano dan Hannah Bull tersebut menunjukkan, pada awal tambang dibuka, terjadi ekspansi pesat dalam radius 20 kilometer. Pertumbuhan itu mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi hingga dua kali lipat.
Namun, euforia pertumbuhan tersebut terbukti tidak bertahan lama. Setelah tambang memasuki fase penutupan, 15 tahun kemudian, geliat ekonomi lokal mulai meredup. Banyak wilayah justru mengalami kemunduran ekonomi signifikan. Pola ini menunjukkan, lonjakan ekonomi yang dipicu tambang hanya bersifat sementara dan tidak berakar kuat dalam struktur ekonomi lokal.
Dengan demikian, meskipun tambang kerap digadang-gadang sebagai motor pembangunan, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa keuntungannya tidak berkelanjutan.
Dampak pertambangan tidak hanya terbatas pada manfaat ekonomi yang sementara, tetapi juga menciptakan konsekuensi ekologis jangka panjang.
Bukannya menghadirkan keberlanjutan, aktivitas tambang justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan berkepanjangan. Hal tersebut diperkuat oleh studi dalam Resources Policy yang mengkaji dampak jangka panjang pertambangan batu bara di Bowen Basin, Queensland, Australia, selama periode 31 tahun.
Penelitian yang digarap oleh Jeremy De Valck dan kolega tersebut membandingkan tiga skenario penggunaan lahan, yaitu penggunaan lahan untuk penambangan batu bara, penggembalaan, dan konservasi alam.
Hasilnya menunjukkan bahwa secara ekonomi langsung, pertambangan memang memberikan keuntungan jauh lebih besar, bahkan 10 hingga 14 kali lipat dibandingkan penggembalaan. Namun, ketika faktor eksternal negatif, seperti polusi, dampak kesehatan, dan kerusakan sosial, turut diperhitungkan, nilai ekonomi bersih dari tambang justru berubah drastis menjadi kerugian. Sementara itu, skenario penggembalaan dan konservasi tetap menghasilkan nilai positif.
Temuan itu menegaskan bahwa keuntungan dari pertambangan bersifat sementara. Pembingkaian keuntungan tambang menjadi menyesatkan apabila tidak disertai perhitungan atas biaya sosial dan ekologisnya.
Rakyat Sebagai "Antagonis" dalam Narasi Pertambangan
Konsep pembangunan tambang sering kali menawarkan iming-iming keuntungan masa depan. Padahal, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak, kekhawatiran justru tertuju pada momen itu juga. Salah satu kekhawatiran terbesarnya adalah kemungkinan kehilangan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Masa depan yang dijanjikan tampak abstrak, sementara ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka ada di depan mata.
Oleh karena itu, wacana pembangunan pertambangan, kerap berhadapan dengan penolakan masyarakat. Penentangan itu khususnya datang dari sekelompok masyarakat yang ruang hidupnya terdampak langsung oleh proyek pertambangan.

Mirisnya, ketidaksetujuan itu justru dipersepsikan seolah-olah sebagai bentuk perlawanan terhadap kepentingan negara dan kesejahteraan nasional. Masyarakat, terutama yang menolak tambang, diposisikan sebagai "aktor antagonis" yang menghambat pembangunan. Tidak hanya itu, protes rakyat terhadap tambang bahkan disebut mengurangi masuknya investasi asing.
Padahal, penolakan masyarakat tidak lahir tanpa dasar. Di balik sikap kritis warga, tersimpan pergulatan batin kompleks. Misalnya, bagi sebagian warga, terutama petani, tambang memang menghadirkan harapan. Namun, di sisi lain, harapan itu kerap dibayangi kekhawatiran karena sifatnya yang sementara.
Tambang memang membawa janji soal fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lapangan kerja. Akan tetapi, warga juga tahu betul bahwa di balik semua itu ada harga yang harus dibayar.
“Isu pertambangan sangat kompleks, di satu sisi memang ada manfaatnya, tapi secara keseluruhan mereka juga menghancurkan kami. Kami bisa mendapatkan banyak hal dari tambang, tapi kerugian terbesarnya adalah keluarga kami yang menjadi korban,” dikutip dari salah satu narasumber dalam studi yang terbit di Ecology & Society.
Di titik inilah, tampak jelas bahwa masyarakat bukanlah ekspresi anti-pembangunan. Justru, ia adalah respons kritis atas model pembangunan yang mengorbankan kehidupan dan masa depan komunitas. Maka dari itu, menyederhanakan kritik sebagai hambatan pembangunan adalah bentuk pengabaian terhadap realitas sosial.
Lalu, benarkah pertambangan merupakan jalan menuju kesejahteraan? Atau, justru klaim tersebut hanya angan-angan normatif alias das Sollen yang diproduksi dan direproduksi oleh negara dan pasar, tanpa jaminan realisasinya dalam kenyataan empiris?
Penulis: D'ajeng Rahma Kartika
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id