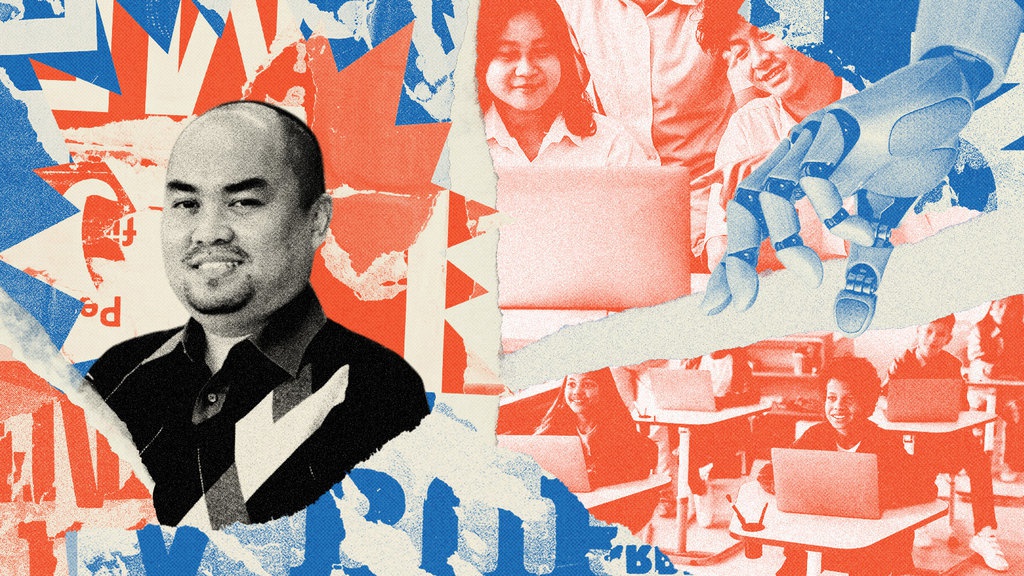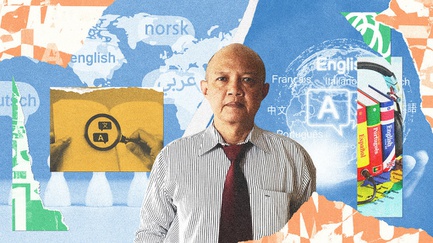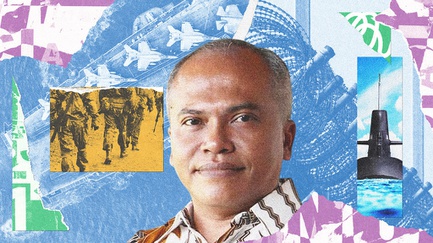tirto.id - Langkah pemerintah yang akan mengintegrasikan akal imitasi (AI) dan coding ke dalam kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2025 mencerminkan ambisi besar Indonesia memasuki era digital. Visi ini terlihat baik, yaitu untuk mempersiapkan generasi muda dengan kompetensi digital esensial untuk bersaing di panggung global yang kian terdigitalisasi.
Berdasarkan naskah akademik yang sudah dibuat, kurikulum AI mencakup pengenalan konsep dasar kecerdasan artifisial, pemahaman etika teknologi, hingga penerapan praktis seperti pemrograman berbasis teks dan aplikasi kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita juga harus realistis, di balik optimisme tersebut, terbentang jurang kesenjangan digital yang menganga.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan skor rata-rata nasional 43,34, masih dalam kategori "sedang" untuk kesiapan digital. Yang lebih mengkhawatirkan, dari 38 provinsi, hanya lima yang dikategorikan memiliki kapabilitas digital tinggi: Jakarta (50,50), Bali (49,05), Kepulauan Bangka Belitung (47,61), Jawa Tengah (47,42), dan Yogyakarta (47,10). Wilayah Papua masih terpuruk di kategori "rendah".
Pertanyaan mendesak kemudian muncul: apakah kurikulum AI akan menjembatani kesenjangan pendidikan ataukah justru memperdalam jurang digital yang telah ada? Tanpa strategi implementasi yang hati-hati dan inklusif, ada risiko nyata bahwa AI akan menjadi privilese baru yang hanya dinikmati segelintir kalangan.
Realitas Kesenjangan yang Menganga
Potret kesenjangan digital Indonesia tidak hanya tercermin dalam infrastruktur, tetapi juga dalam akses dan literasi. Data menunjukkan bahwa meskipun 79,5 persen populasi Indonesia telah mengakses internet, hanya 30,5 persen pengguna berasal dari wilayah pedesaan. Ini menciptakan disparitas akses yang signifikan, terutama mengingat mayoritas sekolah tersebar di pelosok negeri, termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang masih bergulat dengan keterbatasan listrik, apalagi koneksi internet stabil.
Secara global, laporan International Telecommunication Union (ITU) 2024 mencatat bahwa 93 persen individu dari kelompok berpenghasilan tinggi memiliki akses internet, dibandingkan hanya 27 persen dari kelompok berpenghasilan rendah. Indonesia sendiri berada di peringkat ketujuh dari sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dalam Indeks Internet Inklusif, dengan penilaian moderat untuk ketersediaan, keterjangkauan, relevansi, dan kesiapan infrastruktur digital.
Aspek literasi digital menambah kompleksitas masalah. IMDI menunjukkan bahwa hanya 48,1 persen penduduk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan 39,2 persen memeriksa kredibilitas sumber digital . Mayoritas pengguna internet Indonesia (84,5 persen) hanya menggunakan platform untuk pesan instan dan media sosial, mencerminkan literasi digital yang dangkal. Fenomena ini akan menjadi tantangan besar ketika AI, khususnya model generatif yang rentan menghasilkan informasi keliru, diintegrasikan ke dalam pembelajaran.
Lebih jauh, ketimpangan ini tidak hanya teknis tetapi juga sosial. Kelompok berpenghasilan rendah dan perempuan semakin termarginalkan dalam akses ke informasi dan peluang digital. Jika kurikulum AI hanya diterapkan di sekolah dengan infrastruktur memadai, maka prinsip keadilan dalam pendidikan akan tercederai. Anak-anak di daerah kurang beruntung akan semakin tertinggal, bukan karena potensi mereka, melainkan karena ketiadaan akses.
AI: Jembatan atau Jurang Baru?
Paradoksnya, AI yang sering dipandang sebagai teknologi elit justru memiliki potensi demokratisasi pendidikan yang luar biasa. Salman Khan dalam bukunya "Brave New Words" menyebut AI dapat menciptakan global classroom di mana batasan geografis tidak lagi menentukan kualitas pendidikan. AI tutor seperti Khanmigo dapat memberikan pembelajaran personal yang selama ini hanya tersedia bagi kalangan mampu. Ini bisa membantu siswa di daerah terpencil yang kekurangan guru berkualitas.
Dalam konteks Indonesia, AI dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Sistem AI dapat memberikan dukungan pembelajaran 24/7, menyesuaikan kecepatan belajar setiap siswa, bahkan menerjemahkan materi ke dalam bahasa daerah. Konsep co-intelligence yang dipaparkan Ethan Mollick menunjukkan bagaimana kolaborasi manusia-AI dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas, asalkan manusia tetap menjadi pengambil keputusan kritis.

Pendekatan coding unplugged juga menawarkan harapan. Metode ini mengajarkan prinsip-prinsip komputasi tanpa ketergantungan pada perangkat digital, cocok untuk daerah dengan infrastruktur terbatas. Siswa dapat belajar algoritma melalui permainan tradisional seperti Gobak Sodor atau menyusun langkah-langkah masak gudeg, membangun fondasi kognitif sebelum berinteraksi dengan teknologi digital.
Namun, tanpa strategi implementasi yang tepat, kurikulum AI justru dapat memperdalam kesenjangan. Sekolah-sekolah di kota besar dengan infrastruktur memadai akan mampu mengimplementasikan pembelajaran AI secara optimal, sementara sekolah di daerah terpencil akan semakin tertinggal. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan AI, di mana kemampuan berkolaborasi dengan AI menjadi faktor penentu kesuksesan masa depan, sebagaimana dikhawatirkan Matt Beane dalam "The Skill Code" tentang "kesenjangan keterampilan."
Strategi Menuju Pendidikan AI yang Inklusif
Agar AI tidak menjadi menara gading baru yang memperkokoh eksklusi, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang komprehensif. Pertama, investasi masif dalam infrastruktur digital harus diprioritaskan. Program seperti Palapa Ring perlu diperluas untuk memastikan konektivitas internet yang stabil hingga pelosok negeri, disertai penyediaan listrik melalui energi terbarukan di wilayah terpencil.
Kedua, adopsi pendekatan bertahap dan kontekstual, mengikuti pengalaman sukses Singapura dan Cina. Untuk jenjang SD, fokus pada pemikiran komputasional melalui permainan eksploratif tanpa komputer. Di SMP, siswa dapat diperkenalkan dengan platform visual seperti Scratch, sementara di SMA mereka mulai belajar pemrograman sederhana dan etika AI. Pendekatan ini memastikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan kognitif dan tidak membebani siswa.
Ketiga, AI sebaiknya diposisikan sebagai program pengayaan ekstrakurikuler, bukan mata pelajaran wajib, sebagaimana direkomendasikan KPAI. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas penyesuaian dengan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan spesifik setiap daerah. AI juga dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti menggunakan analisis data untuk memahami pola cuaca dalam pelajaran geografi.
Keempat, pelatihan guru komprehensif menjadi kunci sukses. Program pelatihan tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pemahaman pedagogis tentang cara mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Kolaborasi dengan universitas dan industri teknologi dapat menciptakan program sertifikasi guru AI yang berkelanjutan. Sebagaimana ditekankan José Antonio Bowen dan C. Edward Watson dalam "Teaching with AI," guru perlu bereksperimen dengan AI untuk memahami kapabilitas dan batasannya.
Kelima, kurikulum harus menekankan pemahaman konseptual, etika, dan keterampilan abad 21. Pembelajaran AI tidak boleh terjebak pada aspek teknis semata. Siswa perlu memahami logika AI, model bisnis teknologi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi data. Yang tidak kalah penting, diskusi tentang etika AI, termasuk privasi data, bias algoritmik, dan dampak sosial, harus menjadi bagian integral kurikulum.
Terakhir, kolaborasi multipihak dengan melibatkan industri teknologi, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dapat memperkaya implementasi. Perusahaan teknologi dapat menyediakan platform gratis untuk sekolah, sementara universitas dapat mengirim mahasiswa untuk program mengajar di daerah terpencil.
Kurikulum AI Indonesia memiliki potensi transformatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah mengimplementasikan strategi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan matang dan komitmen pada pemerataan, AI dapat menjadi jembatan menuju pendidikan yang setara, mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga berpikir kritis, adaptif, dan beretika. Indonesia berpeluang membangun generasi yang tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi pencipta dan pengelola teknologi AI untuk kemaslahatan bersama.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id