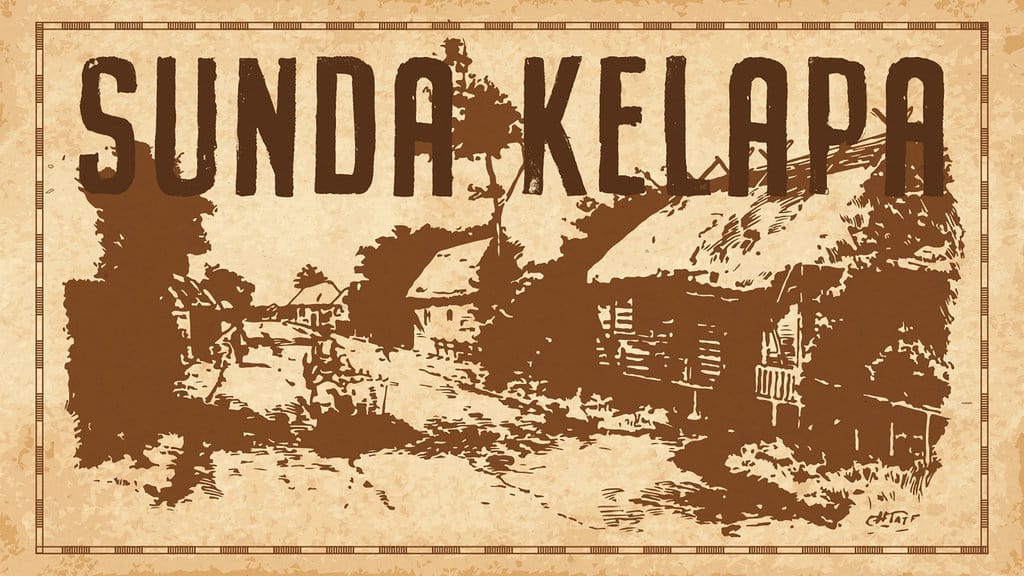tirto.id - Hari jadi Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni merupakan bentuk refleksi para sejarawan terhadap peristiwa besar di abad ke-16, yakni perubahan nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta saat armada Portugis diusir oleh koalisi Kerajaan Demak dan Cirebon.
Sebagaimana disampaikan Heru Erwantoro dalam “Hari Jadi Kota Jakarta” (2009) di Jurnal Patanjala edisi September 2009, pemilihan tanggal tersebut sebagai hari jadi Jakarta dilakukan oleh Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja pada 23 Februari 1956 atas rekomendasi dari Prof. Sukanto.
Berdasarkan teori Sukanto, Sunda Kalapa berhasil direbut oleh aliansi Demak-Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (kadang disebut Paletehan atau Wong Agung Pase) pada Februari 1527. Menurutnya, ketika Portugis berhasil diusir, Fatahillah tidak langsung mengubah nama kota taklukannya itu.
Terlepas bahwa teori Sukanto ini mengalami penolakan, utamanya dari Husein Djajadiningrat dan Slamet Muljana, sebenarnya apabila diperhatikan ada satu paradoks yang mungkin bisa dikemukakan.
Pertama, di satu sisi Sukanto memilih untuk menggunakan penanggalan tradisi agrikultur Sunda dalam memperkirakan “tanggal penting” saat Fatahillah mengubah nama kota taklukannya. Kedua, di sisi yang lain narasi penetapan hari jadi Jakarta seakan-akan menutupi jejak warisan budaya Sunda di Kota Betawi itu, dengan memilih tanggal lepasnya Sunda Kelapa dari pangkuan induknya Kerajaan Sunda.
Padahal, periode “Jakarta sebelum Jayakarta” sebenarnya kaya akan hal menarik, baik dari yang dijelaskan dalam teks-teks Sunda Kuno maupun tinggalan-tinggalan arkeologis bercorak kasundaan yang ditemukan di daerah itu. Wajah inilah yang kira-kira hilang dalam pandangan orang Jakarta hari ini, dan mungkin asing untuk dikenali.
Kalapa tanpa Sunda
Nama “Sunda Kalapa” yang selama ini populer di kalangan awam, sebenarnya memiliki kesan yang agak berbeda apabila dibandingkan dengan nama yang muncul di teks-teks Sunda Kuno. Dalam teks-teks berbahasa Sunda Kuno, seperti dalam Carita Parahyangan yang edisinya dibuat S. Danasasmita dan Atja (1981), misalnya, senantiasa disebut sebagai “Kalapa”, tanpa “Sunda”.
Di kalangan masyarakat Sunda Kuno, Kalapa saat itu dikenal sebagai pelabuhan besar yang paling dekat dengan ibu kota mereka, yakni Pakwan Pajajaran atau sekitar selatan Kota Bogor sekarang. Hal ini membuat posisinya sangat penting, sehingga di sepanjang jalur di antara dua tempat itu tercatat beberapa permukiman atau fasilitas penting di masanya.
Bujangga Manik, misalnya, seorang pangeran Sunda yang catatan perjalanannya pernah ditranskripkan dalam trilogi Tiga Pesona Sunda Kuna (2009) oleh J. Noorduyn dan A. Teeuw, secara detail menyebut beberapa toponim Jakarta Kuno.
Disebutkan bahwa ketika ia hendak pulang dari perjalanan pertamanya, sang tohaan yang juga dikenal sebagai Ameng Layaran ini berlayar dari Pamalang (Pemalang sekarang) ke Kalapa. Ketika mendarat di Kalapa, Bujangga Manik menyebut bahwa ia terlebih dahulu melewati pabean—yang mungkin fungsinya sama dengan bea cukai saat ini.
Kata “Pabean” dalam naskah ini disebutkan berdekatan dengan Ancol Tamiang (mungkin daerah Ancol sekarang). Artinya, jika diasumsikan pusat Kalapa terletak di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa sekarang, maka ia berjalan ke arah timur ke arah Ancol dan terus ke selatan.
Di perjalananya ke selatan itulah Bujangga Manik menyebut keberadaan leuweung langgong—hutan yang luas. Di sini bisa diasumsikan, bahwa sebagian Jakarta (mungkin sekitar Jakarta Pusat dan Selatan) adalah daerah yang jarang permukiman.
Mengenai Pelabuhan Kalapa, Tome Pires yang hidup di abad ke-16, menulis banyak hal dalam catatannya yang berjudul Suma Oriental. Mengutip tulisan Armando Cortesao (1944) yang menerjemahkan karya Tome Pires itu ke dalam bahasa Inggris, disebutkan Calapa (Kalapa) merupakan pelabuhan yang ramai oleh pedagang-pedagang Melayu dari Sumatra dan Semenanjung Melayu, juga sebagian lain dari Jawa dan Bugis.
Komoditas dagang yang diidam-idamkan dari Pelabuhan Kalapa saat itu adalah lada Sunda yang kualitasnya konon salah satu yang terbaik. Mereka biasa menyandarkan kapal-kapalnya di sekitar muara Sungai Ciliwung yang lebar.
Pemujaan Siwa di Kalapa
Dari segi tinggalan arkeologis, daerah Kalapa juga memiliki rentetan potensi artefak yang menarik. Seperti dilaporkan dalam Penelusuran Sejarah Peradaban Jakarta oleh Susanto Zuhdi dkk. (2018), di pinggiran Jakarta Selatan ditemukan berbagai konsentrasi temuan alat kehidupan sehari-hari seperti wadah berbahan keramik, perhiasan, dan alat batu.
Temuan-temuan tersebut menurut Zuhdi dkk. belum termasuk temuan arca-arca yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Arca yang paling awal ditemukan di Jakarta adalah Arca Kali. Arca ini ditemukan di timur Pelabuhan Tanjung Priok. Dari segi ikonografis, Arca Dewi Kali atau sakti (pasangan) Dewa Siwa dalam bentuk ganas (krodha) ini sangat jarang ditemukan di Jawa. Penggambarannya amat menyeramkan, karena dirupakan memiliki rambut jabrik, berkalungkan tengkorak, dan bertaring.
Selain arca menyeramkan tersebut, arca lainnya kebanyakan ditemukan di wilayah selatan. Temuan arca paling awal di Jakarta Selatan adalah Arca Siwa Rajaresi dari daerah aliran Sungai Ciliwung, di Tanjung Barat. Arca ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan Arca Kali dari Tanjung Priok. Namun demikian, atribut arca tersebut terkesan lebih kaya, lantaran sang dewa pelebur dalam Agama Hindu itu digambarkan duduk di singgasana teratai dengan dinaungi payung.
Berdasarkan temuan-temuan arca yang telah diuraikan, tampaknya pada masa Kerajaan Sunda terdapat sekelompok pemeluk agama Hindu Saiwa di Kalapa. Sebab, seluruh arca yang ditemukan di Jakarta hingga hari ini memiliki asosiasi dengan Dewa Siwa, terutama Arca Kali Tanjung Priok. Mungkin dahulu eksis pula pemeluk ajaran Tantrayana di Kalapa, sebab pemujaan terhadap Dewi Kali biasanya berasosiasi dengan aliran tersebut.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id