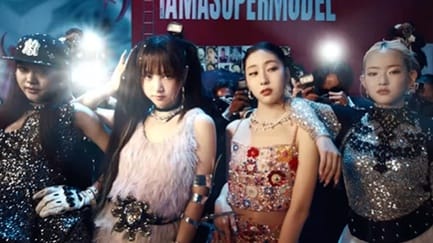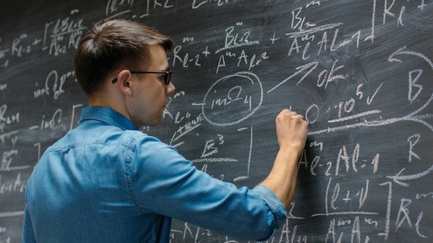tirto.id - Ketika menghadapi "ancaman", baik dari dalam maupun luar, aparatur negara acapkali meresponsnya dengan dua macam pendekatan: akomodasi atau represi. Namun, rasionalisasi kedua opsi itu sering bertubrukan, tergantung seberapa besar biaya dan manfaatnya.
Sering kali, represi terbukti lebih murah dibandingkan akomodasi. Pendekatan akomodasi dianggap menyita banyak anggaran negara, juga tak efektif mengentaskan konflik dalam tempo singkat nan mendesak.
Diskursus tersebut, lewat pengalaman empiris Christian Davenport yang tertulis dalam State Repression and the Domestic Democratic Peace (2007), disebut sebagai Law of Coercive Responsiveness atau Hukum Responsivitas Koersif. Hukum ini menjelaskan hubungan antara rasionalisasi kekuatan negara dan kecenderungan opsi pendekatannya yang relatif menyukai represi.
Meski negara menilai efisiensi biaya sebagai faktor utama memilih pendekatan represi, ada pertimbangan lain yang tak bisa diabaikan. Steven C. Poe dalam “The Decision to Repress: An Integrative Theoretical Approach to the Research on Human Rights and Repression” (2004: 26) menulis, negara harus bersedia melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta siap bertanggung jawab sebagai pihak yang menjadi pelaku kekerasan tersebut.
Dengan segala kemudahan akses, negara dapat dengan leluasa mengotak-atik birokrasi, hukum, dan mengendalikan aparat keamanan negara. Dengan begitu, pendekatan represi yang berkonotasi mengerikan itu justru membuat negara merasa nyaman. Walhasil, terciptalah hubungan kausalitas. Negara, lewat moda represi, makin ringan tangan menggampangkan kekerasan, pengekangan, dan penekanan yang menindas.
Demi menyukseskannya, negara mengatur hukum untuk memudahkan pendekatan koersif dalam melancarkan kebijakan. Karena itu, mereka membentuk aparat "keamanan" untuk menyokong represi negara dengan kuasa atas koersi yang “legal”. Dalam praksisnya menghadapi "ancaman", aparat yang paling tepat ditunjuk sebagai perpanjangan tangan negara adalah polisi.
Militerisasi Polisi: Menindas Masyarakat, Melayani Aparat
Sebagai lembaga yang mengantongi mandataris pemerintah, represi menjelma bentuk ambivalensi terhadap dua tugas utama polisi: menjamin keamanan masyarakat atau melindungi pemerintah dari ancaman yang menggoyahkan kekuasaan. Klimaksnya, ketika terjadi konflik antara masyarakat vis-à-vis pemerintah, polisi dituntut menghamba salah satu kubu.
Yang tampak selama ini, polisi kerap mengekor pemerintah dan/atau swasta. Karenanya, masyarakatlah yang acap jadi korban kekerasan aparat. Hal ini mengerucutkan pandangan yang skeptis terhadap polisi: apakah kewenangan merepresi merupakan representasi atas militansi perlindungan terhadap pemerintah?
Polisi merupakan aktor institusional buatan yang berkapasitas koersif sekaligus represif, tetapi memegang surat kuasa sah untuk menggunakan kekerasan dengan dalih “menjaga keselamatan publik”. Namun, sejauh mana agensi ini bertindak akan sangat bergantung pada kredibilitasnya, yang pada akhirnya turut menentukan keberhasilan kebijakan aparatur negara sebagai pengendali utama tindakan represi.
Sebuah analisis menarik dilontarkan Martin Stavro dan Ryan Welch dalam “Does Police Militarization Increase Repression?” (2023). Melalui studi itu, mereka memperoleh kesimpulan bahwa peningkatan militerisasi polisi berbanding lurus dengan peningkatan represi terhadap masyarakat. Militerisasi polisi adalah keadaan ketika polisi menerima perlengkapan militer, mengorganisasi diri dengan struktur ala militer, dan mengadopsi budaya militeristik.
Dampaknya sungguh dahsyat. Militerisasi polisi menimbulkan pergeseran pola pikir dalam tabiat polisi, menganggap dirinya tengah berperang melawan musuh negara yang sebenarnya adalah masyarakat sipil. Stavro dan Welch menyebutnya sebagai peningkatan persepsi terhadap ancaman.
Fenomena itu memicu dimensi yang kacau balau. Bahkan, tak jarang polisi yang represif justru dianggap layaknya “pahlawan negara” karena telah menghalau "ancaman".
Lihat misalnya militerisasi polisi yang diwartakan Reuterspada 14 Juni 2020, ketika para demonstran melakukan aksi damai di Place de la République, Paris, mengecam brutalitas polisi setelah kematian George Floyd. Polisi menilai unjuk rasa tersebut tidak sah lantaran tak mengantongi izin keamanan. Walhasil, polisi antihuru-hara dikirim untuk membubarkan para pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai justru mendadak menjadi bentrokan membabi buta antara polisi dan masyarakat.

Masalahnya, polisi yang dimiliterisasi akan merasa dirinya sebagai maniak dan sanggup merepresi karena negara menyediakan instrumen pendukungnya. Hal itu selaras dengan analogi yang dituturkan oleh Abraham Maslow dalam The Psychology of Science: A Reconnaissance (1969: 13), “Jika satu-satunya alat yang Anda [aparatur negara -red] miliki adalah palu, mereka [polisi -red] tergoda untuk memperlakukan semuanya seolah-olah itu adalah paku.”
Ketika negara menawarkan kendaraan taktis (rantis) antisergap, antiranjau, serta peluncur granat, kepada polisi, muncul penafsiran bahwa instrumen ini memang sengaja disiapkan untuk tujuan represi. Lagi pula, jika negara tidak bermaksud memberikan instrumen militer kepada polisi dengan maksud merepresi masyarakat, mengapa pengadaan alutsista ini dianggarkan masif, ambisius, dan terus diperbarui?
Dalam studi bertajuk “Does Police Militarization Affect Civilian Deaths?”, Brent S. Echols menyajikan contoh nyata praktik militerisasi polisi yang masif. The Law Enforcement Support Office (LESO), sebuah divisi di bawah United States Department of Defense (DoD), disebut bertanggung jawab atas operasi 1033 Program. Program itu merupakan bentuk upaya memiliterisasi polisi lewat pengadaan berbagai peranti militer ke departemen kepolisian negara.
Jumlah senjata mematikan yang dipasok oleh DoD sangat mengejutkan. Lebih dari 600 Mine-Resistant Ambush Protected vehicles (MRAPs) dan 79.000 assault rifles ditransfer ke DoD negara bagian dan lokal AS dalam kurun 2006-2014. Bahkan, seturut laporan situs web resmi Defense Logistics LESO, rata-rata pengeluaran tahunan 1033 Program untuk satu petugas polisi saja memakan biaya 834,85 dolar AS.
Tak mau kalah, Kepolisian Venezuela juga pernah memboyong alutsista militer dari perusahaan Norinco, salah satu produsen alat tempur terbesar milik pemerintah China. Hasil investigasi The New York Times pada 2017 melaporkan, pemerintah negara tersebut membeli kendaraan berlapis baja tebal, dilengkapi meriam air bertenaga tinggi, lengkap dengan pelontar gas air mata berkaliber 64 mm/38 mm.
Itu hanya sebagian kecil temuan di belahan bumi lain, tapi sudah cukup menunjukkan bahwa aparat telah memberi lampu hijau kepada militerisasi polisi agar mereka makin otoriter melayani kekuasaan yang represif.
Skeptisisme Profesionalitas Kerja Militerisasi Polisi
Tentu saja, pengadaan alutsista yang lebih canggih merupakan wujud perkembangan teknologi dan modernisasi. Namun justru karenanya, polisi (seharusnya) wajib memikul tanggung jawab anyar. Perolehan persenjataan militer menuntut kepolisian membina personelnya dengan tingkatan profesionalitas lebih tinggi. Masalahnya, skema pelatihan militerisasi dalam badan kepolisian negara sangat kurang.
“Ketika militer tidak terlibat dalam pertempuran aktif, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan agar senantiasa siap siaga tempur. Namun, polisi tidak memiliki ‘waktu senggang’ yang diubah menjadi pelatihan. Mereka melakukan patroli aktif hampir sepanjang waktu,” tulis Martin Stavro dan Ryan Welch (hlm. 10).
Hal yang dilakukan Kepolisian Toronto, AS, misalnya, dengan mengerahkan long-range acoustical device (LRAD) selama protes G20, adalah bentuk malapraktik serius. Penggunaan LRAD sebagai basis pengendalian massa justru mendatangkan efek samping—tidak hanya bagi demonstran, tetapi juga polisi—mual, sakit perut, muntah, kehilangan pendengaran, dan bahkan menyebabkan tulang dan sendi bergeser.
Veronica Kitchen dan Kim Rygiel, dalam “Privatizing Security, Securitizing Policing: The Case of the G20 in Toronto, Canada” (2014: 209), menyampaikan bahwa pada mulanya, LRAD adalah perangkat militer khusus yang digunakan tentara AS untuk bertempur melawan perompak Somalia dan pemberontak Irak yang merangsek masuk ke gudang senjata departemen Kepolisian Kanada. Sementara tentara militer memerlukan pelatihan LRAD dengan alokasi waktu mencapai ratusan dan bahkan ribuan jam kerja, Kepolisian Toronto hanya mendapat pelatihan wajib yang terdiri dari satu dari enam tema dalam modul yang memakan waktu tidak lebih dari 2,5 jam.
Cacat prosedural kepelatihan militer disorot Amnesty International sebagai faktor penyebab pelanggaran polisi di Brasil, yang menyalahgunakan senjata militer di daerah perkotaan. Bahkan tak jarang, demi mendayagunakan waktu pelatihan yang nyaris nihil, alutsista militer sengaja diuji coba tanpa persiapan oleh polisi, dengan menjadikan masyarakat sebagai samsak.
“Mengapa harus memberikan surat perintah penangkapan kepada pengedar narkoba dengan senjata kaliber 38 mm? Dengan baju besi lengkap, senjata yang tepat, dan pelatihan, Anda bisa semena-mena dan bersenang-senang,” dikutip dari pengakuan salah seorang narasumber penelitian Peter B. Kraska, "Militarizing the American Criminal Justice System" (2001: 143).
Konteksnya, narasumber tersebut memprotes operasi antinarkotika polisi Brasil karena mengerahkan senjata berat, helikopter, dan kendaraan lapis baja. Peralatan tempur militer itu digunakan secara non-proporsional di Favela dan wilayah periferal.

Polisi yang Represif dan Membunuh Sipil
Penembakan yang menewaskan Michael Brown oleh seorang polisi Ferguson, negara bagian Missouri, pada 9 Agustus 2014, memicu badai kontroversi terhadap represi polisi yang mengingatkan reaksi publik terhadap pemukulan Rodney King pada 3 Maret 1991. Dari kedua insiden tersebut, tidak ada tersangka yang dijatuhi dakwaan.
Tanggal 24 November 2014, Jaksa St. Louis County Bob McCulloch mengumumkan bahwa dewan juri telah memutuskan tidak mendakwa Darren Wilson, polisi yang diidentifikasi sebagai pelaku penembakan Brown. Di sisi lain, empat polisi terdakwa pelaku pemukulan Rodney King (Koon, Briseno, Wind, dan Powell) hanya dibebastugaskan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) pada 29 April 1992, tanpa dihukum.
Keadaan misterius seputar kematian Brown, reaksi polisi yang keras terhadap protes yang menyusul insiden tersebut, dan serangkaian kasus pembunuhan oleh polisi di seluruh Amerika Serikat—seperti penembakan yang menewaskan Philando Castile di Minnesota pada 2016, penembakan yang menewaskan Stephon Clark di California tahun 2018, dan lainnya—memicu perdebatan kontroversial dan meningkatkan pentingnya masalah penggunaan kekerasan oleh polisi.
Hasil rumusan pemaparan (lihat penelitian Echols) menyebut, 1033 Program menghabisi korban sipil sekitar 2 (1,7138) dari setiap 1 juta kematian per tahun di setiap 50 negara bagian AS ditambah Distrik Columbia. Artinya, setidaknya ada 100 pembunuhan (per satu juta kematian) akibat militerisasi polisi yang dilancarkan di seluruh AS setiap tahunnya.
Selain itu, data yang dimiliki oleh Fatal Encounters sejak didirikan pada 2013 makin menggamblangkan gudang data lebih jelas. Ia bahkan berhasil mencatat detail informasi—bukan hanya nama, tetapi juga ras, jenis kelamin, usia, lokasi kejadian, penyebab kematian, dan lain-lain—tentang masyarakat sipil yang dibunuh polisi sejak 1 Januari 2000 hingga saat ini.
Ada 5.057 subjek kulit hitam, yang tampaknya mendukung narasi umum bahwa mereka adalah korban paling rentan pembunuhan oleh polisi. Tingkat kematian tahunan berkisar dari yang terendah 816 pada 2010 hingga yang tertinggi 1.782 pada 2013, dengan rata-rata 1.186 korban jiwa.
Data itu menunjukkan, militerisasi polisi merupakan respons terhadap “ancaman” yang salah satunya ditargetkan kepada kelompok minoritas. Namun, hubungan antara penambahan demografi ras dan peningkatan militerisasi bersifat non-linier.
Dalam asas hak asasi manusia, segala macam bentuk kekerasan dan pembunuhan itu tidak dibenarkan. Hal tersebut juga tak melulu mengacu pada data dan statistik. Sebab, nyawa manusia bukan sekadar angka, melainkan mengandung pengalaman, perasaan, martabat, harapan, dan cerita.
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id