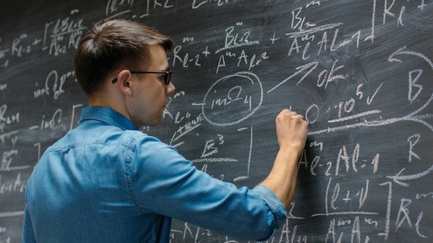tirto.id - “There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen.”
Kutipan Lenin ini menemukan gaungnya di Indonesia pada pengujung Agustus 2025. Dalam satu pekan, sebuah keputusan politik yang tampak seperti urusan teknis berubah menjadi gelombang protes nasional dengan konsekuensi yang jauh melampaui isu awalnya.
Gelombang protes bermula pada 25 Agustus 2025, menyusul beredar luasnya kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang disertai dengan berbagai tindakan dan ucapan tak peka dari sosok-sosok seperti Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Eko Patrio.
Pada 25 Agustus itu, berbagai elemen masyarakat berkumpul di Kompleks Parlemen, Senayan. Menurut laporan Tempo, sebelum ini muncul pesan berantai dari grup yang menamai dirinya "Revolusi Rakyat Indonesia". Agenda utamanya adalah memprotes kesenjangan antara fasilitas yang didapat anggota parlemen dengan kondisi perekonomian masyarakat luas.
Siang harinya, aksi berlangsung tertib, penuh orasi dan spanduk. Namun, tuntutan yang disampaikan dengan santun itu tidak direspons oleh para anggota DPR. Sampai akhirnya, ketika hari sudah gelap, bentrokan pun pecah antara massa yang sudah bercampur dengan pelajar berseragam putih abu-abu dan aparat.
Puncak eskalasi terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika aksi buruh mengambil alih panggung protes. Mereka membawa enam tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, stop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu).
Aksi ini awalnya juga berlangsung damai. Apalagi, massa buruh sudah membubarkan diri pada pukul 12 siang. Akan tetapi, setelah itu gelombang massa mahasiswa dan massa berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung DPR. Mereka menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang mencapai Rp100 juta/bulan.
Demonstrasi gelombang kedua inilah yang berakhir ricuh hingga akhirnya, seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan, yang baru berusia 21 tahun, dilindas rantis Brimob. Ironisnya, Affan bukan bagian dari massa. Dia waktu itu sedang menunaikan tugasnya sebagai pengemudi ojol. Namun, justru Affan yang menjadi korban kebrutalan aparat.
Affan meninggal dunia tak lama setelah itu dan, dengan segera, massa pengemudi ojol mengejar mobil rantis tersebut sampai ke markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat. Markas Brimob itu dikepung dan diserang oleh massa yang naik darah. Tak butuh waktu lama, massa di kota-kota lain seperti Solo pun ikut melakukan hal yang sama. Tuntutan pun bertambah: pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa Affan serta perubahan cara negara merespons aspirasi publik.
Kini, 2 September 2025, sampai tadi siang aksi masih terus berlangsung. Korban masih terus berjatuhan. Total, sudah sembilan orang meninggal dunia di berbagai kota. Lantas, mengapa protes yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu berakhir dengan kekerasan?

Pola Siang-Malam dan “Kejadian Aneh” di Tempat Lain
Ada satu pola yang kerap berulang dalam beberapa tahun terakhir: siang hari protes berlangsung tertib, tetapi memasuki senja dan malam, eskalasi kekerasan sering meledak—dari lemparan gas air mata, dorongan-dorongan yang berubah menjadi bentrokan, sampai pembakaran fasilitas publik.
Pola ini kembali tampak pada pekan terakhir Agustus 2025—sebagian halte TransJakarta terbakar dan kantor-kantor DPRD rusak. Namun, bila dicermati lebih dekat, masalahnya tidak semata urusan “waktu” (malam hari), melainkan juga “ruang”. Pada jam yang hampir bersamaan ketika inti demonstrasi masih damai di satu titik, muncul peristiwa-peristiwa aneh di titik lain—pembakaran dan penjarahan—yang menggeser citra keseluruhan aksi menjadi “anarkis”.
Preseden kuat untuk membaca pola ini datang dari 8 Oktober 2020, ketika Halte TransJakarta Sarinah dibakar di tengah demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Tim Buka Mata Narasi melakukan penelusuran sumber terbuka—menggabungkan video dan foto dari Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, serta cuplikan CCTV—untuk merekonstruksi peristiwa itu menit demi menit.
Hasilnya memperlihatkan sekelompok orang datang berbarengan dari arah Jalan Sunda, berfoto, mengamati lokasi, berkomunikasi melalui ponsel, lalu secara bertahap menyalakan api menggunakan cone lalu spanduk dan kardus—sementara di titik lain massa mahasiswa masih berhadapan dengan polisi.
Temuan ini menyimpulkan bahwa mereka “memang datang untuk membakar halte,” bukan bagian dari arus utama demonstran yang menyuarakan tuntutan kebijakan. Dengan kata lain, kekerasan tidak muncul organik dari tubuh aksi, melainkan disusupkan melalui operasi yang rapi, terukur, dan terpisah secara ruang dari inti protes.
Gambaran serupa muncul kembali pada Agustus 2025 dalam bentuk penjarahan rumah sejumlah anggota DPR. Investigasi visual-naratif Republika menghadirkan kesaksian seorang pemuda bernama “Ahu” yang mengaku direkrut, diberi makan, dan diarahkan untuk ikut menjarah.
Ia menceritakan pola perekrutan yang rapi—bergerak berkonvoi dari luar Jakarta, bergabung dalam “tim pemukul,” menyasar rumah-rumah yang sengaja dibiarkan kosong, serta menjelaskan bahwa barang jarahan berfungsi sebagai “bayaran”. Dalam paket tersebut juga disebut rencana bom molotov dan petasan yang telah disiapkan sebelum masuk lokasi, mempertegas bahwa tindakan itu bukan spontanitas massa, melainkan operasi yang memang dirancang untuk menciptakan kerusakan seluas mungkin.
Dua contoh ini—Sarinah 2020 dan penjarahan terorganisasi 2025—memberi kacamata yang lebih tajam untuk membaca ulang pekan demonstrasi terakhir. Betul, ada pola siang damai lalu malam ricuh di titik aksi utama. Tetapi di luar itu, ada pula skena paralel, di mana tindakan-tindakan kekerasan terencana berlangsung di tempat lain (bahkan pada siang/sore hari), lalu diangkat sebagai tajuk besar sehingga menenggelamkan substansi tuntutan.
Dalam laporan BBC Indonesia, Peneliti politik dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menyoroti kejanggalan dalam aksi penjarahan yang menimpa rumah Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Sri Mulyani.
Kejanggalan lain, menurut laporan yang sama, adalah ramainya gelombang informasi palsu, termasuk deepfake. Contohnya adalah video kerusuhan di Baghdad diklaim sebagai kejadian di Jakarta, ataupun klaim penjarahan di gedung DPR dan Mall Atrium Senen.
"Beberapa hoaks itu sudah menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) berupa deepfake sehingga publik kesulitan mengidentifikasi secara cepat, malah tergocek oleh deepfake itu," kata Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho dalam keterangan tertulis.
Dari lapangan, tanda-tanda provokasi juga terekam. Sebuah rekaman drone memperlihatkan seorang individu berpakaian sipil memukul aparat, lalu situasi seketika melebar menjadi bentrokan di sekitar lokasi. Video ini tidak serta-merta mengungkap identitas pelaku, tetapi memperkuat dugaan bahwa tindakan pemicu kerap dilakukan oleh aktor yang menyaru di tengah massa, sehingga kekerasan tampak “berasal dari demonstran” padahal diawali insiden terarah.
Masalahnya, provokasi semacam ini tidak hanya merusak disiplin non-kekerasan; ia juga menebar kecurigaan yang mematikan. Di Makassar, seorang pengemudi ojol bernama Rusmadiansyah alias Dandi tewas dikeroyok karena salah dicurigai sebagai intel. Peristiwa tragis ini menunjukkan bagaimana paranoia yang disulut oleh operasi terselubung dapat berbalik menghantam warga biasa yang sama sekali bukan bagian dari aparat maupun provokator.
Jika digabungkan, contoh-contoh di atas menjelaskan mengapa pola “siang damai, malam ricuh” sering beriringan dengan kejadian-kejadian aneh di tempat lain: keduanya saling menopang dalam mendistorsi wajah protes. Tindakan terencana—mulai dari pembakaran fasilitas hingga penjarahan rumah pejabat—diletakkan di luar inti aksi, pada waktu dan ruang yang memutus kontinuitas dengan massa damai.
Setelah itu, arus disinformasi memperbesar dampaknya, menempelkan label tunggal “anarkis” ke seluruh gerakan. Hasilnya tentu saja kontraproduktif. Sebab, di sinilah legitimasi protes damai mulai terkikis. Bukan karena demonstran menghendaki kekerasan, melainkan karena aksi mereka ditumpangi dan dibelokkan oleh operasi yang tujuan utamanya justru mendistorsi citra gerakan.
Konsekuensi politiknya terasa segera. Ketika publik disuguhi visual pembakaran halte atau penjarahan rumah pejabat, simpati mudah terbelah; framing “anarkis” menguat, sementara inti protes—kebijakan yang dianggap tak adil, ketimpangan, dan akuntabilitas—tergeser dari percakapan publik.

Respons Sipil: 17+8 Tuntutan Rakyat
Sesudah rangkaian kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan menenggelamkan substansi tuntutan, sebuah kontra-narasi muncul dari masyarakat sipil. Sejumlah artis, kreator, dan figur publik mengunggah “17+8 Tuntutan Rakyat” secara serentak di media sosial—sebuah dokumen ringkas yang merapikan kemarahan menjadi agenda politik yang eksplisit: tujuh belas tuntutan segera dan delapan tuntutan struktural.
17+8 tuntutan itu bertindak sebagai kerangka legitimasi. Di tengah kabut “kejadian janggal” dan narasi "anarkis" yang mendominasi, dokumen ini menjadi kompas yang mempertegas bahwa gerakan masih memilih jalur damai, artikulatif, dan terukur, khususnya setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal membuka jalur dialog.
Dengan merinci isu-isu kebijakan—dari tata kelola keuangan publik, perlindungan kelompok rentan, hingga tata kelola keamanan—17+8 mengangkat protes kembali ke level yang lebih terhormat ketimbang sekadar respons emosional terhadap kekerasan. Bentuknya yang ringkas dan mudah dibagikan juga menciptakan standar pesan lintas kota dan lintas kelompok, mengurangi ruang tafsir yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk mendistorsi tujuan aksi.
Dalam kacamata strategi, 17+8 adalah upaya merebut kendali narasi. Ia menunjukkan bahwa, meskipun aksi jalanan diseret ke dalam pusaran kekerasan dan disinformasi, ada selubung organisasi dan akal sehat yang terus bekerja. Mereka menyederhanakan pesan agar tidak tercerai-berai dan menegaskan komitmen non-kekerasan. Dengan pijakan ini, meski provokasi dan infiltrasi menggerus keunggulan moral gerakan, akal sehat masih menjadi harapan bagi terpenuhinya tuntutan.
Menakar Peluang Keberhasilan Demo Tanpa Kekerasan
Dari pola yang selama ini terjadi, tampak bagaimana massa aksi sebenarnya selalu mengawali unjuk rasa dengan damai. Sama sekali tidak ada maksud untuk berbuat onar apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, di saat yang bersamaaan, selalu ada upaya untuk mendelegitimasi upaya-upaya damai ini dengan provokasi, bahkan "settingan", untuk menciptakan narasi baru yang menenggelamkan tuntutan sebenarnya.
Alasannya bukan moralitas semata, melainkan logika strategi. Pertama, aksi nirkekerasan memperluas partisipasi lintas kelas dan profesi. Ini memungkinkan jumlah peserta aksi semakin banyak setiap harinya. Kedua, ketika warga tak bersenjata direpresi, ini bakal jadi senjata makan tuan (backfire) dengan ongkos politis yang tinggi. Hingga akhirnya, yang ketiga, di kalangan aparat sendiri, upaya menyeberang bisa jadi muncul lantaran sebagian dari mereka memilih untuk berpihak pada massa aksi.
Chenoweth juga memperkenalkan sebuah aturan bernama aturan 3,5 persen. Sederhananya, sebuah gerakan sosial di suatu negara akan berhasil apabila setidaknya ada 3,5 persen populasi yang sungguh-sungguh turun beraksi. Jika penduduk Indonesia adalah 283,5 juta, maka 3,5 persennya adalah sekitar 9,9 juta orang. Jumlah sebesar ini, tentu saja, bisa hadir lewat metode nirkekerasan yang membuat orang merasa aman untuk ikut aksi.
Namun, menurut Chenoweth pula, 3,5 persen ini sebenarnya bukan angka sakti. Ini hanyalah hasil observasinya, di mana tidak ada gerakan yang gagal setelah 3,5 persen populasi berpartisipasi secara aktif. Akan tetapi, dalam paper ini, Chenoweth juga menjelaskan bahwasanya ada pula gerakan yang sukses meski peserta aktifnya tidak sampai 3,5 persen populasi.
Laporan ICNC turut memperkuat hasil temuan di atas. Di sana kurang lebih dijelaskan bagaimana, dibanding gerakan bersenjata, gerakan nirkekerasan secara statistik jauh lebih kecil memicu pembunuhan massal. Sebaliknya, munculnya kekerasan—bahkan dari kelompok sempalan kecil—menaikkan risiko korban sipil secara tajam.
Celakanya, dalam satu dasawarsa belakangan, efektivitas non-kekerasan menurun. Penyebab utamanya, menurut Chenoweth dalam artikel berjudul The Future of Nonviolent Resistance, adalah karena rezim beradaptasi.
Mereka menyusupi gerakan dan memancing kekerasan agar label “anarkis” menempel lebih dulu, mengkriminalkan aktivis, memecah koalisi, serta menguasai ruang informasi sehingga backfire melemah dan defeksi makin mahal. Inilah yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam aksi demo Agustus-September 2025.

Audit pada Kasus Indonesia
Mengapa “keunggulan statistik” aksi damai kadang tak muncul? Dalam literatur, empat mekanisme saling terkait—partisipasi luas, disiplin nirkekerasan, efek backfire, dan peluang defeksi aparat—jadi syarat utama keberhasilan gerakan damai. Sekarang, kita nilai apa yang terjadi dalam kasus Indonesia.
Pertama, partisipasi. Dalam pekan 25–31 Agustus 2025, mobilisasi meluas lintas kelompok—mahasiswa, pelajar, buruh, pesohor, ibu rumah tangga, hingga komunitas pengemudi ojol—dan tersebar ke banyak kota. Sementara, gelombang tuntutan sipil terformalkan lewat “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dipublikasikan figur publik sebagai standar pesan bersama. Dengan kata lain, prasyarat jumlah dan jangkauan sosial sebagian terpenuhi. Namun, sebagaimana ditekankan Chenoweth, angka keterlibatan saja tidak cukup bila tiga mekanisme lain tersumbat.
Kedua, disiplin nirkekerasan. Bukti lapangan kuat menunjukkan inti aksi pada siang–sore hari berlangsung tertib, sedangkan gangguan muncul dari insiden yang terpisah secara ruang dan aktor. Kesaksian “Ahu” tentang penjarahan terorganisasi menguatkan pola bahwa kekerasan banyak lahir dari operasi paralel di luar tubuh aksi. Disiplin inti gerakan ada, tetapi mudah direkayasa dan tampak runtuh ketika peristiwa di “tempat lain” ditempelkan ke citra aksi.
Ketiga, efek backfire. Secara teori, represi terhadap warga tak bersenjata memicu simpati dan mengurangi legitimasi penindakan. Tragedi Affan Kurniawan seharusnya menjadi titik balik seperti itu: ia bukan demonstran, melainkan pekerja yang kebetulan berada di lokasi, dan tewas terlindas kendaraan taktis. Namun efek backfire ini segera tertutup oleh visual pembakaran/penjarahan dan kabut informasi. Dalam kondisi demikian, simpati yang mestinya terkumpul justru terdistorsi, dan amarah publik dialihkan ke wacana “anarkis”.
Keempat, defeksi. Peluang pergeseran loyalitas aparat biasanya meningkat ketika mereka dipaksa menindak warga damai yang jelas-jelas non-kekerasan. Namun, sejauh ini, sinyal defeksi hampir nihil. Perintah negara justru menekankan langkah “setegas-tegasnya” terhadap perusakan dan penjarahan, sehingga “biaya moral” bagi aparat menjadi kabur karena narasi ancaman dibesarkan. Kekosongan defeksi ini memutus salah satu jalur utama yang, dalam studi komparatif, sering mengantar keberhasilan gerakan damai.
Dari audit singkat ini, terlihat bahwa, meski nirkekerasan tetap jalur strategis paling rasional, keunggulannya belum terasa penuh di Indonesia beberapa tahun terakhir. Bukan karena aksi nirkekerasan tidak lagi efektif tetapi karena mekanisme kuncinya dibajak sebelum sempat berfungsi.
Jalan ke Depan: Memulihkan Empat Mekanisme Nirkekerasan
Jika audit pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi sudah meluas tetapi backfire dan defeksi tersumbat oleh provokasi serta kabut informasi, maka pekerjaan rumahnya adalah mengembalikan empat mekanisme kunci nirkekerasan ke posisi kerja penuh.
Pertama, partisipasi harus dijaga tetapi rendah risiko dan tinggi keterlihatan. Pengalaman beberapa hari terakhir membuktikan siang hari relatif tertib sementara malam hari rawan eskalasi.
Disiplin waktu—membatasi durasi dan membubarkan diri sebelum titik rawan—membantu menurunkan biaya pribadi untuk ikut serta, menjaga keterlibatan kelompok rentan, dan mencegah arus massa bercampur dengan elemen yang datang “untuk hal lain”. Mengonsolidasikan pesan bersama—sebagaimana dilakukan oleh publikasi 17+8 Tuntutan Rakyat—juga membuat partisipasi meluas tanpa menyebar ke terlalu banyak isu yang mudah dipelintir.

Kedua, disiplin nirkekerasan perlu diperlakukan sebagai infrastruktur, bukan sekadar etika. Respons yang sepadan adalah membangun kebiasaan pemisahan ruang dan peran: inti orasi tetap di titik yang terang dan terdokumentasi, sementara laporan aktivitas mencurigakan di “titik lain” segera diteruskan ke kanal verifikasi yang bisa dipublikasikan cepat untuk mencegah stempel “anarkis” melekat ke keseluruhan gerakan.
Ketiga, backfire harus dipersiapkan, bukan ditunggu terjadi. Dalam konteks Indonesia, meninggalnya Affan Kurniawan berpotensi menjadi momen simpati nasional, tetapi segera tertutup oleh visual kebakaran/penjarahan dan banjir disinformasi.
Karena itu, dokumentasi forensik terbuka—seperti pendekatan OSINT pada kasus pembakaran halte Sarinah—menjadi alat krusial untuk mengembalikan kronologi dan atribusi dengan cepat. Di sisi lain, arus hoaks dan bahkan deepfake menuntut prosedur “satu video, satu verifikasi” sebelum disebarkan, sekaligus klarifikasi singkat yang mudah dibagikan kembali agar domain tafsir tetap dipegang produsen fakta.
Keempat, membuka peluang defeksi mensyaratkan narasi dan gestur yang konsisten nirkekerasan. Riset menunjukkan pembunuhan massal jauh lebih kecil kemungkinan terjadi dalam kampanye damai—antara lain karena aparat lebih enggan menindak warga tak bersenjata.
Di lapangan, pemantik kontak—seperti figur berpakaian sipil memukul aparat lalu bentrokan melebar—tidak boleh dibiarkan menjadi “cerita utama”. Menjaga jarak yang tegas dari pelaku kekerasan, mengedepankan simbol-simbol damai yang konsisten, serta menampilkan korban sipil secara bermartabat—alih-alih visual destruksi—adalah cara praktis untuk mengembalikan kerangka moral yang membuat penindakan keras terlihat tidak sah di mata publik dan, pada gilirannya, sebagian aparat.
Rencana ini bukan resep kilat. Ia adalah cara mengembalikan syarat-syarat keberhasilan nirkekerasan ke lintasan kerja: partisipasi yang aman dan terarah; disiplin yang tahan provokasi; backfire yang didorong lewat verifikasi cepat dan kronologi terbuka; serta peluang defeksi yang tumbuh dari konsistensi nirkekerasan. Hanya dengan beginilah temuan teoretis, bahwa kampanye damai lebih efektif dan lebih kecil memicu tragedi kemanusiaan, bakal kembali punya peluang terwujud di lapangan Indonesia yang penuh gangguan.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id