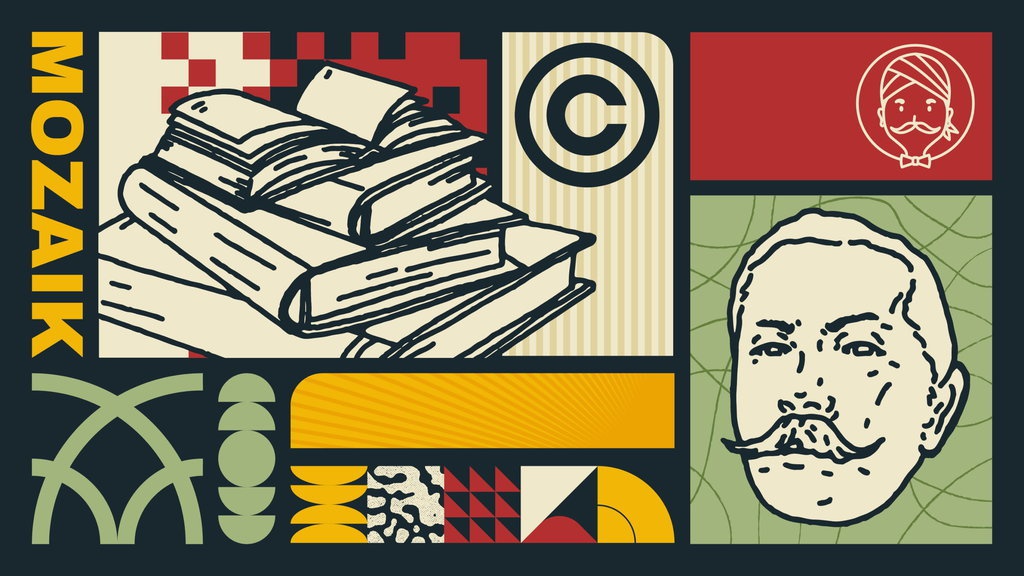tirto.id - Lahir pada 1859 di Edinburgh, Arthur Conan Doyle gemar membaca dan menelaah karya fiksi sejak usia dini. Sayangnya, ia tidak diberi restu orang tuanya untuk memperdalam kecintaannya terhadap dunia sastra.
Ayahnya, Charles Doyle, mengalami depresi karena gagal menjadi arsitek hingga membuat ekonomi keluarga hancur berantakan. Maka itu, sang ibu, Mary Foyle Doyle, tutur Jessica L. Malekos Smith dalam "Sherlock Holmes & the Case of the Contested Copyright" (Intellectual Property, 2016), memaksanya untuk memperoleh profesi mentereng demi keamanan finansial.
"[ibunya] memasukkan Doyle ke bangku perkuliahan di bidang kedokteran di University of Edinburgh," ungkap Jessica.
Karena dipaksa menimba ilmu di bidang yang tak disukai, Doyle tak kerasan. Meski demikian, ia dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikannya. Musababnya, catat Jessica, "Doyle bertemu dengan Dr. Joseph Bell kala menimba ilmu. Mengajari Doyle, dengan jenaka, pentingnya observasi dengan menggunakan semua indra untuk memperoleh diagnosis akurat."
Tak mau menjejali tetek bengek kedokteran berlebihan, Dr. Bell acapkali mengadakan kuis untuk menebak profesi seseorang melalui kombinasi deduktif dan induktif. Cara pengajaran ini--kelak setelah Doyle akhirnya lulus dan bekerja sebagai dokter di kapal ekspedisi Kerajaan Inggris ke Afrika dan Antartika--membuatnya kembali menekuni cinta pertamanya: sastra.
Memanfaatkan Dr. Bell sebagai inspirasi, Doyle melahirkan karakter fiksi bernama Sherlock Holmes, yang termuat dalam novel pertamanya, A Study in Scarlet (1887). Novel ini diterbitkan oleh Beeton's Christmas Annual dengan royalti senilai 25 poundsterling atau sekitar Rp74 juta dalam kurs saat ini. Lalu diterbitkan di Amerika Serikat dan seluruh dunia sejak 1890.
Kisah Sherlock Holmes banyak disukai pembaca yang membuat A Study in Scarlet laris manis. Doyle kemudian menulis dan menerbitkan novel keduanya, Sign of the Four (1890). Selain itu, berkerja sama dengan The Strand Magazine pada 1891, Doyle juga menerbitkan fiksi Sherlock Holmes dalam bentuk cerita pendek.
Ia dipuja para penggemar Sherlock Holmes. Saking lakunya, Doyle menyebut karya-karyanya "setara seperti junk food, yang menghasilkan uang tetapi terasa ringan dan mudah dilupakan."
Maka pada 1893, Doyle memutuskan membunuh karakter Sherlock Holmes melalui The Final Problem (1893). Keputusan ini tentu saja ditentang para penggemar Sherlock Holmes. Doyle bahkan kerap menerima ancaman pembunuhan dari para penggemarnya.
Kala itu, kisah Sherlock Holmes memang menjadi hiburan bagi masyarakat Barat di masa-masa perang. Maka ketika tokoh ini dibunuh, para pembaca meradang.
Sadar bahwa karyanya menjadi pelipur lara bagi masyarakat, Doyle akhirnya melanjutkan kisah Sherlock Holmes lewat The Hound of The Baskervilles (1902). Cerita ini bertutur masa lalu dari pertualangan-pertualangan Sherlock Holmes melalui karakter lain, Dr. Watson.
Setahun kemudian, Sherlock Holmes baru benar-benar dibangkitkan dari kematiannya dalam The Empty House (1903), dan terus berlanjut hingga 1927.
Pembaru Vs Ahli Waris
Tercatat sejak 1887 hingga 1927 Doyle menerbitkan 56 kisah Sherlock Holmes dan empat novel pendamping. Semua karyanya, merujuk paparan Kim Dian Gainer dalam "The Case of the Missing Copyright" (Intellectual Property Annual, 2014), kini telah berstatus "public domain" alias milik masyarakat umum di seluruh dunia.
Maka itu, Leslie Klinger dan Laurie R. King, misalnya, menerbitkan versi baru Sherlock Holmes dalam A Study in Sherlock: Stories Inspired by the Sherlock Holmes Canon pada 2011 lalu.
Karena statusnya milik publik, maka apa yang dilakukan Leslie Klinger dan Laurie R. King bukan masalah, malah dianggap melestarikan warisan Doyle untuk dunia. Terlebih setahun sebelumnya, kisah Sherlock Holmes juga direka ulang melalui serial garapan BBC berjudul Sherlock, yang menampilkan hidup sang detektif dalam suasana modern.
Namun, saat duo penulis cum editor ini tengah menyiapkan novel lanjutan Sherlock Holmes, yakni In the Company of Sherlock Holmes, untuk diterbitkan Pegasus Book, halangan menghampiri.
Dengan dalih revisi perundangan tentang Hak Cipta di Amerika Serikat pada 1998 yang mengukuhkan bahwa seluruh karya Doyle yang terbit setelah 1923 (berjumlah 10 karya) masih dilindungi Hak Cipta, pewaris Doyle menyerang Klinger dan King. Mereka meminta keduanya untuk mengurus lisensi dan membayar royalti.
Jika tidak, sebagaimana dipaparkan Matthew Rimmer dalam "Free Sherlock Holmes" (The Conversation, 2013), pewaris Doyle yang diwakili Estate Company mengancam akan memblokir penerbitan novel tersebut. Mereka sesumbar telah bekerja sama dengan Amazon sebagai toko buku terbesar di dunia.
Serangan serupa terjadi pada 2020 yang ditujukan kepada Netflix serta Legendary Picture, Penguin Random House, dan Nancy Springer karena platform streaming video ini membuat dan merilis film Enola Holmes--versi baru Sherlock Holmes yang melahirkan "adik baru" bernama Enola.
Klaim Estate Company, serangan kepada Netflix dilakukan karena, mengutip pemaparan Dionissia Siozios dalam "Emotions, My Dear Watson" (Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 2020) "Enola menampilkan sisi humanis dari Sherlock Holmes. Sisi yang baru dimunculkan Doyle lewat 10 karya terakhirnya, bukan 50 karya pertamanya."
Netflix tak terima. Terlebih dalam kasus Estate Company vs Klinger dan King, Klinger dan King memenangkan pertarungan. Keputusan hakim AS menyebut novel kedua mereka berbeda dengan 10 karya terakhir Doyle.
Hakim mempersilakan Klinger dan King (serta seluruh penulis di seluruh dunia) mengarang kisah-kisah baru Sherlock Holmes. Khusus bagi penulis yang hendak menerbitkan kisahnya di AS, mereka boleh menulis tanpa mengikutsertakan alur atau pokok inti cerita 10 karya terakhir Doyle.
Uniknya, tak mau lama bertarung di pengadilan, Netflix dan Estate Company berdamai di luar meja sidang.
Opini redaksional The New York Times pada 23 Januari 2010 menyebut, "Estate Company hanya melihat karya-karya Doyle sebagai sapi perah pundi-pundi belaka alias The Adventure of the Cash Cow pada 254 kisah Sherlock Holmes yang muncul di TV atau layar sinema."
Mereka sama sekali tak mau memandang semangat penulis atau kreator memunculkan kisah-kisah baru Sherlock Holmes sebagai elemen terpenting dalam berkarya atau mencipta, yakni pembaruan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesenian.
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Martha Buskirk dalam "Commodification as Censor" (October 60, 1992), esensi utama munculnya perundangan tentang Hak Cipta.

Dua Mata Pisau Hak Cipta
Berbeda dengan hak kepemilikan properti, misalnya, "Hak cipta lahir dengan satu tujuan, yakni memajukan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat," tulis Buskirk. Ini diterjemahkan melalui dua cara: melindungi pemilik karya atas ciptaannya, dan sebaliknya membatasi perlindungan tersebut.
Dengan cara pertama, hak cipta mendorong pemilik karya memperoleh pendapatan atau keuntungan. Ini dilakukan sebagai motivasi bahwa berkarya, tak ubahnya berbisnis ataupun kerja kantoran, adalah aktivitas yang menghasilkan uang.
Atas penghasilan yang diterima, hak cipta ingin mendorong si pemilik karya untuk terus mencipta, menghindari kisah tragis Wolfgang Amadeus Mozart ataupun Vincent van Gogh yang gagal secara ekonomi merasuki jiwa (calon) pencipta karya--bahwa berkarya tak menguntungkan.
Di sisi lain, karena tak ingin membendung pencipta lain dalam berkarya, dengan cara kedua, perlindungan hak cipta dibatasi.
Sebagai contoh, dengan hanya memanfaatkan 8 dari 12 nada musik, terdapat sekitar 6 miliar kemungkinan melodi sebuah lagu. Namun, dengan fakta bahwa tercipta 1 juta lagu per tahun di seluruh dunia, miliaran kemungkinan tersebut suatu saat akan bertautan dan terulang. Maka, jika hak cipta tak dibatasi, pencipta karya di bidang musik di masa depan, misalnya, akan kehabisan melodi untuk diulik.
Umumnya, soal pembatasan hak cipta, perundangan melakukannya dengan dua cara, yakni membatasi usia perlindungan (rata-rata di seluruh dunia selama 70 tahun sejak karya diciptakan). Kedua merilis konsep "fair use", yakni mengizinkan, dalam tataran terbatas, karya orang lain dijiplak untuk membangun karya baru.
Dalam melihat tujuan hak cipta sebagai instrumen "memajukan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat", cara pertama wajib dijunjung tinggi terlebih dahulu sebelum cara kedua diaktifkan.
Masalahnya, di tengah kemunculan cara-cara baru distribusi karya cipta, cara pertama mulai terancam. Dalam bidang musik contohnya, layanan streaming seperti Spotify, Youtube Musik, hingga Apple Music, memberikan royalti tak seberapa bagi musisi sebagai pencipta karya.
Sebagai contoh, dihitung berdasarkan lagu yang diputar penggunanya, Michelle Lewis sebagai pengarang musik indie-rock asal Amerika Serikat, hanya memperoleh penghasilan senilai $17 atas lagunya yang diputar 3 juta kali di Spotify.
Kenyataan ini sedikit banyak akan membuat para musisi kembali berpikir bahwa berkarya memang tak menguntungkan. Akibatnya, akan menghambat "kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat."
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id