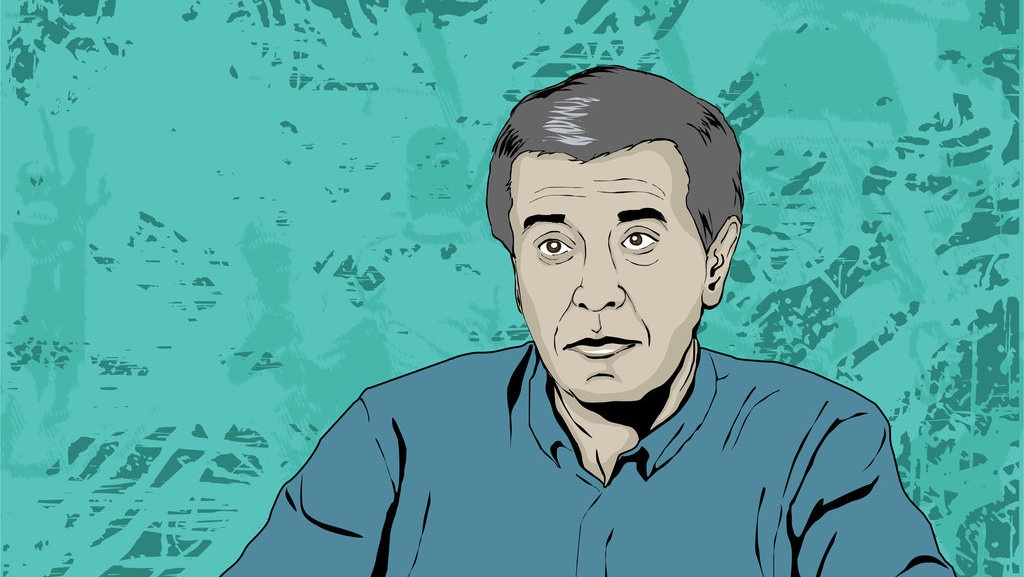tirto.id - Sehari setelah laporan investigasinya tayang di The Intercept dan kemudian Tirto, Allan Nairn berkunjung ke redaksi Tirto. Ia tiba sekitar pukul 14.15 WIB. Allan datang dengan tas selempang kanvas dan berkemeja warna biru muda yang basah oleh keringat.
Tidak tampak kesan kegelisahan atau kehati-hatian yang berlebihan dari sosok yang sehari sebelumnya banyak dibicarakan orang itu. Laporannya yang terbit pada Rabu, 19 April 2017, memang menjadi bahan perbincangan yang seru di kalangan peminat berita politik dan militer Indonesia. Laporannya menjadi cerita sampingan yang meledak di tengah semarak pemberitaan dan kehebohan Pilgub DKI Jakarta 2017.
Ia memang berpengalaman menulis tentang peran militer di berbagai negara yang dikuasai pemimpin otoriter. dari Guatemala hingga Indonesia. Ia menganggap pekerjaannya sebagai semacam tanggungjawab moral sebagai warga Amerika Serikat.
Lebih lengkap tentang rekam jejaknya, baca: Allan Nairn, Mimpi Buruk Para Jenderal
Kepada Tirto ia berkata: "Saya memilih lokasi berdasarkan dua kriteria: Pertama, di tempat itu ada penindasan kelas berat. Kedua, kalau penindasan itu didukung pemerintah Amerika Serikat. Gagasan saya, “Bagaimana kalau seorang warga Amerika Serikat menyelidiki situasi-situasi itu dan menggunakan hasilnya buat menekan pemerintah Amerika Serikat supaya berhenti mendukung para pembunuh tersebut?”
Laporan Allan tentang keterlibatan militer—pensiun maupun aktif—dalam sengkarut Pilgub DKI Jakarta 2017, yang memicu penangkapan beberapa orang karena tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi, memang menghebohkan. Namun, tidak sedikit pihak yang skeptis. TNI sendiri membantahnya. Kapuspen TNI, Mayjend. Wuryanto menganggap laporan Allan "tidak ada yang benar."
Tirto menggunakan kesempatan wawancara dengan Allan untuk menanyakan berbagai hal terkait proses investigasi yang dilakukannya, termasuk mengenai para narasumber.
"Saya belum menghitung persisnya berapa [narasumber]. Tapi ada puluhan," jawab Allan saat ditanya berapa narasumber yang ia wawancarai. Ia juga mengatakan, kendati cukup banyak narasumber yang ia temui, namun ini bukan semata soal jumlah, "[Tapi] juga tergantung pada siapa mereka, seberapa tahu mereka, dan apa yang sungguh-sungguh mereka katakan. Tapi juga pola-pola aktivitas yang bisa dibuktikan."
Pihak TNI membantah laporan Allan Nairn. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang dianggap terlibat oleh Allan, menganggap laporan itu sebagai "kabar bohong." Respons Gatot Nurmantyo berbeda dengan Kapuspen TNI. Ia menyatakan tak akan menuntut Allan Nairn maupun Tirto. "Kamu Mau Berkelahi dengan Orang Gila?" katanya.
Selain menceritakan proses liputan investigasi, Allan juga bercerita tentang pengalamannya meliput konflik di berbagai wilayah, termasuk bagaimana ia menghadapi pihak imigrasi. Kepada Fahri Salam, Windu Jusuf, dan Zen RS dari Tirto, ia juga bercerita tentang keterlibatan CIA di berbagai konflik di dunia ketiga.
Hasil wawancara dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas proses dan pengalamannya melakukan liputan investigasi, termasuk investigasi tentang plot kudeta di Jakarta, sedangkan bagian kedua akan membahas lebih rinci tentang plot kudeta itu sendiri.
Rabu, 19 April, laporan Anda, tentang plot kudeta yang memakai panggung Pilkada Jakarta, tayang. Sejak kapan Anda menginvestigasi ini?
Sejak sekitar setahun silam, ketika pemerintah mulai khawatir soal kudeta. Saya masuk lebih dalam lagi sejak Januari 2017.
[Mulanya] tidak terbayang oleh saya jika kudeta adalah ancaman nyata. Saat itu saya berpikir kalau pemerintah memanfaatkan [isu] kudeta sebagai dalih untuk tidak menyeret para jenderal yang punya masalah HAM ke pengadilan.
Saya kira pemerintah pada intinya mau mengatakan: terlalu berbahaya untuk mengadili mereka. Militer terlalu kuat dan bisa berbalik melawan kami. Tapi, sejurus kemudian, bahaya yang sesungguhnya ternyata berkembang seiring bangkitnya gerakan jalanan FPI, yang kenyataannya digerakkan militer.
Siapa yang mendukung dan mendanai laporan Anda?
The Intercept. [Sikap terakhir media tersebut: The Intercept: We Stand by Our Story]
Banyak yang heran mengapa ada orang-orang yang mau bercerita di balik plot kudeta. Apa yang Anda lakukan untuk memancing mereka bicara?
Ada alasan-alasan kompleks yang menyebabkan orang buka mulut. Dari pengalaman saya, kompleksitas itu bertambah karena riwayat saya sendiri. Saya selalu mengkritik militer Indonesia dan militer Amerika. Dan mungkin paradoksnya itu membuat kebanyakan dari mereka bungkam. Tapi saya coba dekati sebagian besar di antara mereka, dan akhirnya saya ketemu juga yang mau bicara dengan saya. Jumlahnya banyak.
Beberapa dari mereka tertarik mengobrol, menanyakan pertarungan saya dengan militer di masa lalu. Saya tidak terlalu paham motivasinya. Semuanya bisa beda-beda. Tapi jika Anda bisa bertatap muka dengan seseorang dan Anda memahami pekerjaan mereka, orang akan tertarik bicara tentang apa yang mereka kerjakan, terlepas dari apa sesungguhnya pekerjaan mereka. Cukup ngobrol sebentar saja dan pasti Anda dapat sesuatu. Anda harus mempersiapkannya dengan hati-hati, karena fakta akan mengalir deras. Terlepas dari arah pembicaraannya, Anda bisa menanyakan isu-isu yang paling penting dan relevan yang mereka ketahui.
Mengapa pilihan Anda jatuh kepada Jenderal (Purn) Kivlan Zen?
Saya telepon dia dan dia sepakat untuk ketemu saya.
Anda tidak menemui kesulitan saat berhubungan dengan dia?
Awalnya sulit menghubungi Kivlan. Butuh waktu untuk menemukan nomor teleponnya yang masih aktif. Tapi sekali saya berhasil mengontak, dia bilang senang saya bisa menemukan nomornya yang baru saja dipasang. Dia khawatir diawasi oleh intel. Tapi begitu saya berhasil kontak dia, dia setuju untuk bertemu. Saya langsung terbang ke Surabaya.
Tapi, sekali lagi, mengapa Kivlan? Anda tentu tahu reputasi Kivlan yang memang sering bicara ceplas-ceplos dan bahkan ada yang meragukan kredibilitasnya sebagai narasumber?
Faktanya, dia ada di sana, terlibat sebagai bagian dari gerakan itu. Lagi pula apa yang disampaikan Kivlan juga dinyatakan oleh banyak narasumber yang lain.
[Catatan: Kivlan salah satu yang ditangkap kepolisian dengan tuduhan penggulingan kekuasaan pada 2 Desember 2016, menjelang aksi 212. Baca: Safari Kivlan Menjelang Penangkapan]
Memangnya berapa sumber yang Anda pakai dalam laporan terbaru?
Puluhan. Saya belum menghitung persisnya berapa. Tapi ada puluhan.
Untuk standar sumber yang dikonfirmasi tapi menolak untuk menjawab atau bicara anonim, Anda memakai berapa banyak sumber buat mengecek kembali ke lingkaran sumber lain?
Pertama-tama, ini bukan soal jumlah. Ada beberapa sumber lain. Tapi juga tergantung pada siapa mereka, seberapa tahu mereka, dan apa yang sungguh-sungguh mereka katakan. Tapi juga pola-pola aktivitas yang bisa dibuktikan.
Jika Anda merangkai perkataan orang-orang itu dengan hal-hal yang telah dilakukan Gatot Nurmantyo, pidato-pidatonya yang ekstrem, pertemuan-pertemuan yang dia laksanakan untuk menenangkan orang-orang gerakan itu, tidak ada kontroversi sungguhan. Tidak ada yang mengatakan Gatot berseberangan. Mereka mengatakan hal yang sama dengan Kivlan.
Bagaimana dengan Soleman Ponto, orang dari BAIS itu?
Saya bertanya ke dia. Dia katakan, saya boleh kutip semua ucapannya.
[Catatan: Sejak Desember 2016, Tirto mewawancarai beberapa orang yang kami duga di balik gelombang anti-Ahok di Jakarta. Tak ada yang mau dikutip, termasuk Soleman. Setelah laporan Nairn terbit, kami kontak Soleman dengan membagi tautan asli dari The Intercept. Soleman bilang apa yang ditulis Nairn “sudah menjadi rahasia umum.” Belakangan Ponto, pada 21 April, memuat klarifikasi yang menjelaskan beberapa poin, salah satunya bahwa pertemuan mereka sebatas diskusi, bukan permintaan wawancara. Kami membagikan tautan klarifikasi Ponto kepada Nairn. Nairn merespons itu “tidak akurat” plus tidak konsisten dengan jawaban Ponto kepada kami di bagian “sudah jadi rahasia umum.”]
Kami penasaran dengan kiprah Anda di beberapa negara (Guatemala, Haiti, dan Indonesia, untuk menyebut beberapa) dalam menentang para jenderal dan sebagainya. Lalu, Anda pernah dipersulit imigrasi Indonesia, bagaimana Anda menangani persoalan itu?
Pada musim kampanye 2014, setelah saya menerbitkan tulisan tentang Prabowo, ia ingin tentara menangkap saya. Pada satu titik bahkan mereka bilang saya dilarang kembali ke Indonesia karena telah mengancam apa yang mereka sebut “keamanan nasional”. Mereka memang melarang saya kembali. Mereka juga menyatakan bahwa saya pernah ditangkap tentara, tujuh kali. Saya membaca pernyataan-pernyataan itu dan bergumam, “Hah, apa iya?” Soalnya, saya sendiri lupa. Saya lupa sudah berapa kali saya tertangkap.
Tetapi tak jarang pula saya berhasil masuk tanpa tertangkap. Saya punya banyak pengalaman menarik di perbatasan. Saya pernah diinterogasi, tapi kemudian si petugas malah bersimpati kepada apa-apa yang saya katakan.
Saya bilang, “Mau tahu kenapa saya mengkritik tentara?”
Lalu saya ceritakan kepadanya tentang pembantaian yang terjadi dan sebagainya. Tak lama kemudian, setelah menceritakan beberapa kasus, petugas interogasi itu setuju dengan saya dan membiarkan saya pergi. Hal itu terjadi beberapa kali.
Pernah juga saya berhadapan dengan petugas imigrasi yang badannya sangat kecil. Saya menghampiri dia dan cepat-cepat bicara, sebelum dia menanyakan berkas-berkas saya: “Saya tahu Anda siapa, saya baru saja dipindahkan dari Jakarta. Mereka menunjukkan berkas-berkas dan saya pikir Anda bekerja luar biasa baik.” Setelah bercakap-cakap sebentar, ia mengizinkan saya masuk. Mulanya, ia galak sekali.
Jadi, kalian tahulah keadaannya. Dulu lebih sulit ketimbang sekarang.
Saya pertama kali melakukan investigasi seperti ini di Guatemala pada 1980. Saya memilih lokasi berdasarkan dua kriteria: Pertama, di tempat itu ada penindasan kelas berat. Kedua, kalau penindasan itu didukung pemerintah Amerika Serikat.
Gagasan saya, “Bagaimana kalau seorang warga Amerika Serikat menyelidiki situasi-situasi itu dan menggunakan hasilnya buat menekan pemerintah Amerika Serikat supaya berhenti mendukung para pembunuh tersebut?”
Sialnya, waktu itu, ada lebih dari 40 atau 50 negara yang memenuhi kriteria tersebut.
Termasuk Indonesia?
Di Timor Leste dan Indonesia, penindasan yang terjadi sama gawatnya. Pembantaian di Timor itu adalah kasus terparah. Dari segi proporsi jumlah korban, [jumlahnya terbesar] setelah Nazi. Nazi menghabisi 1/3 populasi Yahudi Eropa dan tentara Indonesia menghabisi 1/3 populasi Timor Leste. Bahkan Pol Pot tidak mencapai persentase itu dalam pembantaian yang ia lancarkan di Kamboja.
Di Indonesia, pembantaian 1965 memakan korban hingga, mungkin, sejuta orang [Sarwo Edhie Wibowo, mertua Susilo Bambang Yudhoyono, pernah mengaku menghabisi 3 juta orang komunis]. Tak ada yang tahu angka pastinya, tetapi dengan anggapan satu juta saja, itu adalah salah satu kasus terburuk abad ke-20. Keduanya didukung penuh oleh pemerintah Amerika Serikat.
CIA memberikan daftar nama-nama orang yang dianggap dan simpatisan komunis di Indonesia agar pemerintah kami semakin bersemangat mendukung mereka sampai akhir. Bahkan media-media massa di Amerika Serikat mendukung pembunuhan yang terjadi di sini.
Ada satu artikel di New York Times yang menyebut pembantaian itu: “Kilau Cahaya di Asia”. Dan tentu, soal Timor, Presiden Ford dan Henry Kissinger memberikan lampu hijau secara pribadi kepada Soeharto untuk menggelar operasi militer. 97 persen senjata yang digunakan TNI waktu itu berasal dari Amerika Serikat.
Mereka baru berhenti mendukung kegilaan itu, secara bertahap, setelah rakyat Amerika Serikat menekan mereka soal pembantaian Santa Cruz di Dili. Kami menekan lewat Kongres dan Kongres menekan Presiden. Sistem Kongres Amerika bisa sekuat itu, sebenarnya.
Setelah referendum pada 1999, setelah operasi TNI membunuh ribuan orang dan menghancurkan Timor Leste, Clinton benar-benar menghentikan dukungannya.
Tapi penyelesaian yang adil untuk perkara ini harus mencakup dua hal: tokoh-tokoh militer Indonesia yang berperan harus diadili dan dipenjara. Wiranto, Hendropriyono, Prabowo, Ryamizard, Sjafrie … kalian pasti lebih hafal daftar nama mereka ketimbang saya. Karena itulah pada kampanye 2014 saya menantang Prabowo bertemu saya di pengadilan.
Kedua, Clinton, Carter, Bush tua, Bush kecil, mereka juga harus diadili—bersama klien lokal masing-masing—atas dukungan mereka terhadap negara-negara yang membunuh rakyatnya.
Saya pikir, dalam hal keadilan, kita harus adil. Tak boleh ada bias. Hanya karena seseorang berasal dari negara tertentu, tak berarti ia bisa enak saja membunuh orang. Atau hanya karena ia punya pangkat tertentu—jenderal, presiden—tak berarti mereka berhak. Pembunuhan adalah pembunuhan.
Saat kita bicara soal kejahatan biasa, semua orang sepakat bahwa pembunuh harus dihukum. Itu kesepakatan dalam masyarakat mana pun. Tetapi mengapa para elit dibiarkan saja hanya karena mereka bilang itu “tugas negara”?
Misalnya di Amerika. Jika Presiden Amerika membunuh pasangan mereka, istri atau suami, mereka bakal mengalami kesulitan. Mereka akan dipenjara. Pembunuhan tidak boleh dilakukan.
Tapi jika dilakukan sebagai tugas resmi, misalnya melakukan bombardir, seperti yang dilakukan di Mosul beberapa minggu lalu, yang dilaporkan secara detail dalam investigasi yang saya lakukan dan dirilis minggu lalu, pemboman masjid dan puluhan orang terbunuh, itu pun pembunuhan. [Baca laporan tersebut: “Allan Nairn: Civilian Deaths Are Spiking in Syria & Iraq as U.S. Launches Unrestrained Bombing Raids”]
Mungkin itu bukan pembunuhan dalam tingkat tinggi (first degree), mungkin itu pembunuhan dalam derajat kedua (second degree), mungkin itu pembunuhan tak direncanakan, atau kategori-kategori lain dalam hukum Amerika, tapi itu tetaplah pembunuhan yang ilegal, membunuh orang lain. Anda harus dihukum atau dipenjara. Dan saya pikir kita harus memberlakukan asas itu secara adil, terlepas dari negaranya, atau pangkat seseorang.
Terkait keterlibatan Amerika, dokumen-dokumen rahasia terkait pembunuhan 1965 akan dideklasifikasi musim panas ini oleh pemerintah Amerika. Namun, tidak seperti biasanya, deklasifikasi ini telah diumumkan jauh-jauh hari, bulan Maret lalu. Apakah ini ada hubungannya dengan Freeport? Anda menyebutkan koneksi Trump dan Freeport dalam laporan Anda.
Saya tidak tahu. Tapi saya tidak akan terkejut jika deklasifikasi tidak terjadi atau ditunda. Karena sekarang Trump presidennya. Dia berusaha menyerang hukum, menyerang UU Kebebasan Informasi AS di mana publik dapat memohon dibukanya dokumen-dokumen spesifik. Dan pemerintahan Trump berupaya untuk menghancurkan UU tersebut.
Juga mereka berusaha memecat staf-staf departemen luar negeri yang berwenang atas proyek deklasifikasi dokumen. Saya pikir sedikit sekali peluang dokumen-dokumen itu akan dideklasifikasi, setidaknya tidak akan dideklasifikasi dalam waktu lama ke depan.
Seringkali ada saja hal-hal yang terjadi pada birokrasi di waktu yang salah. Butuh waktu bertahun-tahun buat mengakalinya. Seringkali para politikus dengan kedudukan tinggi juga tidak sadar bahwa keputusan untuk hal-hal semacam itu [deklasifikasi] telah dibuat, sehingga ketika itu terjadi, hal ini sudah tidak signifikan lagi.
Tapi apa yang ingin saya katakan adalah: Lakukan sajalah. Seperti yang kami katakan, orang-orang Amerika, “jangan terus-terusan menunda buat merilis dokumen-dokumen itu.” [Baca analisis kami: Menjelang Dibukanya Arsip Rahasia Amerika Soal 1965]
Satu hal lagi yang harus saya tambahkan terkait dokumen. Pada Oktober 2014, ketika saya mewawancarai Hendropiryono, ketika saya menekan dia untuk maju ke pengadilan, dia bilang siap untuk diadili dalam kasus Munir, Timor Leste, dan Talangsari. Saya juga berhasil membuat dia mengatakan dia akan mengimbau dirilisnya dokumen-dokumen yang relevan untuk kasus-kasusnya, dirilis oleh pemerintah Indonesia, TNI, polisi, intel, serta pemerintah AS, khususnya dokumen dari CIA, Pentagon, dan Gedung Putih. Dia mengatakan “Ya.”
Dalam hukum AS, ada yang dinamakan “privacy waiver” di mana dokumen dirilis dalam situasi mereka harus setuju untuk meloloskan privasinya. Saya tanya Hendro: Apakah dia setuju dia akan mendapat "privacy waiver" jika dokumen-dokumen ini dirilis?
Hendro, secara on-the-record, kepada saya ketika menyatakan kesediaannya, menyerukan kepada pemerintah AS untuk merilis semua dokumen yang berhubungan dengan dia. [Baca: “Rekaman Wawancara Hendropriyono tentang Perannya di Talangsari. Jenderal yang terlibat dalam pembantaian mengklaim para korban “bunuh diri,” mengancam akan “menyerang rumah-rumah gubuk,” dan bersedia diadili untuk kejahatan HAM”. Cerita lengkap tentang tragedi Talangsari, baca: Mengenang Pembantaian Umat di Talangsari]
Saya telah berbicara orang-orang di Kongres AS tentang hal ini dan beberapa dari mereka telah tertarik untuk mendorong eksekutif merilis dokumen-dokumen ini. Ini hal yang harus dilakukan.
Tahun lalu, setelah saya menerbitkan wawancara Hendro, saya diundang ke Komnas HAM untuk membicarakan hal ini. Saya bilang ke mereka: Kalian punya hak untuk meminta dokumen-dokumen ini ke pemerintah AS, bahkan mengeluarkan subpoenas, perintah hukum, untuk mendorong mereka merilis dokumen-dokumen ini.
Dan sebenarnya Indonesia, sebagai negara berdaulat, punya hak untuk mengusut pejabat-pejabat AS jika mereka terlibat dalam kejahatan di Indonesia atau kejahatan yang dilakukan pejabat Indonesia.
Misalnya ketika pembunuhan Munir terjadi, Hendro adalah kepala BIN. BIN memiliki liaison relationship dengan CIA, sebagaimana biasanya. Dan Hendro bilang kepada saya kalau dia bekerja sama dengan CIA ketika menjabat Kepala BIN.
Jadi, CIA punya banyak berkas terkait aktivitas-aktivitas BIN waktu itu, terkait Hendropriyono, terkait percakapan mereka dengan Hendropriyono. [Baca: “Allan Beberkan Soal Hendro ke Komnas HAM”]
Sebagai contoh, saya bertanya ke Hendro: "Apakah CIA mengatakan sesuatu kepada Anda setelah pembunuhan Munir? Misalnya, apakah mereka bertanya siapa pembunuh Munir?" Dia bilang, "tidak."
Ini menarik, karena Hendro adalah aset nomor 1 CIA di Indonesia saat itu dan pembunuhan Munir adalah masalah utama untuk orang yang bekerja di jajaran intel—sensasi besar dalam politik Indonesia. Anda akan berpikir kalau mereka akan tanya: Siapa di balik pembunuhan sensasional ini? Jika pengakuan Hendro benar, CIA ternyata tidak bertanya apa-apa—ini jadi menarik.
Tapi pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengakses dokumen dari pemerintah AS dan berhak juga, di bawah hukum internasional, untuk mendakwa pejabat-pejabat Amerika jika mereka punya peranan dalam penyediaan senjata, uang, atau pelatihan, atau dukungan apa pun kepada personel militer Indonesia yang melakukan kekejaman.
Tentu tindakan ini akan sangat berani. Tapi itu telah dilakukan di Italia. Mereka mendakwa orang CIA dan mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional (international arrest warrant). Beberapa dari mereka telah dibawa ke Italia untuk diperiksa untuk kasus-kasus penculikan, rendition, tindakan-tindakan CIA setelah peristiwa 911 ketika mereka menangkapi orang, menculik orang. Dan pemerintah Italia mempersekusi orang-orang CIA ini. Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan ini jika ia mau.
[Catatan: rendition artinya praktik mengirim tersangka teroris—dalam kasus pasca-911—untuk diinterogasi ke sebuah negara yang ramah terhadap praktik penyiksaan yang brutal terhadap tahanan di penjara buat menggali informasi. Baca, misalnya, laporan soal pemerintahan Bush bertindak kejam terhadap para tahanan di bawah 'perang melawan teror”: “Getting Away with Torture”]
Apakah masih banyak orangnya CIA atau yang telah dilatih CIA di Indonesia, atau menerima fasilitas CIA, dan bagaimana pengaruhnya?
Biasanya hubungan antara intel AS dan pasukan bersenjata/keamanan di negara manapun sifatnya sistematik. DIA [Defense Intelligence Agency, badan intelijen departemen pertahanan AS] berurusan dengan militer. Sementara CIA berurusan dengan intelijen dan polisi.
Dalam kasus Indonesia, CIA berurusan dengan BIN dan polisi. DIA dengan BAIS (Badan Intelijen Strategis) dan berbagai personel militer yang masih aktif.
Tokoh yang bekerjasama dengan DIA adalah Prabowo Subianto. Ketika saya menerbitkan wawancara dengan Prabowo pada 2014, pada bagian 1, dia menyatakan siap menjadi diktator dan dia menghina Gus Dur, ketika dia bicara tentang pembunuhan Santa Cruz, dll.
Bagian II, saya pikir tak banyak yang membaca bagian ini. Seluruh bagian ini berbicara tentang pekerjaannya bersama pemerintah AS, khususnya kerjasamanya dengan DIA dan dia bangga dengan itu—pola-pola hubungan yang mereka rawat secara sistematik. [Baca: Prabowo, Part 2: “I was the Americans' fair-haired boy]
Jadi kita bisa yakin bahwa terdapat macam-macam personel di berbagai lembaga terkait yang yang bekerja sama dengan CIA atau DIA. Kadang-kadang mereka merekrut orang di luar hubungan formal mereka. Anda akan sulit mencari tahu berapa jumlahnya, tapi ini jelas hubungan yang sistematik.
Kampanye anti-Cina, kampanye anti-asing (atau dalam istilah yang lebih mendegradasikan lagi, 'anti-aseng'), menjadi pola dan muncul pada setiap demonstrasi di sekitar Pilkada. Apa yang Anda ketahui soal ini dari pengalaman Anda meliput Indonesia?
Ini menarik. Donald Trump menjalankan kampanye anti-Cina dalam retorikanya ketika berkampanye dan terpilih sebagai presiden. Tapi sekarang setelah bertemu dengan Xi Jinping (Presiden Tiongkok, Sekjen Partai Komunis), dia meninggalkan posisi anti-Cina.
Trump rasis. Dan dia berkampanye sebagai seorang rasis. Ini sikapnya. Perkiraan saya, Trump akhirnya akan mendekat ke Cina, karena mereka memiliki falsafah yang sama: kapitalisme otoritarian. Saya bisa lihat Moskow, Tiongkok, pemerintahan Trump, dan korporasi-korporasi besar akan bersatu membentuk aliansi orang-orang kuat melawan yang lemah. Namun, saya tidak berpikir pemerintah AS mendorong kampanye anti-Cina di Indonesia. Saya pikir tidak masuk akal bagi pemerintah AS untuk melakukannya.
Anda tidak memasukkan isu Anti-Cina ini dalam laporan terakhir?
Saya tidak mengangkatnya di artikel karena keterbatasan ruang. Tapi kampanye anti-Cina di sini sungguh luar biasa. Ketika saya bicara dengan orang-orang dalam gerakan kudeta itu, mereka selalu mengeluarkan racauan-racauan anti-Cina. Misalnya, "Oh, Ahok, dia dikirim ke Beijing untuk dilatih komunis dan kita tahu itu karena sepulangnya ke sini Ahok memakai baju khusus.” Mereka juga mengatakan bahwa jutaan pekerja dari Cina datang ke Indonesia diam-diam dan mereka bisa masuk karena kita membangun banyak bandara baru di daerah-daerah.
Mereka mengatakan hal-hal yang gila. Tapi banyak dari hal-hal gila ini juga datang dari pidato-pidato Jenderal Gatot Nurmantyo. Karena dia mengatakan hal yang sama dalam pidato-pidatonya tentang 'proxy war'. Dalam satu pidatonya, dia bahkan mengatakan jika pengungsi-pengungsi Cina datang ke Indonesia, dia akan menenggelamkan kapal mereka, dan menyembelih sapi supaya hiu-hiu berdatangan dan makan orang Cina. Ini pernyataan yang mencolok untuk seseorang dalam kapasitas panglima TNI. [Catatan: Bahkan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menganggap fenomena LGBT sebagai ancaman proxy war]
Satu elemen dalam gerakan kudeta ini adalah sentimen anti-Cina yang tidak masuk akal. Tapi itu punya sejarah yang panjang dari zaman Soeharto.
Soeharto bermain agak subtil dalam sentimen anti-Cina. Di satu sisi dia bikin kesepakatan dengan pebisnis Cina dan menghasilkan banyak uang. Tapi ketika Soeharto mengalami masalah politik, ia akan mengirimkan preman-premannya untuk menyerang orang Tionghoa. Bukan menyerang pebisnis Cina, melainkan menyerang pedagang dan kelas menengah Tionghoa, menghancurkan toko mereka, main pukul, dan membakar mereka. Kasus yang terkenal adalah Mei 1998 yang selama ini dialamatkan ke Prabowo. Selama bertahun-tahun setelah reformasi, sentimen ini mati. Tapi sekarang merebak lagi dengan dendam dan menjadi alat untuk menggerakkan orang.
Kebanyakan liputan tentang rangkaian demo kemarin menekankan aspek agama. Tapi saya mendapat kesan prasangka etnis yang kuat: anti-etnis Cina, anti-Kristen. Ini cara-cara lama Soeharto. Dan mereka membawanya kembali. Mereka menggunakannya dan membawanya sejauh mungkin.
Penulis: Zen RS
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id