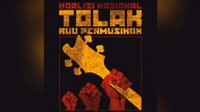tirto.id - Rock n roll dalam bentuk terbaiknya selalu lahir dari rahim yang kecil tapi hangat: klub bau pesing, bar yang menjajakan bir murah, studio berbau keringat; atau dalam kasus The Beatles: bekas gudang buah.
Pada Januari 1957, Alan Sytner membuka The Cavern Club di Liverpool. Terinspirasi dari distrik jazz yang dia saksikan di Paris, Sytner menyewa bekas gudang buah yang pernah dipakai sebagai tempat pengungsian Perang Dunia II. Suatu hari, Sytner bertemu dengan Nigel Walley, manajer dari band bernama The Quarrymen. Walley bertanya, apa bisa The Quarrymen bermain di Cavern. Setelah sempat melalui serangkaian proses audisi, band yang dibentuk oleh remaja bernama John Lennon ini diberi lampu hijau untuk main di Cavern.
Pada 7 Agustus 1957, The Quarrymen tampil pertama kali di Cavern, lantas jadi lumayan sering bermain di sana. Personel datang dan berganti. Paul McCartney kemudian bergabung. Lalu George Harrison. Dan kita semua tahu, The Quarrymen bersulih menjadi The Beatles, band terbesar dalam sejarah musik rock.
Andai Sytner tak membolehkan The Quarrymen tampil, mungkin dunia tak akan kenal The Beatles.
Dua dekade kemudian, di New York, orang-orang menyaksikan bagaimana CBGB tumbuh menjadi sentral kancah musik punk rock. Di bar yang hanya cukup menampung 350 orang itu, bermainlah para musisi yang mulai merintis karier dan kelak akan jadi raksasa.
Saat itu, satu syarat utama bisa manggung di CBGB adalah membawakan lagu sendiri. Sebenarnya Hilly Cristal, pendiri CBGB, memberikan syarat ini karena tak mampu membayar royalti pada The American Society of Composers, Authors, and Publishers jika ada band yang memainkan lagu cover.
Ternyata syarat ini “memaksa” band-band untuk membuat dan memainkan lagu sendiri, dan karenanya punya andil dalam perkembangan kancah musik New York.
Maka, dari CBGB, lahirlah nama-nama seperti Television, Patti Smith, Ramones, The Damned, hingga The Voidoids. Pada dekade 1980-an, band ini juga jadi tempat main bagi Beastie Boys, Agnostic Front, bahkan band asal Los Angeles macam Guns N Roses.
Semangat serupa CBGB juga terjadi di Indonesia. Pada dekade awal 2000, BB’s Bar di Menteng, Jakarta Pusat, menjadi semacam tempat “ibadah” bagi pencinta musik bawah tanah.
Dalam film dokumenter pendek bertajuk “Terekam - Dokumenter Musik Independen Indonesia”, gigs yang dibuat di BB’s berawal dari kebutuhan tempat manggung bagi band-band baru. Dari namanya yang singkatan Blues Bar, BB’s jadi tempat manggung band lintas gagrak.
“Indie saat itu butuh panggung. Mau punk, hardcore, rock, psikedelik, semua butuh panggung,” kata Eunice Nuh, penyelenggara acara di BB’s.
Maka, BB’s jadi saksi hidup kemunculan band-band baru dengan gairah panas khas anak muda Jakarta. Dari Seringai, The Brandals, The Upstairs, White Shoes and the Couples Company, hingga rekan dari Bandung macam The S.I.GI.T. Semua memainkan lagu sendiri, dengan semangat bersenang-senang yang disetel ke titik maksimal. Semangat musisi ini juga menular ke penonton.
“Yang keren dari BB’s itu,” kata Aprilia Apsari, vokalis White Shoes, “tempatnya begitu sempit, tapi semua orang berusaha untuk masuk dan memang niat menyaksikan band-band yang ada di situ.”
Sejarawan-cum-pengarsip musik David Tarigan mengingat suasana BB’s yang bisa menjelaskan hubungan antara rock n roll, tempat sempit, dan kesembronoan yang menyerempet bahaya: “Gila. Dari yang telanjang ada. Yang manggung kepalanya kena monitor terus bocor, MC dengan kata-kata kotor, dan band-band yang sangat variatif."
Salah satu momen paling dikenang dalam sejarah BB’s yang tutup pada 2010 itu adalah pesta peluncuran album Matraman (2004) milik band new wave The Upstairs.
Di YouTube, ada dua rekaman video berharga yang bisa ditonton bersama. Videonya menunjukkan Jimi Danger, vokalis The Upstairs, bertelanjang dada dan berkeringat, bernyanyi setengah meracau, suasana gelap, dan penonton menggila seolah malam itu adalah kesempatan terakhir mereka bersenang-senang.
“Jimi udah enggak ada tempat berdiri, dia berdiri di atas kursi, lalu diarak satu ruangan. Dan Beni sudah enggak pakai baju, pakai boxer doang. Dua backing vokal pingsan. Sisanya tak terkendali. Tapi tetep konteksnya semua saling ngejagain,” ujar Eunice.
Kelak, banyak band yang mengawali karier di BB’s lepas landas menjadi band berpengaruh dalam kancah musik independen Indonesia.
Hal-Hal yang Tak Perlu Diatur Undang-Undang
Obrolan tentang venue musik dan gigs skala kecil ini makin menarik disimak di tengah diskusi panas soal RUU Permusikan. Selain Pasal 5 dan 50 yang paling ramai ditentang oleh para musisi, ada pula pasal 18 dan 19 yang juga sebaiknya dipertanyakan relevansinya.
Pasal 18 mewajibkan promotor maupun penyelenggara acara musik punya lisensi dan izin usaha pertunjukan musik. Selain itu, promotor maupun penyelenggara harus punya izin acara, juga kapan dan lokasi acara, maupun kontrak dan pajak pertunjukan.
Selama ini, penyelenggara konser musik skala kecil maupun besar, lazimnya akan mengurus izin keramaian di kantor Kepolisian Resor (Polres). Namun izin keramaian baru dibutuhkan jika massa atau penonton minimal 300 orang. Untuk konser musik dengan penonton kurang dari 300 orang, barang tentu izin keramaian tak diperlukan.

Mengurus surat izin keramaian tentu sangat merepotkan—dan tak dibutuhkan—bagi penyelenggara gigs kecil, yang biasanya dibikin di kampus, di kafe, atau di lapangan kecil.
Gigs-gigs kecil ini yang jadi pondasi bagi keberlangsungan kancah musik di suatu daerah. Dari Jakarta, Makassar, Ponorogo, Surabaya, Malang, Lumajang, Jember, Samarinda, Jambi, Palembang, atau Jayapura, bisa dipastikan ada banyak gigs skala kecil yang ditonton oleh kurang dari 300 orang.
Pertanyaannya: jika mengurus izin keramaian di gigs kecil saja tak dibutuhkan, apakah lisensi dan izin usaha yang diatur oleh undang-undang masih diperlukan?
Pasal 18 jelas bisa mempersempit gerak penyelenggara gigs skala kecil, yang sudah terbukti bisa melahirkan banyak band baru nan apik. Bahkan tidak hanya di Jakarta, pasal 18 amat berpotensi membunuh pergerakan kancah musik yang baru mekar di kota-kota yang selama ini jauh dari lampu sorot.
“Pasal 18 itu memukul rata semua acara musik tanpa terkecuali, mau besar atau kecil harus memenuhi persyaratan di RUU itu," ujar Amirul BR, salah satu penggerak kancah musik di Ponorogo, Jawa Timur.
"Di Ponorogo, pasal itu jelas memberatkan. Teman-teman di sini bergerak tanpa ada sokongan dana. Murni lewat patungan. Kalau bikin acara agak besar, masih harus izin kepolisian, ada pajak tiket, dan sudah jadi rahasia kalau di zona ini sering banget terjadi pungli. Kalau RUU Permusikan disahkan, bisa jadi biaya perizinan bisa lebih besar ketimbang biaya untuk bikin acara."
Sementara pasal 19 mewajibkan ada pelaku musik Indonesia sebagai pendamping pelaku musik dari luar negeri. Lagi-lagi, pasal ini sudah amat jauh ketinggalan.
Banyak sekali gigs skala kecil yang mengundang (biasanya) band punk rock dari luar negeri, selalu ada band lokal. Begitu pula konser skala besar yang biasanya dibuka oleh band dari dalam negeri. Contoh: Festival Jogjarockarta. Tahun lalu, penyelenggara mengundang Megadeth, dan pembukanya tidak hanya satu band lokal, melainkan tujuh.
Maka, tudingan banyak musisi bisa jadi benar: penyusun naskah akademik dan draf RUU Permusikan ini tidak memahami bagaimana perkembangan kancah musik di Indonesia. Apa yang mereka cantumkan di pasal 18 dan 19 jelas menunjukkan ketidakpahaman mereka—belum lagi pasal-pasal lain—yang menurut Profesor Tjut Nyak Deviana: "95 persennya bermasalah."
=======
Beberapa waktu lalu Tirto merilis serial reportase tentang musik dan kota, dengan pendekatan ke kota-kota luar Jakarta. Laporan ini semakin relevan di tengah kontroversi pasal-pasal karet dalam RUU Permusikan. Kancah-kancah musik ini bergairah dan mewarnai kotanya:
Penulis: Nuran Wibisono
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id