tirto.id - Runa (32) berjuang sekolah S-3 sampai ke Belanda karena ingin menjadi pengajar. Antropolog yang sudah lama meneliti perkebunan sawit di Kalimantan ini menyadari betapa terbatasnya akses pendidikan di Indonesia. “Apabila aku punya ilmu tentang kelapa sawit ini, aku ingin membaginya dengan banyak orang di tanah air,” kata Runa kepada saya, Selasa (31/8/2021).
Koleganya sesama mahasiswa doktoral dari luar negeri kerap bertanya mengapa ia tidak menetap atau bekerja saja di Eropa. Runa menjawab dengan esensi yang kurang lebih sama dengan motivasinya belajar hingga ke luar negeri: “Karena aku ingin membangun negeriku. Ada banyak anak di negara asalku yang belum seberuntung anak-anak di negeri kalian.”
Awal tahun ini, cita-cita Runa tercapai. Ia diterima sebagai dosen di salah satu kampus di Yogyakarta.
Sementara Fitri (29), mahasiswa doktoral tingkat akhir jurusan bioteknologi di Jepang, berminat meneruskan penelitian setelah lulus. “Urutannya buatku adalah riset untuk sektor industri, institut penelitian, atau mengajar di kampus sebagai dosen,” ujarnya ketika dihubungi via pesan singkat, Senin (30/8/2021). “Aku ingin riset, apa pun topik dan bidangnya yang masih berkaitan.”
“Sebelum melanjutkan S-3, aku sempat bekerja di start-up yang memberikan ruang yang luas untuk meneliti. Aku puas dan senang bekerja di sana karena hal tersebut,” tandasnya. Peneliti kopi ini juga tidak menutup kemungkinan berkontribusi di bidang riset untuk industri kosmetik dan kecantikan.
Seperti Runa dan Fitri, perjuangan memperoleh gelar doktor pada umumnya dilalui oleh mereka yang serius meniti karier sebagai pengajar atau peneliti, baik di universitas maupun industri. Pada 2019 silam, Nature merilis survei terkait pengalaman studi doktoral yang melibatkan 6.300 responden dari Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Australasia. Hasilnya, lebih dari separuh responden (56 persen) mengutamakan karier di dunia akademik. Kemudian, sebanyak 28 persen responden menyasar karier riset di ranah industri, diikuti sektor kedokteran (11 persen), dan pemerintahan (10 persen).
Para politikus juga memandang penting gelar doktor. Namun, dari sekian banyak motivasi, sebagian dari mereka tampaknya melihat titel “Dr.” di depan nama penting sebagai aset untuk meningkatkan status dan karier politik.
Jerman
Anggapan bahwa titel doktor penting paling kentara di kalangan elite politik Jerman. Menurut temuan Economist pada 2011, nyaris seperlima anggota Bundestag (majelis rendah), atau sebanyak 114 orang, memiliki gelar S-3. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan Kongres Amerika Serikat yang kala itu hanya memiliki 3 persen (18 orang) anggota dengan gelar S-3, parlemen Inggris (3 persen), juga anggota DPR RI yang hanya sekitar 9 persen.
Melansir statistik 2019, persentase wakil rakyat di parlemen Jerman yang lulus dari perguruan tinggi nyaris mencapai 82 persen, kontras dengan masyarakat pemilik gelar dari universitas yang memperoleh gelar doktor di bidang hukum.
Persentase pemilik gelar doktor berdasarkan partai bisa dibilang cukup rata. Sekitar 21 persen wakil rakyat dari The Green 'Partai Hijau' memiliki gelar doktor. Di bawahnya, kisaran 18-19 persen, pemilik gelar doktor ditemui di partai berhaluan liberal klasik Free Democratic Party (FDP), partai sayap kanan anti-migran A Alternative für Deutschland (AfD), dan faksi Persatuan Demokrat Kristen/ Sosial Kristen (CDU/CSU). Jumlah politikus bergelar doktor dengan persentase terendah ada di The Left 'Partai Kiri' (13 persen) dan Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) (14 persen).
“Apabila politikus Jerman memiliki gelar doktor hukum, mereka akan mencantumkannya dalam selebaran pemilu,” ujar Gerhard Dannemann, dosen hukum dari Humboldt University Berlin dan relawan di lembaga nirlaba pengecek dugaan plagiarisme Vroniplag Wiki, kepada The Guardian Mei silam. Sementara politikus Inggris mungkin justru akan menyembunyikan gelar mereka, imbuh Dannemann.
Kepada Deutsche Welle, Dannemann menjelaskan alasan historis mengapa gelar S-3 dipandang serius di kalangan politikus Jerman. Menurutnya, sampai abad ke-19, tokoh-tokoh berpengaruh Jerman umumnya berlatar belakang bangsawan atau aristokrat. “Kalau Anda cuma orang biasa, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan prestise adalah dengan memiliki gelar akademik,” tutur Dannemann. Bisa dibilang, derajat orang bertitel akan setara seperti mereka yang jadi elite karena darah.
Tradisi politikus bergelar doktor ini bisa ditemui pada era Helmut Kohl, kanselir Jerman Barat (1982-1990) dan Jerman (1990-98). Kohl meraih gelar doktor di bidang ilmu sejarah dari Heidelberg University pada 1958, sebelum terjun ke dunia bisnis dan menjadi politikus mewakili CDU. Demikian halnya Presiden Jerman saat ini yang juga politikus dari SPD, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier mengawali karier sebagai peneliti ilmu sosial di Justus Liebig University. Pada 1991, ia memperoleh gelar doktor di bidang hukum setelah menulis disertasi tentang peranan negara dalam mengatasi kasus tunawisma.
Selain Kohl dan Steinmeier, Angela Merkel yang sebentar lagi mengakhiri masa bakti 16 tahun sebagai kanselir juga memulai karier sebagai akademisi. Setelah menyelesaikan studi fisika di Leipzig University pada 1978, Merkel bekerja sebagai peneliti untuk Central Institute of Physical Chemistry di Akademi Sains Jerman Timur dan meraih gelar doktor di bidang kimia kuantum pada 1986. Tak lama setelah Tembok Berlin runtuh pada 1989, Merkel baru berkecimpung di politik praktis. Kelak, terbiasa dengan pendekatan yang rasional dan berbasis temuan ilmiah membuat Merkel menuai pujian dalam menangani Covid-19.
Sampai 2011, lebih dari separuh kabinet Merkel diisi oleh peraih gelar doktor, yakni 10 dari 16 menteri. Mereka di antaranya Menteri Pendidikan dan Riset Annette Schavan (teologi) serta Menteri Transportasi Peter Ramsauer (administrasi bisnis). Doktor bidang kedokteran diwakili oleh Menteri Buruh Ursula von der Leyen dan Menteri Kesehatan Philipp Rösler, sementara doktor ilmu hukum meliputi Menteri Luar Negeri Guido Westerwelle, Menteri Dalam Negeri Thomas de Maizière, Menteri Lingkungan Norbert Röttgen, dan Menteri Pertahanan Karl-Theodor zu Guttenberg.
Skandal
Mirisnya, obsesi politikus Jerman ini diwarnai dengan beragam skandal, terutama terkait proses pengerjaan disertasi. Salah satunya pernah menimpa Kristina Schröder, anggota DPR dari Partai CDU sejak 2002. Pada 2009, Schröder menerima gelar doktor sosiologi setelah meneliti perbedaan pandangan di kalangan politikus CDU yang menjabat di Bundestag dan di level akar rumput.
Kasus mengemuka ketika Schröder ditunjuk oleh Merkel sebagai Menteri Urusan Keluarga, Lansia, Perempuan dan Pemuda juga pada 2009. Publik menyorot riwayat S-3 Schröder. Rupanya, sebagian data diolah oleh staf bayaran. Sebagai pembelaan, Schröder menganggap lumrah membayar asisten dalam riset.
Selama sepuluh tahun terakhir, segelintir figur di administrasi Merkel mengundurkan diri karena terbelit kasus plagiarisme disertasi.
Kasus yang heboh pernah terjadi 2011 pada Menteri Pertahanan Karl-Theodor zu Guttenberg. Politikus keturunan keluarga ningrat Guttenberg dari kawasan Bavaria yang juga suami dari pembawa acara TV berdarah biru Stephanie von Bismarck ini bak selebritas sampai digadang-gadang bakal jadi kanselir. Citra Guttenberg redup setelah terungkap bahwa sejumlah besar paragraf dalam disertasinya—yang diselesaikan pada 2006 ketika menjabat sebagai anggota dewan mewakili CSU—tidak dilengkapi dengan sumber yang benar.
Media-media Jerman sampai menyindir Guttenberg dengan nama panggilan Baron Cut-and-Paste, Zu Copyberg, dan Zu Googleberg. Setelah University of Bayreuth mencabut gelar doktornya, Guttenberg mengundurkan diri dari kabinet dan pergi ke Amerika Serikat untuk memulai karier baru sebagai penasihat industri start-up.
Menteri Pendidikan Annette Schavan tersandung skandal serupa pada 2013. Komite Heinrich Heine University di Düsseldorf menyimpulkan bahwa politikus CDU ini “secara sistematis dan sengaja” melakukan plagiarisme dalam disertasi berjudul “Pribadi dan Hati Nurani” yang selesai ditulis pada 1980. Empat hari setelah gelar doktornya dicopot, Schavan yang bersahabat dekat dengan Merkel akhirnya mengundurkan diri sebagai menteri. Terlepas dari itu, sejumlah sumber mengungkap bahwa Merkel masih menghormati Schavan. Setahun kemudian, ia ditugaskan sebagai duta besar untuk Vatikan.
Baru-baru ini, Menteri Urusan Keluarga Franziska Giffey juga kehilangan jabatan karena skandal disertasi. Sejak awal 2019, Giffey sudah disorot karena disertasinya—yang diajukan untuk Freie Universität Berlin pada 2010—mengandung unsur plagiarisme. Sebelum bergabung dengan SPD pada 2007, Giffey sempat bekerja sebagai staf perwakilan untuk Uni Eropa. Ingar bingar plagiarisme ini akhirnya memaksanya mundur dari kabinet Merkel pada Mei silam. Sebulan kemudian, pihak universitas resmi mencabut gelar doktornya. Terlepas dari itu, Giffey masih mantap untuk maju sebagai calon Wali Kota Berlin dalam pemilu September mendatang.
Kasus Lain
Politikus bergelar doktor di negara Eropa lain juga pernah tersandung skandal plagiarisme. Misalnya Presiden Hungaria yang terpilih pada 2010 sekaligus peraih medali emas untuk olahraga anggar tahun 1968 dan 1972, Pal Schmitt. Schmitt mengundurkan diri tahun 2012 setelah ketahuan menjiplak hasil karya orang lain untuk disertasi bertema Olimpiade yang disusun pada 1992.
Ada pula kasus Victor Ponta, Perdana Menteri Rumania 2012-2015. Ponta memperoleh gelar doktor saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Di negeri itu, pencapaian akademik dipandang penting oleh elite masyarakatnya, tak terkecuali para politikus. Masalahnya universitas swasta dan negeri bahkan dianggap sudah jadi “pabrik penghasil gelar” yang kurang memperhatikan kualitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan dan malah menyuburkan plagiarisme.
Sementara di Rusia, pelanggaran sistematis di dunia akademik oleh kalangan politikus dan birokrat dipandang sudah lazim terjadi, demikian disampaikan dalam riset berjudul “The real costs of plagiarism: Russian governors, plagiarized PhD theses, and infrastructure in Russian regions” (2020). Studi yang dilakukan oleh Anna Abalkina dan Alexander Libman ini menggunakan sampel sejumlah kepala daerah setingkat gubernur sepanjang 2012-17. Menurut perhitungan kasar, ditemukan separuh di antaranya punya gelar S-3 dan sebagian diketahui terlibat plagiarisme.
Studi ini menyimpulkan bahwa riwayat plagiarisme mencerminkan rendahnya standar etika dan kemampuan manajerial para kepala daerah. Akibatnya, kawasan yang dipimpin gubernur-gubernur plagiator punya performa ekonomi rendah dengan pembangunan infrastruktur yang tersendat.
Abalkina dan Libman juga mencoba memberikan penjelasan kenapa plagiarisme langgeng terjadi di kalangan elite politik Rusia. Pertama, resesi ekonomi setelah runtuhnya Uni Soviet pada dekade 1990-an. Hal ini turut berdampak pada merosotnya besaran gaji staf dosen di kampus berikut status sosial mereka. Akibatnya, mulai marak praktik jual-beli gelar akademik dan perusahaan-perusahaan swasta menawarkan jasa sebagai ghostwriter atau penulis bayangan—kelak pasar ini berpotensi sebagai ladang korupsi.
Di sisi lain, ada pula penjelasan yang berkaitan dengan pandangan di kalangan elite politik dan birokrat Rusia: bahwa gelar S-3 tak hanya memberikan keuntungan material tapi juga status sosial. Pandangan ini diduga merupakan warisan dari era birokratisme Soviet yang menjunjung tinggi pendidikan dan pencapaian akademik. Permintaan akan gelar S-3 palsu pun meningkat seiring munculnya tekanan di kalangan sesama politikus yang mengincarnya.
Kasus plagiarisme yang menjangkiti politikus Rusia ini rupanya jarang berujung pada hukuman seperti kehilangan jabatan yang kerap terjadi di Jerman. Sebagai contoh, posisi Vladimir Putin sama sekali aman meski investigasi think tank Brookings Institution di AS pada 2006 menemukan dugaan plagiarisme pada disertasinya. Bulan April silam, Rusia bahkan meloloskan legislasi yang memungkinkan Putin menjabat sebagai presiden “seumur hidup”, tepatnya sampai 2036.
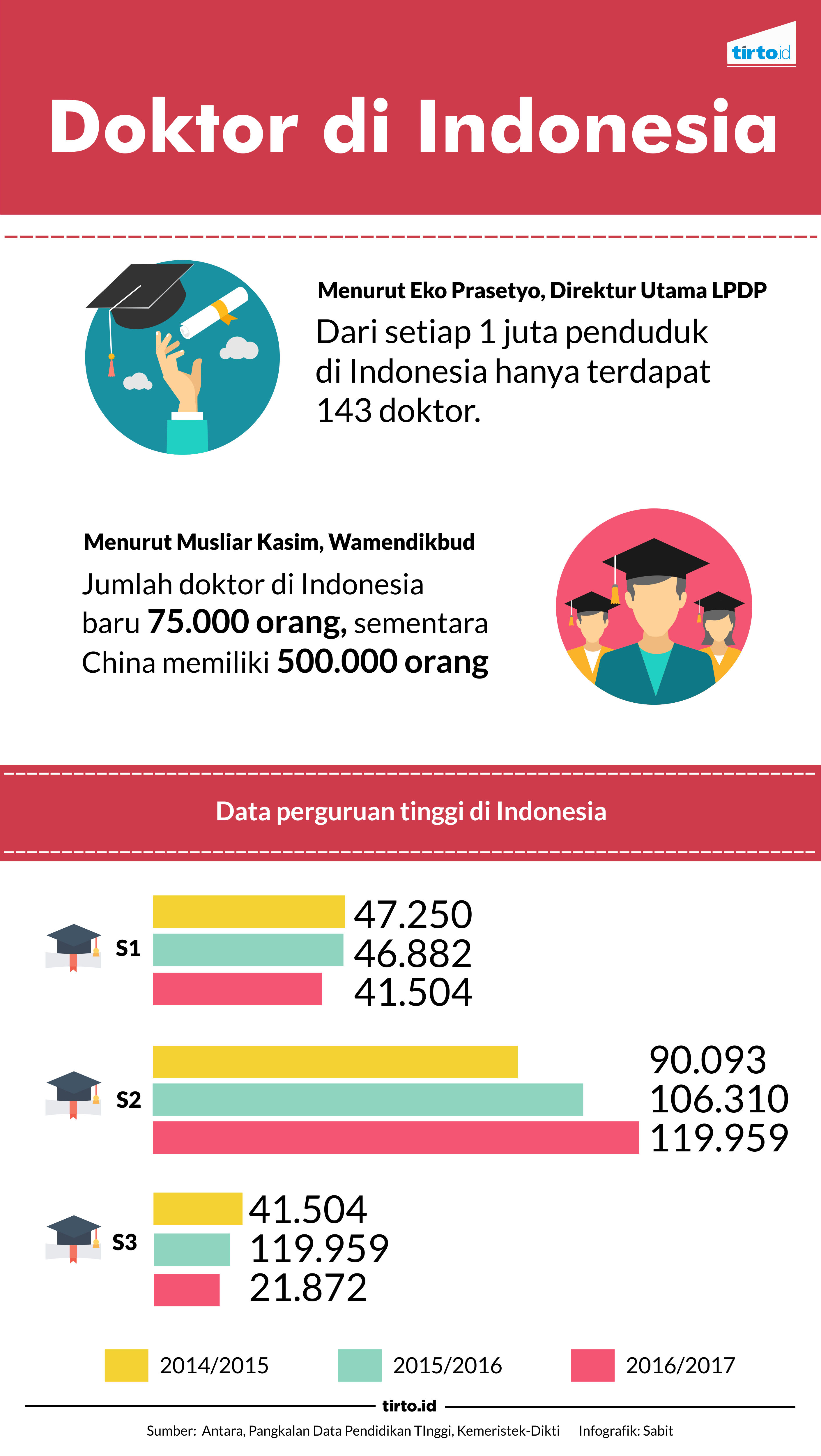
Elisabeth Braw, kolumnis untuk Foreign Policy, mengatakan keahlian spesifik yang diperoleh selama studi S-3 memang berkontribusi meningkatkan kemampuan politikus dalam menerapkan kebijakan publik. Namun ia juga menunjukkan bahwa sejumlah besar pemimpin dunia tanpa gelar S-3 tetap menuai sanjungan karena kepemimpinannya yang baik, seperti Sanna Marin (Perdana Menteri Finlandia) dan Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru).
Braw juga menyorot Kanselir Jerman Helmut Schmidt (1974-82) sebagai pemimpin Jerman pasca-Perang Dunia II paling intelek meskipun tidak bergelar doktor. Ada pula Václav Havel, dramawan dan esais kenamaan yang menjabat Presiden Ceko (1993-2003). Meskipun tak kesampaian sekolah tinggi karena pembatasan rezim sosialis Ceko, karya sastranya senantiasa menjadi bahan penelitian mahasiswa doktoral.
Selain itu, beberapa figur politik berpengaruh bahkan tidak punya gelar universitas, seperti Menteri Luar Negeri Jerman Joschka Fischer (1998-2005) atau Perdana Menteri Swedia Thorbjorn Falldin (1976-82) yang merupakan petani lulusan SMA.
Bagaimana dengan Indonesia? Empat tahun lalu Tirto pernah menurunkan laporan plagiarisme yang dilakukan lima pejabat di lingkungan Pemprov Sulawesi Tenggara, termasuk Gubernur Nur Alam, terpidana korupsi yang kemudian divonis penjara pada Maret 2018, di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Konsekuensinya, rektor dicopot karena dianggap membantu aktivitas ilegal tersebut, sementara plagiator sekadar diminta membuat ulang disertasi baru.
Dari kasus-kasus di atas, nampaknya gelar akademik memang terlalu menarik bagi para politikus, tapi sebagian dari mereka enggan atau bahkan tak mampu meraihnya dengan cara yang benar dan wajar.
Editor: Rio Apinino
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id







































