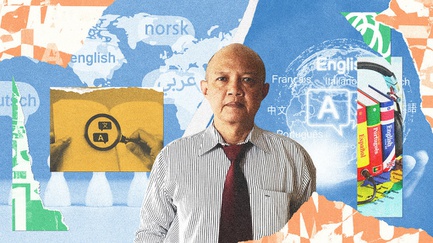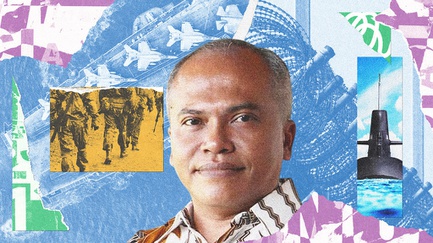tirto.id - Semua orang sepakat bahwa guru di Indonesia harus sejahtera. Namun, untuk pertanyaan apakah guru yang tidak berkualitas layak hidup sejahtera? Boleh jadi, sebagian dari kita menganggap bahwa mereka layak mendapatkan gaji rendah. Itulah salah satu persoalan mengapa guru yang tidak sejahtera menjadi sebuah kelaziman. Meski demikian, ada tiga hal mengapa guru tetap tidak sejahtera.
Pertama, tantangan internal. Tantangan internal ini terbagi tiga. Pertama, yaitu ketidakjelasan posisi guru, apakah ia adalah public servant (pegawai pemerintah) atau profesi otonom. Dalam Decentralization in Education, Institutional Culture and Teacher Autonomy in Indonesia (2004), Christopher Bjork menyebutnya sebagai konflik identitas ganda para guru ASN. Seringkali para guru melihat dirinya sebagai pelayan pemerintah yang bertugas menafsirkan dan menerapkan setiap kebijakan kurikulum apapun warnanya, suka tidak suka.
Sementara, jika guru menyadari bahwa profesinya otonom, maka ia bisa menolak, atau mengkritik sebuah kebijakan pendidikan, atas nama profesinya dan keahlian bidangnya, tanpa mengkhawatirkan statusnya sebagai ‘abdi negara.’ Ketika dihadapi oleh pilihan yang sulit, terutama guru ASN, akan mengutamakan kewajiban administrasi daripada substansi mencerdaskan anak bangsa.
Laporan administrasi menjadi penentu karir para guru semacam ini. Oleh sebab itu, keberadaan paradigma ‘evidence based learning’ memperparah keadaan ini, bahwa guru harus menyusun laporan atas kegiatannya sendiri. Waktu habis untuk administrasi. Sehingga, tidak ada lagi ruang diskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan kemampuan dalam bidang mata pelajaran spesifiknya.
Tantangan internal kedua adalah sulitnya mengembalikan kesadaran masa lampau para guru ke masa kini. Di masa pergerakan, organisasi guru Persatuan Goerroe Hindia Belanda (PGHB) tercatat sebagai pelopor dan atau organisasi serikat pertama yang lahir di Hindia Belanda.
Pergerakannya cukup progresif. Organisasi ini mendirikan koran dengan barisan opini dari para guru yang cukup keras menentang kebijakan pemerintah. Seringkali dengan satir tanpa menuliskan nama asli, dan menjadikan surat kabar sebagai media komunikasi keadaan antar guru di tiap daerah. Selain itu, organisasi ini menerbitkan laporan keuangan di bagian belakang koran.
Karakteristik guru intelektual semacam ini makin terkikis oleh waktu. Paska Indonesia merdeka, PGHB bertransformasi menjadi PGRI. Puncaknya, pada masa Orde Baru, Rakhmat (2019) menyebut bahwa organisasi serikat guru malah bertranformasi menjadi corong kampanye Orde Baru. Terutama para guru yang memiliki kemampuan public speaking yang baik, selalu hadir dalam setiap kampanye Golkar.
Pada masa Orde Baru, terjadi pembersihan gerakan-gerakan serikat, sehingga organisasi guru juga menjadi mandul dan sangat birokratis. Kesadaran bahwa para guru berada dalam konteks ketertindasan yang sama dengan para pekerja lain, seperti buruh, makin memudar.
Walhasil, seperti ditulis Vina Adriany dalam artikel jurnal "“We are not labors; we are teachers":Indonesian early childhood teachers’ organizations as a form of a panopticon", sangat sulit dilakukan konsolidasi untuk perjuangan kesejahteraan guru, sebab mereka sendiri tidak mau disamakan dengan buruh (Adriany, 2023).
Tantangan internal ketiga adalah lemahnya intelektualitas guru. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstrernal, seperti jam kerja (waktu luang), relasi kuasa di sekolah dan pemerintah, serta relasi guru terhadap profesinya sendiri. Intelektualitas ditentukan oleh sejauh mana para guru mampu merefleksikan bidang pelajarannya, kehidupan siswa dan peristiwa aktual yang sedang terjadi.
Seringkali guru mulai kehilangan otonominya ketika bicara peristiwa aktual. Misal, dalam beberapa peristiwa politik seperti demonstrasi, para guru seringkali berada pada posisi aktor lapangan aparatus ideologis negara. Misal, praktik menghimbau siswa agar tidak ikut berdemonstrasi atau menjadi juru bicara untuk membenarkan semua program pemerintah dengan sasaran para siswa di sekolah.
Tantangan Eksternal
Tantangan eksternal guru untuk sejahtera berasal dari rantai distribusi guru. Pertama, pada level produksi, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia melahirkan ratusan ribu calon-calon guru yang harus berebut di pasar kerja guru setiap tahun.
Lulusan LPTK, termasuk LPTK swasta yang jumlahnya 90%, seringkali dilaporkan “gampang masuk dan gampang keluar", menyebabkan pasar kerja guru makin bersaing ketat, bukannya dalam hal kualitas, namun persaingan dengan para penganggur kronis, sehingga harga guru di pasar pendidikan makin jatuh. Ini belum dihitung dengan migrasi pengangguran terdidik dari sektor non-LPTK atau lulusan ilmu murni yang memilih menjadi guru, karena sulitnya mencari pekerjaan di bidangnya. Mereka dengan mudah menjadi guru hanya tinggal mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Tantangan eksternal kedua, adalah kasta guru. Kasta guru ini terbagi secara yuridis, institusional, serta secara status kepegawaian. Secara yuridis, guru di Indonesia diatur oleh lebih dari lima undang-undang. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
Seorang guru di Indonesia dilahirkan oleh LPTK, dan mendapatkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di institusi Perguruan Tinggi. Jika mereka ASN, maka mereka adalah pegawai pemerintah daerah. Jika mereka non-ASN maka mereka adalah pegawai yayasan atau lembaga tempat terselenggaranya sekolah tersebut.
Namun, jika mereka guru ASN madrasah, mereka adalah pegawai Kementerian Agama. Jika mereka guru madrasah swasta, mereka pegawai yayasan atau lembaga penyelenggara madrasah yang bersangkutan. Penentu kepesertaan PPG guru adalah Dirjen GTK Kemdikdasmen dan Kemenag, sementara yang memberikan pendidikannya adalah Perguruan Tinggi.
Ini belum termasuk keberadaan Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda, yang artinya saat ini pendidikan tidak hanya dikelola oleh Kemdikdasmen dan Kemenag, namun dikelola oleh Kemendiktisaintek yang sejatinya mengelola pendidikan tinggi, serta Kementerian Sosial yang sejatinya mengelola anak terlantar, malah membuka Sekolah Rakyat.

Status kepegawaian guru juga beragam. Di atas kertas, hanya ada dua jenis guru, ASN dan non-ASN. Untuk ASN terbagi dua, yaitu PNS dan PPPK. Namun, guru yang bekerja di lingkungan sekolah/madrasah negeri bukan hanya ASN. Tapi juga ada guru honorer yang terbagi menjadi dua jenjang.
Jenjang pertama dengan kesejahteraan minimal, disebut honorer daerah (honda) yang artinya bukan ASN namun dbayar pemda sesuai UMR. Jenjang paling bawah disebut guru honorer ‘murni.’ Kata 'murni' mengacu pada ketiadaan status sama sekali, sehingga guru tersebut sejatinya tidak diakui kepegawaiannya, kecuali hanya oleh kepala sekolah tempatnya mengajar. Seringkali itu hanya kesepakatan lisan. Inilah yang membuat daya tawar posisi guru makin rendah.

Status kepegawaian guru juga berkasta-kasta. Meskipun sudah menjadi guru honorer bertahun-tahun, belum tentu sekolah memasukan namanya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Misal, guru honorer mendapatkan posisi aman jika sudah masuk namanya dalam Dapodik. Pada tahap berikutnya, guru semacam ini akan terdata dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Keberadaan NUPTK menjadi syarat kepesertaan Pendidikan Profesi Guru atau PPG, yang ujungnya sertifikasi guru. Namun belakangan, dalam PPG kali ini, guru bisa mengikuti tanpa harus memiliki NUPTK.
Pada sisi lain, adalah guru honorer swasta yang disebut Guru Tidak Tetap (GTT) yayasan. Artinya guru tersebut berstatus tidak tetap sehingga mempengaruhi gaji dan pendapatannya. Yang lebih miris adalah guru-guru honorer swasta yang berasal dari madrasah. Karena sebagian besar madrasah didirikan dengan misi sosial, serta bayaran supermurah, maka gurunya pun dibayar lebih murah dan nyaris tidak mendapatkan gaji sama sekali.
Untuk sebuah pengakuan tanpa kesejahteraan yang melekat sekalipun, para guru tetap kesulitan dan harus mengemis untuk memperjuangkan keberadaan dirinya yang selama ini tidak diakui. Entah sampai kapan para harus guru secara rutin mengunjungi Komisi X DPR-RI, menangis lagi, dan terus seperti itu, mengulangi sampai tahun-tahun yang akan datang.
Semua masalah ini bisa diselesaikan jika pemerintah melakukan perbaikan pendidikan secara multisektor, memperbaiki disparitas dan kesenjangan antara Undang-Undang yang mempengaruhi guru, merampingkan institusi yang mengelola guru, serta memberikan langkah pasti sebagai komitmen mensejahterakan guru melalui program yang langsung berdampak. Semua itu nampak mudah jika seandainya Presiden Prabowo sedikit menyempatkan dalam hidupnya, satu kali, menandatangani Peraturan Pemerintah dan menetapkannya sebagai upah minimum guru. Namun itu tidak pernah terjadi, hingga sekarang.
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id