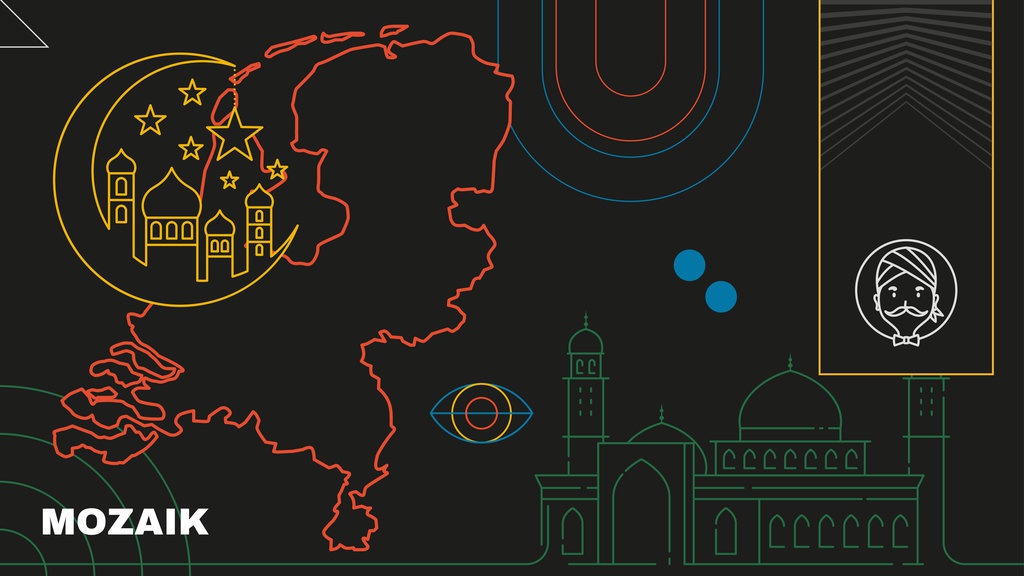tirto.id - Sekitar 5 persen atau kira-kira satu juta jiwa dari total populasi Belanda saat ini beragama Islam. Orang-orang keturunan Turki menjadi penyumbang terbesar kaum muslim Belanda dengan 372.000 jiwa, kamudian Maroko 335.000, Pakistan 50.000, Irak 45.000, Afghanistan 38.000, dan Iran 30.000.
Sedangkan Indonesia menyumbang sekitar 10.000 jiwa. Sisanya digenapi oleh negara-negara lain yang jumlahnya lebih kecil, termasuk keberadaan 12.000 warga asli dan keturunan Belanda serta Eropa lainnya yang menjadi pemeluk Islam.
Keberadaan muslim di negeri ini tak berhubungan dengan kolonialisme, melainkan migrasi terutama dari negeri berpenduduk muslim besar yang berjarak tidak terlalu jauh dari Belanda, demikian dituturkan Thijl Sunier dalam "Islam in the Netherlands, Dutch Islam" (Muslims in 21st Century Europe, 2010).
Pada 1960-an, dipicu keengganan warga asli Belanda melakukan kerja-kerja kasar berupah minim, warga negara Turki dan Maroko yang mayoritas beragama Islam didatangkan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja ini. Mereka diasumsikan akan kembali ke kampung halamannya usai memperoleh uang yang cukup. Namun, sebagian besar justru bertahan.
Bahkan warsa 1970-an kaum migran yang didatangkan Belanda ini turut mengundang keluarga mereka untuk hidup bersama di Belanda. Akhirnya mereka melahirkan generasi baru, yakni warga yang lahir di Belanda dan beragama Islam.
Belanda kemudian mencoba melakukan pengklasifikasian. Warga asli Belanda beragama Islam keturunan perantau asal Turki dan Maroko (serta negara lainnya) disebut sebagai “allochtonous” atau “warga Belanda keturunan non-Belanda”. Kelompok ini mendampingi warga yang berstatus lebih tinggi, yakni “autochthonous” atau “warga Belanda keturunan Belanda”.
Menurut W. A. R. Shadid dalam "Islam in the Netherlands: Constitutional Law and Islamic Organization" (Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 16 1996), beruntung usaha merendahkan status warga yang beragama Islam ini tak berhasil dilakukan karena Belanda menerapkan “pillarisation-system”.
Sistem yang dibangun pada akhir abad ke-19 ini memberi kebebasan masyarakat Belanda untuk memeluk agama (ataupun tidak memeluk) sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang diterjemahkan dalam Pasal 1 (tentang non-diskriminasi), Pasal 6 (tentang beragama), dan Pasal 7 (tentang pendidikan) konstitusi Belanda.
Pada 1981, Belanda juga meratifikasi kehendak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan falsafah hidup.
Lewat dukungan yuridis, juga karena warga Belanda kian tak peduli dengan agama (kini mayoritas penduduk Belanda tak beragama), Islam tumbuh dan berkembang secara baik di Belanda. Ini dibuktikan bukan hanya dengan semakin menjamurnya masjid--yang disubsidi negara jika diajukan tak kurang dari 10.000 penganut (berlaku untuk agama lain)--juga kian berkembangnya pendidikan Islam di sekolah-sekolah.
Menurut K. H. Ter Avest dalam "Half a Century of Islamic Education in Dutch Schools" (British Journal of Religious Education, Vol. 39 2017), pendidikan Islam di Belanda tak hanya tersaji di sekolah Islam atau sekolah privat yang umumnya didirikan kaum perantau beragama Islam, tetapi juga di sekolah-sekolah umum. Dengan menerapkan pelajaran bertajuk Geestelijke Stromingen atau “Gerakan Spiritual,” Islam diajarkan di Belanda secara umum.
Sayangnya, kehidupan beragama Islam di Belanda yang tenteram sejak 1960-an ini tak bertahan lama. Memasuki dekade 1980-an, meskipun negara tetap netral terhadap kehidupan beragama, sentimen negatif terhadap Islam menggelora di tengah publik Belanda, khususnya dari warga Belanda keturunan Belanda atau “autochthonous”.
Ironisnya, perubahan sikap ini tak dipicu kejadian di dalam negeri, melainkan oleh Revolusi Iran 1979 dan fatwa Khomeini pada 1989 yang ditujukan untuk Salman Rushdie. Yang terbaru adalah lewat Peristiwa 9/11 pada 2001.
Menurut Leen d’Haenens dalam "Islam in the Dutch Press" (Media, Culture & Society, Vol. 29 2006), mayoritas penduduk Belanda yang melihat Islam sebagai biang pelbagai masalah di negerinya, persis seperti masyarakat Jerman melihat kaum Yahudi pada akhir Perang Dunia Pertama.
Sikap ini, misalnya, dapat dilihat melalui sejumlah pemberitaan negatif tentang Islam di media-media Belanda, yang ironisnya memilih non-muslim sebagai sumber informasi. Atas perubahan sentimen ini, perlahan perlakuan negara pun berubah. Kini tak ada lagi subsidi pembangunan masjid, juga tempat peribadatan agama lainnya.
Pemerintah Belanda dan sebagian besar masyarakatnya yang kian sekuler, kian sigap memonitor pergerakan Islam, salah satunya yang dilakukan Tweede Kamer der Staten-Generaal (setara dengan DPR di Indonesia) dengan menginisiasi pemonitoran skala besar-besaran terhadap Islam pada 1998 dan 2002.
Sikap ini juga pernah dilakukan Belanda kala pertama kali berhubungan dengan Islam di Hindia Belanda (Indonesia).
Ketakutan Belanda
Melalui amandemen konstitusi, sejak 1848 pertanggungjawaban terhadap wilayah koloni diserahkan dari kuasa raja ke tangan parlemen. Menurut Michael F. Laffan dalam "'A Watchful Eye': The Meccan Plot of 1881 and Changin Dutch Perceptions of Islam in Indonesia" (Archipel Vol. 63 2002), implementasi peralihan kekuasaan ini ditandai dengan dimulainya pengiriman mailrapporten atau surat laporan secara rutin setiap minggu.
Surat laporan ini dikirim dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) kepada Menteri Koloni yang berkedudukan di Den Haag.
Jika laporan yang dikirim super penting, maka mailrapporten langsung diserahkan kepada parlemen untuk dibahas dan dimasukkan ke dalam verbalen atau risalah parlemen.
Secara umum, mailrapporten yang dikirim berisi tentang tetek bengek roda perdagangan Belanda di Hindia. Dalam tataran terbatas, mailrapporten juga berisi petikan keputusan Dewan Hindia (Raad van Indie), berita penjelajahan, ekspedisi militer, peraturan kolonial, dan Keputusan Pemerintah (besluiten).
Singkatnya, segala gerak-gerik Belanda di Hindia Belanda serta apapun yang terjadi di negeri jajahannya tersebut dilaporkan ke pusat melalui mailrapporten, termasuk tentang invasi Belanda ke Aceh.
Invasi yang berlarut-larut karena kegigihan ulama Aceh memimpin perlawanan, memunculkan ketakutan Belanda terhadap Islam untuk pertama kalinya. Dan mulai saat itu, Islam menjadi tema utama mailrapporten.
Tema ini sebelumnya tak pernah muncul, bahkan ketika petani di Cianjur mengadakan protes pada Mei 1872 terhadap pajak yang dibebankan Pemerintah Kolonial Belanda dengan dalih mereka telah membayar zakat. Atau saat gerakan yang mengaku Imam Mahdi pimpinan Soero Soemito dan Soero Setiko di Surakarta muncul pada 1869.
“Belanda khawatir kegigihan ulama Aceh mampu mempersatukan pribumi secara agama dan menghapus semua program Belanda yang ‘bermaksud baik’,” tulis Laffan.
Terlebih, setelah pembukaan Terusan Suez, banyak pribumi Hindia Belanda yang melakukan perjalanan suci ke Tanah Suci. Pada Mei 1880, Makkah dikuasai Abd al-Muttalib, sang “Sharif of Mecca” yang terkenal anti-nasrani cum tokoh utama di balik pembantaian orang Kristen di Jeddah pada 1858. Tak hanya itu, Abd al-Muttalib juga salah satu tokoh utama perjuangan masyarakat Mesir dan Aljazair melawan penjajahan Barat.
Reputasinya ini, imbuh Laffan, dikhawatirkan Belanda dapat memompa semangat perlawanan yang dilakukan ulama-ulama dan para jemaah haji asal Aceh.
Ketakutan ini kian menjadi-jadi setelah sebuah surat berbahasa Arab yang ditulis di Makkah oleh seorang Arab Sumatra bernama Muhammad Salih bin Abd al-Qasim berhasil dicegat Belanda. Dalam surat itu disebutkan bahwa muslim di Hindia Belanda akan berkumpul untuk membicarakan perang di rumah salah satu pemimpin mereka bernamas Syaikh Oelah di Batavia.
Hal ini membuat Belanda tak hanya memantau pergerakan Islam di tanah jajahannya, tetapi juga dari Jazirah Arab dan Turki Usmani sebagai kekuatan Islam terbesar di dunia saat itu.
Tak lama kemudian tersiar kabar burung dari Konstantinopel yang menyebut ada “dua ulama Muhammad” dari Makkah yang mengaku mendengar bahwa umat Islam di Inggris (Malaysia) dan Hindia Belanda tengah bersiap untuk berperang melawan orang-orang kafir (Inggris dan Belanda).
Pada 14 Maret 1881, Gubernur Jenderal J. W. van Lansberge mengeluarkan dekrit meminta anak buahnya di segala administrasi lokal/regional Hindia Belanda untuk melaporkan tindak tanduk pergerakan Islam, ia khawatir “Holy War” akan muncul.
Mereka lalu membuat daftar hitam penduduk Hindia Belanda beragama Islam yang dicurigai mengancam, termasuk warga keturunan Arab dan terutama orang-orang pribumi yang telah melakukan ibadah haji.
Kala ada orang Arab baru yang ditengarai hendak ke Hindia, sirine dinyalakan. Gubernur Jenderal F. Jacob pernah mencegah empat warga Arab, yakni Said Hoessein ibn Said Mohamad Alkoedsi, Sheikh Abdul Hamid Murlad (Murdad), Sheikh Achmed bin Abdul Karim Salawij, dan Said Arsa masuk ke Hindia dengan menggiring mereka kembali ke titik asal non-Hindia pertama, yakni Singapura.
Kecurigaan Belanda terhadap kemungkinan munculnya pergerakan perlawanan berbasis Islam juga dilakukan dengan mengirim pasukan khusus untuk memantau pergerakan Maharaja Abubakar dari Johor yang tengah berkunjung ke Jawa pada 1881. Kala itu, Maharaja Abubakar sebetulnya hanya pelesiran.

Nasihat Holle
Untuk menekan kekhawatiran, Belanda lantas berencana menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kaum muslim di Nusantara. Terlebih, Karel Frederik Holle, Penasihat Pemerintah Kolonial Belanda cum tokoh Belanda yang berperan penting dalam melestarikan bahasa Sunda, mendukung rencana ini.
Dalam surat yang dikirimkan Holle pada Maret 1872, ia merekomendasikan semua penghulu ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kolonial. Holle merekomendasikan bahwa orang-orang yang ditunjuk ini harus dikeluarkan dari jabatannya jika mereka terlalu bersemangat soal Islam. Ia yakin meningkatnya jumlah haji yang kembali dari Makkah membawa aliran baru kefanatikan agama di Jawa.
Tak cuma itu, Holle juga memberi nasihat panjang lebar: (1) Penduduk asli harus dihukum karena mengadopsi nama dengan referensi keagamaan, (2) Semua hoofd panghoeloe (kepala penghulu) harus ditunjuk pemerintah, (3) Tidak ada “fanatieken” yang boleh ditunjuk untuk jabatan tersebut, (4) Bupati harus disingkirkan dari pengaruh Islam, (5) Para haji dilarang mengenakan jenis pakaian Arab atau Turki.
Selanjutnya, Holla juga mengusulkan: (6) Pengawasan harus dipertahankan tidak hanya pada pers pribumi, tetapi juga pada setiap terbitan berkala atau teks yang ditulis dalam bahasa Arab, (7) Pengawasan serupa dipertahankan terhadap misionaris "fanatik" atau "berpikiran sempit" yang aktif di wilayah muslim, (8) Bupati yang bertindak sebagai imam harus bersumpah setia kepada pemerintah di atas Al-Qur'an, (9) Bupati disumpah dengan kalimat selain "Maka tolonglah aku Tuhan Yang Maha Esa", dan (10) Seorang mata-mata ditempatkan di Makkah untuk bertindak di bawah arahan Konsul Jeddah.
Namun rencana ini dengan kemungkinan adanya “Holy War” di Nusantara tak semuanya diterapkan Belanda. Pasalnya, melalui penelitian komprehensif yang dilakukan L. W. C van den Berg, administrator Hindia Belanda cum akademisi fikih lulusan Universitas Leiden, ketakutan Belanda terhadap Islam hanyalah omong kosong.
Menurut van den Berg, jika Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan aturan anti-Islam di Hindia Belanda, maka aturan tersebut akan berbalik terhadap Belanda sendiri. Mengubah ketakutan yang hanya omong kosong menjadi nyata.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id