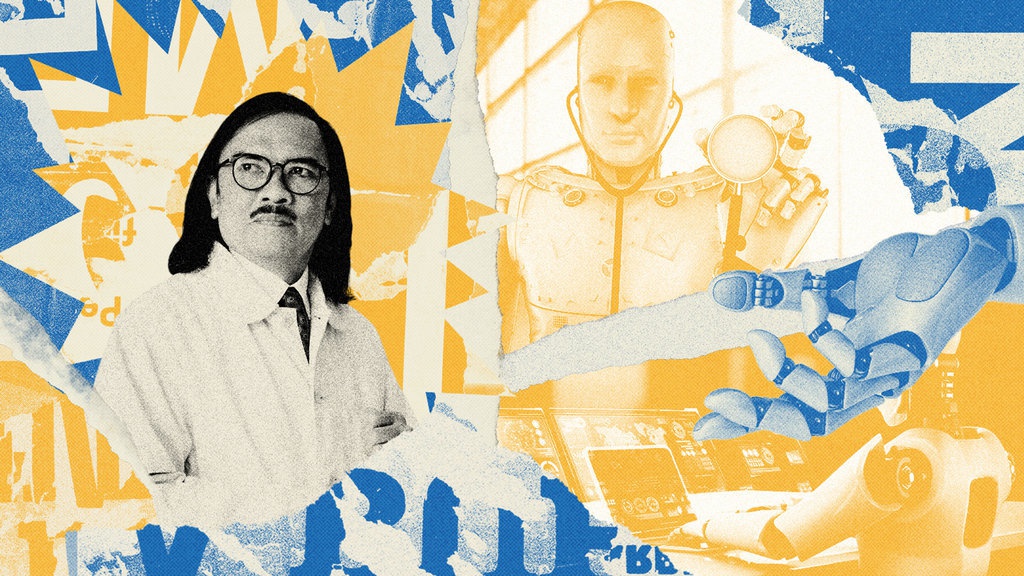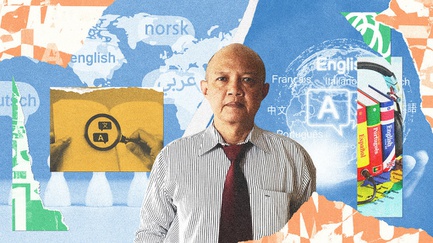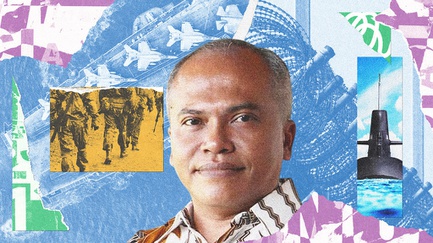tirto.id - Peluncuran Veo 3 oleh Google di tengah acara Google I/O2025 disambut riuh. Perangkat berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan ini tak henti-hentinya mengundang decak kagum.
Veo 3 disebut mampu mengubah susunan kata dalam prompt menjadi video profesional. Gerbang pengartikulasian ide-gagasan-konsep terbuka lebar. Substansi yang semula abstrak dapat dihadirkan sebagai material konkrit.
Walapun Veo 3 bukan yang pertama hadir–sebelumnya ada SoraAI dengan kemampuan serupa–namun disebut eksekutif Google, perangkat baru ini punya lebih banyak keunggulan. Unggul menyajikan gambar jernih beresolusi 4K, unggul mengartikulasikan ide-gagasan-konsep sebagai narasi yang representatif, dan unggul dalam proporsi waktu. Sajian video Veo 3, sangat cermat menyamarkan keartifisialannya.
Namun bukan itu yang hendak dibicarakan di sini. Sebab jika hanya sebatas itu, kapabilitas-kapabilitas AI berkembang pesat setiap hari. Hari-hari dilewati dengan lompatan kemampuan AI yang makin mengagumkan. Sehingga tak ada jeda untuk tak kagum.
Perangkat cerdas ini makin menerobos batas kemampuan manusia dalam wujudnya yang makin alamiah. Panca indera biasa makin sulit membedakan yang alamiah dari yang artifisial.
Lalu, apa implikasinya bagi nasib manusia sebagai tenaga kerja?
Sebagai ilustrasi, jika pekerjaan menghasilkan sebuah video memerlukan setidaknya sutradara, juru kamera, dan editor–ada 3 jenis pekerjaan manusia, maka kehadiran Veo 3 telah mampu menggantikan 3 jenis pekerjaan itu. Mungkin memang tak serta merta hasilnya diterima pasar. Tapi profesi-profesi tradisonal ini telah diganggu.

Di balik decak kagum, memang tanda tanya besar selalu menyertai pengembangan AI: bagaimana masa depan pekerjaan manusia. Ini jadi sisi muram wajah AI.
Deskripsi gamblang soal nasib tenaga kerja ini termuat pada “The Impact of AI on Job Roles, Workforce, and Employment: What You Need to Know” yang ditulis oleh Robert Farrell pada 2023.
Farrell menyebut AI mengubah total pasar kerja. Ini terjadi dengan cara menciptakan jenis pekerjaan baru akibat tak dilakukan lagi pekerjaan-pekerjaan lama imbas otomatisasi tugas-tugas rutin.
Hingga tahun 2030, diperkirakan 20-50 juta jenis pekerjaan baru hadir di pasar kerja. Ini meliputi pekerjaan di bidang perawatan kesehatan, farmasi, dan industri.
Bagaimana pekerjaan baru itu terbentuk?
Dapat disaksikan hari ini, misalnya makin jarang dokter mendiagnosis penyakit pasiennya dengan memanfaatkan indera peraba dari permukaan tangannya, mencermati detak jantung pasien pun dibantu stetoskop, dan alat lain untuk melihat perubahan warna mata serta lainnya. Dokter bekerja dengan mengandalkan sensor perangkat yang membaca kondisi tubuh pasien yang menghasilkan data indikasi pasien. Lewat data inilah diagnosis ditegakkan, dan pengobatan ditentukan.
Pekerjaan dokter sebagai profesional yang mengandalkan panca indera telah digantikan oleh perangkat otomatis yang lebih meyakinkan dan di antaranya juga berbasis AI. Dokter hari ini adalah profesional intepreter data dan pengambil keputusan pengobatan. Pergeseran ini terjadi akibat struktur metode diagnosis yang diubah oleh AI.
Dengan cara serupa, pekerjaan guru, jurnalis, penyiar, musisi, akuntan, hakim, pemasar, customer relation, pengemudi, dan banyak tenaga kerja lainnya dapat tergantikan. Tergantikan tapi sayangnya tak serta merta mendapat pekerjaan baru.
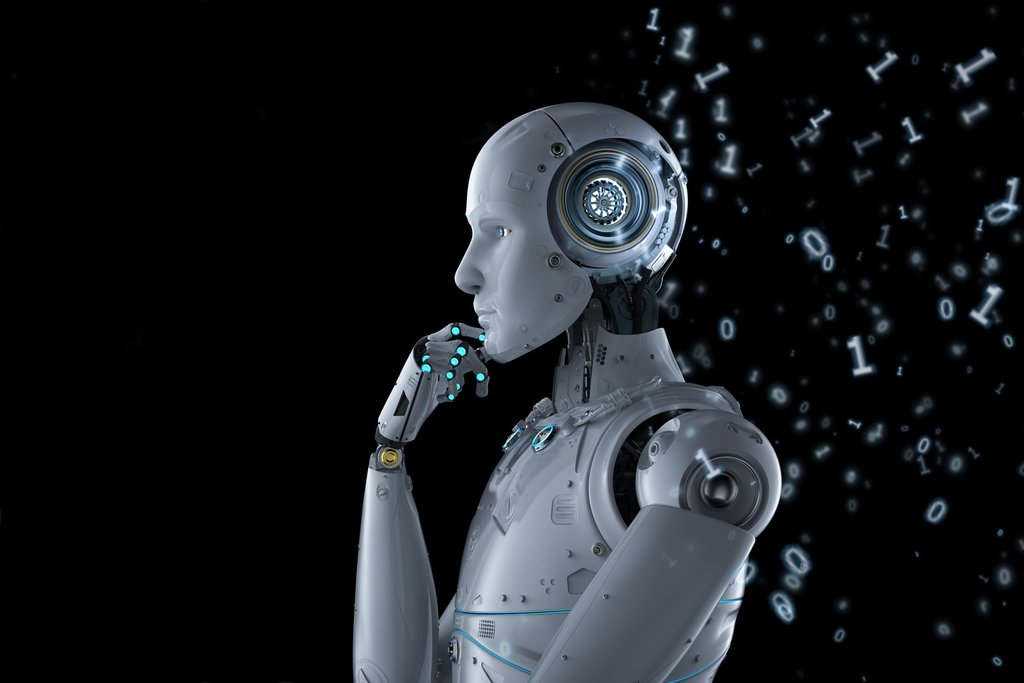
Dalam prosesnya yang menyedihkan, irelevansi tenaga kerja ini didahului pemutusan hubungan kerja, PHK. Shivani Tiwari (2025) dalam laporan yang berjudul “AI and the Layoff Wave: Is the Workforce Entering an Era of Permanent Disruption?” menyebut: lebih dari 61.220 tenaga kerja yang tergabung di industri teknologi telah di PHK di tahun 2025. Dan ribuan lainnya, telah dipaksa meninggalkan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah besar tenaga kerja itu berasal dari 130 perusahaan.
Alasan di balik gelombang PHK pada raksasa-raksasa teknologi–semacam Microsoft, IBM, Google, maupun Amazon–adalah perombakan struktural, rasionalisasi biaya, dan fokus yang lebih tajam pada profitabilitas.
Tak ada kaitannya dengan dominasi AI? Jelas AI pelaku utamanya.
Hal ini dimungkinkan lewat jejaring pengaruh AI terhadap profitabilitas yang tercapai melalui rasionalisasi biaya. Rasionalisasi biaya dicapai melalui perombakan struktural setelah adanya AI yang jadi agennya. Peran struktural AI–yang semula dipromosikan untuk meningkatkan kapabilitas manusia–hari ini justru hadir untuk mengotomatisasi pekerjaan.
Tenaga kerja yang semula menghasilkan produk kecerdasan lewat kemampuan alamiahnya, tergantikan peran tradisonalnya oleh struktur yang dijalankan AI. Irelevansi didorong pemanfaatan AI di berbagai bidang kerja. Kecepatan yang dapat dicapai perangkat cerdas ini pun tak pernah mampu disamai keadaan sebelumnya. Para pelaku usaha memandang fenomena ini sebagai peluang dihasilkannya pertumbuhan baru.
Melihat realitas ini, World Economic Forum meluncurkan laporan berjudul “Future of Jobs Report 2025” menyebut perkembangan AI jelas telah mengganggu peran tradisional manusia. Sekitar 40% pelaku usaha berencana mereduksi sejumlah tenaga kerja jika dapat diotomatisasi oleh AI.
Perkembangan AI menghadirkan 11 juta jenis pekerjaan baru, tapi juga menghilangkan 9 juta jenis pekerjaan. Terjadi relasi penyeimbangan yang rumit. Sebab, mereka yang kehilangan pekerjaan tak serta merta mendapat ganti pekerjaan yang baru.
Serupa dengan keadaan di era media sosial, hadirnya pekerjaan-pekerjaan seperti influencer, YouTuber, content creator, social media specialist diciptakan sendiri oleh pengguna platform. Demikian juga harusnya dengan AI. Pekerjaan baru pengganti ini mungkin bakal diciptakan para penggunanya.
Bagaimana dengan Indonesia? Tak mudah memperoleh gambarannya. Sebab, tak tersedia data yang dapat dirujuk tentang minat para pelaku usaha terhadap pemanfaatan AI. Selain langkanya data, praktik penggunaanya pun masih belum tentu arah.
Dalam laporan Komdigi (2024) berjudul “Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Kampus Optimalkan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial” menyebut bahwa Indonesia mampu meraih potensi besar dalam ekonomi digital. Kontribusi sektor ini diproyeksikan meningkat dari 90 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 135 miliar dolar AS pada 2027.
Data juga menunjukkan, Indonesia menduduki peringkat ketiga pengguna AI terbanyak di dunia. Terdapat 1,4 miliar kunjungan ke platform berbasis AI ini.
Namun terdapat kritik yang perlu dipikirkan serius soal penggunaan AI di salah satu industri di Indonesia. Kritik ini disampaikan Janet Steele, profesor jurnalisme di George Washington University, AS. Pendapatnya disampaikan saat diwawancarai jurnalis detik.com. termuat dalam laporan berjudul “Kritik Profesor Jurnalisme AS untuk Pemakaian AI di Media Massa Indonesia”.
Menurutnya, penggunaan AI di industri media massa Indonesia menarik tetapi aneh. Kritiknya muncul saat pewawancara mengilustrasikan penggunaan AI pada salah satu stasiun televisi Indonesia di hadapan Steele. Tergambarkan adanya presenter buatan AI yang menyampaikan berita, juga AI yang bertugas sebagai pewawancara narasumber dalam siaran radio.
Dibandingkan penerapannya di bidang jurnalistik di AS, penggunaan AI di Indonesia tergolong berani. Para jurnalis di sana menggunakan AI untuk merangkum tulisan yang panjang agar diperoleh kandungan substansinya. Juga digunakan untuk menelusuri data-data pendukung dari peristiwa lama.
AI yang digunakan untuk melakukan pekerjaan utama tak terjadi di AS. Karena aneh.
Walaupun Steele tak gamblang mengungkapkan argumentasi tentang diksi “aneh” itu, namun dapat diduga lewat cara penggunaan AI seperti itu manusia justru menyerahkan pekerjaannya untuk digantikan. Kepraktisan dan cepatnya hasil ditukar dengan irelevansi dirinya sebagai tenaga kerja.
Melihat fenomena ini, tentu saja para pemilik media akan melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk mengganti tenaga kerja manusia dengan AI. Manusia itu sendiri yang mendorong proses irelevansi dirinya.
Maka dapat diduga, pemanfaatan AI di Indonesia ada dalam 2 spektrum itu. Di satu ujungnya ada sekelompok pengguna yang memanfaatkan AI sebagai kolaborator. Di spektrum ini dihasilkan kreativitas-kreativitas baru. Batas-batas ketakmampuan tenaga kerja manusia ditembus oleh kecerdasan AI. Produk baru dihasilkan.
Namun di sisi seberang, terdapat kelompok yang gagap menggunakan AI. Penggunaan yang justru membahayakan relevansi manusia sebagai tenaga kerja. Terdapat adagium yang berlaku “kehadiran internet menihilkan biaya informasi dan kehadiran AI menihilkan biaya kognisi”. Di tangan kelompok gagap ini, AI malah didorong untuk menghasilkan pekerjaan utama. Penggunaan yang seperti itulah yang mengancam relevansi manusia.
Seluruhnya jika ditelusuri berpangkal pada etika yang menyertai pengembangan teknologi, bukan pada pengguna yang bisa memanfaatkan secara benar atau salah. Tiap teknologi harusnya menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan. Sehingga tak perlu ada yang terjebak, menggerus relevansi dirinya hanya gara-gara salah menyikapi teknologi.
Editor: Rina Nurjanah
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id