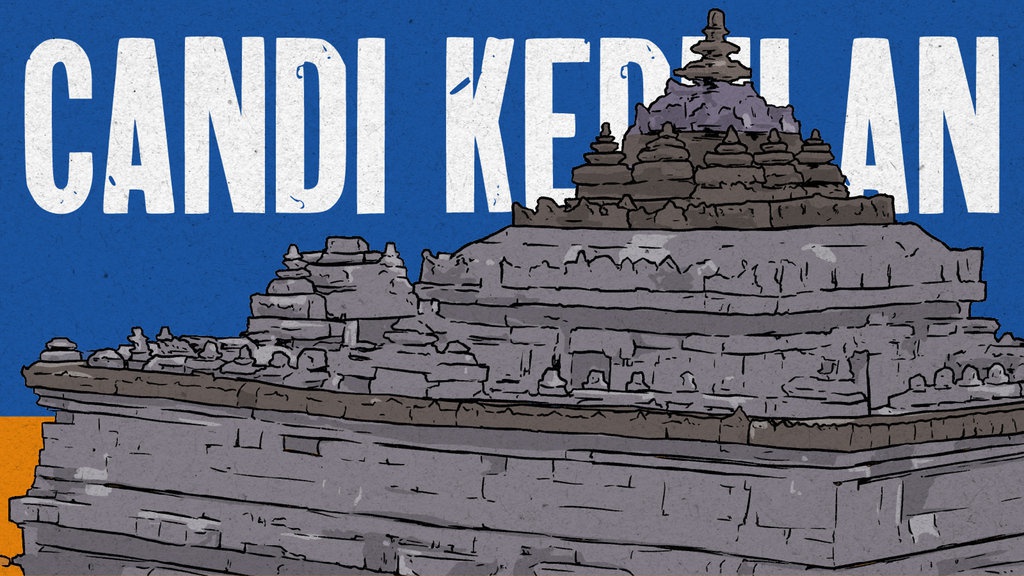tirto.id - Candi-candi paling awal dalam sejarah Jawa sebagian besar terkonsentrasi di tiga kawasan, yakni Dataran Tinggi Dieng, Perbukitan Kedu di sekitar Magelang, dan di Lembah Prambanan.
Seperti disinggung Edi Sedyawati dkk. dalam Candi Indonesia: Seri Jawa (2013), bangunan kepurbakalaan yang umumnya dipergunakan sebagai tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha ini rata-rata berasal dari abad ke-8 sampai abad ke-10 M.
Kekhasan dari candi-candi yang dibangun Dinasti Sailendra di Jawa Tengah ini adalah rata-rata dibangun dari batuan andesit—walau sebagian ada pula yang berbahan bata, kontras dengan candi-candi Singhasari-Majapahit di Jawa Timur yang jamaknya dibangun dari bata atau terakota.
Para arkeolog yang meneliti candi-candi di Jawa Tengah ini umumnya mengetahui penanggalan serta konteks historis yang melatari pembangunan candi-candi itu dari temuan prasasti yang dijumpai di sekitar bangunan tersebut.
Dalam Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuna (Jilid 2) (2010) yang disunting oleh M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto, prasasti yang berasosasi dengan pembangunan suatu bangunan suci paling awal di Jawa Tengah salah satunya adalah Prasasti Canggal (654 S/732 M) yang berbahasa Sansekerta.
Prasasti ini menyebutkan pembangunan sebuah lingga sebagai perwujudan Dewa Siwa oleh Maharaja Sanjaya di Desa Kunjarakunja. Para peneliti terdahulu menganggap bahwa lingga yang dimaksud dalam prasasti itu adalah yang berada di bangunan candi yang sekarang disebut sebagai Candi Gunung Wukir, pasalnya letak candi itu berdekatan dengan tempat penemuan prasasti.
Selain hal tersebut, terdapat satu bangunan suci lain dari era yang lebih baru, yang menunjukkan gejala interelasi kebijakan politik seorang raja dengan pembangunan suatu candi.
Pembangunan candi ini tampaknya begitu penting, sampai-sampai dari dua rezim yang memerintah, diperlukan setidaknya tiga dokumen resmi (prasasti) yang menaungi bangunan suci tersebut. Salah satu dokumennya bahkan dibuat setelah sang raja blusukan ke daerah tersebut.
Bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kedulan, yang hidup dari saluran irigasi pemerintahan Jawa Kuno.

Kekecewaan Sang Raja
Alkisah, sekitar tahun 900 Masehi, Raja Dyah Balitung melakukan kunjungan ke wilayah kerajaannya yang disebut sebagai Tlu Ron. Di daerah yang berarti 'tiga daun' itu sang raja bermaksud mengunjungi bangunan suci bagi pemujaan bhatara beserta saluran irigasi yang telah dibangun beberapa tahun sebelum pemerintahannya.
Namun, ketika ia sampai ke sana, bangunan bendungan yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Demikian kekecewaan Dyah Balitung dari pembacaan yang dilakukan oleh Tjahjono Prasodjo dan J.S.E. Yuwono dalam tulisannya berjudul “Ḍawuhan, Wluran, Pañcuran: Penelusuran Aspek Hidrologi terhadap Isi Prasasti Tlu” (2019).
Namun, bagaimana uraian cerita yang sebenarnya? Kisah kekecewaan Dyah Balitung ini bisa ditelusuri jauh sebelum kedatangannya ke Tlu Ron, yakni sejak tahun 791 S/ 869 M, atau lebih dari tiga puluh tahun sebelum ia tiba di tempat itu.
Menurut Prasasti Sumundul yang dimuat dalam Pusaka Aksara Yogyakarta: Alih Aksara dan Alih Bahasa Prasasti Koleksi Balai Peninggalan Purbakala Yogyakarta (2015), sejak tahun 869 M sebenarnya telah dikeluarkan perintah untuk mendirikan suatu bendungan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan persawahan dalam menghidupi bangunan suci di Tlu Ron.
Perintah ini begitu pentingnya, sampai-sampai yang mengeluarkan kebijakan harus mengeluarkan dua prasasti bagi dua tempat, yakni Sumundul dan Pananggaran (tempat berdirinya bendungan). Tokoh yang memberi perintah itu adalah seorang pendeta perempuan dari Paḍaṅ Lor bernama Pu Manoharī.
Tokoh ini bukan sosok sembarangan, karena ia merupakan ibu dari seorang rakryan (raja daerah) di Padelegan. Dalam perintah itu, sang pendeta perempuan telah memerintahkan seorang kuncen yang menjadi mandor berbagai urusan pembangunan serta pengaturan sistem pengairan, yakni Vimaleśvara.
Ternyata perintah itu tidak dijalankan dengan baik. Bahkan ketika proyek itu kemudian dilanjutkan oleh Rakai Hino Pu Aku, pembangunan saluran air bagi penghidupan candi di Tlu Ron tidak juga berlangsung. Atas dasar itulah, menurut Prasasti Tlu Ron, Dyan Balitung yang kecewa kemudian segera pulang ke istananya dan menanyakan proyek tersebut pada seorang pejabat yang bernama Sang Tiruanu Pu śivāstra.
Pejabat istana itu menjawab bahwa pembangunan fasilitas pengairan telah diselesaikan oleh seorang makudur (tetua) bernama Sang Relam, yang mengerjakan proyek itu selama setahun penuh. Namun, jawaban itu tidak memuaskan hati Dyah Balitung, sehingga ia pun menginisiasi proyek revitalisasi dengan bantuan dana pusat.
Sang prabu mengeluarkan dana miliknya pribadi sebesar 10 suwarna (satuan beberapa gram emas) untuk dialokasikan bagi proyek revitalisasi saluran air beserta sosialisasi programnya bagi warga setempat. Balitung menghendaki masyarakat untuk mengambil keuntungan dari saluran air itu, selain pembagian keuntungan bagi bangunan suci di Tlu Ron, dengan harapan agar warga juga ikut memelihara bangunan itu.

Candi Kedulan dan Letusan Gunung
Seperti telah disinggung sebelumnya, bangunan suci Tlu Ron yang dihidupi oleh saluran air yang digarap ulang oleh Dyah Balitung adalah Candi Kedulan. Candi yang terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, DIY ini mungkin sekali dibangun sejak zaman pemerintahan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala berdasarkan angka tahun Prasasti Sumundul dan Pananggaran.
Arsitektur bangunan suci ini memiliki keunikan tersendiri. Seperti disinggung oleh Dwi Pradnyawan dalam “Arsitektur dan Seni Candi Kedulan” (2023), kemungkinan besar Candi Kedulan merupakan representasi dari arsitektur bangunan suci di Jawa Tengah dari periode yang paling akhir.
Dalam beberapa aspek, ciri lawas dari candi ini masih bisa dijumpai dari keberadaan pagar langkan dan pradaksinapatha—selasar tempat dilakukannya ritual mengelilingi candi—yang dalam hal ini hanya bisa dijumpai di dua candi tipe Jawa Tengah, yakni Candi Prambanan dan Candi Sambisari.
Dalam penataan ruangnya, bangunan yang berunsur Hindu Saiwa itu menerapkan sistem wastupurusamandala (diagram suci yang merupakan pedoman pembagian tata ruang di bangunan suci), tempat kedudukan tersakral berada di Brahmastana berupa lingga patok.
Menurut Sugeng Riyanto dalam “Beberapa Sumbangan Pemikiran bagi Konsep Rencana Pelestarian Situs Kedulan” (2005), candi ini sempat ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya lantaran terkena dampak letusan Gunung Merapi sampai berkali-kali. Oleh karena itulah, ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1993, lokasi candi ini berada di daerah penambangan pasir. Bagian-bagian dari candi ini pun sempat terserak di beberapa tempat dan sebagian besar tertutup oleh sedimen abu vulkanik bekas letusan gunung di masa lalu.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id