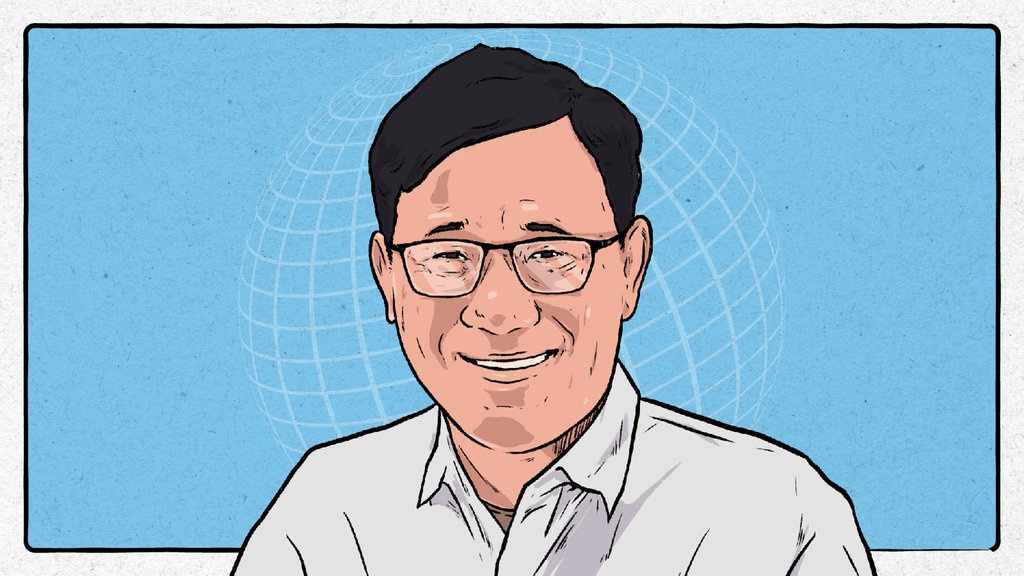tirto.id - Pertama kali menjadi badan dan berdiri setara kementerian/lembaga pemerintahan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) langsung bekerja dan turun ke masyarakat. Kinerja lembaga baru ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024 yang, apabila merujuk pada nomenklatur aturan tersebut, BP Taskin bertugas untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan percepatan pengentasan kemiskinan secara sinergis dan terpadu.
Dalam sejarahnya, BP Taskin merupakan lembaga tim strategi yang bersifat koordinasi dan tidak berbentuk badan. Di periode pemerintahan 2010-2024, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di 2005-2010, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Hingga di era Orde Baru, pada 1993-1998, dinamakan dengan Program Inpres Desa Tertinggal.
Kini, BP Taskin dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko, sosok mantan politisi PDIP yang memiliki jejak rekam dalam penanganan kemiskinan sejak duduk di parlemen. Kepada Tirto, Budiman menceritakan sejumlah aksi yang telah dilakukannya untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antara strategi yang ditawarkannya adalah penanganan di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, pengolahan, hunian, kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan.
Budiman juga menawarkan penggabungan kerja sama lintas kabupaten/kota dalam bingkai aglomerasi. Menurutnya, pengentasan kemiskinan memerlukan kerja kolektif antara kementerian, lembaga, dan antara hingga perusahaan nasional sampai multinasional.
Berikut petikan wawancara Pemimpin Redaksi Tirto, Rachmadin Ismail, dengan Budiman Sudjatmiko.
Kemarin sempat ramai adanya perbedaan data antara survei BPS dan sejumlah LSM yang kemarin diributkan di UN (United Nations) dan World Bank, itu bagaimana?
Itu data yang di BPS, itu juga diakui oleh Bank Dunia, bagus, dan itu sudah digunakan sejak 1998. Kenapa masih dipakai? Pertama, agar kita konsisten penarikan survei. Ada misi metode yang selama ini dilakukan, itu dari Bantuan Sosial, BLT, non-BLT, subsidi, ada progres nggak?
Ternyata ada, ternyata ada progres. Dengan standar itu kita hanya sedang melihat sebagai satu kacamata, parameter ada progres, ada progres dengan evolusi berbagai macam metode berdekatan. Sesuai dengan waktu, dengan konteks, dan relevansinya.
Tapi apakah itu puas? Pak Prabowo eventually mengatakan, waktu beliau meminta kami untuk jadi kepala BPS, mungkin waktu awal diundang di kantor, di rumah beliau, di Jalan Kartanegara, beliau mengatakan, kita pakai pada data itu, tapi bukan berarti kita berpatok di situ saja, karena bisa jadi masalahnya juga lebih dalam. Itu hanya untuk konsistensi saja.
Kedua, terus sampai sejauh mana ukuran itu bisa relevan. Karena kemiskinan itu dari desil 1, 10 persen termiskin, desil 2, 20 persen termiskin, sampai desil 10. Negara kita tidak pelit terhadap kemiskinan. Dalam hal keberpihakan, negara kita sudah di jalan yang benar.
Tetapi masalahnya, kenapa tidak efektif? Karena sebesar apa pun anggaran, tetap terbatas, tetap terbatas. Sekarang begini, kemiskinan itu kan banyak desil 1, desil 2, lewat BPS. Andai kita naikkan dengan Bank Dunia, sebenarnya jumlahnya nggak berubah. Jumlah faktanya berubah nggak? Nggak kan.
Tapi sebenarnya kita misalnya dinaikkan dengan Bank Dunia, tidak kemudian yang rumahnya permanen, desil-desil permanen, udah diabruk, nggak. Oke. Tapi kebutuhan dengan BPS itu, dengan kita, dengan ukuran 560 sekian per bulan per kapita.
Ini kan kita memfokuskan orang miskinnya 24 juta sekaligus. Ada dinaikkan, maka orang miskinnya jadi tambah secara statistik. Secara faktual tidak. Ketika kita naikkan, tambah. Sementara budget kita terbatas. Kira-kira berarti akan ada lebih banyak mulut yang akan disuapin.
Sementara antara desil-1 sama desil-4 kesenjangannya pun tinggi. Antara yang disebut miskin versi Bank Dunia nantinya pun tinggi. Nanti kita pakai ini, maka anggaran yang terbatas itu akan disebar ke 4 desil bawah.

Saya sering dibahasnya gini, kamu punya 2 anak, dengan anggaran Rp 10 ribu kamu bisa kasih makan mereka Rp 5 ribu per hari. Tapi 4. Anakmu 6. Kemudian 4 disebut miskin. Dengan 10 ribu kamu bagi 4 orang nantinya. Kita kurang fokus pada the most needy one, yang paling butuhkan, yang maaf, yang juga kena penyakit.
Kemudian, sama seperti saya sering dibahas, perahu Titanic. Karena di sekoci itu, sebanyak apa pun, sekoci itu terbatas. Tidak bisa menampung semua penumpang.
Biasanya sekoci hanya untuk anak-anak atau orang tua. Kemudian tiba-tiba, diubah aturan. Ukuran tuanya diturunkan, ukuran anaknya dinaikkan. Akhirnya kemudian yang umur 1 tahun sampai 5 tahun, yang tadinya dapat jatah, jangan berkurang jatahnya, diambil oleh mereka umur 7 tahun. Sementara perbedaan antara si balita dengan umur 8 tahun tinggi.
Jangan antara anak-anak versi barunya. Kita pendekatan BPS, agar kita fokus pada the most needy one. Dengan anggaran terbatas. Ketika saya sebutkan terbatas, relatif. Karena sebesar-besar apa pun anggaran itu, tetap terbatas.
Sebenarnya pendefinisian itu berfokus pada ujungnya, yaitu alokasi anggaran.
Sehingga pendekatannya adalah pendekatan sifatnya aspek sosialnya daripada ROI (Return of Investment)-nya. Kalau kita naikkan, berarti lebih banyak aspek sosialnya, growth-nya tidak terjadi.
Tapi kalau kita ke satu dan dua, ketika pendekatannya pra-BP Taskin, aspek sosial sepenuhnya, Bansos dan BLT. Tapi dengan pendekatan baru, dengan data yang ada, maka yang sosial itu langsung dihubungkan dengan yang namanya inclusive growth. Pertumbuhan yang inklusif. Kita akan tetap berangkat pada desil satu dan dua.
Soal kemiskinan, Mas Budi dikenal sebagai orang mendorong dana desa, kalau kita lihat dari BPS, kemiskinan terbesar itu justru ada di desa?
Yang baru minggu lalu, udah dirilis dua minggu lalu, lebih tinggi daripada desa, baru pertama ini.
Itu melihat desa dan kemiskinan kenapa akhirnya berpindah dari desa ke kota, apakah itu ada hubungannya dengan PHK yang terjadi?
Dengan dana desa, desa jadi memiliki jaring pengamanan sosial, dan dana desa berarti desa juga punya jaring sosial pengamanan finansial. Pelembagaan ekonomi yang ditopang oleh pelembagaan sosial budaya itu membuat pengentasan kemiskinan di desa menjadi lebih sukses, lebih cepat. Sementara di kota-kota, dari kebanyakan investasi, dan segala macam adalah industri padat karya.
Sementara di kota ada orang miskin dari desa, tapi tidak punya jaring pengaman sosial kultural.
Kedua, seluruh investasi di kota merupakan sektor yang butuh high skill, sektor teknologi, sektor keuangan, terutama itu. Sementara orang miskinnya di kota sudah tidak punya jaring pengaman sosial finansial.
Tidak punya jaring pengaman sosial kultural, jaring pengaman sosial finansial, uang paling cuma bahan sosial. Sementara di desa ada daerah desa, ada bank, ada BUMDes, apalagi nanti ditambah dengan koperasi desa Merah Putih.
Sementara di kota tidak punya kemewahan. Di lain, investasinya padat modal, padat teknologi, padat karya. Akibatnya investasinya tidak berpengaruh pada soal penyerapan tenaga kerjanya, yang memang dibawa sekarang, itu pada sektor-sektor teknologi.
Artinya, sekarang ketika desa mengatasi kemiskinan lebih cepat, berusaha berasal dari UU Desa, dari jaring sosial budaya tadi, dari pangan, bukan berarti membanggakan UU Desa.
Berarti ini menjadi tantangan bagi BP Taskin untuk menangani kemiskinan di perkotaan?
Ini tantangan baru buat BP Taskin. Apa yang disebut miskin? Selama ini asumsi disebut miskin artinya kurang cash, kayak kurang cash, kurang uang tunai. Maka ada BLT, ada bantuan sosial. Padahal yang disebut miskin bagi BP Taskin itu ada tiga: ada uang tunai, kurang aset, dan kurang akses. Di desa aset banyak. Sebelum ada Indonesia, nggak ada akses kepada cash. Tapi ada Indonesia, ada cash, ada aset, ada cash.
Kita menolong desa, tinggal tambahkan akses: akses kepada pemerintah, teknologinya, akses kepada pasar, akses kepada infrastruktur, apalagi akses kepada pasar. Mereka pindah ke modern. Pak Prabowo datang, ada sekolah rakyat, dan Makan Bergizi Gratis, akses pada makan, makan bergizi gratis.

Desa tadinya hanya ada aset. Dengan ada undang-undang Indonesia, ada uang, cash, tunai, dengan ada ekonomi makanan bergizi gratis, seolah-olah ada akses pada pendidikan, akses pada makan bergizi. Lengkap di desa ini jadinya, kan? Itu yang menarik.
Sementara di kota, akses itu banyak: akses ilmu pengetahuan, akses infrastruktur, akses pendidikan modern, akses digital, informasi, ya. Cash-nya paling cuma BLT. Rumah ngontrak, tanah mahal, tanah juga ngontrak, nggak punya tanah. Orang kota sehingga melarat karena aset kurang, akses banyak, uang cash-nya cuma BLT.
Sementara investasi yang datang padat modal, ada teknologi yang belum bisa dijangkau. Ada dua alternatif pertanyaan bagi pengasas pendidikan. Balik ke desa, karena gula-gula sudah ada di desa. Dulu kan mereka ada teknologi karena gula cuma bongkahan gula di kota. Dulu.
Tapi sekarang ada di negeri Undang-Undang Desa, bongkahan gulanya dibagi ke desa-desa. Ada dua. Balik ke desanya, ikut dalam industri padat karya di sana, paham berkisi kreatif, suasana berat banget, itu sekarang sudah berkembang.
Atau stay di kota, tapi alternatifnya tingkatkan skills. Di situlah penting. Di situlah kementerian kerja-kerja bekerja. Di situlah kepentingan kementerian pendidikan bekerja. Di situlah kepentingan investasi-investasi juga menyediakan CSR-CSR. Nanti usaha kita itu bagaimana kemungkinan skills.
Kasih pilihan. Stay di sini, tapi tingkatkan ilmu, harus catch it up. Atau balik ke desa.
Kembali ke jaringan sosial, kultural, pengamanan. Sekarang ada jaringan pengamanan. Kira-kira begitu.
Sudah ada pembahasan belum, bahwa ada opsi untuk balik ke desa?
Sudah dong. Sebenarnya gini, sebenarnya dengan ada dapur-dapur, dengan ada koperasi desa Merah Putih, itu sudah bisa gini. Sebenarnya tuh, nyiapin dulu dong, baru horor-horornya nanti. Siapin dulu, kemudian ayo pulang. Ini emang betul.

Data statistik Tirto menunjukkan pembaca Tirto yang mencari konten terkait Koperasi Merah Putih meningkat dalam 2-3 bulan terakhir?
Artinya ada gula di kampungnya, gaji pegawai Koperasi Merah Putih. Artinya, gulanya, jadi, ada magnetnya di desa. Tiba-tiba, menambah kemiskinan di kota. Inilah pendulum yang sedang kita coba geser.
Inilah yang diarahkan Pak Presiden, dan coba kami terapkan ini. Yang paling penting adalah melakukan transformasi sosial. Desa punya daya tarik kembali. Desa yang dulu ditinggalkan, sekarang punya daya tarik.
Kira-kira gitu. Itu kan revolusi. Transformasilah berdampaknya. Orang malas itu nggak takut istilah revolusi. Transformasi minimal ah gitu. Transformasi sosial. Nah, kami menerjemahkan visi Pak Prabowo Subianto, visi-misi Pak Gibran Astacita, maupun tulisan-tulisan Pak Prabowo tentang Paradoks Indonesia, maupun strategi transformasi bangsa.
Kita coba terjemahkan dalam perjalanan yang begitu. Dengan cara-cara operasional. Dengan terjemahannya diaglomerasi. Itu sebagai semua konsep dalam prakteknya yang terbaik.
Lalu bagaimana, menurut Mas Budiman, tentang cara mengatasi ego sektoral lintas Pemkot dan Pemkab?
Alhamdulillah, kalau soal sektoral, Pak Presiden dalam waktu terakhir selalu mengatakan bahwa kita bekerja sebagai sebuah tim. Kalau pengalaman kami dengan lima kabupaten dan kota di Kota Brebes, Cirebon, dan sebagainya, mereka bisa saling berbicara, dan kita sudah berkolaborasi. Kemudian dari Jember segala macam, kemarin dari Bondowoso datang. Minggu.
Kemarin juga dari teman-teman IKN juga tertarik untuk berbicara soal aglomerasi, dan Jakarta bisa aglomerasi.

BP Taskin ini akan menjadi leading sector?
Kami diminta oleh Pak Presiden untuk melakukan kooperasi antara pemerintahan khusus isu kemiskinan. Khusus pengentasan kemiskinan ekonomi dan dengan pendekatan dari multidimensional ecosystem aglomerasi. Jadi inisiatif dan harmonisasi di teman-teman BP Taskin.
Bagaimana irisian antara proyek aglomerasi dan kolaborasi lintas kabupaten/kota yang diurus oleh BP Taskin, salah satunya seperti BGN?
Misalnya contoh program BGN, itu utamanya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu kan di level hilir, di level piring sampai masuk mulutnya 82 juta orang setiap hari. BGN mengurus bagaimana setiap piring masuk ke mulut 82 juta orang setiap hari. Ini kerja masif.
Kalau menurut saya makan bergizi gratis bisa tercapai. Tapi apakah produktivitasnya seperti yang kita harapkan tercapai? Apakah realisasi produk pertanian tercapai? Apakah employment di sektor pertanian bisa tercapai?
Penulis: Irfan Amin & Rachmadin Ismail
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id