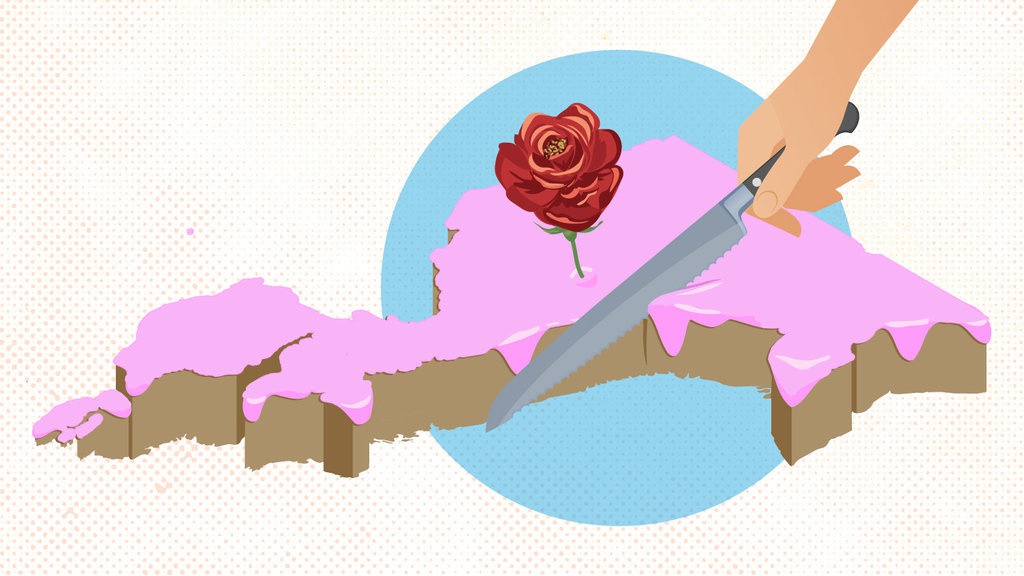tirto.id - Dermaga pelabuhan Kelapa Lima nyaris tak pernah sepi setiap sore. Para buruh dermaga yang tinggal di sekitarnya kerap menghabiskan sore dengan kongkow sambil berbincang-bincang di sana.
Dermaga di pusat kota ini pernah jadi penghubung utama antar-wilayah di Merauke sebelum ada jembatan di sisinya. Kini dermaga berfungsi sebagai kapal sandar ke kabupaten tetangga seperti Asmat dan Mappi.
Agapitus Tingginimu, salah seorang buruh, berkata kapal bersandar dua kali sepekan untuk mengangkut sembako, bahan bakar dan barang lain yang dibawa truk dari kota.
“Sekali bongkar muat kami dapat Rp30.000 sampai Rp50.000,” kata dia kepada Tirto di Merauke, 18 Desember 2019.
Albertus Topimu bilang tidak ada pekerjaan lain selama 20 tahun belakangan ini bagi warga sekitar selain menjadi buruh dermaga. Albertus adalah kepala buruh dermaga setempat. Ia adalah orang Mappi, kabupaten baru dari pemekaran Merauke pada 1997.
Sebagai kepala buruh dermaga, ia bertanggung jawab membagi upah kepada 35 anak buahnya. Tarif bongkar muat untuk setiap truk adalah Rp500 ribu. Ia berharap dinas setempat menaikkan tarif agar upah yang diterima makin besar.
Lima tahun lalu saat dermaga baru dibangun, ia sudah bekerja di sana. Dari dulu semua buruh di bawahnya adalah warga dari suku asli setempat.
“Yang penting ada KTP sudah cukup. Untuk sementara tidak menerima buruh dari pendatang. Mungkin nanti,” ujar dia.
Albertus mengikuti isu pemekaran Provinsi Papua yang menyasar wilayah Merauke di bagian selatan pulau ini. Ia berharap ada pemekaran agar jadwal kapal sandar makin padat dan bongkar muat bertambah, sehingga pekerjaannya meningkat.
Dari tengah kota, kami ke sisi perbatasan Merauke dengan Papua Nugini (PNG) untuk bertemu warga lainnya. Berjarak satu jam dari pusat kota, Distrik Sota menawarkan pemandangan hutan di wilayah Taman Nasional Wasur. Sejauh mata memandang, ada rumah semut raksasa bertebaran di sisi jalan Transpapua yang telah mulus.
Sebelum masuk ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Merauke, ada persimpangan jalan menuju Boven Digoel. Di sana berjajar warung yang sebagian besar dioperasionalkan para pendatang. Lokasi ini merupakan tempat istirahat bagi sopir dan penumpang angkutan antar-kota.
Angkutan ini melayani rute dari Merauke-Boven Digoel dengan tarif mulai Rp300ribu hingga Rp700ribu per orang. Angkutan ini umumnya menggunakan mobil dobel gardan Hilux dengan bak terbuka. Mobil ini sanggup melaju hingga kecepatan 120 kilometer per jam di ruas jalan yang hanya bisa untuk dua mobil.
Sekitar 200 meter dari persimpangan menuju Boven Digoel, merupakan kompleks PLBN. Kantor polisi dan tentara di sisi sebelum pintu. Di luar bangunan pos ini ada kios dari kayu beratap kain terpal milik warga PNG dan lokal. Mereka satu suku yang terpisah oleh garis batas negara.
Jalanan masih berupa tanah. Penduduk PNG melintasi hutan dengan jalan kaki atau bersepeda untuk jual-beli dengan warga Merauke.
Sepetak tanah dengan pepohonan rindang jadi tempat sempurna untuk menjual nanas, minyak kayu putih, dan noken buatan warga. Bendera PNG berkibar di tanah ini.
Kondisi di dalam kompleks perbatasan Merauke berbeda dari perbatasan PNG. Pembangunan kawasan ini terus berdenyut sejak pemerintah ingin mencitrakan perbatasan yang modern dan maju secara fisik.
Margaretha Naib, 45 tahun, seorang pedagang suvenir di pos perbatasan Merauke, memastikan mereka tidak menjual makanan dan minuman terlarang. Namun, ia menjual suvenir yang diklaimnya dari satwa endemik Papua seperti topi burung Cenderawasih seharga Rp2 juta dan gantungan kunci kuku burung Kasuari dan potongan kaki Kanguru yang sudah dikeraskan seharga Rp50ribu-Rp60ribu.
“Ada warga yang menjual ke kami. Mereka sudah kami kasih tahu bahwa ini melanggar hukum. Tapi bagaimana kalau sudah menyangkut perut?” kilahnya.
Enam bulan terakhir ia berjualan di sana. Kini, iamenunggu pembangunan kios di kompleks perbatasan rampung.
Dalam penantian ibu dua anak ini, ia berharap pemekaran Papua berlanjut di Merauke menjadi Papua Selatan agar "ada pekerjaan bagi anak-anak saya."
"Jadi tukang sapu atau tukang mengelap kaca tak apa," katanya. "Daripada mereka menganggur.”
Gerakan Pemekaran
Pemekaran di Papua bergulir kembali tak lama setelah terjadi protes besar-besaran terkait rasisme pada Agustus 2019. Berselang sebulan, pertemuan 61 tokoh yang diklaim pemerintah mewakili masyarakat Papua bertemu Presiden Jokowi dengan membawa aspirasi, salah satunya pemekaran Provinsi Papua.
Pertemuan ini menghidupkan gairah elite lokal di Papua. Mereka gerak cepat membentuk asosiasi bupati dan mendeklarasikannya untuk menunjukkan pemekaran adalah kehendak rakyat.
Tak kurang ada tiga kelompok kepala daerah di Papua telah mendeklarasikan diri sebagai calon daerah pemekaran berdasarkan wilayah adat: Provinsi Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom, dan Sarmi; Papua Selatan atau wilayah adat Ahim Ha mencakup Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel; Papua Tengah yang mencakup kawasan adat Meepago meliputi Nabire, Puncak, Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, dan Deyai.
Ketiga kelompok ini telah bergeriliya usai pertemuan ‘61 tokoh’. Mereka datang ke Jayapura hingga menemui Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Ketua DPR Papua John Rouw Banua menyebut sehari setelah dilantik jadi anggota legislatif, tiga kelompok bupati dari wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Tabi hendak menemuinya.
“Kami tolak bertemu karena baru dilantik. Belum ada kelengkapan alat dewan. Mereka mau menyampaikan aspirasi pemekaran ke kami. Ada satu kelompok dari Tabi yang ditemui [karena dekat di Jayapura], tapi hanya sebagai tamu,” kata John kepada Tirto di Jayapura, 16 Desember 2019.
Posisi lembaga ini strategis, karena berdasarkan Pasal 76 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, persetujuan pemekaran provinsi harus mengantongi persetujuan DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Menurut Ketua MRP, Timotius Murib, aspirasi para bupati ini belum sampai ke mejanya. Sejak pertemuan ’61 tokoh’ dan manuver bupati ke Jayapura dan Jakarta, MRP tak dilibatkan.
Namun, ia mengaku berpegang pada keputusan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin yang masih memberlakukan moratorium pemekaran.
“Pemekaran ini, kan, bukan dari rakyat, tapi tokoh 61. Orang Jakarta tahu, orang Papua punya kelemahan. Kalau menangis kasih bunga, nanti tertawa dan senyum. Pemekaran juga belum tentu dikasih. Kami ketemu Wapres minggu lalu bicara pemekaran Papua dengan MRP. Wapres bilang pemekaran tidak di Papua. Pemekaran hanya isu saja. Para bupati malah semangat,” kata Murib pada 16 Desember 2019.
Murib mencurigai ada motif elite dalam pemekaran terutama para bupati/wali kota yang sudah menjabat dua periode, sehingga ingin mencari jabatan lagi sebagai gubernur/wakil gubernur.
Pintu Masuk Lebih Banyak Aparat
Pastor Anselmus Amo MSC, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, menilai pemekaran bukan hanya kepentingan elite lokal, tapi secara politik juga punya strategi nasional untuk amankan Papua dari gerakan—meminjam bahasa pemerintah—"separatis." Tapi, kelompok ini inginnya disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
“Dengan pemekaran, paling tidak ada kodam baru, berarti militer semakin banyak. Polda baru. Anggota semakin banyak. Untuk mengurung ini. Jadi mereka mengamankan posisi selatan. Barat sudah, berarti mengurung [OPM] di tengah dan utara,” katanya.
Tapi, hal ini dibantah Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. Menurut dia, pemekaran merupakan aspirasi warganya sejak 2012. Pemkab Jayapura, kata dia, telah menjalin kerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengkaji pembentukan Provinsi Tabi.
“Jadi ada yang dicurigai pasti ini kepentingan elite. Tidak. Jadi kami ini mau mengurai kepentingan Papua. Orang salah persepsi dengan Papua. Papua itu identik dengan Otsus. Tidak. Itu orang hanya kejar uangnya saja. Kita harus tunjukkan kita punya potensi harus hidup,” ujar dia pada 14 Desember 2019.

Rakyat Dapat Apa?
Bupati Merauke Frederikus Gebze mengaku sudah 17 tahun menanti pemekaran daerahnya menjadi Papua Selatan.
Gebze dan Awoitauw berkata pemekaran akan menguntungkan daerahnya. Gebze bilang dengan pemekaran Papua bisa mengatasi masalah karena dua gubernur saja tidak cukup. Pertumbuhan dan perkembangan daerah akan terjadi bila ada pemekaran.
Namun, jumlah pendatang di Merauke lebih banyak dari orang asli Papua (OAP) sehingga dikhawatirkan non-OAP jadi pihak utama yang menikmati pemekaran.
“Ada yang anggap Papua Selatan ini hanya untuk orang Jawa. Saya pikir salah. Itu justru ada provinsi supaya hak kita pegang. Kita atur lewat regulasi, adat, budaya, perempuan,” katanya.
Saat ditemui, ia baru saja melantik dan merotasi ratusan pejabat Pemkab Merauke di sebuah hotel. Dari nama-nama yang dibacakan protokol acara, terdengar banyak pejabat memiliki nama Jawa.
Alasan dia menempatkan banyak orang non-OAP untuk mengurus Merauke, “Karena kita masuk dunia kompetisi, maka harus siapkan diri dari sekarang supaya jangan salahkan orang lain.”
Awoitauw menilai, dengan adanya Provinsi Tabi, indeks pembangunan manusia bisa berada di urutan ke-8 di Indonesia, sehingga Papua tak lagi masuk daerah termiskin dan tertinggal.
“Kami paling siap sebetulnya untuk jadi provinsi. Kalau dari fasilitas, infrastruktur sangat siap. Dari pembiayaan. Potensi besar. Hutan masih. Apalagi [akan ada pembangkit] energi di Mamberamo Raya. Kelautan kita kelola. Kita tidak perlu Otsus,” ujar Awoitauw.
Perkara pemekaran juga menyangkut sumber daya manusia. Menurut Haryy Ndiken, tokoh suku Marind di Merauke, jumlah ASN OAP di Pemkab Merauke berkisar 800 orang dari total ASN di sana sebanyak 5.000 orang.
Keterwakilan OAP kursi DPRD Merauke periode 2019-2014 hanya 3 dari 30 kursi. Situasi yang sama juga terjadi seluruh wilayah Papua.
“OAP di sini sudah mencakup orang Serui, Jayapura, Mappi, Asmat, dan Marind. Mau bikin pemekaran dari mana? Apakah kita harus harus ‘impor’ ASN lagi?” ungkapnya.
Pemekaran tanpa menyiapkan OAP, kata dia, hanya menjadikannya sebagai "penonton". Ia meminta agar tidak pakai "kaca mata kuda" melihat kebijakan afirmatif di Papua yang mewajibkan kepala daerah adalah OAP.
Xaverius Bavo Gebze, ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind-Imbuti yang membawahi masyarakat asli Merauke di kota, menginginkan kesejahteraan warga tetap jadi perhatian baik ada maupun tidaknya Provinsi Papua Selatan.
Selama ini, penduduk asli Merauke bingung dengan pemerintah daerah, karena program pelatihan yang dibuat tak ditindaklanjuti. Ada warga yang dibawa ke Surabaya dan Sorong untuk dilatih mengoperasikan kapal, namun tak berlanjut ke pemberian bantuan.
“Orang maunya sejahtera. Kita mau mengadu ke mana itu kesejahteraan datang. Bisa sekolah dengan aman [bisa] cari kehidupan dan nafkah dengan layak. Ini tidak ada. Sepertinya program itu ada, [pelatihan] hanya 2-3 jam. Tetap [kehidupan] kita jalan di tempat. Hanya pelatihan saja. Tidak ada bantuan modal dan usaha,” katanya.
Anselmus Amo menyebut, pemberdayaan OAP di wilayah selatan Papua penting karena mereka kini sudah termarginalisasi akibat kehilangan tanah adat. Proses peralihan dari ketergantungan hidup dari hutan tak bisa instan, sehingga saat diketok ada Provinsi Papua Selatan harus disiapkan sumber daya manusia OAP.
“Ada yang bilang [ASN non-OAP] supaya ada yang bisa belajar dari orang luar. Tapi saat ini OAP sudah dijembatani apa belum. Tahapannya apa saja. Kalau tidak, dia akan tetap terbelakang,” kata dia.
Nasib OAP yang kami jumpai di pusat kota dan perbatasan negara diamini oleh Anselmus sebagai bukti nyata di Merauke mereka selama ini jadi penonton dari derap pembangunan.
“Ada provinsi atau tidak, sudah jadi tugas pemerintah untuk pemerataan pembangunan sampai pelosok,” imbuh Anselmus.
_______
Laporan ini terbit berkat kolaborasi antara Tirto dan Jubi. Sejak santer usulan pemekaran provinsi Papua dilontarkan oleh pemerintahan Jokowi, mungkin demi menutupi protes antirasisme di seluruh Papua, para elite lokal yang bersekongkol dengan para pencari rente di Jakarta mulai serius menanggapi usulan tersebut. Laporan ini merupakan salah satu seri liputan yang menguji usulan pemekaran itu sekaligus masa depan seperti apa yang dihadapi rakyat Papua dan Indonesia.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Mawa Kresna
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id