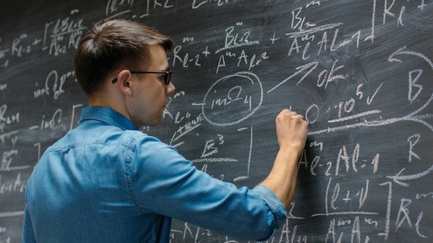tirto.id - Serial Game of Thrones bisa dibilang identik dengan hewan mitologi naga karena hewan ini punya peran penting pada jalan cerita adaptasi novel George R. R. Martin itu. Namun, naga bukan satu-satunya hewan yang eksis di semesta tersebut. Ada mamut yang jadi kendaraan para raksasa, ada kraken yang berasosiasi dengan Dinasti Greyjoy, lalu ada pula serigala dire (dire wolf) yang merupakan lambang Keluarga Stark.
Dalam karyanya Martin memang menggabungkan hewan mitologi dengan hewan-hewan yang sudah tidak lagi eksis di muka bumi. Naga dan kraken jelas hewan mitologi. Sementara mamut dan serigala dire dulu pernah ada tetapi sudah punah. Kedunya dinyatakan punah sekitar 10 ribu tahun silam.
Apa yang eksis di dunia fiksi tidak serta-merta bakal ada di dunia nyata. Itu sudah pasti. Mustahil bagi kita, misalnya, untuk tiba-tiba menciptakan seekor naga. Akan tetapi, bagaimana dengan makhluk yang telah punah? Bisakah mereka dihidupkan kembali?
Jawabannya antara ya dan tidak. Pada Oktober 2024, sebuah perusahaan rintisan bioteknologi bernama Colossal Biosciences mengumumkan kelahiran tiga anak canid hasil rekayasa genetika yang mereka sebut sebagai representasi modern dari serigala dire. Ketiganya diberi nama Romulus, Remus, dan Khaleesi.
Nama Romulus dan Remus diambil dari legenda berdirinya kota Roma. Keduanya merupakan anak kembar yang diasuh oleh serigala, lalu disebut menjadi pendiri kota yang sekarang berlokasi di Italia. Sementara nama Khaleesi memang agak aneh karena karakter ini, dalam epos Game of Thrones, sebenarnya lebih dikenal sebagai penakluk naga. Akan tetapi, lantaran Khaleesi (yang diperankan Emilia Clarke) merupakan karakter perempuan paling ikonik dari Game of Thrones, dipilihlah nama tersebut sebagai wakil dari budaya modern.
Romulus, Remus, dan Khaleesi adalah hasil dari sebuah proyek yang secara umum disebut sebagai de-extinction. Yakni, upaya ilmiah untuk menghidupkan kembali spesies yang telah punah dengan tujuan tertentu. Colossal menyebut kelahiran Romulus, Remus, dan Khaleesi sebagai "pencapaian genomik terhebat" mereka sejauh ini.
Akan tetapi, de-extinction sendiri menyimpan segudang kontroversi. Etiskah menghidupkan kembali spesies yang telah punah? Siapa yang berhak menentukan spesies apa saja yang boleh dihidupkan kembali? Lalu, adakah impak negatif yang mungkin saja muncul dari de-extinction ini sekalipun itu semua dilakukan dengan iktikad baik?
Apa Itu De-Extinction?
De-extinction adalah cabang baru dalam bioteknologi yang bertujuan untuk menciptakan kembali spesies yang telah punah melalui rekayasa genetika. Proses ini bukan sekadar menghidupkan kembali fosil atau menciptakan salinan identik dari hewan masa lalu, melainkan membangun kembali ciri-ciri kunci spesies yang punah dengan bantuan teknologi seperti pengeditan genom dan kloning, menggunakan kerabat dekat dari spesies tersebut sebagai titik awal.
Colossal Biosciences, perusahaan yang didirikan pada 2021, menjadi pelopor dalam upaya ini dengan pendekatan yang disebut mereka sebagai "genetic resurrection". Dalam kasus serigala dire, para ilmuwan mendekode genom dari sampel fosil berusia 13.000 dan 72.000 tahun, kemudian mengidentifikasi 14 gen penting yang bertanggung jawab atas karakteristik khas spesies tersebut—seperti ukuran tubuh, struktur rahang, warna bulu, dan pola vokalisasi.

Alih-alih menggunakan jaringan tua dari spesimen yang telah punah, Colossal mengambil sel progenitor endotelial dari darah serigala abu-abu modern, lalu menyunting gen-gen tersebut untuk meniru profil genetik serigala dire. Sel-sel yang telah dimodifikasi ini kemudian dimasukkan ke dalam ovum anjing yang intinya telah diangkat, menciptakan embrio hasil rekayasa yang kemudian ditanamkan ke rahim induk pengganti. Dengan teknik ini, Colossal menghasilkan anak canid yang mewarisi karakteristik morfologis dan perilaku dari spesies punah, bukan klon langsung dari nenek moyangnya.
Sejumlah ilmuwan, termasuk George Church dari Harvard, menyebut pendekatan ini sebagai terobosan karena menghindari prosedur kloning tradisional yang lebih invasif—misalnya yang dulu digunakan untuk menciptakan domba Dolly. Proses ini juga memungkinkan pengulangan skala besar karena lebih efisien dan minim risiko bagi hewan donor.
Tiga Metode Utama De-Extinction
Secara umum, ada tiga pendekatan utama yang digunakan dalam proyek de-extinction: back-breeding, kloning, dan genome editing.
Back-breeding adalah metode tertua yang berusaha menyilangkan hewan-hewan modern yang masih memiliki sifat-sifat nenek moyangnya. Tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang mendekati fenotipe spesies punah. Pendekatan ini digunakan, misalnya, dalam upaya menghidupkan kembali auroch—nenek moyang sapi domestik—melalui persilangan sapi modern yang dianggap masih menyimpan gen auroch. Meskipun metode ini relatif sederhana, hasil akhirnya tetap merupakan produk rekayasa selektif, bukan auroch otentik secara genetika.
Kloning lebih ambisius. Ia menggunakan inti sel hewan punah yang diawetkan, lalu menanamkannya ke ovum donor dan membiarkannya berkembang dalam rahim pengganti. Ini adalah metode yang digunakan saat menciptakan Pyrenean ibex (Capra pyrenaica pyrenaica) pada 2003. Hasilnya, hewan tersebut hanya hidup selama beberapa menit akibat kelainan paru-paru. Meski begitu, ini tetap menjadi bukti bahwa kloning spesies punah secara teknis memungkinkan, meski risikonya tinggi.
Dan teknologi yang menjadi andalan Colossal Biosciences adalah yang ketiga: genome editing, khususnya dengan CRISPR/Cas9. Metode ini tidak mencoba menyalin spesies lama bulat-bulat, melainkan menyunting DNA dari kerabat dekat untuk menyisipkan gen-gen kunci dari spesies yang punah.
Dalam kasus serigala dire, Colossal menyunting 14 gen penting dari serigala abu-abu agar sesuai dengan profil genetik serigala dire kuno. Dengan 20 perubahan di lokasi spesifik dalam genom, mereka menghasilkan hewan yang tidak hanya mirip secara morfologi, tetapi juga menunjukkan perilaku khas serigala dire, seperti pola vokalisasi dan respons terhadap manusia.
Pendekatan ini juga diterapkan pada proyek ambisius lainnya seperti mamut berbulu, yaitu dengan menyunting genom gajah Asia agar mendekati karakteristik mamut: bulu panjang, metabolisme lemak cepat, dan adaptasi terhadap suhu dingin. Tidak ada DNA mamut yang langsung disisipkan; gen-gen gajah hanya dimodifikasi agar menyerupai mamut sebanyak mungkin.
Perbedaan utama antara ketiga metode ini terletak pada seberapa dekat mereka bisa mendekati spesies asli yang telah punah. Back-breeding hanya menyasar tampilan luar, kloning bertujuan menciptakan salinan genetik, sedangkan genome editing menciptakan sesuatu yang baru dengan spesies lama sebagai fondasi.
Alasan di Balik Pemilihan Spesies Tertentu
Di balik setiap spesies yang ditargetkan untuk “dihidupkan kembali” tersimpan alasan ilmiah, ekologis, hingga simbolis. Serigala dire, mamut, thylacine, dan dodo bukanlah pilihan acak. Mereka adalah ikon yang dipilih karena kombinasi unik antara daya tarik publik dan peluang teknis.
Serigala dire, misalnya, dipilih karena keberadaan fosilnya yang melimpah dan kondisi genetiknya yang relatif dapat didekode. Spesies ini juga memiliki kerabat dekat yang masih hidup—yaitu serigala abu-abu—yang memudahkan proses penyuntingan genom menggunakan metode CRISPR. Selain itu, statusnya sebagai lambang budaya populer melalui Game of Thrones membuatnya sangat cocok untuk menarik perhatian publik.
Sementara mamut dipilih bukan hanya karena daya tariknya sebagai “gajah berbulu” zaman es, tetapi juga karena proyek ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang bagaimana meningkatkan ketahanan gajah Asia terhadap perubahan iklim. DNA mamut digunakan sebagai model untuk menyunting gen-gen pada gajah, dengan harapan bahwa “hibrida gajah-mamut” ini kelak bisa membantu merestorasi tundra yang terdegradasi di Siberia.

Thylacine (Harimau Tasmania) juga memiliki tempat istimewa karena kepunahannya disebabkan langsung oleh manusia pada abad ke-20. Sebagai marsupial predator terbesar di Australia, thylacine diyakini memiliki peran ekologis penting, terutama dalam mengontrol populasi mangsa (kanguru, wombat, dll.) yang kini tak lagi seimbang. Upaya menghidupkan kembali thylacine dianggap sebagai cara menebus dosa ekologis masa lalu, meskipun efektivitasnya dalam praktik masih diperdebatkan.
Selain faktor genetik dan ekologi, ada pula dimensi ekonomi dan komersial yang tidak bisa diabaikan. Proyek-proyek de-extinction Colossal menarik investasi besar, dan status ikon dari hewan-hewan seperti mamut dan serigala dire berkontribusi langsung terhadap nilai pasar dan eksposur media. Tak heran jika spesies yang punya daya tarik cerita—baik dalam mitologi, sejarah, atau budaya populer—lebih disukai daripada melindungi spesies yang kini masih eksis, tetapi mungkin kurang populer.
Artinya, pemilihan spesies untuk de-extinction tidak semata-mata ditentukan oleh sains. Ia adalah hasil dari gabungan antara peluang teknis, urgensi ekologis, dan nilai simbolis yang dapat dikapitalisasi, baik untuk konservasi maupun untuk keuntungan.
Harapan, Risiko, dan Suara yang Terbelah
Proyek de-extinction seperti yang dilakukan Colossal Biosciences tampak sangat revolusioner. Namun, di balik teknologi yang memesona, terdapat perdebatan serius yang membelah komunitas ilmiah, bioetika, dan publik secara umum.
Sebagian pihak melihatnya sebagai terobosan ilmiah. Beth Shapiro, Chief Science Officer Colossal, menyatakan bahwa teknologi ini adalah "kewajiban moral" manusia untuk memperbaiki kerusakan ekologis yang telah mereka sebabkan. Ia menyebut manusia sebagai “kekuatan evolusioner” yang kini memegang kendali atas nasib spesies lainnya. Pendekatan ini bukan hanya tentang membangkitkan kembali masa lalu, tetapi juga membuka potensi untuk menyelamatkan spesies yang hampir punah—seperti red wolf dan quoll—melalui pemanfaatan teknik yang sama.
Namun, suara optimistis ini dibayangi kekhawatiran besar dari ilmuwan lain yang menyebut de-extinction sebagai langkah berisiko dan menyesatkan.
Salah satu kritik paling mendasar datang dari sisi etika. “Hewan-hewan itu bisa sangat menderita,” kata Robert Klitzman dari Columbia University, merujuk pada risiko komplikasi selama kehamilan hingga cacat genetik yang umum terjadi dalam kloning hewan. Ia mempertanyakan legitimasi menciptakan makhluk baru hanya untuk hidup dalam kurungan dan studi eksperimen sepanjang hidupnya.
Kritikus juga menyoroti ketidakcocokan ekologis dari spesies yang dihidupkan kembali. Serigala dire, misalnya, dulunya berburu megafauna seperti mamut dan bison raksasa zaman es. Mereka adalah predator spesialis dan, ketika mangsanya punah, mereka pun ikut lenyap.
“Semakin spesifik makanannya, semakin besar risikonya,” ujar Rick McIntyre, pakar predator dari National Park Service yang menjadi penasihat Colossal. Peringatan ini menggarisbawahi bahwa, meskipun binatang-binatang tersebut berhasil hidup kembali, mereka mungkin tidak akan pernah cocok hidup di alam bebas.
Beberapa ilmuwan menuduh proyek ini sebagai aksi publicity stunt semata, bukan langkah konservasi nyata. Artikel The Conversation menyebutnya sebagai “harapan palsu”—seolah-olah kepunahan bisa dibatalkan begitu saja, padahal ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati seperti perusakan habitat dan perubahan iklim masih berlangsung tanpa solusi.
Kekhawatiran itu diperkuat oleh potensi konsekuensi tak terduga. Proses rekayasa genetik tak selalu linier. Alison van Eenennaam dari UC Davis memperingatkan soal pleiotropy, di mana satu gen bisa memengaruhi banyak karakter sekaligus—menjadikan hasil akhir sulit diprediksi. Bahkan jika serigala dire hasil rekayasa terlihat sehat, mereka bisa saja menyimpan cacat tersembunyi yang berdampak jangka panjang.
Dari sudut pandang konservasi sumber daya, banyak yang bertanya: mengapa membiayai de-extinction saat masih banyak spesies hidup yang terancam? “Kita bisa menyelamatkan spesies yang masih ada sekarang dengan biaya jauh lebih murah,” tulis para peneliti dalam The Conversation. Di tengah keterbatasan dana lingkungan, proyek ambisius seperti ini bisa membajak perhatian publik dan pendonor dari kebutuhan mendesak lainnya.
Di luar komunitas ilmiah, reaksi publik pun terpecah. Bagi sebagian orang, kebangkitan hewan seperti serigala dire adalah momen keajaiban ilmiah yang membuka babak baru dalam sejarah evolusi. Bagi yang lain, ini adalah bentuk manusia “bermain Tuhan”.
Kini, de-extinction berada di persimpangan. Pertanyaannya bukan lagi soal bisakah kita, melainkan haruskah kita melakukannya. Sampai semua pertanyaan dan keraguan bisa dijawab dengan pasti, alangkah baiknya jika segala fokus dikerahkan untuk menjaga apa yang saat ini masih ada namun terancam oleh keserakahan manusia.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id