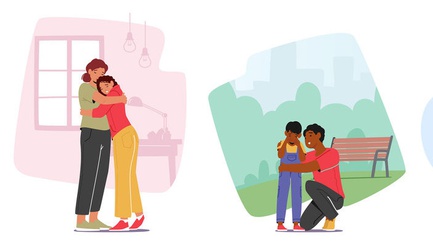tirto.id - Ada alasan mengapa perusahaan-perusahaan teknologi begitu mendewakan informasi. Para pemilik platform media sosial, misalnya Meta, memperlakukan informasi bak bongkahan emas yang, tak cuma harus dipergunakan secara strategis, tetapi juga terus digali dari sumbernya, yaitu kita, para pengguna.
Bagi perusahaan-perusahaan tersebut, informasi adalah komoditas yang menopang seluruh ekosistem ekonomi digital. Makin banyak perilaku atau preferensi pengguna yang bisa direkam, dianalisis, dan diprediksi, makin besar pula potensi keuntungan yang dihasilkan, entah lewat iklan yang ditarget (targeted ads), rekomendasi berbasis algoritma, maupun pengembangan produk.
Bagi individu pun semestinya begitu. Tanpa informasi yang cukup, tindak-tanduk kita bisa jadi tidak terarah. Karena itu, mestinya, makin banyak informasi, makin bagus untuk kita. Dengan begitu kita bisa menerapkan yang disebut informed decisions, yakni keputusan dibuat setelah menganalisis segala macam kemungkinan berdasar informasi yang tersedia.
Namun, praktiknya tidak sesederhana itu. Ada kecenderungan dalam diri manusia untuk menghindari informasi. Anda mungkin pernah melakukannya. Misalnya, ketika sedang tidak enak badan, Anda menghindari fasilitas kesehatan karena takut diagnosis dokter nantinya bakal mengungkap hal-hal yang tidak ingin Anda dengar. Tadinya cuma batuk, eh, begitu ke dokter, kok, malah jadi bronkitis? Kira-kira begitu.
Fenomena itu disebut sebagai information avoidance, yakni keputusan sadar untuk tidak mencari, membaca, atau memproses informasi yang sebenarnya ada. Menurut artikel studi terbitan Carnegie Mellon University, seseorang melakukannya bukan karena malas, tetapi karena memang secara sadar tidak ingin tahu.
Information avoidance bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang disebut physical avoidance atau penghindaran fisik, misalnya dengan tidak membuka pesan dari dokter atau mematikan notifikasi berita karena enggan mendengar kabar buruk. Ada pula attention avoidance atau penghindaran atensi, seperti ketika seseorang membaca atau menonton berita tetapi hanya setengah-setengah.
Selain itu, ada biased interpretation atau penafsiran berbias. Seseorang tetap menerima informasi secara utuh, tetapi kemudian memelintir informasi yang tidak sesuai harapan supaya "hasilnya" tetap sejalan dengan keyakinan diri. Terdapat pula penghindaran dengan berpura-pura lupa (motivated forgetting). Ini terjadi ketika seseorang sengaja mengubur informasi yang sudah diketahui, seperti berpura-pura lupa soal tagihan yang menumpuk.
Yang terakhir, masih menurut para peneliti Carnegie Mellon University, adalah self-handicapping atau dengan sengaja menempatkan diri pada situasi yang membuat dirinya tidak bisa mengakses informasi. Contohnya yaitu ketika seseorang ogah berobat ke dokter agar tidak perlu tahu hasil diagnosis medis.
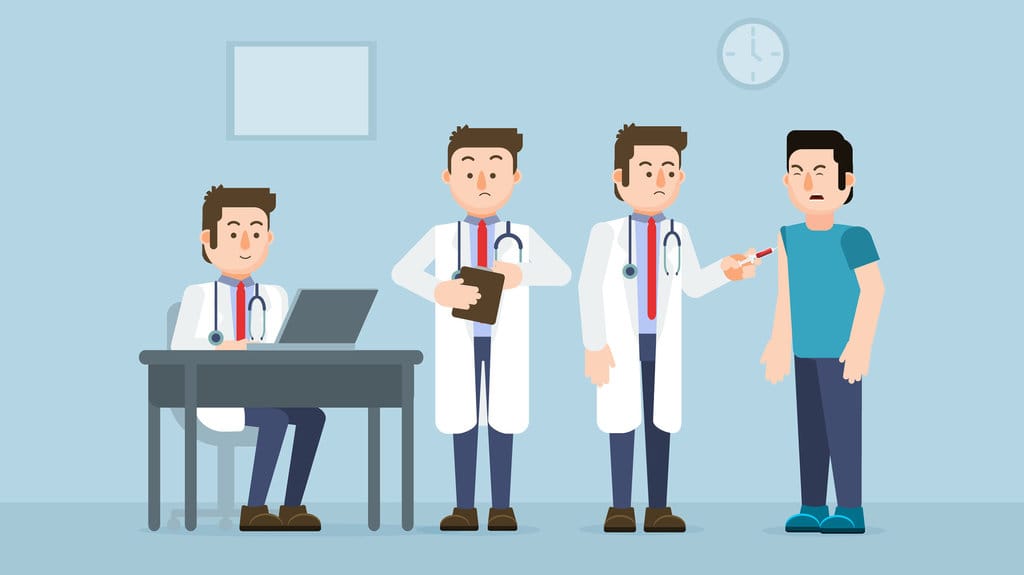
Hal yang dipaparkan ilmuwan Carnegie Mellon University bukanlah satu-satunya definisi soal information avoidance.Alison Hicks dan kolega, dari University College London, tidak melihat information avoidance sebagai kebalikan dari information seeking atau pencarian informasi, melainkan cara manusia mengatur hubungannya dengan informasi itu sendiri.
Menurut Hicks dan kolega, information avoidance bisa dilakukan dari sisi intensitas, dengan cara membatasi jumlah informasi yang diterima, atau dari sisi granularitas dengan tidak mendalami detail-detail tertentu. Ada pula sisi engagement dan control: seseorang mengambil jarak dari sebuah informasi serta memutuskan sendiri tindakannya. Selain itu, keputusan untuk melakukan information avoidance sering kali bergantung pada aspek relevansi, kualitas, serta ketepatan waktu. Tujuh hal inilah yang menjadi cara manusia menata hubungannya dengan informasi.
Hidup Tenang dengan Menghindari "Kenyataan"
Ada satu fakta menarik tentang information avoidance yang berkaitan dengan usia. Studi Cornell University (2022) tentang kebiasaan konsumsi menunjukkan, makin tua seseorang, kecenderungan untuk melakukan information avoidance makin besar.
Banyak orang tua menilai, informasi baru sering kali tidak membawa perubahan berarti, bahkan justru menambah kecemasan dan kelelahan mental. Maka dari itu, mereka memilih menghindarinya sebagai bentuk "efisiensi emosional". Makin tua, stabilitas dan kesederhanaan berpikir ternyata lebih berharga dibanding rasa ingin tahu berlebihan.
Fenonema tersebut tak dapat dilepaskan dari perubahan prioritas manusia. Selagi muda, manusia berburu pengetahuan untuk memperbesar peluang, sementara ketika sudah tua mereka lebih memilih keseimbangan dan hal-hal yang bermakna secara personal. Dalam konteks ini, information avoidance tidak bisa hanya diartikan sebagai kemalasan, melainkan upaya untuk mengambil kendali atas diri sendiri.
Meski demikian, bukan berarti yang melakukan information avoidance hanyalah orang tua. Semua kelompok usia, dalam kondisi tertentu, berpeluang besar melakukannya, terutama saat stres, cemas, atau tidak siap menghadapi kenyataan. Bagi mereka, menghindari informasi adalah cara menenangkan pikiran, meskipun efeknya hanya sementara.
Seorang asisten profesor Converse University, Jeremy Foust, pernah melakukan studi tentang itu terhadap sejumlah mahasiswa S1. Dari 181 partisipan riset, hanya 14 orang yang mengaku tidak pernah melakukan information avoidance selama dua pekan durasi penelitian. Selain itu, rata-rata responden mengaku melakukannya dalam 10 hari atau lebih.
Mengapa mereka melakukan itu? Lagi-lagi jawaban utamanya adalah untuk "meregulasi emosi". Akan tetapi, ada juga alasan lain, yaitu keengganan mengemban tanggung jawab yang muncul akibat ketersediaan informasi. Contohnya, saat seseorang tahu dirinya mengidap darah tinggi, dia harus mengurangi sate kambing. Sebaliknya, apabila tidak mengetahui diagnosis tersebut, dia tak perlu merasa terbebani sehingga bisa terus makan sate kambing sepuasnya.
Selain regulasi emosi, information avoidance juga bisa terjadi karena seseorang tidak mau pandangannya terhadap dunia terguncang. Misalnya, seorang anggota Projo menolak menonton film dokumenter Dirty Vote karena tidak mau keyakinannya terhadap kualitas Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Joko Widodo, terguncang oleh deretan fakta yang disampaikan secara gamblang dan bernas oleh para ahli di bidangnya.

Penelitian Carnegie Mellon University juga menyebut avoidance yang bersifat "strategis". Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan justru dapat menjadi pilihan rasional, misalnya dalam negosiasi, dilema moral, atau situasi emosional berat. Di sini, adanya kepastian justru tidak membantu terjaganya harapan.
Terakhir, ada yang disebut self-efficacy atau kemampuan diri. Laporan dari Max Planck Institute menemukan, orang yang merasa tidak cukup memahami topik tertentu, khususnya hal teknis seperti risiko medis, lebih memilih tidak tahu-menahu karena mereka menganggap itu semua hanya jadi beban, baik bagi pikiran maupun perasaan.
Senjata Makan Tuan
Memang benar bahwa information avoidance bisa jadi keputusan rasional yang bermanfaat. Akan tetapi, dalam titik tertentu ia bisa juga jadi senjata makan tuan.
Max Planck Institute melaporkan, satu dari tiga orang secara aktif menghindari informasi medis tentang diri sendiri, termasuk hasil tes genetik, diagnosis penyakit kronis, dan risiko Alzheimer. Alasannya bermacam-macam, mulai dari takut stres sampai takut merasa putus asa karena tidak bisa mengubah hasilnya.
Meski begitu, itu tidak bisa dibenarkan secara medis. Keterlambatan pemeriksaan dan pengobatan justru bisa membuat seseorang kehilangan waktu intervensi (penanganan). Bukan cuma kualitas hidup makin menurun, menunda-nunda intervensi medis tentu saja bisa berakibat fatal.
Selain itu, artikel studi Carnegie Mellon University menjelaskan, information avoidance bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir serta cara hidup yang--mungkin tidak salah--sudah tidak lagi relevan terhadap perkembangan dunia. Akibatnya, decision making yang dilakukan seseorang pun bisa jadi keliru karena penolakannya terhadap informasi baru.
Lagi pula, seperti yang ditemukan Foust dalam penelitiannya, para responden mengaku, meskipun information avoidance bisa memberikan kebahagiaan atau ketenangan sesaat, itu tidak serta merta menyelesaikan masalah. Bisa dikatakan, dalam beberapa kasus, information avoidance adalah bentuk lari dari masalah. Hal itu, tentu saja, hanya akan menimbulkan kerugian besar di kemudian hari.
Dengan demikian, kunci dalam melakukan information avoidance adalah sikap bijak. Ada informasi yang memang harus kita ketahui dan ada, bahkan banyak, informasi yang sebaiknya memang tidak perlu diketahui karena tidak bermanfaat. Di sinilah kebijakan itu bermain: memilah dan memilih mana yang perlu dan tidak. Jika dilakukan dengan bijak, information avoidance bakal memberi manfaat bagi para pelakunya.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id