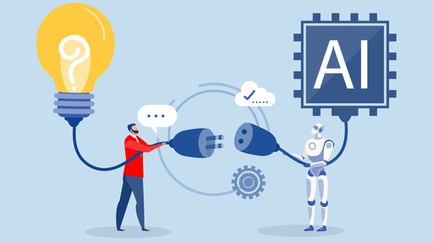tirto.id - Sepanjang April-Mei 2025, lembaga survei Nafas Indonesia Malang dan Bandung berhasil menyalip Jakarta dalam daftar peringkat kota dengan kualitas udara terburuk. Dua daerah yang kerap menjadi “pelarian” dari hiruk-pikuk metropolitan itu ternyata tidak aman dari ancaman udara kotor.
Sejauh yang diketahui awam selama ini, Jakarta merupakan kota dengan kualitas udara terburuk se-Indonesia. Terlebih, setiap tahun, ibu kota selalu terdaftar sebagai salah satu dari 10 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, sebagaimana rangking yang disusun oleh IQAir.
Akan tetapi, dua bulan terakhir, dua kota yang selama ini dianggap sejuk, yakni Malang dan Bandung, justru menempati posisi atas dalam daftar daerah dengan udara paling tercemar di Indonesia. Beberapa kota lain yang juga buruk kualitas udaranya meliputi Tangerang dan Tangerang Selatan, Surabaya, serta Semarang. Dalam daftar 10 kota dengan udara paling tercemar itu, Jakarta justru menempati kategori "aman" yakni di peringkat 8.
Tercemarnya udara di kota-kota bercuaca dingin seperti Bandung dan Malang tidak seyogianya dipandang sebelah mata. Meskipun suhu sejuk sering kali diasosiasikan dengan udara segar dan bersih, fakta justru menunjukkan sebaliknya.
Udara Sejuk Tidak Selamanya Udara Bersih
Untuk menghibur tubuh dari sesaknya udara metropolitan, orang-orang Jakarta kerap mencari pelarian ke kota-kota bersuhu rendah seperti Bandung dan Malang. Ini dianggap wajar karena udaranya dianggap lebih bersih dan menyehatkan, mengingat suhu rendah yang menyelimuti dua kota tersebut.
Namun, anggapan ini tak sepenuhnya benar. Suhu yang dingin justru bisa membuat polusi udara terjebak di dekat permukaan tanah. Fenomena ini disebut inversi suhu, yaitu kondisi ketika lapisan udara hangat berada di atas udara dingin. Situasi tersebut membuat polutan seperti PM2.5 dan ozon tidak bisa naik ataupun menyebar ke atmosfer. PM2.5 adalah singkatan dari Particulate Matter berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil dan sangat bisa masuk ke paru-paru.
Inversi suhu tak bisa dimungkiri membuat polusi menumpuk di lapisan troposfer Bumi. Timbunan polutan itu secara otomatis membuat kualitas udara memburuk, meskipun cuacanya terasa sejuk.
Memburuknya kualitas udara di kota-kota bersuhu dingin dan sejuk, seperti Malang dan Bandung, berkaitan erat dengan fenomena kemarau basah.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau basah adalah kondisi ketika hujan masih turun secara sporadis meskipun kalender musim telah memasuki periode kemarau. Menurut laporan yang sama, fenomena ini diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus 2025.
Kemarau basah, yang merupakan periode kekeringan disertai curah hujan tidak merata atau rendah, berdampak kompleks terhadap polusi dan pencemaran udara.
Di masa kemarau basah, kelembapan udara relatif tinggi meskipun curah hujan terbatas. Kondisi ini memperlambat naiknya polutan ke atmosfer. Kelembapan yang tinggi juga mendukung reaksi kimia pembentukan partikel polutan sekunder seperti PM2.5 yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara.

Secara teknis, hujan yang turun dengan intensitas ringan dan inkonsisten tidak cukup kuat membersihkan atmosfer dari partikel pencemar, seperti PM2.5 dan ozon (O3). Di sisi lain, kelembapan tinggi yang ditimbulkan dari kondisi tersebut justru memperparah akumulasi polutan.
Sebuah studi yang terbit dalam jurnal Science of the Total Environmentmenguatkan hipotesis tersebut. Penelitian itu menunjukkan, di beberapa kota di Tiongkok, selama musim dingin dan musim semi yang kering, terjadi peningkatan kadar PM2.5 mencapai 81 persen dan O3 hingga hampir 37 persen dibandingkan periode normal. Puncaknya terjadi pada Maret dan April.
Jika dikontekstualisasikan dengan situasi di Indonesia, terutama di wilayah dengan suhu dingin seperti Bandung dan Malang, periode transisi serupa rentan memicu akumulasi polusi. Maka dari itu, terjadilah fenomena kualitas udara yang memburuk meskipun suhu terasa sejuk, sebagaimana disajikan melalui visualisasi data Nafas Indonesia di atas.
Kemarau Basah yang Membayangi Hari-Hari Depan
Meskipun istilah kemarau basah baru menyeruak akhir-akhir ini, fenomena kemarau basah sejatinya bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tren musim kemarau yang tetap diselingi hujan kerap terjadi. Bahkan, sudah sejak 2022 BMKG menyoroti peristiwa turunnya hujan secara berkala meski sudah memasuki musim kemarau.
Hal ini menunjukkan adanya pola yang makin konsisten. Para ahli mengaitkan kecenderungan ini dengan perubahan iklim global yang memperlemah siklus musiman. Akibatnya, transisi musim menjadi tidak menentu.
Bahkan, hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan, telah terjadi perubahan temperatur signifikan di pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari pembandingan kondisi suhu antara rentang 2021-2050 dan 1991-2020.
Tak dapat dimungkiri, fenomena kemarau basah berhubungan erat dengan perubahan cuaca yang ekstrem. Menurut artikel penelitian berjudul “Extreme weather in a changing climate” (2023), fenomena cuaca ekstrem merupakan dampak awal dari meningkatnya suhu global.
Cuaca ekstrem berdampak besar bagi kehidupan, baik manusia maupun ekosistem alam. Ia berpotensi meningkatkan mortalitas, cedera, dan penyakit pada makhluk hidup, serta memberikan dampak sosial ekonomi yang besar.

Sorotan mengenai masalah kemarau basah ini harus ditempatkan pada akar masalah yang lebih mendasar, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Lebih dari 99 persen komunitas ilmiah yang menerbitkan artikel di jurnal bereputasi menyatakan, secara eksplisit maupun implisit, bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia.
Aktivitas destruktif manusia terhadap perubahan iklim mencakup emisi gas rumah kaca, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan berbagai praktik merusak lainnya.
"Menurut ringkasan IPCC AR6 [Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report] dan banyak studi sebelumnya, upaya mengurangi pemanasan di masa depan memerlukan tindakan mendesak untuk menghentikan pembakaran bahan bakar fosil dan sumber utama emisi gas rumah kaca lainnya," demikian ditegaskan melalui catatan kesimpulan dalam penelitian ilmiah yang terbit di jurnal Environmental Research Letter (2021).
Dengan kata lain, kemarau basah bukan hanya fenomena alam semata, melainkan cerminan dari krisis ekologis yang kita ciptakan sendiri. Pencemaran udara di balik suhu sejuk merupakan wujud krisis nyata di sekitar kita.
Saat ini, paradoks tersebut terpampang nyata: kota-kota yang selama ini menjadi destinasi pelarian dari sesak napas justru berbalik menjadi perangkap gas beracun tak kasatmata.
Jika kota-kota sejuk pun sudah tercemar, ke mana lagi kita bisa pergi untuk sekadar bernapas lega?
Penulis: D'ajeng Rahma Kartika
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id