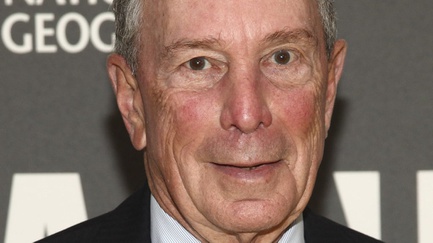tirto.id - Kalau Anda merasa hidup berkecukupan tapi masih sering diejek miskin, jangan buru-buru merasa tersinggung. Sebab, boleh jadi ejekan itu ada benarnya. Bahkan, mungkin saja mereka yang mengolok-olok Anda juga berada di perahu yang sama: sama-sama masuk kategori miskin menurut standar terbaru Bank Dunia.
Per Juni 2025, lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington, D.C. tersebut merilis pembaruan garis kemiskinan global. Untuk negara negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, ambang batas kemiskinan kini naik dari 6,85 dolar menjadi 8,30 dolar per hari. Perubahan ini mengikuti pembaruan metode penghitungan berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017 yang sebelumnya digunakan.
Selain itu, Bank Dunia juga merevisi garis kemiskinan untuk kelompok negara lain: dari 2,15 dolar menjadi 3,00 dolar per hari untuk negara berpendapatan rendah, dan dari 3,65 dolar menjadi 4,20 dolar per hari untuk negara berpendapatan menengah bawah.
Perubahan tersebut berimbas pada berubahnya angka orang melarat di Indonesia. Berdasarkan garis kemiskinan internasional yang baru, jumlah penduduk miskin di Tanah Air mencapai 194,4 juta jiwa atau setara dengan 68,91 persen dari total populasi naik dari sebelumnya 60,3 persen pada laporan Macro Poverty Outlook April 2025. Artinya, hampir dua dari setiap tiga warga Indonesia kini dikategorikan miskin menurut standar global.
Harap diingat bahwa angka tersebut berbeda jauh dengan penghitungan kemiskinan versi BPS, yang mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 hanya mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Sebab, lembaga statistik nasional tersebut menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam menentukan garis kemiskinan, yakni dengan memperhitungkan pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan makanan (2.100 kilokalori per hari) dan kebutuhan bukan makanan, seperti perumahan dan listrik.
Dan tulisan ini tak hendak mengulang polemik soal perbedaan ambang batas garis kemiskinan BPS—yang berada di angka Rp595.243 per orang per bulan—dengan data Bank Dunia. Sebab, menurut ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, perdebatan mengenai kemiskinan di Indonesia terlalu terpaku pada garis kemiskinan yang disusun secara teknokratis oleh Bank Dunia maupun BPS.
Temtu persoalan mendasarnya tidak terletak pada ukuran angka itu, melainkan pada kenyataan pahit yang dialami mayoritas penduduk di 60 persen lapisan terbawah masyarakat. “Nasib mereka tidak berubah meski garis kemiskinan digeser naik atau turun. Pemerintah seakan terjebak dalam permainan statistik, mengklaim penurunan kemiskinan padahal ketimpangan ekonomi justru semakin memburuk dari rezim ke rezim,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (11/6/2025).
Syafruddin juga menekankan bahwa selama ini akar persoalan kemiskinan sesungguhnya, yakni distribusi kekayaan dan penguasaan aset yang semakin timpang, kerap luput dibahas secara serius. “Lihat saja data Sensus Pertanian dari 1963 hingga 2023, atau Sensus Ekonomi dari 1976 hingga 2016, semuanya menunjukkan tren ketimpangan yang konsisten dan mengkhawatirkan,” tuturnya .
Pernyataan tersebut sejalan dengan data BPS yang menunjukkan gini ratio Indonesia naik dari 0,379 menjadi 0,381 antara Maret dan September 2024. Tidak meratanya distribusi pendapatan pada periode sama juga terekam oleh data Bank Dunia yang mencatat bahwa porsi pengeluaran kelompok 20 persen terkaya meningkat dari 45,91 persen menjadi 46,24 persen, sementara kelompok 40 persen kelompok termiskin stagnan di kisaran 18,4 persen.
Padahal, sebagai negara berpendapatan menengah atas, dengan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau sekitar 4.960 dolar AS, ketimpangan di Indonesia harusnya bisa ditekan sebagaimana tergambar dalam teori Simon Kuznets tentang kurva U terbalik—bahwa ketimpangan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, mencapai titik puncak, dan kemudian menurun seiring dengan kemajuan ekonomi.
Hemat Syafruddin, ketimpangan tersebut berkorelasi erat dengan koefisien gini kepemilikan lahan di Indonesia. Dalam sejumlah penelitian di wilayah Sumatera, misalnya, ia menemukan bahwa tanah pertanian terkonsentrasi pada beberapa orang tertentu sehingga menyebabkan petani dengan lahan terbatas dengan pendapatan minim kian banyak.
Redistribusi lahan untuk rumah tangga petani berlahan kecil atau tidak punya lahan sama sekali, melalui reforma agraria, dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus ketimpangan dimaksud.
“Pemerintah seharusnya berhenti mengejar angka semu dan mulai menatap realitas di lapangan. Menurunkan kemiskinan berarti menurunkan kesenjangan ekonomi. Tanpa upaya serius untuk mereformasi distribusi tanah, mengoreksi struktur kepemilikan aset, memperkuat sektor rakyat, dan merancang pajak yang adil, maka kemiskinan hanya akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” jelasnya, sembari menambahkan bahwa Indonesia punya data lengkap, sejarah panjang, serta punya kapasitas institusi untuk melakukan hal tersebut.
“Yang ditunggu hanyalah keberanian politik untuk keluar dari perangkap garis kemiskinan, dan mulai menjadikan kesetaraan ekonomi sebagai pondasi utama keadilan sosial,” imbuh Syafruddin.
Sementara itu, peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Muhammad Anwar mengatakan bahwa pembaruan garis kemiskinan versi Bank Dunia harus dilihat sebagai sinyal serius bahwa kualitas hidup sebagian rakyat Indonesia masih rapuh dan belum terlindungi secara layak oleh sistem ekonomi nasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk bertindak lebih progresif dan berani dalam menyusun kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Setidaknya, tutur Anwar, ada lima strategi yang bisa dijalankan pemerintah.
Pertama, membenahi basis data kemiskinan dalam konteks distribusi bantuan sosial— hal fundamental yang harus segera dilakukan namun kerap diabaikan. Dengan melakukan perbaikan data, pemerintah dapat memitigasi masalah utama yang terjadi di lapangan, baik berupa exclusion error atau tidak masuknya keluarga miskin yang membutuhkan ke dalam daftar penerima, maupun inclusion error atau kondisi di mana orang-orang yang sebenarnya tidak miskin atau tidak lagi memenuhi kriteria justru tetap terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Pemerintah harus menjadikan pembenahan data sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar urusan teknis kementerian sosial atau lembaga statistik,” ucap Anwar. “Tidak akan pernah ada program pengentasan kemiskinan yang benar-benar efektif jika data yang digunakan oleh pemerintah masih berantakan, tumpang tindih, atau tidak mencerminkan realitas sosial yang ada,” sambungnya.
Kedua, menunjukkan komitmen melalui alokasi anggaran yang kuat dan progresif untuk rakyat miskin dan APBN dan APBD bukan hanya sekadar instrumen teknokratis, tapi menjadi alat keberpihakan yang nyata.
“Belanja negara yang besar seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan proyek atau kelompok elit tertentu. Transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran sangat menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.
Ketiga, perluasan dan peningkatan kualitas jaminan sosial yang adaptif dan inklusif, di mana program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya perlu ditata ulang agar lebih presisi, tepat sasaran, dan mampu memberdayakan, bukan hanya menenangkan.
Jaminan sosial tidak boleh menjadi alat politik, tapi menjadi bagian dari kontrak sosial negara dengan rakyat miskin yang berhak dilindungi ketika tertimpa musibah atau mengalami ketimpangan struktural.
Ke depan, jaminan sosial juga harus diarahkan pada peluang mobilitas sosial, misalnya melalui subsidi pendidikan berkualitas, pelatihan kerja produktif, dan akses terhadap perumahan terjangkau.
Keempat, reindustrialisasi ekonomi rakyat demi menciptakan ekosistem industri padat karya berbasis komunitas yang tersebar di daerah-daerah, sekaligus menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan terakhir, pembenahan sistem pendidikan serta kesehatan sebagai alat perbaikan struktural jangka panjang.
“Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak miskin mendapat akses pendidikan berkualitas sejak dini, tanpa diskriminasi, dan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah terpencil tidak hanya berdiri, tapi juga berfungsi optimal. Gizi buruk, stunting, dan rendahnya capaian pendidikan adalah akar yang mengunci kemiskinan antar generasi,” tandasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra & Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id