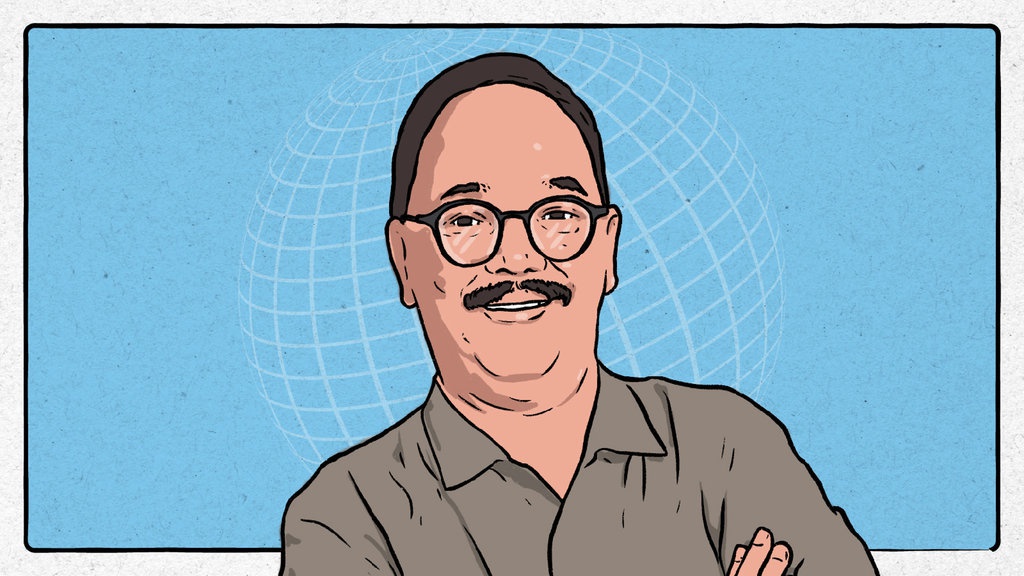tirto.id - Setiap 30 September, Indonesia mengenang salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Republik: Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30S dan tragedi berdarah yang lahir setelahnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu, namun luka dan perdebatan di seputar peristiwa ini masih terasa buram.
Narasi tunggal yang mendominasi di era Orde Baru telah membentuk pemahaman kolektif, terutama bagi generasi yang tumbuh di bawah rezim tersebut. Lalu, bagaimana dengan anak muda hari ini?
Survei yang dilakukan oleh Tirto dan Jakpat mencoba memotret persepsi tersebut. Hasilnya menunjukkan temuan menarik, namun tidak begitu mengagetkan. Mayoritas anak muda kita masih mengandalkan sumber resmi dari sekolah dan film propaganda Orde Baru pada kaitan tentang informasi peristiwa G30S.
Dalam wawancara eksklusif dengan Tirto, sejarawan Andi Achdian mengupas tuntas temuan survei. Andi melihat terjadi paradoks dalam cara anak muda hari ini menyikapi sejarah.
Dibanding generasi sebelumnya, mereka tidak lagi terbebani trauma politik masa lalu. Jarak waktu dan minimnya tekanan membuat anak muda hari ini mampu bersikap lebih objektif. Namun, pengetahuan yang mereka serap ternyata masih “sepotong-sepotong”, didominasi oleh satu versi sejarah yang mengubur sumber alternatif lain.
Menurut Andi, ini adalah konsekuensi dari dominasi sumber resmi yang sudah terformalisasi lewat institusi pendidikan hingga budaya populer yang disokong penguasa. Meski telah hadir banyak sumber alternatif seperti buku dan film dokumenter, sumber-sumber tersebut tidak mudah dijangkau oleh publik luas.
“Yang mainstream itu yang masih juga dipilih. Yang produk pemerintah punya gitu kan. Saya mau bilang tekanannya ada pemahaman yang tidak lengkap tentang sejarah masa lalu,” kata Andi kepada Tirto lewat sambungan telepon, Rabu (24/9/2025).
Lebih lanjut, Andi menekankan pentingnya sumber-sumber alternatif yang dilengkapi adanya dialog kritis. Pengetahuan, kata dia, harus dilengkapi dengan dialog agar dapat berkembang menjadi kesadaran kritis. Jika ruang dialog ditutup, kita akan terus terjebak dalam lingkaran pemahaman sejarah yang dangkal dan parsial.
Lantas, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Apa yang dapat dilakukan agar anak muda lebih kritis dalam menyikapi sejarah kelam bangsa? Simak petikan wawancara Tirto bersama Andi Achdian di bawah ini:
Secara umum bagaimana Anda melihat persepsi anak muda hari ini soal peristiwa G30S?
Dari segi bagaimana pengetahuannya, saya kira mungkin masih akan tetap sama ya dengan generasi-generasi yang lalu gitu. Dari zaman saya juga bahwa orang dapat sebuah peristiwa enggak utuh. Cuma dalam cara memahaminya agak berbeda menurut saya. Kalau generasi tahun 70an, 80an, mereka mendapatkan informasi dengan juga mereka nanti ikut di dalam era ketakutan dan politiknya Orde Baru.
Jadi mudah terintimidasi oleh tekanan gitu ada traumanya juga di dalamnya. Tapi kalau generasi muda sekarang mereka mendapatkan informasi tanpa beban. Jadi mereka lebih bisa objektif gitu tidak dapat terintimidasi, tidak mempan dituduh macam-macam. Jadi mereka lebih berjarak, karena dari segi waktu membuat mereka lebih berjarak, jadi lebih banyak kesadaran kognitif yang kuat tanpa ada beban emosional atau beban historis traumatik.
Namun kenapa dari segi pengetahuan terhadap peristiwa G30S kenapa masih sama?
Karena memang informasinya sama produknya ya. Jadi kalau di publik kan biasanya orang akan dapet [narasi sejarah] yang formal dulu kan. Tapi yang formal itu sendiri menolak atau menguburkan cerita lainnya itu. Jarang ada yang sampai ke kita di luar itu, yang kajian-kajian akademi, film, dan sebagainya yang merupakan sumber alternatif.
Tapi sumber alternatif kan tidak mudah mendapatkannya. Orang harus effort dulu, bacanya dan sebagainya. Kalau sumber resmi memang disampaikan. Maka pengetahuan tetap selalu akan selalu sifatnya sepotong-sepotong. Tentang antara PKI itu salah, atau tidak, dan lain-lain lah pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab.
Survei Tirto dan Jakpat memotret mayoritas responden (59 persen) mengaku mengetahui G30S dari pelajaran di sekolah, dan hanya 37 persen yang mencari lebih lanjut setelah dapat versi formal. Menurut Anda bagaimana hasil temuan ini?
Itu jadi meneguhkan apa yang kita bicarakan sebelumnya bahwa saluran resmi pengetahuan itu ada di sekolah dan kita tahu yang terbesar dalam memberikan pengetahuan buat anak muda sekarang. Sementara yang kita ketahui secara saintifikal apa yang mereka dapat tidak utuh atau hanya satu versi dari versi pemerintah yang masih menyangkal pelanggaran HAM berat setelah peristiwa G30S.
Maka menurut survei itu kan baru yang 37 persen tercerahkan, mendapatkan sumber lain dari film atau sumber alternatif lain. Tapi kan yang 50 persenan masih di dalam siklus itu.
Dari segi informasi, mayoritas responden mengaku sumber informasi soal G30S didapat dari buku pelajaran sekolah. Menariknya, banyak responden juga mengaku mendapat informasi soal G30S dari film Pengkhianatan G30S/PKI. Artinya versi sejarah ‘resmi’ memang dominan, apa konsekuensinya?
Maka kita masih punya problem dalam melihat masa lalu kita. Meskipun sudah banyak juga film bagus soal itu [tragedi 1965], tapi kan itu masih terbatas tuh. Kalau kita bicara kan film , yang mainstream itu yang masih juga dipilih. Yang produk pemerintah punya gitu kan.
Saya mau bilang tekanannya ada pemahaman yang tidak lengkap tentang sejarah masa lalu. Itu yang terjadi
Apakah memang sumber resmi Negara soal G30S masih membentuk persepsi anak muda soal peristiwa ini?
Saya kira iya, paling tidak masih. Jadi akhirnya mereka melihat korban [tragedi 1965-1966] itu bukan sebagai korban yang kehilangan haknya tapi sebagai korban yang patut dikasihani saja. Mereka adalah orang yang bersalah, dari itu dulu kan yang tidak berubah.
Kemudian kalau mereka bersalah, ‘ya tetap perlakukan dengan baik lah’. Tapi pada poinnya tidak berubah, mereka tetap dipandang bersalah. Padahal kesalahan itu yang tidak pernah jelas apa salahnya.
Kenapa orang dipenjara, dibunuh. Jadi tetap informasinya berdasar versi mainstream, bahwa orangnya bersalah. Tapi kemudian muncul empati terhadap korban.
Karena sampai sekarang kan, apa yang menjadi kesalahan sehingga mereka mendapatkan hal seperti itu ya? Kan itu yang menjadi problem. Tidak ada peradilan, tidak ada penetapan, orang ditangkap dieksekusi dan lain sebagainya. Jadi hanya hukuman sosial dan hukuman politik. Dan itu tidak adil, orang tidak berbuat apa-apa tapi dihukum gitu.
Kembali ke survei, mayoritas responden anak muda ini memandang G30S sebagai peristiwa pembunuhan jenderal di lubang buaya dan pengkhianatan PKI. Baru sekitar 50 persen yakni di urutan ketiga, responden menilai G30S sebagai momen awal mula pembantaian orang PKI dan simpatisannya. Menurut Anda, kenapa urutannya bisa seperti ini?
Sekali lagi kan itu menegaskan poin survei sebelumnya, informasi G30S sejarah yang mereka dapat informasi yang mereka dapat dari sekolah. Artinya kalau mereka hanya mendapatkan dari sekolah, ya memang ada masalah dalam kesadaran sejarah sekarang.
Walaupun sebetulnya sudah bagus, ada 50 persen yang mulai tahu [peristiwa pembantaian 1965-1966]. Jadi bisa dibilang juga kalau generasi sekarang atau anak muda sekarang lebih terdidik juga dibanding sebelumnya. Meskipun informasi yang lebih dominan informasi yang mainstream dalam proses belajar mereka.
Medium alternatif soal G30S memang sudah banyak lewat buku, film dokumenter, yang itu di luar sejarah resmi versi Orde Baru. Bagaimana Anda melihat perkembangan sumber alternatif ini?
Kita bisa lihat positif ada sebuah sumber-sumber media dari media sosial, online, dan digital lainnya yang menjadi sumber alternatif terhadap sejarah masa lalu. Walaupun sebenernya survei Tirto juga membuktikan bahwa sistem pendidikan jauh masih tetap mempengaruhi di pemahaman sejarah. Hasil survei-nya mengatakan bahwa top of mind yang mereka tahu soal Lubang Buaya atau pembunuhan jenderal.
Artinya sekolah masih jauh lebih mempengaruhi pikiran dan kesadaran sejarah di banding narasi sejarah yang muncul di media sosial atau ruang digital. Logikanya belum lengkap, meskipun kemudian muncul sumber-sumber alternatif bahwa mereka bisa berpikir dengan cara yang baru.
Seberapa urgensi adanya sumber-sumber alternatif terkait peristiwa G30S dan 1965?
Pastinya dibutuhkan banget, problemnya begini di dalam di dunia digital sekarang orang itu enggak kekurangan informasi menurut saya tapi justru kebanjiran informasi. Informasinya begitu masif banjir, tapi tak tahu informasi apa yang terbuka.
Jadi bukan masalah kurang informasi atau kurang tahu, tapi justru tahu,‘seperti apa?’, yang menjadi problem.
Lantas bagaimana agar lebih kritis menyikapi sejarah di tengah banjir informasi?
Kesadaran kritis hanya bisa berkembang dengan dibarengi dialog. Kalau hanya mengandalkan informasi satu arah saja, kita hanya tahu. [Misal] dari informasi online kan, kita tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk sampai ke kesadaran kritis pengetahuan itu harus dilengkapi dialog.
Proses dialog ada dalam lembaga pendidikan atau lembaga organisasi yang membuka ruang itu. Karena kalau hanya tahu aja tidak bisa mengubah apapun. Tapi dengan dialog ada proses dialogis pembaruan kesadaran dan itu yang membuat pengetahuan lebih baik. Jadi jangan sampai ruang dialog itu ditutup, apalagi oleh pemerintah.
Semakin banyak kaum muda membuka dialog dalam proses mencari pengetahuan itu. Dari pendekatan yang ada di permukaan di ruang digital, jadi bisa dipahami dalam keseharian untuk membangun kesadaran yang terbuka dan kritis.
Dialog ini bentuknya harus ada diskusi, proses belajar di sana, formal maupun informal.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id