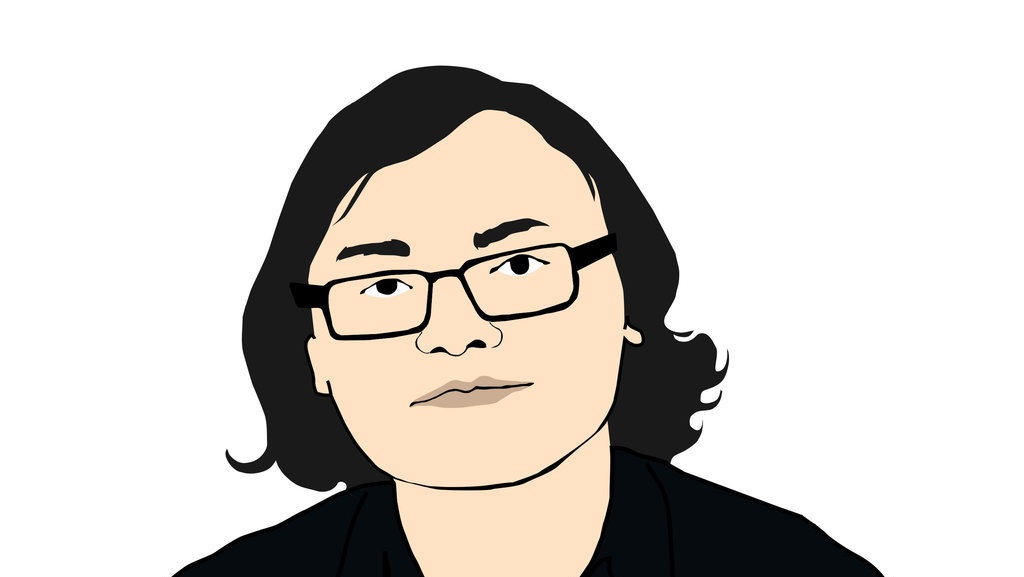tirto.id - “Reforma Agraria” kembali ramai jadi perbincangan publik pasca Debat Calon Presiden beberapa waktu lalu.
Yang paling diingat mungkin ialah penekanan Jokowi terhadap penguasaan lahan Prabowo yang mencapai ratusan ribu hektar. Keriuhan di media sosial tambah hangat saat muncul berbagai diagram dan gambar yang memperlihatkan orang-orang di lingkaran kedua calon Presiden yang menguasai lahan dengan luas fantastis. Sebagian gambar menyematkan keterangan “Tuan Tanah” kepada mereka.
Meski barangkali berguna untuk memberi nuansa tertentu, istilah tuan tanah secara konseptual mungkin kurang terlalu akurat. Tuan Tanah (landlord) umumnya merujuk pada mereka yang mendasarkan pengambilan laba dari sewa (baik dalam bentuk sewa tetap atau bagi hasil). Para ‘tokoh’ penerima hak penguasaan tanah negara dalam jumlah fantastis itu bukanlah tuan tanah yang menyewakan tanahnya untuk kemudian menerima uang sewa atau bagi hasil.
Mereka adalah pemilik modal yang menggunakan tanah untuk memproduksi komoditas untuk dijual di pasar dengan mempekerjakan buruh. Dengan kata lain, mereka mendasarkan pengambilan laba dari nilai yang diciptakan para buruh. Secara deskriptif, inilah yang disebut pengusaha atau secara konseptual biasa dikenal dengan kapitalis.
Klarifikasi ini kiranya penting sebelum membahas polemik mengenai Reforma Agraria (RA). Dalam debat capres kedua, Jokowi sebagai petahana kembali menyinggung bahwa Reforma Agraria telah dijalankan dan akan terus dilanjutkan jika ia terpilih kembali. Di samping secuil janji redistribusi lahan yang telah dilunasi, sertifikasi tanah masih menjadi andalan utama yang dibanggakan dalam program Reforma Agraria ala Jokowi.
Tak Hanya Bagi-bagi Tanah
Namun, jika dilihat secara historis, RA selalu melibatkan “perombakan” atau “penataan ulang” terhadap penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber kunci agraria seperti tanah dan air. Tidak heran jika sudah banyak kritik (dan tidak perlu diulang disini) yang menekankan bahwa sertifikasi tanah bukanlah bagian dari RA. Program sertifikasi tanah yang gencar dipromosikan Bank Dunia di seluruh dunia ini juga bukan khas pemerintahan Jokowi, karena pemerintahan SBY telah lebih dulu memulainya. Klaim agenda RA tanpa redistribusi lahan hanyalah komedi yang tidak lucu.
Redistribusi lahan sebagai agenda RA sejati bahkan juga tidak akan memadai jika hanya menyasar “kapitalis besar” penguasa tanah konsesi negara. Secara substansial, ini bermasalah karena jika kita memang teguh pada prinsip “tanah untuk penggarap”, “kapitalis kecil” di pedesaan yang mengandalkan tenaga buruh untuk menggarap lahannya (tidak menggarapnya dengan tenaga keluarganya sendiri) juga patut menjadi sasaran RA.
Implikasinya secara riil politik amat penting. Sudah banyak studi agraria kritis menunjukkan bahwa “kapitalis kecil” di pedesaan yang berada di sekitar konsesi perkebunan seringkali menjadi “centeng” atau tangan kanan para “kapitalis besar” pemilik konsesi. Di pedesaan pertanian padi, “kapitalis kecil” inilah yang sejak Revolusi Hijau paling menikmati bantuan negara dan menjadi pendukung setia pemerintah. Apakah memungkinkan menggusur “kapitalis besar” tanpa melawan “kapitalis kecil”, atau paling tidak memperhitungkan posisi politik mereka?
Ini berkaitan dengan aspek lain dari RA. Dari sejarah, kita belajar bahwa RA yang sejati (redistribusi) hanya dimungkinkan dengan dukungan kekuatan politik dari bawah. Memang ada pengecualian seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. RA di ketiga negara yang terjadi pasca-Perang Dunia II diinisiasi dari atas, dengan intervensi militer Amerika Serikat. Tapi dalam konteks Perang Dingin, inisiatif itu hanya dilakukan karena program redistribusi lahan oleh kaum komunis yang telah dilakukan di banyak tempat dikhawatirkan akan menarik simpatisan di ketiga negara.
Tanpa konteks geopolitik ini, tidakkah lucu jika negeri kapitalis seperti Amerika Serikat justru ‘memaksakan’ agenda komunis (redistribusi lahan)? Inilah mengapa dalam kasus Indonesia, ketika kekuatan komunisme telah dihancurkan pada 1965, Amerika Serikat tidak lagi “memaksakan” dilakukannya RA disini, tapi justru mendukung Revolusi Hijau yang tak punya urusan sama sekali dengan redistribusi lahan.
Harus ditekankan bahwa ‘kekuatan dari bawah’ ini bukan sekedar petani (dari berbagai kelas sosial berbeda) yang tergabung dalam wadah serikat petani untuk melawan korporasi atau negara. Di sinilah analisa kelas menjadi penting. Serikat petani yang didominasi petani pemilik lahan (apalagi yang mempekerjakan buruh untuk menggarap lahannya) mungkin tidak akan militan memperjuangkan RA. Mereka lebih tertarik mendorong kampanye “Kedaulatan Pangan”, “Subsidi Pertanian”, “Harga Produk Pertanian yang Pro Petani” atau “Pertanian Organik”.
Yang bisa diandalkan menjadi penggerak RA dari bawah hanyalah serikat tani berisikan mayoritas buruh tani tak bertanah dan petani gurem yang masih menggarap tanahnya dengan tenaga sendiri.
Sejarah takkan berpihak kepada kita jika kita sekedar mengandalkan kemauan politik para elite untuk melaksanakan RA. Pidato Jokowi yang sekedar ‘menunggu’ para pemilik konsesi seperti Prabowo untuk mengembalikan tanah konsesinya dengan cuma-cuma tak ubahnya pungguk merindukan bulan. Di sisi lain, ada juga aktivis agraria yang percaya RA sejati dapat dilakukan dengan membonceng kekuasaan seorang tokoh yang dianggap bersih dan punya kemauan politik tapi didominasi para “kapitalis besar”, tanpa membangun serikat tani berbasis buruh tani dan petani gurem. Kita tidak tahu apakah mereka melupakan sejarah atau sedang membohongi diri sendiri.
Beberapa Pertanyaan
Soalnya tidak berhenti di situ. Dalam perjalanannya, RA juga tidak pernah berhenti sekedar berurusan dengan tanah atau pertanian belaka. RA juga berarti reorganisasi menyeluruh produksi di berbagai sektor (pertanian, industri, jasa). Terutama soal koordinasi antar-sektor pasca-redistribusi lahan seandainya sudah dibagikan.
Beberapa pertanyaan mesti didiskusikan dengan serius. Misalnya, apakah upah pekerja di sektor pertanian akan tetap dijaga rendah seperti saat ini, atau diselaraskan dengan sektor lain (misalnya manufaktur) meski akan beresiko meningkatkan ongkos produksi pertanian dan mengurangi tingkat keuntungan usaha tani? Jika kita ingin mengurangi secara drastis jumlah pekerja di pertanian dan memastikan mayoritas petani pemilik lahan menggarap lahannya sendiri alias tak mempekerjakan buruh pertanian, apakah model kepemilikan lahan individu dapat memenuhi tuntutan efisiensi dan produktivitas?
Yang tak kalah penting, apa kebijakan harga pertanian yang harus diambil? Banyak pihak yang mendukung tuntutan “Harga Produk Pertanian yang Pro Petani”. Jika “pro” disini berarti harga yang “mahal”, bagaimana akses mereka yang bukan produsen pertanian, terutama para buruh baik di perkotaan atau pedesaan yang bukan penghasil produk pertanian? Dalam hal beras misalnya, apakah para buruh mesti terus membayar harga beras produk dalam negeri yang harganya lebih mahal dari harga internasional? Di perkebunan rakyat, apakah tanaman komoditas seperti sawit, karet, cokelat perlu dilanjutkan mengingat dampak lingkungannya yang buruk (terutama sawit) dan resiko gejolak pasar global yang mengombang-ambingkan harga jual? Jika diganti, tanaman apa yang memiliki nilai ekonomis serupa tapi tidak bergantung pada gejolak pasar global?
Ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya: apakah memang kita akan terus bertumpu pada pertanian dan menjual produk pertanian (bahan mentah) dengan nilai tambah rendah ke pasar global sementara kita bergantung pada produk manufaktur dengan nilai tambah tinggi dari luar negeri? (Tukar guling antara Pesawat Tempur Sukhoi Rusia dengan produk pertanian kita adalah contoh paripurna).
Juga, apakah pertanian difungsikan untuk mendukung industrialisasi, atau sebaliknya industri dikembangkan ala kadarnya untuk menjaga citra “negeri agraris” sementara puluhan juta pekerja yang bakal tak kebagian redistribusi lahan terombang-ambing di antara desa-kota tanpa perlindungan hukum negara memadai (informal)?
Pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak penting bagi para penguasa konsesi tanah negara, tapi mustahil dihindari siapapun yang hendak menjalankan RA sejati. Sayangnya, perspektif sektoral dalam melihat RA yang seringkali dipromosikan sebagian aktivis agraria dan pegiat NGO selama ini menjauhkan kita dari membahas pertanyaan-pertanyaan lintas sektoral itu.
Tanpa mendiskusikan aspek-aspek fundamental dari RA di atas, mungkin lima tahun lagi kita akan menertawakan calon presiden yang mengampanyekan “Reforma Agraria”. Mereka mungkin bukan lagi calon yang berlaga di pilpres sekarang. Namun, tanpa pembangunan kekuatan politik dari bawah, para calon baru itu juga tak akan jauh-jauh wujudnya dari kaum—meminjam istilah Sukarno—“ongkang-ongkang kaki” yang memeras keringat buruh agar menjalankan pabrik atau merawat lahan pertanian yang bukan milik sendiri.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id