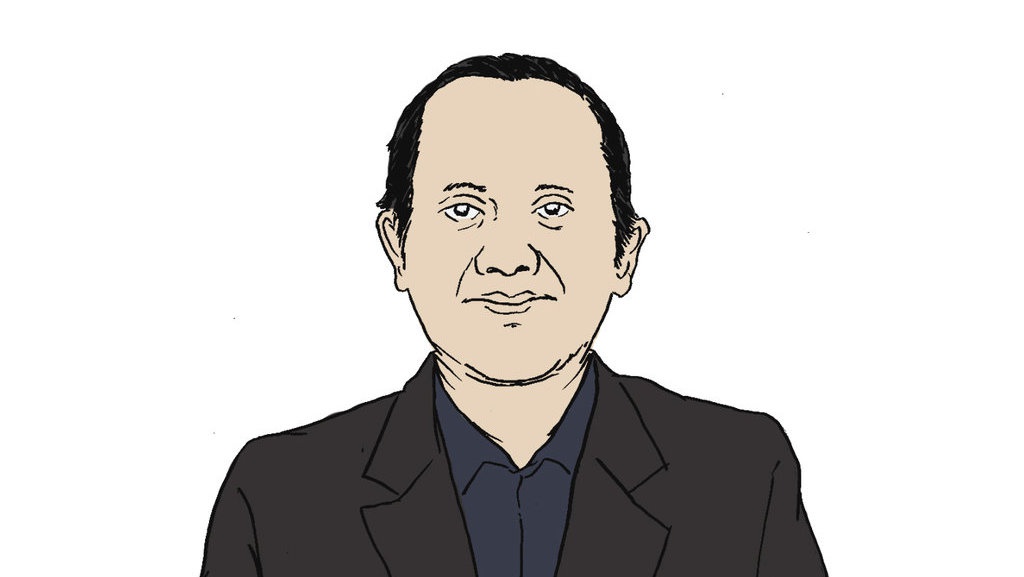tirto.id - Pilpres kali ini kembali diwarnai oleh perdebatan dan saling klaim seputar siapa calon presiden yang paling peduli dengan kehidupan wong cilik pedesaan—petani, nelayan, dan segenap masyarakat miskin desa lainnya. Baik Jokowi, capres petahana, maupun Prabowo, capres penantang, sama-sama mencitrakan diri sebagai pemimpin yang pro-kepentingan petani.
Benarkah demikian?
Observasi yang lebih cermat akan menunjukkan bahwa retorika dari kedua capres jauh panggang dari api. Menjelang debat capres kedua pada 17 Februari nanti yang fokus kepada isu-isu energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastuktur, kita perlu melihat tawaran kebijakan agraria dari kedua capres.
Perlu diingat bahwa agraria bukan sekedar persoalan “pertanahan”, melainkan perkara ruang hidup bagi para produsen langsung (direct producers) komoditas pedesaan yaitu buruh tani, petani kecil, petani menengah yang mengalami kerentanan ekonomi, dan masyarakat miskin desa yang bergantung kepada sumber daya pedesaan seperti tanah, ruang, lingkungan, dan berbagai ikatan sosial yang melekat kepada segenap sumber daya tersebut.
Sebelum mengevaluasi proposal kebijakan dari kedua capres, kita perlu lebih seksama melihat kondisi agraria Indonesia. Dalam konteks persoalan agraria, kedua capres sama-sama menghadapi tantangan yang akut dan bersifat struktural: tiga dekade pembangunan desa yang otoritarian selama Orde Baru dan dua dekade ekspansi kepentingan pasar di daerah pedesaan di masa Reformasi. Selama lima puluh tahun itu, persoalan klasik di desa tetap berlangsung: kemiskinan, kesenjangan sosio-ekonomi yang terus meningkat, perampasan lahan dan ruang hidup, serta keterbatasan ruang politik bagi warga desa.
Rekam Jejak Kebijakan Jokowi
Dalam konteks pasca-otoritarian, setidaknya ada lima masalah agraria yang mendesak untuk segera ditanggapi, yaitu 1) ketimpangan struktur penguasaan tanah dan sumber daya pedesaan, 2) investasi skala besar oleh korporasi dan negara di sektor pertanian dan perkebunan yang merampas ruang hidup rakyat, 3) kesenjangan yang terus meningkat di dalam desa dan antara desa dengan kota, 4) instabilitas harga komoditas pertanian, dan 5) penyempitan ruang demokrasi bagi petani dan rakyat pedesaan.
Lima persoalan tersebut bukanlah klaim yang mengada-ada. Sudah banyak berbagai data dan kajian yang mengonfirmasi betapa nyata dan peliknya lima tantangan tersebut.
Sejumlah masalah agraria akut yang kita hadapi saat ini adalah buah dari perubahan struktural di sektor agraria selama beberapa dekade terakhir. Sebagai contoh, dalam kurun waktu 50 tahun (1963-2003) jumlah petani gurem—mereka yang memiliki tanah kurang dari setengah hektar—bertambah dari 44% ke 51%.
Kemudian, investasi skala besar oleh pihak swasta dan negara di area pertanian dan perkebunan terus meningkat. Selama kurun waktu 12 tahun (2000-2012) saja, para investor telah berhasil menguasai 9.5 juta hektar tanah di Indonesia, sebuah angka yang amat fantastis. Salah satu dampak utama dari ekspansi kapital dan kepentingan pasar ke daerah pedesaan ini adalah naiknya angka konflik agraria antara masyarakat dan kepentingan negara dan korporasi di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, konflik struktural dan kesenjangan yang bersifat terbuka bukanlah satu-satunya masalah. Kesenjangan sosio-ekonomi di desa-desa dan antara kota dan desa, yang berpotensi menimbulkan sejumlah masalah, juga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga diperparah oleh ketidakstabilan harga komoditas pertanian, mulai dari komoditas pangan seperti beras hingga komoditas ekspor seperti karet. Banyak warga desa adalah konsumen alih-alih produsen beras. Dalam perbincangan dengan keluarga tani yang saya temui ketika melakukan riset lapangan, mereka juga mengeluhkan naiknya harga ongkos produksi beras dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Masalah lain yang juga tak kalah mengkhawatirkan adalah penyempitan ruang demokrasi bagi petani dan rakyat pedesaan. Semakin tersedianya saluran partisipasi politik formal dan meningkatnya mobilisasi massa oleh para petani dan pegiat gerakan agraria pasca-Reformasi juga dibarengi oleh masifnya upaya kriminalisasi dan intimidasi kepada rakyat pedesaan dan aktivis agraria dengan sejumlah dalih dan fitnah.
Melalui perspektif inilah tawaran kebijakan dari masing-masing capres seharusnya bisa dievaluasi. Dengan kata lain, kita harus lebih kritis menguliti jargon-jargon nasionalistis dan populis dari kedua kubu capres dan menilai sejauh mana solusi yang mereka tawarkan akan menyasar lima persoalan tersebut.
Kita mulai dari kubu petahana. Jejak rekam administrasi Jokowi dalam menangani persoalan agraria dalam periode pertamanya boleh dibilang mengecewakan. Dukungan dan antusiasme yang begitu masif dari elemen-elemen masyarakat sipil selama proses pencalonan dan di masa-masa awal kepresidenannya gagal mendorong Jokowi untuk melawan kepentingan elit-elit oligarkis di sektor agraria dan perkebunan, serta mempromosikan kebijakan-kebijakan agraria yang lebih progresif.
Dalam banyak hal, kebijakan agraria Jokowi sedikit banyak hanya meneruskan kebijakan agraria Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlampau fokus kepada upaya sertifikasi legal atas tanah-tanah rakyat (untuk kebijakan sertifikasi tanah di masa kepresidenan SBY, lihat misalnya disertasi ini). Dalam lima tahun kepresidenannya, Jokowi menggunakan tiga instrumen kebijakan untuk mengatasi persoalan agraria, yaitu sertifikasi tanah, perhutanan sosial, dan dana desa.
Repotnya, ada sejumlah masalah dengan ketiga instrumen kebijakan tersebut. Pertama, sertifikasi tanah memang memberi kepastian hukum tentang kepemilikan tanah bagi banyak rumah tangga tani, tetapi sertifikasi tanah juga berpontensi untuk membuka jalan bagi komodifikasi tanah—proses transaksi jual-beli tanah yang cenderung menguntungkan korporasi dan negara dan kemudian melemahkan posisi petani dan masyarakat pedesaan.
Kedua, skema kebijakan sertifikasi tanah dan perhutanan sosial juga tidak menyasar salah satu akar persoalan dari permasalahan agraria di Indonesia, yaitu proses perampasan lahan oleh pihak negara dan swasta dengan dalih “kepentingan umum” dan “konservasi” yang telah berlangsung sejak dekade 1970-an.
Ketiga, sebagaimana telah dibahas oleh Muhtar Habibi dalam artikelnya di Tirto baru-baru ini, dana desa yang digadang-gadang dapat mengatasi persoalan kemiskinan pedesaan nyatanya rawan dimanipulasi oleh segelintir elit desa demi kepentingan golongannya saja.
Kemudian, pemerintahan Jokowi juga tidak menunjukkan itikad dan usaha yang jelas untuk menekan laju investasi skala besar terutama di sektor-sektor ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan yang hanya menguntungkan segelintir elit serta dan menimbulkan dampak sosio-ekologis negatif yang begitu besar bagi masyarakat.
Pemerintahan Jokowi pun tidak mencegah upaya-upaya kriminalisasi dan penyempitan ruang demokrasi bagi masyarakat dan pegiat agraria yang memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi turut berkontribusi memperburuk permasalahan agraria yang ada melalui berbagai proyek pembangunan infrastrukturnya.
Prabowo-Sandi Bagian dari Masalah
Bagaimana dengan kubu Prabowo-Sandi? Kubu oposisi menggarisbawahi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia, mengkritik kebijakan infrastruktur dan agraria Jokowi, mengurangi impor pangan, dan mempromosikan ekonomi terbarukan dan aplikasi teknologi di bidang pertanian? Tetapi, apakah benar janji kubu penantang memang semanis itu?
Sejauh amatan saya, usulan-usulan dari kubu oposisi masih cenderung sloganistik.
Ada beberapa pertanyaan penting yang harus ditujukan ke kubu Prabowo-Sandi. Misalnya bagaimana memastikan bahwa proses moratorium Hak Guna Usaha (HGU)—yang sering dipakai oleh korporasi-korporasi untuk melanggengkan kontrol mereka atas tanah rakyat—dapat dijalankan, apalagi moratorium atas HGU yang diberikan kepada rekan-rekan politik dan bisnis mereka sendiri?
Kemudian, jika kubu Prabowo-Sandi ingin mengurangi impor pangan, maka instrumen kebijakan apa yang perlu diambil untuk memastikan ketersediaan pangan? Pada saat bersama, bagaimana menjaga stabilitas harga komoditas pangan bagi para produsen?
Prabowo-Sandi juga mengklaim akan mempromosikan energi terbarukan dan aplikasi teknologi di bidang pertanian. Namun, solusi yang mereka tawarkan cenderung teknis dan teknokratis, abai dengan realitas sosial dan ketimpangan relasi kuasa di pedesaan yang sangat berurat-akar.
Dalam foreign media briefing kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 yang saya hadiri baru-baru ini, tim Prabowo-Sandi mengatakan bahwa mereka akan mempromosikan sejumlah skema inovatif di kedua bidang tersebut, misalnya perkebunan aren, aplikasi teknologi terbaru di bidang pertanian, dan promosi partisipasi anak muda di sektor ekonomi pedesaan.
Tapi, saya tidak mendapat gambaran yang jelas mengenai bagaimana investasi di bidang perkebunan aren dapat dilakukan dan dikontrol secara demokratik oleh buruh pengumpul getah aren—apakah melalui organisasi rakyat seperti serikat buruh, koperasi, dan kelompok usaha? Atau lewat investasi skala besar yang justru berpotensi untuk mereproduksi ketimpangan sosial di pedesaan?
Pertanyaan lain yang juga tidak terjawab adalah bagaimana memastikan aplikasi teknologi di bidang pertanian dapat dilakukan secara bertahap sehingga tidak membuat tenaga kerja pertanian di pedesaan—ibu-ibu petani, yang peranannya rentan tergantikan oleh aplikasi teknologi baru—kehilangan mata pencarian?
Yang juga tak kalah penting, saya masih bertanya-tanya sejauh apa kubu Prabowo-Sandi akan berkomitmen kepada promosi ruang demokrasi di pedesaan dan pembatasan jenis-jenis investasi yang merampas ruang hidup rakyat desa?
Ada dua fakta yang perlu dipertimbangkan di sini. Prabowo aktif terlibat dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sebuah organisasi desa bentukan Orde Baru yang awalnya dibentuk untuk mengekang ekspresi politik warga desa. Sementara Sandiaga punya kepentingan besar dalam industri ekstraktif.
Sangat wajar apabila banyak elemen di gerakan agraria dan masyarakat sipil tetap skeptis dengan komitmen kubu oposisi terhadap demokrasi politik dan ekonomi bagi rakyat desa.
Menariknya, kedua calon presiden dan wakil presiden ini sama-sama mengabaikan satu prasyarat menuju perubahan agraria yang fundamental: bahwa keadilan agraria hanya akan tercapai melalui upaya untuk melawan ketimpangan agraria melalui redistribusi—dengan kata lain, reforma agraria dalam artian yang sebenarnya—yang didukung oleh upaya advokasi dan mobilisasi politik yang mandiri dan kuat oleh rakyat desa sendiri.
Bagaimana dengan respon dari masyarakat sipil, terutama menanggapi dinamika politik agraria selama lima tahun terakhir? Sejauh penelitian doktoral saya berlangsung, saya menemukan organisasi-organisasi tani dan pegiat gerakan sosial di bidang agraria cenderung terfragmentasi. Akibatnya, kita tidak punya satu posisi alternatif bersama yang dapat digunakan untuk melawan diskursus dominan dari negara dan pasar.
Berbagai eksperimen politik yang dilakukan oleh beberapa organisasi dan individu pegiat agraria, misalnya memasuki institusi negara sebagai birokrat, berpartisipasi dalam forum yang cenderung didominasi diskursus neoliberal dan pro-pasar seperti Global Land Forum (GLF), dan keikutsertaan dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal belum membuahkan hasil yang signifikan. Sejumlah eksperimen tersebut bahkan menunjukkan kenaifan dan sampai tingkat tertentu justru memperlihatkan oportunisme politik dari gerakan agraria itu sendiri.
Inilah catatan yang perlu diperhatikan para capres dan publik Indonesia menjelang debat kedua. Keadilan agraria dan kesejahteraan bagi rakyat desa hanya akan bisa dicapai melalui gerakan agraria yang demokratik, solid, dan militan—alih-alih sekadar mengekor dan menitipkan agenda ke tangan elite politik.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id