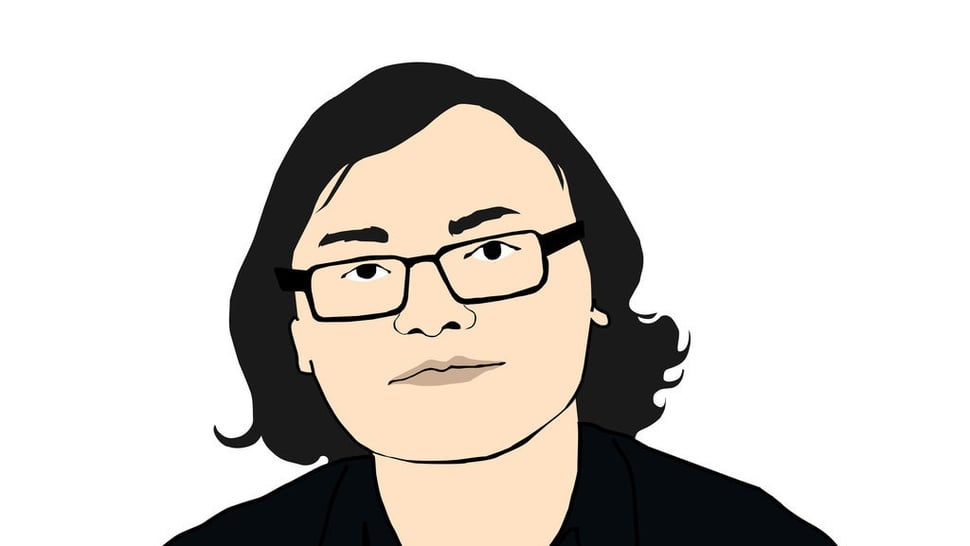tirto.id - Ada ironi pahit di pedesaan belakangan ini.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dengan bangga mengumumkan pencapaian Dana Desa (DD) dalam empat tahun terakhir, terutama ekspansi pembangunan infrastruktur di pedesaan.
Di sisi lain, BPS mengabarkan meningkatnya angka pengangguran terbuka di pedesaan.
Kematian Tuti Tursilawati, seorang buruh migran dari keluarga miskin di pedesaan Majalengka yang dihukum pancung di Arab Saudi, mestinya jadi tamparan keras untuk DD. Meski Tuti telah meninggalkan desanya jauh sebelum DD, tapi masih banyak buruh migran yang dilaporkan keluar dari desa bahkan setelah disalurkannya DD. Mereka sama rentannya dengan Tuti.
Kita lantas bertanya apakah DD benar-benar memiliki dampak bagi pekerja miskin di pedesaan. Menurut pemerintah, DD dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan di desa melalui pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama, meski secara retorik tidak mengabaikan aspek ‘pemberdayaan’ dan inovasi sosial-ekonomi lainnya.
Program ini memperlakukan desa sebagai unit intervensi dengan beberapa asumsi yang bermasalah. Pertama, DD mengasumsikan bahwa desa terdiri dari para penduduk yang hidup secara harmonis dalam tradisi ‘gotong royong’ untuk kebaikan bersama, sehingga bantuan tunai kepada mereka akan memakmurkan desa secara keseluruhan. Tentu saja, asumsi ini bersandar pada asumsi lainnya, yakni desa adalah entitas sosial-ekonomi yang relatif homogen.
Tetapi bagi mereka yang cukup akrab dengan studi agrari kritis pedesaan akan sulit untuk tidak menemukan bahwa sebagian kecil elit di desa mengakumulasi kekuasaan ekonomi, sosial dan politik untuk mendominasi ekonomi pedesaan (baik melalui penguasaan tanah maupun bisnis di luar pertanian) dan menguasai jabatan politik. Sebaliknya, barisan pekerja tak bertanah mesti menggarap lahan tetangganya yang lebih makmur, entah di sawahnya atau di tempat lain.
Pendeknya, yang dominan terjadi di desa adalah pengambil-alihan tenaga oleh majikan terhadap pekerjanya, alih-alih praktik ‘gotong royong’ sebagaimana ‘mitos pedesaan’ (White, 2017) yang diyakini pemerintah dan sebagian LSM.
Tak heran jika ketimpangan di pedesaan masih tinggi seperti yang dilaporkan BPS—belum lagi tingkat kemiskinannya. Lebarnya jurang ekonomi dan relasi kuasa yang berlaku di pedesaan, klaim bahwa DD akan menguntungkan semua penduduk desa tentu amat meragukan.
Kita bisa mulai dari kasus korupsi. Selama empat tahun terakhir, lebih dari 900 pejabat desa ditangkap karena tersangkut korupsi DD. Aktivis anti-korupsi dan pegiat LSM sering menyalahkan kelemahan implementasi DD yang membuka peluang bagi korupsi. Mereka sering merekomendasikan perbaikan susunan teknis kelembagaan DD untuk meminimalisir “bahaya moral” (“moral hazard”).
Meski diperlukan hingga tahap tertentu, langkah semacam itu cenderung mengabaikan fakta bahwa setiap susunan kelembagaan masyarakat (termasuk desa) selalu dikondisikan oleh relasi sosial, khususnya relasi kuasa dalam masyarakat. Pertanyaannya, bisakah kita benar-benar dapat berharap pekerja miskin pedesaan akan mampu secara efektif mengontrol pejabat pemerintahan desa dari penyelewengan DD? Masalahnya, pekerja-pekerja ini terikat dalam kontrak penyakapan, terjebak dalam ketergantungan pekerjaan, dan terjerat hutang pada pejabat pemerintahan desa merangkap tuan tanah.
Pertanyaan ini membawa kita pada masalah DD yang lebih serius.
DD memang menciptakan pekerjaan tambahan di sela musim tanam pertanian dan memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja miskin pedesaan—tapi sampai kapan ini akan berlangsung? DD punya masalah utama: tidak menyentuh akar persoalan kesempatan pekerjaan di pedesaan; ketimpangan penguasaan sumber penghidupan penting di pedesaan seperti tanah juga tak disorotii. Padahal, kondisi inilah yang telah membuat banyak orang tak bertanah dan mesti menerima pekerjaan apapun yang tersedia.
Merujuk data BPS, meski upah riil buruh pertanian telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, nilainya masih jauh di bawah upah buruh manufaktur di perkotaan. Tak sedikit pula dari buruh tani ini yang bekerja secara informal, dengan kondisi kerja, upah, dan jaminan sosial yang dilindungi negara. Kondisinya kian memburuk dengan meningkatnya pengangguran terbuka pedesaan seperti yang dilaporkan BPS.
Tak heran, pekerjaan sebagai buruh migran seperti yang dijalani Tuti tetap populer bagi pekerja miskin pedesaan yang kian frustasi dengan ketersediaan dan kondisi kerja di lingkungannya.
Pendekatan teknis DD takkan mampu mengobati rasa frustasi ini. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa DD hanya memuluskan akumulasi kekayaan pemangku kekuasaan di desa (petani kaya penguasa tanah-pejabat pemerintahan desa), daripada memberdayakan kelompok termiskin seperti buruh tani.
Ketimbang sekedar menggelontorkan bantuan tunai, upaya-upaya untuk menggerakkan perubahan sosial di pedesaan perlu menyasar ketimpangan relasi kuasa di pedesaan—sesuatu yang berpangkal pada ketimpangan penguasaan sumber-sumber material kehidupan yang penting di desa. Langkah ini bisa dimulai dengan memberikan perhatian yang besar pada pekerja. Pekerja pertanian dan pekerja lain di pedesaan dapat ditranformasi menjadi petani yang layak melalui Reforma Agraria.
Jika pilihan itu tidak mudah mengingat tidak terorganisirnya pekerja dan kian kuatnya elite (salah satunya berkat DD), kita barangkali perlu secara langsung menaruh perhatian pada perlindungan para pekerja. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa mereka harus bekerja dengan pengaturan informal tanpa perlindungan negara. Mereka punya hak yang sama dengan rekan-rekannya yang bekerja di pabrik, kantor, atau tempat-tempat lainnya.
Perbaikan kondisi kerja pertanian dan non-pertanian serta kenaikan upah riil bagi pekerja di pedesaan adalah intervensi penting untuk mengimbangi tumbuh pesatnya kekuasaan elite desa.
Dalam kedua opsi, perang terhadap ketimpangan adalah kunci untuk memperkuat kontrol warga terhadap pemangku kebijakan agar lebih akuntabel, dan mempersempit celah korupsi.
Akhirnya, penciptaan pekerjaan layak di desa akan sangat krusial karena dapat mengurangi banyaknya pekerja manual kita yang terbang menjadi buruh migran hanya untuk dipancung setelah diperkosa dan disiksa.
Tanpa mengarusutamakan isu ketimpangan sosial dan politik serta kondisi kerja, ironi antara klaim pemerintah dengan realitas rakyat pekerja miskin pedesaan akan terus berlanjut dalam sejarah republik.
Yang terjadi hari ini adalah tragedi. Yang berikutnya, jika terulang lagi, adalah lelucon.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.