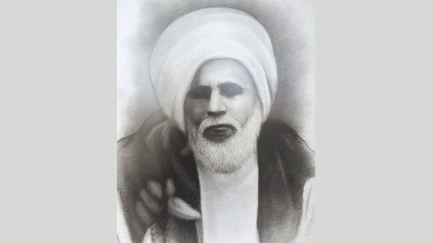tirto.id - Jawa dan Islam memiliki riwayat pertalian panjang yang sukar dipisahkan. Bagai tinta dengan kertas, sinkretisme dua corak kebudayaan ini kerap berlangsung simultan. Pun tak sedikit membuahkan akulturasi budaya yang saling bertautan dan beriringan.
Salah satu tonggak penting simbol sinkretisme Jawa-Islam tercatat pada 1633 Masehi, ketika Sultan Agung Hanyakrakusuma sang penguasa Mataram Islam melakukan revolusi almanak. Dia menggabungkan kalender Saka dengan penanggalan Hijriah hingga lahir sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai Kalender Jawa-Islam.
Sebagai catatan, tahun 1633 Masehi bertepatan dengan 1554 Saka dan 1043 Hijriah. Sementara tahun baru Islam yang diperingati saban 1 Muharam oleh masyarakat Jawa disebut sebagai 1 Suro, penanda yang sama untuk awal tahun.
Dalam buku Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa (2010) yang ditulis M. Sholikhin, “Suro” berasal dari bahasa Arab asyura yang artinya sepuluh. Pengertian ini merujuk pada tanggal 10 Muharam yang kemungkinan sebagai tanggal penting yang memengaruhi pendefinisian bulan Suro. Pelafalan bahasa Arab asyura berasimilasi dalam lidah orang Jawa dan lantas menjadi suro.
Sholikhin menulis, “Pada tanggal 10 Muharam atau Asuro, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang sangat mengharukan umat Islam. Di mana terjadi peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein secara sangat tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazin bin Mu’awiyah,” (hlm. 30).
Meski begitu, peristiwa itu tak cukup kuat menjadi dasar utama penanggalan Jawa memilih hari ke-10 Muharam untuk memadankan bulan pertama penanda awal Kalender Jawa-Islam. Seakan mengesampingkan akar etimologi bahasa, peringatan 1 Muharam pada hari ini telah dianggap sama dengan 1 Suro. Sebaliknya, justru karena insiden pembantaian keturunan Nabi, bulan ini dianggap sakral, baik dalam tradisi Islam maupun Jawa.
Menurut kepercayaan kejawen, bulan Muharam adalah bulan kedatangan Aji Saka di Tanah Jawa. Bak mesias, Aji Saka membebaskan Jawa dari cengkeraman makhluk gaib dan raksasa (banul jan) yang memporak-porandakan dunia manusia.
Fenomena ini boleh jadi inspirasi Sultan Agung atas peristiwa bencana “banjir besar” yang konon menenggelamkan seluruh daratan di dunia. Diikuti munculnya bahtera Nabi Nuh sebagai moda penyelamat para pengikut yang bertauhid kepada Allah SWT. Tanggal 10 Muharram menandai momen ketika seluruh penumpang bahtera Nabi Nuh turun dari kapal dan merintis ulang kehidupan di dunia yang baru.
Prapto Yuwono, pengajar Sastra Jawa di UI menjelaskan, sebagai lanjutan atas sinkretisme budaya itu, Sultan Agung meminta rakyatnya untuk turut bersama “merayakan” Tahun Baru Islam saban Malam 1 Suro. Rakyat diajak menepi, prihatin, dan mawas diri dengan menyambut tahun baru tanpa pesta yang bergelimang kemewahan.
Selain itu, sebagai wujud syukur dan penghormatan terhadap leluhur, Malam 1 Suro adalah momen ketika umat berbondong-bondong evaluasi, benda pusaka dicuci, tempat bersejarah disucikan lewat ritual tertentu, serupa kehidupan yang tengah terlahir kembali.
Kebudayaan Jawa punya beragam ritual unik untuk menyambut Tahun Baru Islam. Salah satunya tapa bisu, tradisi yang masih lestari di kalangan Kesunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta, poros kebudayaan Jawa hari ini.

Tapa Bisu di Yogyakarta dan Surakarta
Siapa pun boleh mengikuti tapa bisu, tanpa mengenal pangkat dan kasta, faktor ekonomi, atau turunan biologis. Ritual ini hanya menuntut syarat-syarat tertentu yang disepakati secara kultural, bukan paksaan.
Herman Sinung Janutama dalam “Mubeng Beteng Karatan Ngayogyakarta Hadiningrat” dalam Goresan Peradaban #1: Kumpulan Ragam warisan Budaya Takbenda Daerah Istimewa Yogyakarta (2018: 169-173) mengatakan, tradisi tapa bisu di Yogyakarta terinspirasi oleh perjalanan Nabi Muhammad saat hijrah dari Makkah ke Madinah.
Walhasil, tapa bisu hanya menuntut agar pelakunya menjalani ritual dengan laku prihatin dan tirakat, berjalan tanpa alas bak di atas lautan pasir yang panas. Ritual perjalanan ini disebut dengan istilah lampah ratri oleh Keraton Pakualaman Yogyakarta, yang berarti “berjalan di malam hari”. Pemilihan waktu malam hari dimaksudkan agar prosesi tapa bisu lekat dengan suasana yang tenang, lengang, dalam keheningan yang bersih nan jernih.
Rute perhelatan tapa bisu pada masing-masing wilayah keraton tentu berbeda-beda. Tahun ini, tapa bisu di Solo menjadi salah satu rangkaian acara bertajuk “Kirab Pusaka Dalem 1 Suro” yang digelar pada Kamis (26/6/2025) mulai pukul 19.00 WIB di Pura Mangkunegaran, Solo. Rutenya melewati Pura Mangkunegaran-Koridor Ngarsopuro-Jalan Slamet Riyadi-Jalan Kartini-Jalan R. M. Said-Jalan Teuku Umar-kembali ke Pura Mangkunegaran.
Sedangkan tradisi tapa bisu di Yogyakarta dikenal pula dengan istilah lain, yakni mubeng beteng. Hal tersebut berkenaan dengan rute perjalanan yang ditempuh oleh para pelaku tapa bisu. Tahun ini, mubeng beteng dihelat pada Kamis (26/6/2025) mulai pukul 23.00 WIB. Keberangkatan dimulai dari Bangsal Ponconiti, Kompleks Kamandungan Lor (Keben), Keraton Yogyakarta. Dari sana, pelaku dari kalangan mana pun boleh ikut, beserta rombongan abdi dalem Keraton Yogyakarta, mereka mengitari kompleks Benteng Baluwarti Keraton Yogyakarta, melawan arah jarum jam.
Perbedaan mendasar antara Surakarta dan Yogyakarta dalam perhelatan tapa bisu adalah peserta rombongan yang menghelat ritual. Di Surakarta, tradisi ini menjadi bagian dari hajat kesunanan. Oleh karenanya, pangombyong yang mengawal tapa bisu selalu dibersamai keluarga kesunanan. Bahkan tak jarang Sri Sultan Pakubuwana turut serta.

Sementara di Yogyakarta, menurut pengakuan Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projosuwasono, salah satu abdi dalem Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwana tak pernah terlihat mengikuti acara tapa bisu atau mubeng beteng.
“Mubeng betengtanggap warsa setiap tahun di Yogyakarta itu bukan hajat dalem. Tetapi hajatnya kawula dalem,” ungkapnya. Jadi, para pangombyong garda terdepan yang turut serta dalam tapa bisu mubeng beteng mayoritas berasal dari kalangan abdi dalem, bukan keluarga kerajaan.
Awalnya, mubeng beteng merupakan acara resmi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang langsung dititahkan oleh sultan kepada abdi dalem. Namun pada 2017, setelah pelepasan dan restu dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, putri Sri Sultan Hamengkubuwana X, mubeng beteng hanya dilaksanakan oleh komunitas abdi dalem saja dengan disertai masyarakat umum.
Selain itu dalam tata cara busana, abdi dalem Kesunanan Surakarta (peserta resmi) mengenakan beskap hitam, blangkon, jarik sogan (bukan motif parang/lereng), dan memanggul keris untuk pria. Sedangkan perempuan diwajibkan mengenakan kebaya hitam dan sanggul.
Sedangkan di Keraton Yogyakarta, peserta resmi wajib mengenakan surjan lurik berwarna gelap, dengan jarik dan blangkon untuk pria. Sementara untuk perempuan, mengenakan kain panjang dan kemben, serta dilarang memakai aksesoris kalung atau gelang.
Di samping acara tapa bisu, Malam Satu Suro juga diisi dengan rangkaian acara lain yang tak kalah ramai dan menarik. Di Yogyakarta, misalnya, terdapat kirab dan ritual memandikan kebo bule yang dihelat pada Jumat (27/6/2025) di Jogja Exotarium.
Sementara di Kesunanan Surakarta, kirab kebo bule mendapat keistimewaan sebagai cucuk lampah (pembuka jalan) sebelum ritual tapa bisu dihelat. Kebo bule yang dipilih harus berjumlah gasal dan merupakan keturunan Kebo Kyai Slamet, yang menjadi hewan ternak suci semenjak pemerintahan Pakubuwana II.
Ada pula ritual jamasan pusaka, yakni menyucikan benda-benda pusaka keraton. Misalnya senjata (tosan aji) dan gamelan. Biasanya, jamasan pusaka di Keraton Yogyakarta dihelat pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, dengan pusaka perdana yang disucikan adalah tombak Kiai Ageng Plered. Juga ada tradisi bubur suran, yakni bubur yang biasanya disantap setelah prosesi mubeng beteng. Bubur ini terdiri dari tujuh jenis kacang, yang melambangkan tujuh hari dalam sepekan, sebagai simbol syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Filosofi Tapa Bisu Malam Satu Suro
Ritual tapa bisu saban Malam Satu Suro bukan hanya tentang derap langkah kaki yang Berderet pelan tanpa terburu-buru. Bukan macam deru bising knalpot yang merisak suasana, melainkan khidmat sunyi penuh sahaja. Sebagaimana makna harfiahnya, tapa bisu mengajarkan kepada manusia kesederhanaan ritus tanpa suara, tidak berisik—baik secara lahiriah maupun batiniah.
Tapa bisu merupakan munajat ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keheningan, laku tapa mengharuskan manusia benar-benar menundukkan diri. Menanggalkan segala hiruk duniawi, meratap takzim pada refleksi dan kesejatian diri. Berjalan telanjang tanpa alas sebab kesudian, bukan paksaan. Tak hanya lisan yang membisu, tapi juga membungkam ego dan menyiah hawa nafsu.
Di antara gema langkah, terselip doa dan harapan yang tak terucap lewat suara, melainkan dengan rasa. Ini adalah bentuk komunikasi lain yang melampaui kata-kata. Suara hati yang menembus langit dan diperdengarkan kepada Yang Maha Kuasa.
Bentuk tertinggi atas kontemplasi, tatkala manusia dihadapkan pada haribaan Tuhan. Mengurai keluh kesah selama setahun ke belakang, guna menyongsong harapan untuk tahun-tahun berikutnya. Orang-orang mendatangkan doa, membeberkan penyesalan dan harapan sekaligus, memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Uniknya, tapa bisu yang dilakoni ratusan bahkan ribuan hampir pasang kaki semakin menjadikan ritual ini begitu personal. Langkah kaki yang berirama khidmat tanpa saling sapa, tanpa basa-basi, dan hampir-hampir tanpa gawai dan potret kamera. Segalanya meluber dalam kesunyian yang nyaris mistis.
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id