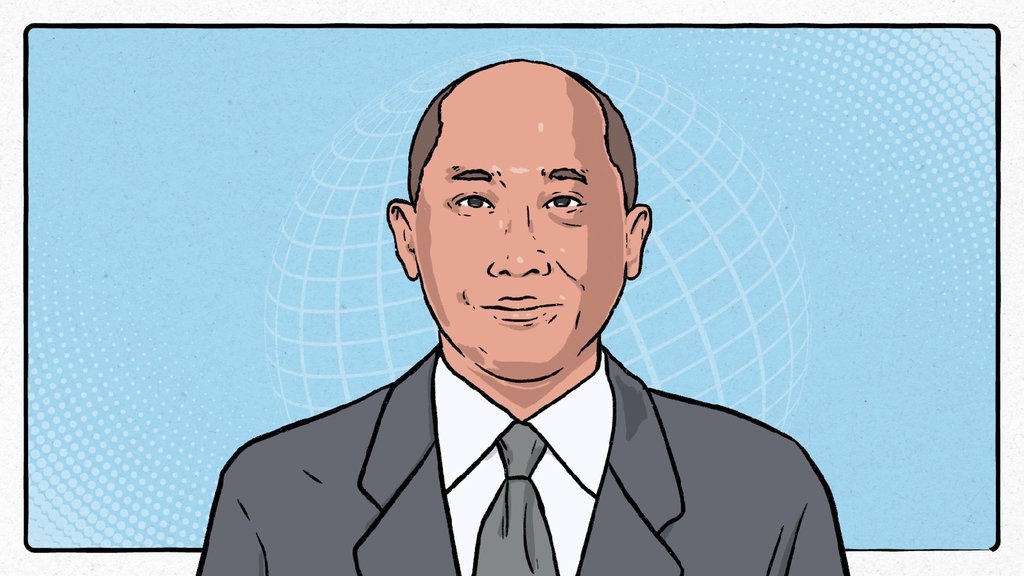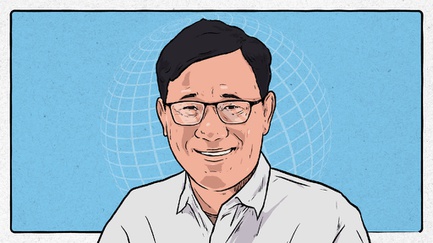tirto.id - Langkah pemerintah merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN), dengan mengubah status energi nuklir bukan lagi sebagai opsi terakhir dalam bauran energi, menandai babak baru dalam strategi transisi energi Indonesia.
Dalam waktu kurang dari satu dekade, reaktor nuklir dengan kapasitas 250 Megawatt (MW) ditargetkan menyuplai setrum ke dalam sistem kelistrikan nasional. Ini bukan sekedar rencana jangka menengah, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia mulai menatap energi nuklir sebagai bagian penting dari solusi dekarbonisasi.
Di balik pergeseran kebijakan tersebut, Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memegang peran kunci. Lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ini tak hanya bertugas mengembangkan teknologi ketenaganukliran, tapi juga menjembatani kolaborasi internasional, memberi supervisi teknis, dan memastikan kesiapan ekosistem nuklir di dalam negeri.
Untuk menggali lebih jauh kesiapan dan tantangan yang dihadapi Indonesia, Tirto mewawancarai Kepala ORTN BRIN, Syaiful Bakhri, di kantornya yang berlokasi di Kompleks Sains dan Teknologi BJ Habibie, Serpong, Tangerang Selatan, pada Jumat (2/5/2025). Selama lebih dari satu jam, pakar yang juga merupakan anggota ahli Pusat Kolaborasi Pemeriksaan Non Destruktif IAEA itu menjelaskan arah kebijakan, kapasitas teknologi, hingga peta kolaborasi global yang tengah dijajaki. Berikut petikan wawancaranya:
Dalam rapat di Komisi XII akhir April lalu, Sekjen Kementerian ESDM menyebut revisi PP Kebijakan Energi Nasional telah disetujui, dan nuklir bukan lagi opsi terakhir dalam pengembangan energi baru terbarukan. Apa peran ORTN dalam meloloskan regulasi tersebut?
Sekarang kalau bicara tentang aturan, sebenarnya yang porsinya yang paling besar sih ya di DEN (Dewan Energi Nasional) dan di Kementerian ESDM. Kami di BRIN ini, kita punya satu kedeputian khusus, tapi bukan di tempat saya (ORTN). Di Deputi Kebijakan, Riset dan Inovasi sama Deputi Kebijakan Pembangunan. Ya mereka, dua kedeputian itu, khusus untuk menyiapkan kebijakan yang terkait dengan policy pembangunan maupun policy yang berkait dengan riset inovasi. Baik yang disiapkan oleh BRIN ataupun yang disiapkan oleh beberapa stakeholder lain.
Apa langkah selanjutnya yang disiapkan ORTN dan/atau BRIN terhadap kebijakan baru ini?
Kami mendukung kebijakan ini, terus terang. Kemudian, dari sisi Deputi Kebijakan Publik di BRIN, mereka sedang menyiapkan peta jalan ketenaganukliran yang harapannya nanti dapat mendukung peta jalan dalam KEN. Di RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) sudah ada peta jalannya, sudah tercantum kapan nuklir akan mulai masuk, berapa gigawatt yang direncanakan, dan berapa kapasitas pada akhir 2060. Semua itu sudah ada di RUKN.
Posisi kami adalah mendukung RUKN jika memang ingin dijalankan. Penyiapan roadmap tersebut mencakup rekomendasi teknologi-teknologi yang kira-kira tepat untuk dibangun di Indonesia. Kemudian juga menyiapkan pengembangan sumber daya manusia di BRIN, untuk hal ini ditangani oleh kedeputian SDM. Sementara dari ORTN, kami fokus pada penyiapan teknologi yang tepat, proven, aman, dan selamat, sehingga memenuhi tiga syarat utama: safety, security, dan safeguard (3S).
Kami menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknologi PLTN yang memenuhi kriteria 3S tadi. Teknologinya juga proven, artinya memang sudah terbukti, telah digunakan, dan dibangun sebagai demo plant di negara lain.Dari sisi SDM, kami juga menyiapkan sumber daya manusia. Misalnya, kami memiliki Politeknik Nuklir. Kami juga memiliki para periset di unit saya, yang nantinya bisa mendukung semua pemangku kepentingan baik itu PLN, Kementerian ESDM, DEN, maupun IPP (independent power producer).
Siapa pun yang akan membangun PLTN, kami siap memberikan dukungan SDM dan mendampingi mereka dalam berbagai aspek, mulai dari teknologi reaktor, bahan bakar, pengelolaan limbah, aspek teknoekonomi, hingga evaluasi tapak. Pokoknya, kami siapkan dalam bentuk paket komplet.
Kalau soal teknologi, yang tadi Anda sebut proven, sebenarnya yang seperti apa dan negara mana yang sudah menguasainya?Reaktor itu, secara umum, dibagi menjadi tiga jenis: micro, small modular, dan large reactor. Micro reactor adalah reaktor kecil dengan kapasitas hingga 10 megawatt (MW). Kemudian, reaktor dengan kapasitas di atas 10 MW hingga 300 MW disebut small modular reactor. Sementara yang kapasitasnya di atas itu disebut large reactor. Itu dari sisi skala, ya. Dari sisi generasi, reaktor dibagi menjadi generasi I, II, III, III+, dan IV.
Yang saya lihat, reaktor yang paling banyak dibangun di dunia saat ini adalah generasi II, III, dan III+. Sementara generasi IV masih sangat jarang. Sekarang Generasi I, generasi pertama itu, juga sudah jarang.
Yang mana yang mau dibangun di Indonesia?
Selain proven, yang kedua yang supply chain-nya kuat. Iya dong? Kita membangun, enggak mau, kan, kalau ternyata maintenance-nya susah, repot. Kemudian pemasoknya. Jangan sampai rantai pasoknya ternyata enggak kuat begitu, ya. Supply chain-nya ini termasuk juga dari konstruksinya (engineering, procurement and construction/EPC), maupun bahan bakarnya. Jangan sampai ada reaktornya tapi enggak ada bahan bakarnya. Kalau bisa memang yang sudah dapat sertifikasi design di negara lain, dan antara generasi III, atau III+ yang akan dibangun. Kemudian, dari sisi regulasinya sudah approved. Artinya, certificate design-nya sudah disetujui di negara asalnya.
Di dalam KEN yang baru, disebutkan bahwa sampai 2030 nanti paling tidak kita sudah operasikan PLTN 250 MW. Kira-kira dalam jangka waktu lima tahun dari sekarang, apakah target tersebut realistis?
Kalau KEN, kami belum bisa bicara. Belum diketuk aturannya. Tapi di RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), antara 2030 sampai dengan 2034 itu first nuclear power plant. Antara itu ya.
Kemudian yang di 2035 sampai dengan 2039 itu ekspansi. Lalu 2040 sampai dengan 2045 itu kemandirian. Di RUKN, itu pertama commercial operation date (COD) 2032. Tapi, ini kan baru skenario. Jadi ke depan masih akan sangat mungkin untuk dinamis, berubah.
Harusnya, jika sudah di RUKN nanti akan dimasukkan juga di RUPTL-nya, kan Di RUPTL kapasitasnya ya antara 300-350 MW. Tapi, memang, itu bukan patokan. Kalau misalkan pemerintah mau langsung (bikin PLTN) yang besar juga enggak masalah.
Normalnya, berapa lama pembangunan PLTN dari tahap persiapan sampai commissioning?
Coba kita lihat pengalaman beberapa negara dalam membangun PLTN berkapasitas besar. Asumsinya, untuk small modular reactor, waktunya bisa lebih cepat. Fase pembangunan reaktor besar itu ada yang memakan waktu 10 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun. Cina bahkan bisa lebih cepat dari itu, sekitar 5 tahun. Kenapa mereka bisa lebih cepat? Karena mereka sudah terbiasa membangun. Yang sudah mereka bangun sekarang saja ada sekitar 30 PLTN, dalam satu negara. Jadi, pembangunan mereka memang cepat. Kalau small modular reactor, mungkin bisa 3 atau 4 tahun. Bisa jadi.
Tapi, saya tidak bisa memastikan selesai dalam 3 atau 4 tahun, karena banyak faktor yang memengaruhi. Termasuk kesiapan vendornya. Kalau vendornya siap, supply chain-nya juga siap. Karena yang paling lama itu biasanya menyiapkan komponen utama seperti pressure vessel. Ini disebut long lead item. Membuat pressure vessel yang besar itu sendiri bisa memakan waktu hingga 4 tahun untuk proses forging-nya.
Berarti, jika targetnya kapasitas PLTN 250 MW sampai 2030, dan estimasi pembangunan SMR sekitar 3-4 tahun, seharusnya tahun depan kita sudah mulai konstruksi PLTN pertama?
Ya, tantangannya memang di situ. Harus lihat dulu: SMR mana yang mau dibangun? Itu kan tantangannya, kan? SMR mana, sih, sebenarnya yang sudah siap untuk dibangun? Enggak banyak, lho.
Kalau melihat data yang Anda paparkan, sepertinya negara-negara yang SMR-nya sudah proven itu mereka yang sudah datang dan menawarkan kerja sama ke Indonesia. Apa kemungkinan negara-negara itu yang akan kerja sama dengan kita untuk teknologi SMR?
Enggak juga. Saya enggak berani mengatakan mereka datang, kemudian kita deal gitu. Enggak banyak kok, SMR saat ini. Yang sudah bangun, paling tidak, satu, Cina [Proyek ACP100 di Hainan]. Kemudian Rusia sedang bangun. Enam sudah operasi dia sebagai ice breaker.
CNNC (China National Nuclear Corporation) sudah lebih dulu?
Iya, mereka sudah lebih duluan. Jadi, kalau bicara reaktor SMR, sebenarnya nggak banyak. Kalau mau reaktor yang besar, banyak yang sudah dibangun, tinggal pilih saja. Enggak ribet, kok, kalau mau yang besar. Besok pun, dari Rusia, kalau sudah diinstruksikan oleh Presiden, kita bisa memilih itu: mana reaktornya yang mau dibangun.
Yang besar, lho, ya. Kemudian dibuat semacam big invitation, gitu kan, buat para vendor ini supaya bisa masuk ke kita. Atau semacam beauty contest lah, ya, untuk menimbang nimbang antara satu dengan yang lain, mana yang paling cocok. Ini semua sudah pernah dibangun.
Berarti, kalau Presiden minta dibangun untuk percontohan dulu, yang paling mungkin buat kita teknologinya Cina sama Rusia?
Ya itu yang menyimpulkan Anda. Kalau yang cepat, memang itu [Rusia dan Cina], ya. Tapi, kan, pembangunan butuh waktu. Butuh tahapan. Dan masing-masing tahapan tergantung dengan berbagai hal, mulai dari kesiapan tapaknya dan lain-lain. Jadi, ada 19 infrastruktur yang harus disiapkan. Semakin lengkap ini, satu sampai dengan 19 ini, semakin cepat kita juga masuk ke dalam tahapan pembangunan.
Kalau lokasi, mana yang paling potensial di Indonesia untuk dibanung PLTN dalam waktu dekat?
Kita sudah punya tapak yang evaluasinya cukup lengkap. Yang evaluasinya sudah selesai, evaluasi tahap awal, ada di Bangka Belitung, kemudian di (Semenanjung) Muria. Itu dua tapak. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana menyusun financing. Untuk membangun itu, model bisnisnya seperti apa? Kemudian baru memilih teknologi dan vendornya juga seperti apa. Siap enggak kita untuk mengundang para vendor untuk bidding, mengajukan penawaran kepada kita untuk membangun PLTN pertama?
Tapak yang sudah siapu itu cocok untuk buat PLTN kapasitas micro, SMR, atau large?
Semuanya bisa. Yang di Muria itu memang paling memungkinkan untuk large reactor. Kenapa? Ya, karena grid di Indonesia yang demand-nya cukup besar itu ada di Jawa dan Sumatera. Dua wilayah itu rata-rata dipasok oleh reaktor dengan daya yang cukup besar, kan?Kalau nyelipin pembangkit yang kecil di situ, seperti microreactor, enggak masuk akal. Nanti malah merusak sistem secara keseluruhan.
Jadi, kemungkinan untuk tapak Muria itu cocok untuk large reactor. Sementara Bangka Belitung bisa kombinasi antara large dan small reactor. Tapi di sana bisa menampung sampai 7 gigawatt kalau nggak salah. Jadi bisa kombinasi, large dengan small begitu nantinya.
Kenapa yang siap bukan di tempat yang elektrifikasinya rendah? Jawa, kan, sudah surplus listrik?
Nah, nuklir ini kan masuk dalam bagian peta transisi, ya. Nanti kalau misalkan ada PLTU yang masuk phase out, yang sudah perlu diakhiri masa operasinya karena skema transisi itu, ya, nuklir bisa masuk untuk menggantikan itu di Jawa dan Bali.
Jadi, skenario transisi itu harus kita pahami juga. Batu bara kan turun. Apa yang bisa masuk dan kira-kira sepadan dengan itu? Nuklir. Karena sifatnya baseload, stabil, tidak terpengaruh cuaca atau perkembangan eksternal. Jadi kalau batu bara turun, yang kemungkinan masuk adalah pembangkit baseload seperti nuklir dan geothermal.
Itu untuk Jawa. Untuk di luar itu, Kalimantan, Sulawesi, microreactor atau small modular reactor masih memungkinkan?
Ya, memungkinkan. Terutama di beberapa lokasi yang masih pakai diesel. Itu ada sekitar 200 lokasi, totalnya 255 MW. Ada di mana? Contohnya di NTB, 20 MW. Kecil, kan? Ya, bisa dimasuki, diganti nanti dengan microreactor. Dua reaktor, misalnya. Kemudian, Papua hanya 0,2 MW. Oh, bisa nanti diganti dengan microreactor yang 1 MW, misalnya. Maluku, 40 MW, bisa diganti. Ini kita melihat yang masih pakai diesel-diesel saja. Ke depan, kalau diesel tadi mau diganti dengan nuklir. Karena kita tidak mau bergantung pada bahan bakar fosil, ya, potensinya seperti itu.
ORTN dan BRIN, dalam publikasi dan pemberitaan kelihatannya lebih banyak bekerja sama dengan Cina. Misalnya dengan CNNC, atau Tsinghua University. Dengan yang lain, seperti Thorcon, misalnya, apakah pernah?
Kita kerja sama dengan Tsinghua karena sedang mengembangkan PLTN generasi ke IV, namanya high temperature gas-cooled reactor (HTGR). Dan teknologi HTGR ini paling banyak dikuasai oleh Cina, kemudian Jepang. Teknologi ini asalnya dari Jerman, lalu menyebar ke AS. Demo plant-nya itu yang punya Cina dan Jepang. Nah, kita belajar dari mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat.
Kenapa kita menekuni generasi ke-IV? Ya, karena masih banyak peluang untuk research and development. Logis, ya? Karena peluang R&D-nya masih terbuka luas. Generasi ke-IV ini belum 100 persen komersial, walaupun Cina sudah mulai mengomersialkannya. Nah, setelah itu, kita masuk ke sini dan harapannya, dengan belajar bersama mereka, kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Kita bisa lebih melihat di mana letak gap-nya, lalu setelah itu kita bisa mengembangkan teknologi kita sendiri. Ya, tentunya jadi lebih sejajar dengan mereka.
Yang sudah kami bangun, namanya Peluit, pembangkit listrik uap untuk industri, yang kapasitasnya 30 Megawatt. Itu hasil kerja sama kita dengan mereka. Teknologi lain juga kita pelajari. Sejauh ini, kita sudah siap dengan PHWR (pressurized heavy water reactor). Itu teknologi yang sudah kita pelajari sejak zaman mbah-mbah kita. Karena kita punya fasilitas PHWR dengan pendingin air berat (pressurized heavy water reactor).
Anda melihat pengalaman di negara lain yang sudah bekerja sama dengan Cina. Misalkan di Pakistan, di Karachi. Itu bagaimana progresnya?
Progresnya bagus sejauh ini.
Selain teknologi, soal pembiayaannya bagaimana? Apakah ada yang bisa kita tiru atau pelajari dari mereka?
Ya, cost listriknya rata-rata itu 4-8 cent per KWH. Ini bisa beragam, tergantung dengan plant-nya, tergantung site-nya di mana, grid-nya seperti apa. Banyak faktor lah yang pengaruh itu. Depending on various factor. Project financing-nya kayak apa, ngutangnya itu kayak apa. Utangan itu kan bisa bikin mahal juga kan. Termasuk power purchase agreement-nya kayak apa, scheme-nya dengan mereka.
Kemudian (konstruksinya) durasinya seperti apa? Semakin lambat, semakin lama, ya pasti juga bengkak kan costnya. Ya pasti nanti akan berdampak pada capex-nya juga.
Di luar persoalan teknologi, bagaimana ORTN mengantisipasi masalah limbah nuklir?
Mengenai limbah, BATAN dan sekarang ORTN BRIN itu sudah berpengalaman mengelola limbah dari dulu. Kita punya fasilitas pengelola limbah, boleh nanti dikunjungi. Jadi dengan basis pengalaman itu, ya kita yakin kita bisa mengelola limbah. Dan pengelolaan limbah nuklir itu sebenarnya cukup sederhana dibanding dengan pengelolaan sampah. Sederhana, kan, yang diproduksi hanya limbah dari PLTN. Dan limbah PLTN yang perlu diwaspadai prioritasnya adalah bahan bakarnya.
Dan dari bahan bakar, yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai limbah itu enggak lebih dari 6 persenan. 94 persen itu masih bisa dipakai lagi loh bahan bakar itu.
Didaur ulang?
Iya, 6 persennya itu lah limbah. Tapi bukan limbah sebenarnya, karena masih bisa dipakai lagi. Kenapa? Ada yang namanya plutonium. Plutonium itu bisa direcycle untuk reaktor yang lain. Jadi, memang ada reaktor yang bisa menggunakan bahan bakar plutonium dan uranium, namanya MOX.Kemudian yang lain, misalnya cesium, lalu strontium. Cesium ini bisa dipakai untuk aplikasi goji, untuk aplikasi teknologi nuklir yang lain, untuk iradiasi, untuk pengukuran level. Banyak, sebenarnya.
Strontium, samarium, masih bisa dipakai juga. Di bagian 6 persen ini, sebenarnya limbahnya kecil. Limbah PLTN setelah 40 tahun hanya seukuran lapangan basket. Coba bandingkan dengan PLTU.
Terus, coba lihat limbahnya reaktor riset yang kita punya. Hanya satu kolam. Dari dulu, masih begitu. Gampang, kan, mengelola limbah? Cukup di container. Itu kalau mau dipeluk kontainernya sama orang tuh juga bisa. Hangat dia, tapi enggak ada radiasinya. Nah, limbah-limbah yang tadi itu nanti bisa dimasukkan ke dalam penyimpanan limbah lestari. Masukin ke dalam kerak bumi, 100 meter ke bawah, kemudian ditinggal. Tapi limbah-limbah yang memang umur waktunya panjang, yang long half-life, itu saja yang kita concern.
Bagaimana dengan masalah bahan bakarnya?
Jadi, bahan bakar reaktor itu uranium, dan thorium juga ada. Kita punya uranium, kita punya thorium. Uranium kita itu sekitar 89 ribu ton. Ya, itu baru potensi, tapi di daerah sekitar Kalimantan.
Nah, bahan bakar kita, yang 89 ribu ton uranium itu, enggak mesti langsung digunakan. Bisa jadi kita beli dari luar. Ngapain, gitu kan, memanfaatkan bahan bakar yang kita punya sementara di luar lebih murah, kan? Kita simpan dulu ini. Pada saat memang kita butuh, nanti ya boleh kita gunakan.
Bisa jadi, bahan bakar reaktor pertama nanti kemungkinan besar akan dibeli dari luar. Setelah jalan sekian tahun, baru kita domestikasi.
Biasanya seperti itu. Istilahnya, kalau keekonomiannya sudah cukup. Jangan sampai kita bangun pabrik bahan bakar, tapi ternyata lebih mahal dibanding kita impor. Keekonomian bahan bakar itu baru muncul setelah jumlah PLTN-nya mulai banyak—mulai 2, 3, 4, 5 PLTN. Nah, hitungannya udah masuk, tuh. Sudah. Akhirnya kita domestifikasi. Kemudian kita produksi sendiri di dalam negeri.
Kalau di Asia Tenggara, dalam pengembangan energi nuklir di mana posisi Indonesia?
Sebenarnya Filipina malah sudah lebih dulu punya PLTN, hanya saja terbengkalai. Lihat aja di Google, PLTN Bataan. Itu PLTN mereka sudah jadi, tapi nggak ada bahan bakarnya. Jadi mereka stop proyeknya. Kalau nggak ada bahan bakar nuklinnya di dalam reaktor ya nggak bisa dikatakan sebagai reaktor dong? Bisa jadi ya hanya museum itu.
Tapi, ya, Indonesia dari sisi SDM, dari sisi kesiapan teknologi ini lebih siap dibanding dengan negara negara lainnya. Karena kita juga punya reaktor yang lebih banyak daripada mereka, reaktor riset terutama ya.Kemudian pengembangan SDM kita juga sudah sejauh ini, kalau saya bilang ya konsisten. Karena kita punya Politeknik Nuklir. Dan, kita juga sejauh ini terus melakukan riset di bidang ini. Soal PLTN, sekarang berpulang lagi kepada pemerintah: kapan mau digulirkan?
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id