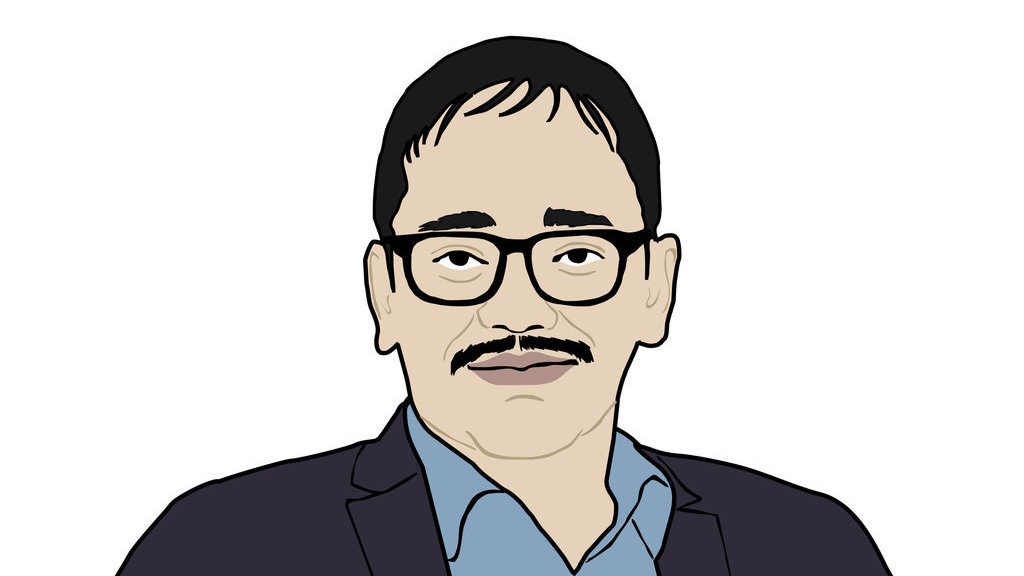tirto.id - “Mestinya dia yang (yang melarang buku) ditangkap saja”, ujar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat ditanya tentang bagaimana pendapatnya ketika Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan peredaran buku-buku sejarah untuk SMP dan SMA kurikulum 2004. Gus Dur menegaskan praktek pelarangan buku melanggar konstitusi (UUD). Pernyataan itu disampaikan pada 2007 sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan UU No.4/PNPS/1963—landasan hukum Kejaksaan Agung melarang peredaran buku—sebagai produk hukum yang inkonstitusional pada 2010.
Ketetapan MK menjadi dasar hukum bahwa pelarangan dan penyitaan buku hanya mungkin dilakukan melalui proses pengadilan dengan sejumlah prosedur yang harus dilalui sesuai KUHAP.
Kurang dari satu dekade, aparat hukum di Indonesia kembali mencoba menghidupkan praktek inkonstitusional itu. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan di hadapan wartawan pada 23 Januari kemungkinan pihaknya menghidupkan kembali fungsi clearing house dan mempersiapkan praktek razia buku dalam skala nasional.
Sikap ini mengherankan. Laporan Tirto memberikan gambaran bahwa pernyataan Jaksa Agung itu muncul menanggapi pemberitaan terkait razia buku yang dilakukan aparat TNI, POLRI dan Kejaksaan di beberapa daerah. “Mungkin perlu dilakukan razia buku yang memang mengandung PKI dan dilakukan perampasan di mana pun buku itu berada,” ujarnya.
Kerjaan Kaum Terdidik
Ada banyak pandangan terkait praktek sebuah rezim dalam melarang buku. Seorang penulis asal Venezuela, Fernando Báez, dalam Penghancuran Buku dari Masa ke Masa (2017) menyatakan bahwa “buku-buku dihancurkan bukan oleh ketidaktahuan awam atau kurangnya pendidikan, melainkan justru oleh kaum terdidik dengan motif ideologis masing-masing”.
Penghancuran buku bukan sekedar persoalan benang kusut dan konspirasi politik dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga mewakili kenyataan keberadaan seseorang atau sekelompok orang di dalam dan luar pemerintahan yang berpikir bahwa opini dan pandangan mereka adalah satu-satunya gagasan yang boleh beredar. Praktek ini juga berangkat dari narsisme diri bahwa mereka sedang melindungi masyarakat dari potensi yang meracuni pikiran banyak orang.
Dalam kaitan ini, pelarangan buku dalam banyak hal terjadi tidak saja di negara-negara otoriter, tetapi juga di negara dengan sistem politik demokratis seperti Amerika Serikat sampai sekarang ini. Dengan dorongan semangat keagamaan, atau keprihatinan orang tua dan sejumlah kalangan terhadap pornografi, para pustakawan mendapatkan desakan untuk menyembunyikan sejumlah buku dari daftar katalog perpustakaan mereka. Ringkasnya, banyak hal terjadi seputar persoalan larangan peredaran buku di dalam masyarakat.
Dalam kasus yang terjadi di Indonesia sekarang, razia dan pelarangan buku secara prinsip tidak dapat disangkal mewakili sisi kelam kekuasaan. Publik yang jengkel boleh jadi memaklumi tindakan aparat hukum di daerah. Mereka cuma bawahan yang dapat ditakar tingkat pemahaman hukumnya. Namun, pernyataan Jaksa Agung sebagai pejabat tinggi terkait penegakan hukum mengundang sejumlah pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di republik ini? Kegentingan seperti apa yang memaksa Jaksa Agung mengarahkan aparatnya bertindak inkonstitusional? Mengapa Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di republik ini?
Kegagalan Reformasi de Graeff
Kontroversi pernyataan Jaksa Agung terkait razia dan pelarangan buku sesungguhnya mengingatkan kembali sebuah ironi dalam catatan sejarah politik dunia ketika penguasa “dipaksa” bertindak di luar atau bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Ada sejumlah preseden dalam sejarah tersebut yang memberikan darah dan daging bentuk psikologi kekuasaan ini, dan ilustrasi terbaik tentang ini bisa juga kita lihat dalam catatan sejarah Indonesia. Gambaran terbaiknya dapat dilihat pada kiprah Andries Cornellis Dirk de Graeff sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda (1926-1931).
Andries Cornellis Dirk de Graeff datang ke Hindia-Belanda menggantikan Gubernur Jenderal Dirk Fock (disingkat Pak De oleh kaum pergerakan anti-kolonial) yang dikenal sebagai gubernur jenderal yang keras dan kasar dalam tindakannya. Berbeda dengan penggantinya, de Graeff adalah seorang diplomat karir berpandangan liberal dengan latar belakang kebangsawanan yang kuat. Sebagai gubernur jenderal yang baru, ia berharap dapat membawa semangat reformasi politik di Hindia yang menemui jalan buntu di bawah gubernur jenderal sebelumnya.
Visi de Graeff tentang masa depan Hindia-Belanda dapat dilihat dalam surat kepada sahabatnya van Limburg Stirum yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada 1916 sampai 1921. Dalam surat itu de Graeff menyatakan pemerintah kolonial tidak lagi bisa menunggu “kematangan politik” penduduk di koloni dan siapa pun harus siap menelan “apel yang masam” apabila tidak ingin menghadapi revolusi di Hindia (Penders, 1977: 131).
Namun, sejarah mencatat semangat reformasi politik yang hendak digulirkan de Graeff harus berhadapan dengan kenyataan politik reaksioner warga Eropa di koloni. Dibanding serangan politik kaum pergerakan, sikap politik warga Eropa di koloni menjadi pukulan lebih berat yang harus dihadapinya. Dalam suratnya kepada Van Limburg Stirum, de Graeff mengeluhkan bahwa setelah pemberontakan komunis, pers Belanda terus-menerus mengipasi “insting rasial, superioritas, dan kebencian ras” yang membangkitkan ketakutan besar di antara mereka. “Saya ingin melawan arus itu, tetapi sepertinya percuma ... situasi di Hindia membuat pertentangan semakin tajam antara kulit putih dan sawo matang” (Penders: 135). De Graeff sendiri mengomentari kemunculan Vaderlandsche Club (VC), satu kelompok yang menyuarakan serangan rasial dan kebencian terhadap kaum pergerakan, sebagai “bayi yang mati sebelum kelahirannya”.
Visi perubahan de Graeff pada akhirnya harus menghadapi batu terjal konservatisme politik warga Eropa di Hindia-Belanda. Ujian terbesar baginya terjadi pada awal tahun 1929 dengan beredarnya desas-desus pemberontakan baru yang digulirkan kaum nasionalis Indonesia.
Polisi kolonial (PID) dikabarkan menemukan sebuah surat yang berisi rencana pemberontakan baru terhadap pemerintah, dan menemukan sejumlah kaitan dengan para pemimpin nasionalis seperti Sukarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya. Desas-desus tersebut berkembang liar menjadi suara keras yang menjadi tuntutan di suratkabar-suratkabar berbahasa Belanda yang merasa cemas dengan perkembangan politik yang terjadi. Gubernur Jenderal dan aparatnya memiliki pengetahuan yang cukup bahwa desas-desus tersebut adalah sebuah permainan politik—di Hindia dan di negeri Belanda—yang bertujuan melemahkan rencana-rencananya.
Pada akhirnya de Graeff dan Jaksa Agung tidak dapat berbuat banyak selain memenuhi tekanan itu dengan menangkap Sukarno dan para petinggi PNI atas tuduhan mengganggu ketertiban umum (rust en orde) meski dengan bukti-bukti yang lemah sekalipun. Melihat kenyataan arus balik kegagalan reformasi politik di koloni Hindia-Belanda, De Graeff pun akhirnya pulang ke negeri asal.
Persoalan razia dan pelarangan buku yang ramai dibicarakan belakangan ini menjadikan kisah de Graeff karikatur sejarah yang relevan dalam melihat perkembangan politik Indonesia kontemporer. Pemerintahan Jokowi Widodo muncul dengan serangkaian janji terhadap perubahan politik yang menyegarkan. Sejumlah pendukungnya pun terkenal sebagai juru bicara yang gigih dalam mengusung kebebasan sipil. Namun, sepertinya ia pun harus menerima kenyataan untuk menelan apel yang masam dalam menjalankan agenda-agenda politiknya.
Lebih dari sekedar apel masam, anti-komunisme adalah telur busuk yang dilemparkan lawan-lawan politiknya. Tuduhan ini dilontarkan bukan saja kepada para pembantu dan pendukungnya, tetapi juga kepada sosok presiden secara pribadi. Berbagai razia di daerah-daerah mengukuhkan kembali aroma busuk yang dilemparkan kepada pemerintahan ini. Pernyataan Jaksa Agung adalah upaya membersihkan aroma busuk dalam tubuh pemerintahan. Namun langkah itu dilakukannya dengan memberi aroma busuk itu kepada publik.
Tentu saja kita tidak ingin turut menikmatinya.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id