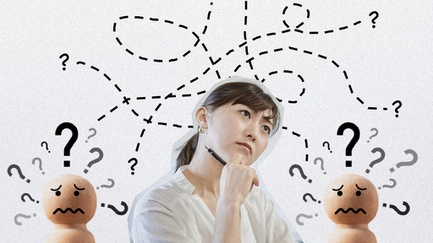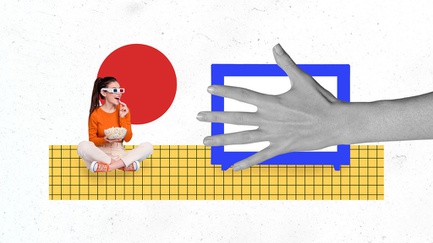tirto.id - “Ya Allah ndak mud kerja."
"Lu orang kok pada mantep mantep sih gaweannya."
"Ya Allah semoga gajiku nanti mantep."
“Semua gue lamaran. Apakah ada yang nyangkut? Enggak. Akhirnya? Nggak tau. Ilang aja udah. Pesannya? Simpel: Nasi goreng satu, sedeng, telornya didadar."
Kalimat di atas bukan cuitan random di X atau caption lawak di Instagram maupun TikTok.
Percaya atau tidak, kalimat tersebut merupakan unggahan beberapa pengguna di LinkedIn yang sempat viral di dunia maya.
Tidak hanya lucu, konten yang sebagian berasal dari curahan hati Gen Z itu seakan mendobrak aturan main LinkedIn yang biasanya dituntut formal dan profesional.
LinkedIn pertama kali diluncurkan pada 5 Mei 2003. Reid Hoffman, sang pendiri, memiliki misi untuk menghubungkan para profesional dari seluruh dunia.
Dari sekadar wadah untuk mempermudah terjalinnya relasi, LinkedIn menjadi platform utama untuk membangun personal branding pengguna lewat sharing pencapaian, pendapat, hingga saran seputar dunia profesional yang digeluti.
Posisi LinkedIn juga unik karena konsep yang ditawarkan berbeda dengan media sosial lain.
Instagram, X, TikTok, dan Facebook memberikan lebih banyak kebebasan bagi pengguna untuk menggunakan identitas samaran, sedangkan LinkedIn mensyaratkan pengguna untuk menggunakan foto dan nama asli ketika berinteraksi.
Karakter LinkedIn otomatis mendorong user untuk membuat konten yang merepresentasikan diri maupun pekerjaannya.
Maka dari itu, konten yang dibuat pun harus dikurasi secara hati-hati. Konten di LinkedIn juga digunakan untuk memperlihatkan keahlian pengguna di bidang tertentu.
"Banyak orang lelah dengan sifat toksik dan perasaan tak terlihat di platform media sosial lain. Mungkin mereka juga merasa bahwa medsos selain LinkedIn terlalu performatif, menjemukkan, serta terlalu berisik."
Begitu pendapat Jennifer Thompson, seorang Digital Marketing Strategist, di blognya.
Tentu tidak salah untuk merayakan pencapaian lewat media sosial, tapi tren personal branding juga berpotensi membuat interaksi di antara users menjadi tidak tulus dan seragam.
Misal, umum bagi pengguna untuk menemukan komentar dengan nada seragam seperti “very insightful”, “I agree”, Thank you for sharing this”, yang berulang di unggahan berbeda-beda.
Komentar tersebut tidak ditulis karena ketertarikan dengan konten tertentu. Sebaliknya, meninggalkan komentar di unggahan profesional adalah cara untuk meningkatkan engagement online.
Personal branding yang berlebihan juga berpotensi membuat seseorang terjebak dalam ketidakjujuran ketika mempresentasikan diri sendiri di internet.
Ini terjadi, misalnya, pada seorang pengguna bernama Janney Hujic.
Dalam unggahan LinkedIn, ia menceritakan pertemuannya dengan mantan CEO DBS Bank bernama Piyush Gupta.
Pertemuan tidak sengaja itu digunakan Janney untuk menceritakan proyek yang akan ia kerjakan kepada Piyush, "Aku membagikan misiku kepadanya: untuk memberdayakan perempuan lewat perjalanan transformatif yang akan menawarkan tantangan, penyembuhan, dan juga membebaskan potensi yang selama ini terkunci."
Piyush pun segera memberikan klarifikasi, sosok laki-laki yang berfoto dengan Janney bukanlah dirinya.
Masalah semakin panjang usai laki-laki dalam foto turut memberikan klarifikasi tambahan: sedari awal ia sudah menjelaskan kepada Janney bahwa dirinya bukanlah Piyush Gupta.
Usai didesak netizen, Janney mengaku ia dan temannya mengunggah konten tersebut sebagai “lelucon yang tidak berbahaya”.
Dalam kasus Janney, ia dengan sengaja memanfaatkan nama Piyush untuk meningkatkan citra diri dan bisnisnya di LinkedIn.
Kasus Janney menunjukan bahwa personal branding juga memerlukan integritas.
"Dengan fakta yang terang benderang, ia [Janney] terus berbohong. Aku tidak yakin apakah integritas masih relevan akhir-akhir ini. Atau jangan-jangan kita sudah terlalu berlebihan dalam membangun personal branding maupun [ketika berupaya] mem-branding sesuatu?" tanggapan Benjamin Loh, Brand Strategist, melihat perkembangan kasus Janney.
Bagi Benjamin, kurangnya integritas dan kejujuran membuat upaya untuk memoles citra profesional menjadi kacau. Hal ini berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan orang lain saat melihat konten serupa.
Apa yang diutarakan oleh Benjamin juga relevan dengan kritikan dari pengguna LinkedIn lain bernama Tim Denning.
“Ketika keegoisan diperlihatkan kepada publik umum, lantas jutaan orang melakukannya secara bersamaan, rasanya mengerikan," Tim berkata jujur melihat fenomena poles-memoles citra di LinkedIn.
Menurutnya, jebakan personal branding membuat pengguna tidak lagi bisa melihat dirinya sendiri dengan jernih.
Dari kasus Janney hingga kritikan Tim, kita dapat sepakat bahwa yang bermasalah bukanlah upaya melakukan personal branding.
Persoalan muncul ketika upaya personal branding dilakukan dengan rumus baku: harus menampilkan pencapaian hebat, cerita yang fantastis, menggurui dan menghakimi pengguna lain, menunjukkan ekspektasi yang tidak masuk akal, serta tidak berangkat dari kejujuran.
Apa yang dilakukan oleh Gen Z dengan membuat konten-konten lucu di LinkedIn menjadi semacam angin segar.
Ia menjadi pengingat bahwa manusia tidak bisa terus-menerus menampilkan citra diri yang sempurna. Personal branding yang dilakukan secara simultan hanya membuat penampilan diri terlihat semakin dibuat-buat.
Penulis: Erika Rizqi
Editor: Sekar Kinasih
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id