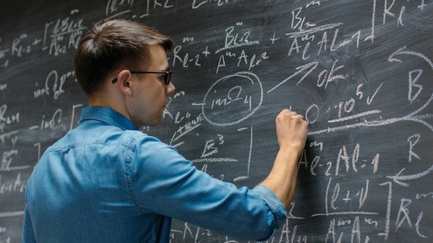tirto.id - Beberapa tahun terakhir, industri perbukuan Indonesia sempat memasuki fase yang mencemaskan. Toko buku gulung tikar, minat baca menurun. Banyak anak muda lebih akrab dengan layar ponsel daripada halaman cetak.
Namun, kini perubahan besar dalam tren membaca datang dari tempat yang tidak terduga: TikTok. Di balik konten joget-joget, tips kecantikan, komedi sketsa, dan tren viral lainnya, tumbuh sebuah komunitas yang pelan-pelan tapi pasti mengubah cara orang memandang buku. Namanya BookTok.
BookTok lebih dari sekadar ajang pamer buku bacaan. Ia adalah gerakan sosial, ruang ekspresi, dan algoritma yang menyulap buku sehingga mengandung emosi kolektif. Lewat video berdurasi 15 hingga 60 detik, para pengguna—kebanyakan anak muda—berbagi tanggapan emosional mengenai cerita, karakter, atau bahkan sekadar satu kalimat dalam novel yang mengena di hati.
Yang mengejutkan, pengaruh BookTok terbukti nyata. Buku-buku yang sempat tenggelam kembali naik daun. Penjualan melonjak. Toko buku yang sebelumnya sepi kini mulai menyesuaikan diri dengan rak “BookTok Favorites”. Yang tak kalah penting: muncul semangat baru dalam budaya membaca.
Saat Membaca Jadi Pengalaman Sosial
BookTok, seperti namanya, adalah dunia mini dalam TikTok, wadah orang-orang membicarakan buku. Di sana, pengguna menangis setelah membaca akhir cerita, tertawa karena alur cerita yang absurd, atau marah-marah karena karakter favoritnya mati. Emosi menjadi bahasa utama.
Selaras dengan temuan studi East South Social Science and Humanities Journal (2023), konten BookTok di Indonesia umumnya berbentuk ringkasan cerita, ulasan singkat, kesan pertama, atau reaksi emosional. Jenis konten ini memicu keterlibatan tinggi, komentar, likes, bahkan diskusi lanjutan.
Hal yang dulu dilakukan sendiri—membaca dalam keheningan, menyusun makna secara personal—kini justru menjadi awal dari obrolan bersama. Orang tak lagi hanya ingin tahu isi bukunya, tapi juga hal yang dirasakan orang lain saat membacanya. Inilah yang disebut oleh Digital Society sebagai “perpustakaan emosional kolektif”. Setiap video BookTok menjadi semacam testimoni afektif yang mengundang penonton untuk ikut merasakan, bereaksi, dan terlibat.
Tak heran jika tagar BookTok global telah mencapai lebih dari 55 juta unggahan. Bahkan, di Indonesia, tagar #SerunyaMembaca sudah menyentuh lebih dari 400 ribu video per Mei 2025. Lewat BookTok, buku tak hanya dibaca; ia juga dipertunjukkan, dibicarakan, bahkan diperebutkan.

Dalam wawancara dengan Whiteboard Journal, beberapa pembuat konten BookTok mengaku bahwa kini kebiasaan membacanya bukan lagi hanya untuk diri sendiri, tetapi agar bisa berbagi kesan. Pengalaman membaca menjadi bersifat sosial, bukan karena medianya berubah, tapi karena teknologinya memungkinkan narasi personal disalurkan secara publik.
Pendek kata, BookTok telah menjelma bentuk baru dari komunitas literasi: cair, ekspresif, dan sangat bergantung pada kekuatan algoritma serta emosi.
Kekuatan Storytelling dan Identitas
Di Indonesia, para kreator seperti Indra Dwi Prasetyo dan Syarif (@menceriakan) menggunakan BookTok sebagai ruang ekspresi yang jujur dan dekat. Mereka tidak tampil sebagai kritikus sastra, melainkan sebagai pembaca yang terhubung secara emosional. Reaksi mereka autentik dan tidak ndakik-ndakik. Justru karena itulah para penonton merasa sedang mendengar teman bercerita, bukan sedang disuruh membaca oleh "polisi literasi".
Laporan Whiteboard Journal menyebut, BookTok membuka ruang baru bagi pembaca untuk menampilkan identitas dan preferensi literasinya. Buku bukan lagi simbol eksklusif, barang kolektor, atau aktivitas elitis. Ia telah menjadi bagian dari narasi pribadi, katalis emosi yang bisa dibagikan kepada jutaan orang dalam sekali gulir.
Windy Ariestanty, salah satu kurator Patjar Merah, menyebut BookTok sebagai “perayaan storytelling” yang jauh lebih kuat dari sekadar strategi promosi. Ketika orang-orang membicarakan buku dari sudut pandang pribadi, lahirlah rasa memiliki. Perasaan itulah yang menyulut rasa ingin berbagi.
Hal itu pula yang menjadi alasan viralnya video tentang buku, tanpa perlu menyebut data penjualan atau testimoni dari penulis terkenal. Yang dibutuhkan hanyalah cerita yang terasa nyata; kisah tentang sebuah buku yang membuat seseorang merasa tidak sendirian. Dengan begitu, BookTok bukan lagi sekadar tren, melainkan ruang aman emosional, tempat cerita menjadi alat koneksi dan identitas.
Efek Domino: Penjualan, Komunitas, dan Toko Buku
Efek BookTok tidak berhenti di layar. Ia menjalar ke dunia nyata, ke toko-toko buku yang nyaris mati, ke etalase daring yang mendadak penuh, bahkan ke pojok-pojok kota tempat komunitas baru mulai tumbuh.
Menurut laporan Consumeri.id, BookTok mendorong lonjakan penjualan buku. Fenomena ini tidak hanya berlaku untuk judul-judul baru, tetapi juga buku klasik yang sempat dilupakan. It Ends With Us karya Colleen Hoover, Tuesdays with Morrie karya Mitch Albom, hingga The Song of Achilles karya Madeline Miller, semuanya mengalami lonjakan popularitas setelah menjadi bahan pembicaraan emosional di TikTok.
Berkat itu, toko buku pun ikut merasakan dampaknya. Di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, beberapa toko yang sempat sepi kini mencatat pertumbuhan penjualan signifikan. Tidak sedikit yang akhirnya menyesuaikan tampilan fisiknya, misalnya dengan menyediakan rak bertanda “BookTok Favorites” agar pembeli bisa langsung mengenali tren. Bahkan toko daring seperti Shopee dan Tokopedia pun mulai menambahkan label serupa.

Resonansi BookTok bahkan melahirkan komunitas baru berbasis pengalaman. Di Jayapura, misalnya, klub buku Torang Baca lahir dari interaksi pengguna TikTok yang ingin membaca bersama. Tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya, mereka dipertemukan oleh satu-dua video rekomendasi yang menyentuh hati, lalu disusul komentar, DM, dan akhirnya kopi darat. Berkat BookTok, transformasi pengalaman membaca menjadi aktivitas kolektif kini terjadi kian masif.
Hal ini sejalan dengan hasil studi East South Social Science and Humanities Journal. BookTok di Indonesia telah membentuk ekosistem literasi baru yang memadukan hiburan, informasi, dan emosi. Studi tersebut menemukan bahwa BookTok mendorong keterlibatan tidak hanya dalam bentuk konsumsi pasif, tetapi juga partisipasi aktif, mulai dari membuat ulasan, berdiskusi di kolom komentar, hingga membentuk komunitas membaca.
Dalam konteks tersebut, BookTok berfungsi sebagai “ruang sirkulasi makna”. Buku-buku dibicarakan, ditafsirkan ulang, dan dihidupkan kembali melalui emosi kolektif pengguna.
Festival-festival literasi seperti Patjar Merah pun ikut mengakomodasi gelombang baru itu. Pengunjungnya kini tidak hanya datang karena ingin bertemu penulis atau membeli buku langka, tetapi karena ingin merayakan kegiatan membaca sebagai pengalaman emosional yang dibagi.
BookTok, dalam wujudnya yang paling kuat, telah mengubah buku dari benda sunyi menjadi pengalaman sosial; dari aktivitas pribadi menjadi percakapan publik; dari produk komersial menjadi simbol koneksi antar manusia.
Tantangan, Kritik, dan Masa Depan BookTok
Popularitas yang besar membawa konsekuensinya sendiri. Bisa jadi, membaca buku hanya dilakukan karena viral, bukan karena kualitas isinya. Genre-genre tertentu seperti romance atau coming-of-age mendominasi algoritma, sementara karya sastra lokal yang lebih kompleks bisa saja tenggelam di antara konten-konten rekomendasi buku yang lebih mudah dipahami dan lebih “menjual” secara emosional.
Siklus konsumsi yang cepat juga menciptakan budaya “move on” literasi. Buku yang kemarin dipuja-puja, hari ini sudah dilupakan karena ada judul baru yang lebih dramatis. Dalam dunia BookTok, perhatian adalah mata uang utama, dan dalam kompetisi itu, tidak semua buku punya peluang sama.
Namun di balik semua itu, terbentang peluang yang luar biasa.
BookTok telah menjadi pintu gerbang literasi baru bagi generasi digital. Bagi banyak remaja dan dewasa muda, barangkali ini merupakan kali pertama mereka merasakan pengalaman membaca yang seru, relevan, dan—yang paling penting—tidak sendirian. Buku bukan lagi simbol intelektualisme yang kaku, tetapi media ekspresi diri yang beresonansi.
Bukan hanya pembaca yang diuntungkan. Penulis-penulis muda kini memiliki panggung baru untuk menunjukkan karyanya secara langsung kepada audiens, tanpa harus menunggu legitimasi dari penerbit besar. Bahkan beberapa buku yang awalnya diterbitkan secara indie bisa menjadi best seller berkat momentum satu video ulasan jujur yang viral.
BookTok juga memberi harapan baru bagi toko buku dan pelaku industri literasi. Mereka kini bisa membaca tren secara real-time, menyesuaikan katalog, dan menjangkau audiens yang sebelumnya sulit disentuh. Dengan strategi yang adaptif dan kolaboratif, industri buku bisa tumbuh di tengah dominasi digital, bukan kalah olehnya.
Digital Society menyebut BookTok sebagai “surga baru bagi pecinta buku” yang haus akan keterhubungan. Ungkapan itu tepat karena, lebih dari sekadar tagar atau tren, BookTok menunjukkan bahwa generasi muda tidak kehilangan minat baca; mereka hanya menunggu medium yang berbicara dalam bahasa mereka.
Jika tren ini terus dijaga—dengan literasi yang dikembangkan, komunitas yang dirawat, dan dukungan dari penerbit maupun institusi pendidikan—kita mungkin sedang menyaksikan bukan sekadar kebangkitan membaca, tetapi kelahiran generasi pembaca baru yang lebih ekspresif, inklusif, dan terbuka terhadap cerita-cerita yang menggugah hati.
Mereka tidak membaca karena diwajibkan, melainkan karena benar-benar ingin tahu hal yang akan terjadi di halaman berikutnya.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id