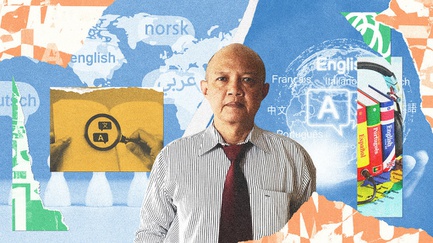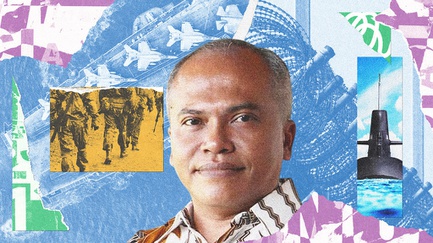tirto.id - Pada siang mendung di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebuah insiden memperlihatkan Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM), menghentikan truk limbah di tengah jalan lalu menegur sang sopir karena membuat jalanan kotor.
Insiden ini kemudian diunggah ke kanal YouTube resminya: Kang Dedi Mulyadi Channel. Video-video seperti ini banyak dijumpai di channel itu.
Sejak lama KDM dikenal sebagai sosok politisi yang kerap tampil dalam video dengan ekspresi emosional kuat, seperti marah, berteriak, bahkan menangis. Gubernur Jawa Barat ini beberapa kali menegur preman, berkonflik dengan pedagang liar, hingga memberi bantuan kepada rakyat kecil.
Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan dan komunikasi populis yang bersifat performatif. Sebelum kita mendalami gaya kepemimpinan dan komunikasi KDM, penting untuk bersama-sama memahami teori populisme.
Terdapat dua pendekatan utama dalam studi populisme, yaitu sebagai ideologi dan sebagai gaya komunikasi. Seperti halnya sosialisme, liberalisme, dan konservatisme, keberadaan -isme dalam kata populisme menjadi salah satu indikator bahwa populisme adalah ideologi. Proponen dari klaster ini adalah Mudde, Stanley, dan Rooduijn.
Pendekatan ideologis menganggap populisme sebagai ideologi tipis yang berasumsi tentang konflik antara “rakyat baik” dan “elite jahat”. Namun, pendekatan ini sulit diterapkan dalam konteks Indonesia karena politisi Tanah Air jarang berafiliasi dengan ideologi tertentu secara eksplisit.
Sebaliknya, pendekatan gaya komunikasi yang dirumuskan Benjamin Moffitt dan Simon Tormey lebih relevan. Mereka menyebut populisme sebagai "repertoar penampilan" dalam membangun hubungan politik. Ciri-cirinya adalah: (1) klaim mewakili rakyat dalam melawan “musuh”, (2) narasi krisis, dan (3) "perilaku buruk" atau gaya komunikasi non-konvensional. Ketiga ciri ini terlihat jelas dalam kepemimpinan dan komunikasi KDM.
Pertama, KDM membangun narasi bahwa dirinya mewakili rakyat melawan musuh yang mengganggu pembangunan. Namun, musuh yang dia tampilkan sering kali bukan elite politik, tetapi individu atau kelompok dalam masyarakat seperti preman, pelaku tambang ilegal, atau pedagang liar.
Dalam banyak video, dia tampil sebagai pahlawan yang turun langsung untuk menindak tegas para “pengganggu”. Ini sejalan dengan konsep populisme menurut Moffitt dan Tormey yang tidak selalu mengidentikkan musuh dengan elite, melainkan bisa juga dari rakyat itu sendiri.
Kedua, KDM membingkai wilayah kekuasaannya seolah berada dalam kondisi krisis. Dia pernah menyatakan Jawa Barat dalam kondisi darurat premanisme dan memposisikan oknum organisasi masyarakat (ormas) dan LSM sebagai penghambat pembangunan.
Narasi ini diperkuat dengan video-video di YouTube yang menampilkan dirinya menindak langsung para preman atau oknum ormas nakal. Bagi pemimpin populis seperti KDM, krisis menjadi panggung yang melegitimasi tindakan cepat dan personal, serta menegasikan pendekatan birokratis yang dianggap lamban.
KDM pun tak segan menyuarakan ketidaksukaannya terhadap pendekatan formal yang berjenjang. Dalam sebuah video, dia menegaskan pentingnya tindakan langsung: "Kalau tidak dicontohi, tidak turun, susah selesai. Saya ingin menempuh hal-hal itu dilakukan dengan cepat."
Ketiga, dalam gaya komunikasinya, KDM menunjukkan “perilaku buruk” dalam pengertian Moffitt dan Tormey. Dia tampil emosional, ceplas-ceplos, berbicara dengan bahasa sehari-hari—termasuk bahasa Sunda kasar—dan menunjukkan sikap egaliter. Judul-judul videonya pun menggunakan "bahasa tabloid" sensasional, seperti “AMARAH KANG DEDI MELED4K”.

Perilaku semacam ini efektif mendekatkan politisi kepada rakyat. Dengan menanggalkan gaya formal dan teknokratis, KDM membangun citra sebagai politisi yang memahami dan berbagi perasaan dengan rakyat. Dia tampil bukan sebagai birokrat, tapi sebagai bagian dari masyarakat, hanya saja dengan kekuasaan dan sumber daya lebih untuk bertindak.
Apa yang dilakukan KDM terbukti sangat atraktif. Kanal YouTube-nya meraih performa tinggi, dengan rating B+ dari Social Blade dengan jumlah penonton lebih dari dua miliar. Youtube KDM menduduki peringkat 171 sebagai kanal dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia, bersaing dengan kanal hiburan terkenal di Indonesia seperti Windah Basudara dan Nessie Judge.
Gaya populisme KDM juga tercermin dari kebijakan-kebijakannya. Misalnya, dia mendorong wajib militer di SMA untuk menekan tawuran dan balap liar. Dia juga membentuk satgas anti-premanisme dari gabungan TNI-Polri.
Kebijakan ini didasarkan pada logika umum atau “common sense” masyarakat bahwa kriminalitas bisa ditekan dengan penegakan hukum keras dan disiplin militer. Padahal, pendekatan ini bertentangan dengan arah kebijakan publik modern yang lebih menekankan pencegahan dan rehabilitasi. Contoh lain adalah penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
KDM menyatakan kebijakan ini lahir dari logika sederhana: lebih baik membantu rakyat kecil daripada memikirkan uang triliunan. Walau popular, kebijakan ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Jawa Barat, yang masih bergantung pada dana pusat, berisiko mengalami pelemahan keuangan daerah akibat kebijakan ini.
Gaya populisme KDM punya kesamaan dengan banyak pemimpin dunia yang turut berselancar dalam tren populisme. Dalam dua dekade terakhir, populisme mengalami lonjakan signifikan, terutama setelah krisis keuangan global 2008, gelombang migrasi besar-besaran, dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi konvensional. Mereka menampilkan diri sebagai pelindung rakyat dari kejahatan.
Sebagai contoh Duterte membungkus narasinya dalam “Perang Melawan Narkoba” dan dikenal dengan pendekatan hukuman ekstrem. KDM tidak seekstrem Duterte, namun logika populisme penal tetap terlihat dalam narasi dan kebijakannya: mengidentifikasi musuh (preman), menekankan darurat, dan mendorong tindakan represif.
Kesamaan lain antara Duterte dan KDM adalah kemampuannya mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan struktural. Duterte, meski gagal mengentaskan kemiskinan, tetap terkenal karena dianggap tegas terhadap pengedar narkoba. Sementara KDM, walaupun kebijakannya berpotensi melemahkan struktur fiskal, tetap disanjung karena dianggap pro-rakyat dan aktif “turun langsung”.
Meski efektif dalam membangun citra, politisi populis dengan gaya kepemimpinan performatif menyimpan risiko jangka panjang, terutama dalam konteks tata kelola dan pembangunan berkelanjutan.
Namun apapun itu, di era politik yang sarat pencitraan dan kejenuhan publik terhadap birokrasi, gaya populis terbukti mampu menarik simpati dan dukungan luas dari masyarakat.
Editor: Rina Nurjanah
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id