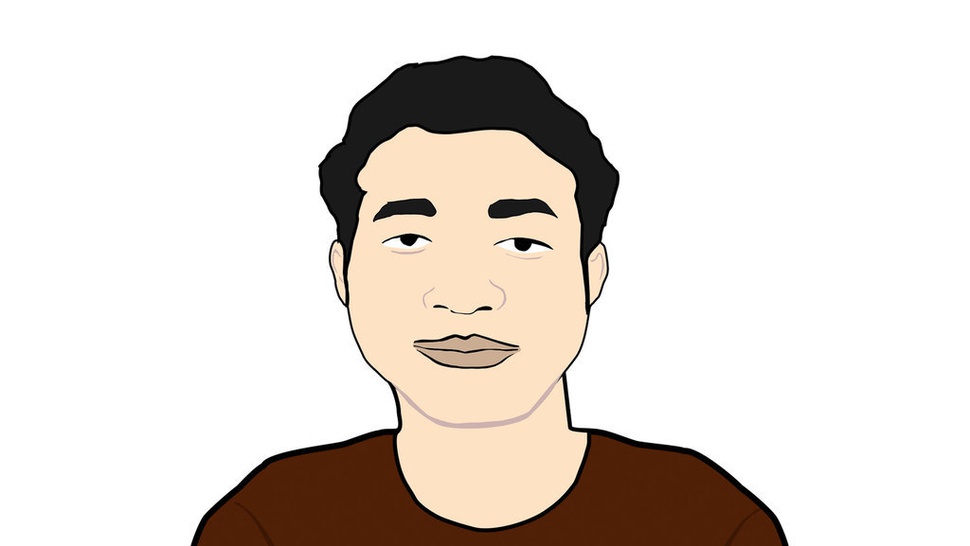tirto.id - Masuk tahun politik, masyarakat kembali dilirik dalam kalkulasi khas lima tahunan. Namun, ada yang berbeda kali ini.
Piramida penduduk Indonesia semakin gemuk di rentang usia tengah (17-39 tahun), yang berjumlah sekitar 40 persen (data BPS). Sedangkan rentang usia dewasa (40-70 tahun) menjadi hanya sekitar 32 persen. Di sisi lain, kita dihadapkan pada gelombang perubahan nyata. Penetrasi teknologi informasi, yang menjadi faktor terikat (embedded) dalam realitas ekonomi-politik selama sepuluh tahun terakhir, telah mengubah kebiasaan hidup masyarakat.
Pertalian itu melahirkan fenomena "generasi baru". Artinya, struktur ekonomi-politik dan kebijakan seharusnya telah masuk dalam babak lanjut. Hari ini peran generasi itu sebagai subjek sekaligus objek yang mewarnai sistem. Pertanyaannya, seberapa derajat pengaruh penentu (determinasi) mereka jika berhadapan struktur lawas di Indonesia? Dan siapkah kita menerima perubahan?
Karakter Hero
Kelompok muda tak punya karakter khusus tanpa kesadaran kelas. Namun, di tengah kepolosan pengalaman historis dan politik, kaum muda berupaya merevisi zaman. Strauss dan Howe (1991, 1997) menjelaskan soal karakter hero setiap generasi baru, yang selalu melahirkan upaya mereka mengompensasi ekses atau kesalahan generasi sebelumnya atas kondisi sekarang.
Karakter hero generasi baru memiliki skeptisisme pada struktur dan cara lama yang keliru atau sudah usang. Hero dan teknologi berimbas pada masifnya penyebaran segala jenis informasi yang mampu menggalang perhatian publik. Penyalahgunaan wewenang, buruknya birokrasi, hingga keluhan konsumen terangkat di media sosial, yang bisa mendorong tindakan dalam hitungan detik, menit, dan jam.
Konvergensi informasi memunculkan rasionalitas dan pragmatisme. Dalam ekonomi, mereka menghancurkan jurang informasi harga dan kualitas sembari menawarkan model bisnis baru. Pilihan-pilihan ekonomi kini lebih mudah dibuat karena nilai barang dan nilai tambah lebih gampang diketahui. Sementara dalam politik, blunder dan prestasi seseorang dapat diketahui dari jejak digital. Antipati dan simpati mudah dikerahkan sejalan arus cepat lalu lintas informasi di ranah publik.
Segala keterbatasan, lapisan, dan hierarki informasi, yang melahirkan rezim multi-level-marketing (MLM) ekonomi dan politik, beralih menjadi ketersediaan, bypass, dan pilihan informasi dalam model personalized-marketing. Tak terhitung komunitas digital yang mengemas aksi sosial, ekonomi, dan politik dengan cara-cara yang belum pernah terpikirkan. Dari beragam variannya, ada satu kesamaan: melipat lapis komunikasi menjadi person-to-person.
Meski dimensi tindakannya belum tentu ideologis, mereka tetap menciptakan kolektivitas dalam rational-choice kekinian. Misalnya kemunculan ragam startup amal yang menggunakan streategi crowd-funding untuk membantu pihak yang membutuhkan. Banyak juga yang jadi jembatan antara investor dan bisnis. Dalam gerakan sosial, kita ingat "koin untuk Prita" (2009) dan KPK (2012), serta mobilisasi Aksi 411 dan Aksi 212 hingga tagar #SayaPribumi.
Aksi ‘hero’ tidak terbatas di dunia maya. Enterpreneur dan sociopreneur dalam produk kreatif, pariwisata, dan jasa menggantikan bisnis migas, rezim industri lawas andalan negara. Crowd-economy (padat karya) dari pariwisata saja telah menyumbang 13,5 miliar dolar AS (2016) dan diproyeksikan jadi penyumbang devisa utama pada 2019.
Kontradiksi Populis
“Hampir semua hal besar dibuat kaum muda”—yang diucapkan politikus Benjamin Disraeli—menjadi jargon populer di Inggris pada abad 19. PM Inggris dari Partai Konservatif ini gemar membuat langkah non-konservatif, yaitu merangkul kelompok muda, buruh, dan industri baru.
Inggris saat itu dihadapkan kondisi kesejahteraan pekerja dan pangan. Sementara Amerika Serikat mengalami era Rekonstruksi. Adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan-perubahan ekonomi-politik membuat Inggris saat itu dikenal "rumah industri" dan AS sebagai "rumah demokrasi". Ini mengilustrasikan perubahan peran (khususnya negara) dari pihak yang terdampak perubahan menjadi pemain.
Bagaimana Indonesia?
Kondisi Indonesia hari ini mengingatkan kita pada gambaran futurolog Alvin Toffler (1980) tentang "gelombang ketiga"(third wave). Tak semua pihak siap menerima kebaruan dan keterbukaan. Generasi muda hari ini mungkin punya pengaruh besar. Namun, jika ditanya soal determinasi, jawabannya "belum tentu"; berkebalikan dengan jumlah populasi, keaktifan, dan alternatif yang dimiliki mereka.
Rendahnya determinasi dapat kita lihat dari kontradiksi di lapangan. Jakarta adalah hub proyek-proyek startup yang punya potensi ekonomi dan prospek bermitra dengan pemerintah untuk menangani problem daerah.
Jumlah startup Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara (data CHGR, 2016), dan mayoritasnya di Ibu Kota. Ditambah komposisi penduduk muda di Jakarta, seharusnya pemerintah bisa mengakomodasi creative-economy dan crowd-economy. Namun, beberapa kebijakan pemerintah Jakarta justru cenderung memihak struktur yang kental oligarki seperti PKL Tanah Abang dan transportasi becak.
Kasus lain dapat ditemukan dalam konflik angkutan online dan konvensional di 10 kota besar selama dua tahun belakangan. Beberapa pemerintah daerah menerapkan langkah pembiaran sampai pelarangan. Padahal, konfliknya bukan semata persaingan pendapatan. Ada alasan-alasan politik di baliknya. Sementara efek crowdeconomy, yang beroperasi secara online (pertumbuhan sektor kuliner dan jasa, misalnya), telah melampaui sektor-sektor ekonomi konvensional.
Alasan Politik
Praktik kebijakan populis di Indonesia diartikan berbeda. Jika penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan disepakati sebagai kebutuhan bersama, terobosan kebijakanlah yang lebih logis disebut "populis". Namun, keterikatan sistem konvensional (angkot, ojek, becak, atau PKL) terhadap infrastruktur politik daerah memang lebih kuat. Di baliknya ada rantai komando ke atas, tersambung kepada para elite daerah. Akhirnya, mempertahankan yang lawas lebih disebut populis.
Kemauan adaptasi yang rendah menyebabkan para elite lebih suka berinvestasi pada struktur lawas. Sementara karakter generasi baru dengan keterbukaannya berkebalikan dengan model multi-level marketing struktur lawas yang bersandar pada jurang informasi. Gampangnya, jika antarpihak bisa tersambung satu sama lain, lalu elite mendapatkan apa?
Pada 2018, Pilkada serentak diadakan di 171 daerah dengan 569 pasangan calon. Tak banyak calon muda mengajukan diri. Hal paling krusial adalah minimnya program yang menyasar penduduk usia muda dan tengah, yang berjumlah antara 30-40 persen di tiap daerah.
Program macam itu mensyaratkan edukasi kebijakan dan tata pemerintahan pada konstituennya. Lima bulan (Januari-Juni) persiapan menuju Pilkada tak akan cukup bila tanpa kesiapan parpol dan mesin politik berkomunikasi dengan alternatif baru. Sebut saja calon termuda dalam Pilkada, Karolin Margret Natasa (Cagub Kalimantan Barat) dan Emil Dardak (Cawagub Jawa Timur), marketing politiknya masih cenderung menjual umur muda sang politikus, alih-alih kebaruan program.
Politik yang berinvestasi pada sistem lawas pada era informasi jelas destruktif. Sambutan setengah hati terhadap generasi baru akan membuat kondisi tersebut lebih problematik. Alih-alih bertarung dalam tawaran baru, strategi-strategi politik sekarang menekankan sentimen kebencian berbasis agama atau etnis lewat kemudahan teknologi dan keaktifan usia muda.
Dalam lanskap media sosial, Indonesia adalah negara degan pengguna Facebook terbanyak keempat dunia (data We Are Social dan Hootsuite, 2017). Pada akhir 2016, Kemkominfo mengatakan ada 800 ribu situs penyebar berita palsu (hoax) dan kebencian (hate speech). Jaringan hoaks ini bekerja terutama seputar isu politik dan SARA. Apakah mereka bergerak tanpa kepentingan? Terbongkarnya sindikat Saracen pada 2017 membuktikan hoaks dan siar kebencian adalah strategi politik yang biayanya jauh lebih murah ketimbang menjanjikan program.
Usai perhelatan politik, kelompok muda disayang dan dibuang. Survei LaKIP di Jakarta menunjukkan hampir 50 persen siswa mau ikut aksi kekerasan dalam isu agama. Sedangkan survei Mata Air dan Alvara melaporkan 1 dari 4 pelajar terkontaminasi radikalisme.
Dengan segala gambaran ini, yang kita lihat adalah persimpangan masa depan politik Indonesia. Bukan sekadar gelombang teknologi informasi yang sedang kita hadapi, lebih dari itu, masyarakat sipil diuji mengenai pilihan peradaban: apakah menuju kemajuan dan rasionalitas, atau kembali mempertahankan oligarki politik.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.