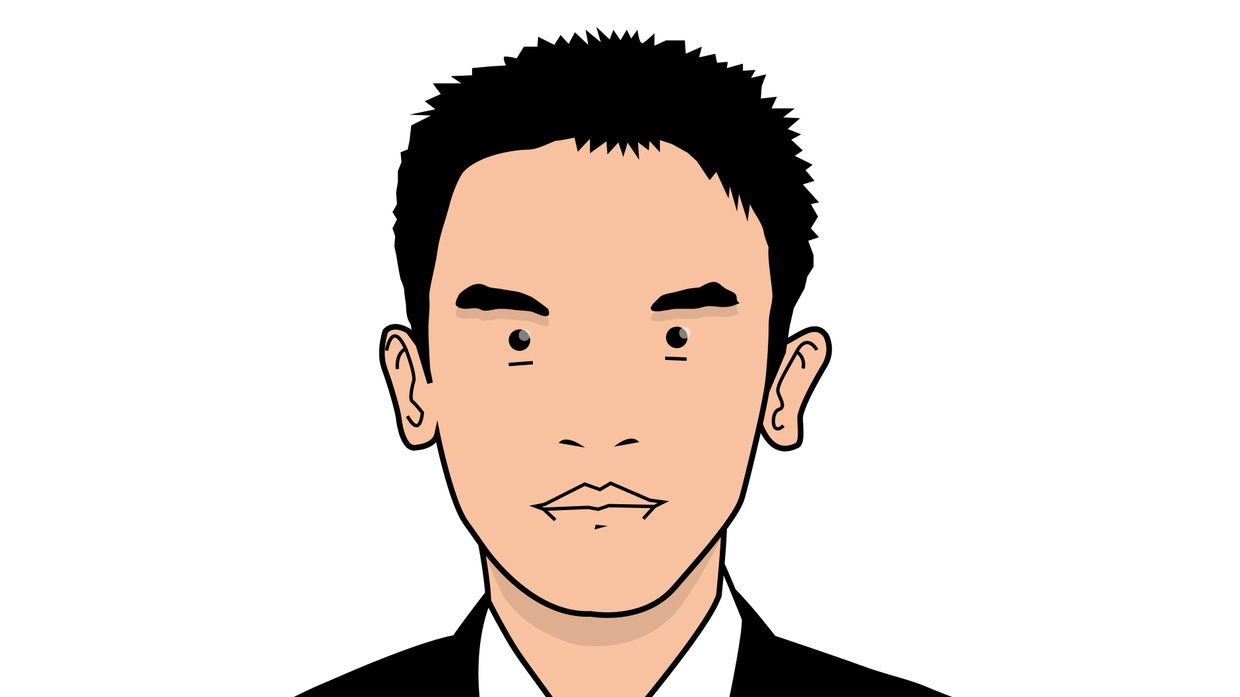tirto.id - Beberapa hari belakangan, media-media di Inggris memberikan pelajaran penting tentang bagaimana cara meliput dan memberitakan kasus kekerasan seksual.
Dalam kasus “pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris” yang dilakukan mahasiswa Indonesia bernama Reynhard Sinaga, kita bisa membaca kombinasi antara pemberitaan yang berorientasi dan menghargai privasi korban dengan disiplin mengawali proses pengadilan selama hampir dua tahun belakangan berhasil memberikan gambaran lengkap betapa brutal dan mengerikan kasus ini.
Dengan skala kasus demikian besar di mana jumlah korban diperkirakan lebih dari 200 orang, dan pelakunya adalah seorang imigran, sangat mudah untuk mengangkat hal-hal sensasional dan mengundang klik. Apalagi Inggris adalah negara di mana genre jurnalisme tabloid lahir, jurnalisme yang fokus pada unsur sensasionalisme atas suatu kasus.
Namun, sejauh yang saya baca, hal itu tidak dilakukan dalam pemberitaan kasus Reynhard Sinaga. Bahkan, media-media yang terbiasa menjual gosip murahan seperti The Sun dan Daily Mail tidak melakukannya. Atau, setidaknya tidak sesensasional biasanya.
Yang ada adalah kisah kerja keras media. Menariknya, ini tidak hanya dilakukan oleh media-media nasional yang berbasis di London seperti BBC, The Guardian, dan The Telegraph, melainkan juga media lokal seperti Manchester Evening News. Manchester adalah kota tempat pelaku melakukan kejahatannya dan proses pengadilan digelar.
Ada beberapa catatan menarik dari pemberitaan media-media Inggris mengenai kasus ini.
Privasi korban benar-benar dilindungi. Kita tidak menemukan penanda yang memberikan petunjuk bagi identifikasi siapa saja korban pemerkosaan. Selain itu, tidak ada narasi murahan victim blaming yang mempertanyakan pakaian, kondisi fisik korban, dan sebagainya. Yang ada, foto dan nama pelaku dipampang besar-besar di halaman pertama beberapa koran.
Deskripsi apa yang dilakukan oleh pelaku dan dialami korban diletakkan dalam konteks yang wajar. Deskripsi yang kontekstual itu berfungsi memberikan gambaran kepada pembaca semengerikan apa peristiwa yang terjadi. Dengan sensitivitas yang mungkin ditimbulkan, beberapa media serius memberikan petunjuk dan informasi soal apa yang bisa dilakukan pembaca. Termasuk juga apabila ada pembaca yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual.
Saya hampir yakin kalau deskripsi kekerasan seksual yang terjadi tersebut ditulis oleh media-media di Indonesia, beberapa jurnalis senior akan mengategorikannya sebagai cerita stensil, persis seperti komentar terhadap liputan pers mahasiswa Balairung mengenai kasus kekerasan seksual di UGM pada akhir 2018.
Penghargaan atas privasi, khususnya selama proses persidangan, ini juga didukung oleh sistem hukum di Inggris. Dalam kasus-kasus khusus, seperti kasus kekerasan seksual, ada larangan untuk memberitakan persidangan (reporting restriction) karena dikhawatirkan bisa memengaruhi proses yang sedang berlangsung. Wartawan boleh hadir selama proses di persidangan.
Normalnya, larangan pemberitaan ini berakhir ketika proses pembuktian sudah selesai. Namun, dalam kasus Reynhard Sinaga, hakim memperpanjang masa larangan pemberitaan sampai setelah pembacaan vonis pada 6 Januari 2020. Keputusan ini bisa dibanding oleh media-media. Namun, media seperti Manchester Evening News memilih tidak melakukannya dengan mempertimbangkan sensitivitas kasus.
Larangan pemberitaan ini bisa meminimalisir trial by the press yang sangat mungkin terjadi jika media bebas dibiarkan meliput sejak awal proses persidangan. Selain itu, menunjukkan hukum yang berpihak kepada korban karena ia melindungi korban dari publisitas media. Dan, dalam kasus Reynhard Sinaga, melindungi dan memberikan kesempatan kepada kemungkinan korban yang belum melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami.
Jadi Gosip Murahan
Awalnya saya khawatir kasus ini akan digunakan oleh khususnya media-media sayap kanan di Inggris untuk menggaungkan sentimen anti-imigran di Inggris yang beberapa tahun ini meningkat. Apalagi, ini bukan kasus biasa, bahkan disebut-sebut sebagai “pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris”. Sangat mudah untuk menyerang baik imigran maupun kelompok minoritas di Inggris yang posisinya rentan.
Namun, sejauh ini, tidak banyak media yang berfokus pada latar belakang pelaku. Pada banyak berita, penyebutan Indonesia sebagai asal negara Reynhard juga hanya sekilas. Lebih banyak narasi tentang aktivitasnya sebagai mahasiswa. Selain itu, tidak ada perhatian berlebihan atas orientasi seksual pelaku. Tentu narasi ini muncul karena kesadaran bahwa kasus kekerasan seksual tidak berhubungan dengan orientasi seksual seseorang.
Pelbagai pemberitaan tentang kasus Reynhard Sinaga mestinya lebih dari cukup untuk mengirim pesan kepada media-media arus utama di Indonesia bahwa cara penulisan dan pemberitaan kasus kekerasan seksual harus diperbaiki.
Namun, tentu saja, syahwat bisnis lebih menggiurkan bagi banyak media di Indonesia. Sementara dari media-media Inggris, kita membaca dan bisa memahami kasus pemerkosaan dengan memadai, dari media-media—khususnya beberapa media online—di Indonesia, kita akan mendapatkan hal sebaliknya.
Kesempatan bagi media menjadi ruang publik untuk mendiskusikan kasus yang sensitif ini menjadi hilang. Padahal dari sana kita bisa belajar banyak hal: dari membincangkan respons internal media sendiri terkait etika pemberitaan, regulasi yang berpihak kepada korban, narasi yang tidak victim blaming, dan yang lebih penting: memastikan kasus semacam ini tidak terjadi di masa depan. Ringkasnya, kasus ini menyediakan pelbagai pelajaran penting.
Sayangnya skala kasus biadab ini yang semestinya bisa menjadi pelajaran berharga tersebut direduksi jadi gosip murahan.
Kita diajak untuk membaca berita-berita yang tidak kontekstual, juga tidak penting, bahkan menjijikkan. Misalnya, berita tentang gaya selfie pelaku, potret rumah mewah pelaku, juga pernyataan-pernyataan selebritis yang sama sekali tidak relevan.
Tentu saja model-model pemberitaan clickbait akan dengan mudah mendatangkan klik pembaca yang pada tahap selanjutnya dikapitalisasi menjadi profit. Ironis, memang, karena tren ini tidak hanya dilakukan media-media yang selama ini terkenal mempraktikkan jurnalisme kuning, tetapi juga melanda media-media yang punya nama besar dan memegang kepercayaan publik.
Sikap semacam itu menunjukkan beberapa media sebenarnya sedang mendelegitimasi dirinya sendiri. Mereka sedang menabung bom waktu yang suatu saat membuat jurnalisme sebagai profesi bisa kehilangan kepercayaan publik.
Tentu saja, masih ada waktu untuk memperbaikinya, dan ada banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari Inggris. Itu kalau media-media di Indonesia mau belajar.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id