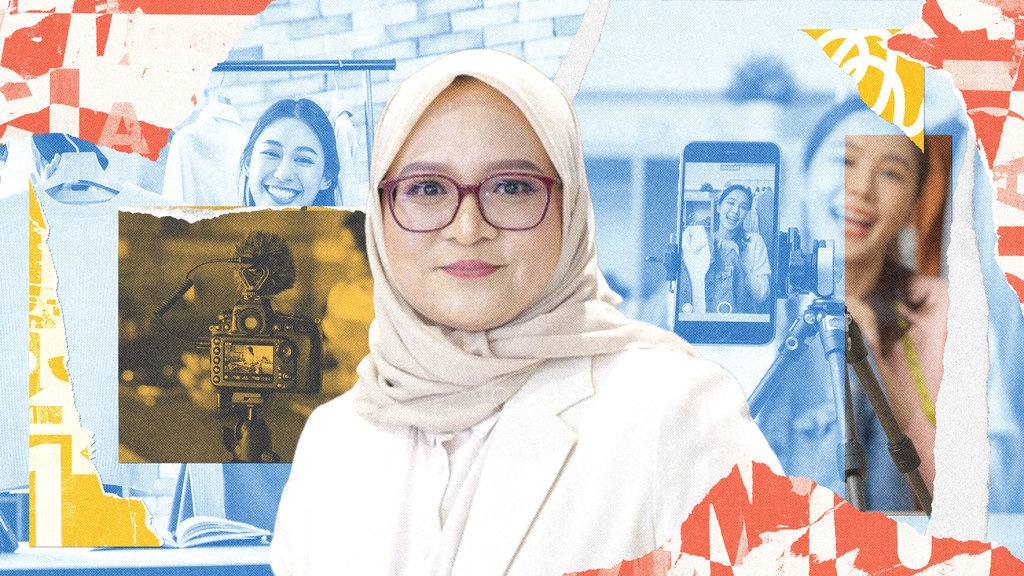tirto.id - Semakin besarnya peran pemengaruh (influencer) di media sosial dalam keseharian, membuat adanya anggapan bahwa pakar kini bisa siapa saja. Bahkan, ada yang mengatakan, bahwa kepakaran telah mati, sehingga siapa saja bisa menjadi pakar.
Seorang pemilik akun TikTok yang kesehariannya adalah petani nilam bisa membahas tentang perang tarif ke puluhan ribu pengikutnya dan mendapatkan ratusan komentar. Padahal, ia tak pernah belajar tentang ilmu perdagangan internasional dan tidak pernah terhubung dengan para pemegang kebijakan yang bolak-balik menegosiasikan tarif dengan pemerintah asing.
Saya ingin berargumen bahwa influencer tumbuh subur, bukan saja karena model bisnis internet dan media sosial yang memungkinkan siapa saja bisa memproduksi informasi dan menyebarkannya. Namun, influencer juga tumbuh subur karena mereka dapat mengisi kekosongan informasi yang tidak diisi oleh pemengaruh konvensional formal yang selama ini kita andalkan–media massa, institusi pendidikan, dan institusi pemerintahan.
Dalam ilmu ekonomi, ada konsep tentang informasi asimetris, yakni sebuah kondisi dimana pihak pembeli dan penjual di pasar tidak memiliki informasi yang sama. Misalnya saja, saat ingin membeli sebuah produk, seorang pembeli belum tentu memahami betul keandalan dan kelemahan fitur-fitur produk tersebut. Di sisi lain, penjual berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, misalnya menjual barang termahal meski kualitasnya tidak prima. Selain mengandalkan informasi resmi, misalnya informasi yang tertera di kemasan atau situs produk, seorang pembeli biasanya mengandalkan informasi berupa testimonial dari pembeli sebelumnya.
Seorang pembeli cenderung akan mengandalkan informasi lebih besar, jika ia tidak memiliki cukup pengetahuan terhadap barang yang akan ia beli. Misalnya, seseorang yang baru pertama kali membeli laptop, akan cenderung membutuhkan banyak informasi ketimbang seseorang yang sudah pernah membeli laptop. Selain itu, seorang pembeli juga akan membutuhkan informasi lebih banyak jika risiko kerugian akibat salah beli lebih besar.
Misalnya saja, seseorang yang akan membeli rumah, cenderung mengumpulkan informasi yang banyak ketimbang seseorang yang akan membeli es kopi. Jika salah beli es kopi (misalnya rasanya tidak enak), risiko kerugian (membuang es kopi dan beli lagi yang baru) lebih bisa ditanggung. Ketimbang misalnya membeli rumah (dengan menguras semua tabungan) dan ternyata rumahnya jelek (banyak bocor, mesti direnovasi ulang, dan sebagainya).
Tanpa informasi yang memadai dan akurat, pengambilan keputusan menjadi tidak rasional dan tidak optimal–inilah mengapa teori informasi asimetris begitu penting dalam ekonomi.
Manipulasi dalam periklanan daring, dengan menggunakan influencer ataupun ulasan palsu, merupakan hasil utama dari asimetri informasi.
Kehadiran internet dan media sosial, yang memungkinkan siapa saja membuat konten, akhirnya dimanfaatkan oleh para penjual untuk memanipulasi informasi. Jika beriklan ataupun berpromosi di media massa mahal dan ada risiko tidak lolos kurasi media, maka media sosial menjadi pilihan yang jauh lebih murah. Hal ini diperparah dengan praktik-praktik endorsement yang tidak mendahulukan etika, misalnya menyampaikan informasi bohong, sesat, ataupun yang sudah dimanipulasi (misalnya diberikan 'likes' dari bots).
Lalu, bagaimana dengan informasi penting terkait dengan kemaslahatan publik? Apa peran influencer di sana?

Pasar informasi
Memahami informasi asimetris berarti memahami peran penting yang dimainkan informasi dalam perekonomian, dalam kehidupan publik, dalam kehidupan institusi, dalam kehidupan personal. Pada kehidupan ekonomi, pasar membutuhkan informasi untuk berfungsi efisien. Kebijakan publik memerlukan informasi yang akurat untuk mengidentifikasi isu, menyusun alternatif kebijakan, dan memutuskan kebijakan. Sementara itu, organisasi, baik swasta ataupun publik, juga membutuhkan informasi untuk beroperasi.
Sayangnya, kondisi sosial-ekonomi-politik di sebuah negara seringkali membatasi institusi formal untuk menyediakan informasi. Pada negara yang institusi medianya dikuasai oligarki, media tidak bebas untuk meliput dan memberitakan peristiwa, isu, dan kebijakan yang dapat mengganggu kepentingan bisnis dan politik oligarki.
Pada negara yang tidak demokratis, institusi pemerintahan tidak sepenuhnya transparan atas informasi berkaitan dengan hukum ataupun kebijakan yang menguntungkan elite politik dan penguasa. Padahal, warga membutuhkan informasi agar berdaya dan mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Terlebih lagi, warga memerlukan informasi berkualitas untuk membantunya menilai kinerja pemerintah.

Pada isu-isu sensitif yang dapat sangat mengganggu kepentingan penguasa, kekosongan informasi (yang luput/tidak diisi oleh institusi media massa) dapat diisi oleh siapa saja, termasuk para influencer media sosial. Seringkali, bahkan, interpretasi media massa ataupun pandangan para expert (ahli) ataupun elite politik terhadap sebuah isu justru tidak mewakili apa yang dirasakan masyarakat. Padahal, naluri dasar manusia akan mencari orang ataupun kelompok yang pandangan atau pengalamannya mirip. Setidaknya, dia akan mencari informasi ataupun pandangan yang masuk akal.
Pada isu tingkat pengangguran dan lapangan kerja di Indonesia, misalnya, informasi-informasi dari pemerintah justru banyak yang kontroversial, bahkan diwarnai dengan pernyataan-pernyataan nirempati saat membalas kritik tentang “kabur aja dulu” dari Indonesia.

Survei Edelman Trust Barometer 2025 di 28 negara menunjukkan bahwa influencer yang dianggap berpengaruh atau memiliki “legitimate influence” justru adalah influencer yang memahami apa yang “dibutuhkan” dan “diinginkan” masyarakat.
Disebutkan pula dalam laporan itu, bahwa "Ketika rasa ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini atau keluhan sangat tinggi, maka gelar atau jabatan formal menjadi kurang berarti." Artinya, di tengah kondisi ekonomi yang stagnan, pejabat sekalipun, jika dia tidak menunjukkan gestur “memahami” kondisi, maka masyarakat pun akan mengabaikan mereka. Tidaklah mengherankan jika lalu hadir influencer-influencer dengan kemampuan analisis terbatas bahkan mungkin “cacat logika” tetap mendapatkan simpati.
Di sisi lain, orang-orang yang rasa ketidakpuasannya terhadap kondisi saat ini tinggi, ternyata cenderung menganggap bahwa media massa lebih tertarik menarik perhatian pembaca dengan berita-berita sensasional daripada berita yang memang dibutuhkan.
Influencer mungkin tidak sepiawai jurnalis dalam mengecek fakta ataupun menginterpretasikan fenomena. Besar kemungkinan juga mereka menyebarkan misinformasi.
Namun, pada isu-isu lokal yang dekat dengan masyarakat, para influencer lebih leluasa memberikan interpretasi. Mereka sebenarnya tidak menggantikan peran expert atau jurnalis, tapi mereka mengisi kekosongan informasi yang tidak terjangkau oleh media ataupun tidak terlihat dari menara gading para expert di universitas.
Bagaimana menyikapi influencer?
Jika pada awalnya influencer lebih dikenal sebagai perpanjangan tangan industri periklanan—dengan fokus utama pada endorsement produk dan jasa—maka fenomena yang berkembang menunjukkan peran yang jauh lebih kompleks. Influencer kini telah bertransformasi menjadi pengisi gap informasi yang menunjukkan bahwa dalam era digital, legitimasi tidak lagi hanya berasal dari kredensial formal, tetapi juga dari kemampuan memahami dan merespons kebutuhan informasi masyarakat.

Meskipun penggunaan influencer membawa risiko penyebaran misinformasi dan interpretasi yang tidak akurat, kehadiran influencer juga mengungkap kegagalan sistemik institusi formal dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukanlah menghilangkan peran influencer, melainkan menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat—di mana institusi formal dapat belajar dari kedekatan influencer dengan masyarakat, sementara influencer dapat meningkatkan literasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Dalam lanskap informasi yang demokratis, kualitas informasi tidak hanya bergantung pada siapa yang menyampaikannya, tetapi juga pada seberapa baik informasi tersebut dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih rasional dan optimal untuk kehidupan mereka.
Maka itu, tugas kita bukan hanya mengkritisi keberadaan mereka, tetapi juga merefleksikan mengapa masyarakat lebih memilih suara-suara dari pinggiran ketimbang suara-suara dari pusat kekuasaan dan keilmuan. Jika informasi yang adil, jujur, dan kontekstual tidak mampu dihadirkan oleh media, pemerintah, dan akademisi—maka ruang itu akan terus diisi oleh mereka yang mampu berbicara, didengar, dan dipercaya.
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id