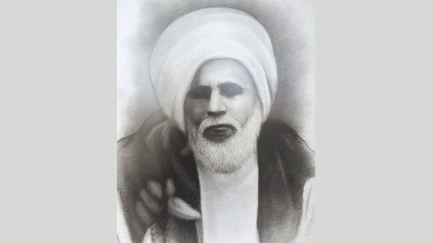tirto.id - Salah satu dari tiga genre paling laris di industri film Indonesia adalah komedi. Dalam daftar 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa, terdapat dua film komedi. Agak Laen (2024) berhasil meraih lebih dari 9 juta penonton, sedangkan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 (2016) meraih lebih dari 6,5 juta penonton.
Kesuksesan Agak Laen tampaknya menginspirasi grup komedian dan pengisi podcast (siniar) GJLS untuk membuat film panjang pertamanya. Meski begitu, mereka sebelumnya telah bereksperimen melalui film pendek yang didistribusikan di YouTube saat pandemi.
Kini, film GJLS: Ibuku Ibu-ibu telah meraih lebih dari 500.000 penonton. Lewat bloopers, komedi absurd, dan humor slapstick, grup komedi ini berhasil mempertahankan signature-nya di bawah arahan sutradara Monty Tiwa. Namun, film ini tidak lepas dari kritik.
Apakah ini merupakan sebuah kemajuan atau kemunduran dalam komedi film Indonesia? Apakah ada batas beban moral yang perlu dipertimbangkan pembuat film saat membuat film komedi?
Alih Wahana Komedi
Mengapa film komedi memiliki begitu banyak penonton di Indonesia? Singkatnya, karena penonton ingin tertawa dan melepaskan penat dari persoalan hidup mereka. Film panjang adalah salah satu medium yang bisa menyalurkan kebutuhan tersebut.
Namun, penting diingat bahwa film bukan satu-satunya medium dalam budaya populer kita. Ada sitcom di TV, sketsa di YouTube atau media sosial, bahkan stand-up comedy. Sudah bukan hal baru bagi para komedian untuk tampil di layar lebar.
Di Indonesia, Warkop DKI adalah contoh grup lawak yang sukses membintangi banyak film. Sebelumnya, mereka dikenal sebagai pengisi program radio Warkop Prambors. Strategi serupa digunakan oleh Agak Laen dan kini oleh GJLS: Ibuku Ibu-ibu, yang sebelumnya dikenal lewat siniar mereka.

Namun, penonton film GJLS dan Agak Laen bukan hanya pendengar podcast mereka. Selain itu, berbeda dengan podcast yang cenderung spontan dan kasual, film membutuhkan persiapan panjang—dari tahap pengembangan hingga penyuntingan.
Itu artinya, yang dialihwahanakan bukan hanya kekayaan intelektualnya, tetapi juga bentuk komedinya. Komedi dalam podcast tidak disajikan dalam bentuk cerita berstruktur seperti dalam film. Candaan tanpa konteks yang cocok di podcast belum tentu efektif atau pantas saat diadaptasi dalam film.
Pertanyaannya sekarang: seperti apa bentuk komedi yang efektif untuk film?
Komedi dan Korban-korbannya
Apa itu komedi, dan apakah komedi memiliki batas? Apakah sesuatu yang lucu bagi mayoritas orang secara otomatis berarti aman?
Dari sekian banyak teori komedi, ada dua yang cukup kontras: relief theory (teori kelegaan) dan superiority theory (teori superioritas).
Secara sederhana, teori kelegaan menjelaskan bahwa humor adalah cara melepaskan emosi atau ketegangan yang terpendam. Filsuf Immanuel Kant percaya bahwa humor membantu meredakan ketegangan, misalnya karena rasa takut, dengan melepaskan respons fisik berupa tawa. Ketegangan yang dibangun dalam set-up akan terasa melegakan saat dilepas melalui punchline.
Sementara itu, teori superioritas yang dikemukakan filsuf Thomas Hobbes menjelaskan bahwa kita tertawa karena merasa lebih unggul dari orang lain. Kita menertawakan kemalangan orang lain karena kita tidak sedang berada dalam posisi mereka.
Dalam penulisan komedi, ada dua elemen penting: set-up dan punchline. Set-up bertugas membangun ekspektasi penonton, sedangkan punchline bertugas mematahkannya. Lalu bagaimana kedua teori itu diterapkan dalam praktik?
Dalam salah satu adegan film GJLS, Rispo tampak sedang berjudi online ketika ayahnya memarahinya. Melihat hal itu, sang Ayah kesal dan melempar ponsel yang digunakan Rispo, lalu berkata, “Berhenti main judol di HP-mu!”
Rispo mengangkat kepala dan berkata, “Tapi itu HP Bapak.” Ayahnya pun langsung lari mengambil ponselnya sendiri yang telah ia buang ke luar. Adegan ini memancing tawa penonton karena Ayah justru melempar ponselnya sendiri.
Menurut teori kelegaan, situasi ini terasa lucu karena ketegangan antara ayah dan anak menjadi mereda. Sedangkan menurut teori superioritas, kita menertawakan Ayah yang menjadi korban akibat kekesalannya sendiri.
Audiens film komedi berbeda dengan audiens podcast atau stand-up comedy. Mereka mencari cerita, sesuatu yang bisa mereka bawa pulang. Meski mereka ingin tertawa, mereka tetap ingin larut dalam cerita yang utuh.
Dalam film, set-up dan punchline disajikan dalam bentuk pengadeganan audio-visual yang memiliki perubahan kondisi. Siapa yang menjadi korban? Di sinilah pembuat film harus berhati-hati. Hanya karena mayoritas penonton tertawa, bukan berarti lelucon itu aman. Maka, bagaimana cara pembuat film dapat lebih bijak dalam memposisikan "korban"?

Beban Moral Industri Film
Film komedi Indonesia telah hadir jauh sebelum era reformasi. Namun, bukan berarti bentuk komedi yang diwariskan selalu relevan atau layak diteruskan. Perempuan yang dijadikan punchline pada era Warkop DKI, misalnya, belum tentu memunculkan efek komedi yang sama hari ini.
Ada banyak pilihan artistik dalam proses produksi film, dari penulisan naskah hingga penyuntingan. Di beberapa produksi, bahkan terdapat profesi khusus “konsultan komedi” yang bertugas meningkatkan efektivitas komedi dalam skenario maupun saat pengambilan gambar. Sutradara film komedi Imajinari seperti Muhadkly Acho juga memulai karier penyutradaraannya dari profesi ini.
Saat saya menonton GJLS: Ibuku Ibu-ibu, saya tidak merasa ada lelucon yang benar-benar ofensif. Bahwa tidak semua lelucon cocok dengan selera saya adalah hal yang wajar—karena komedi bersifat subjektif. Namun, apakah film ini memosisikan perempuan dan aktor disabilitas sebagai korban komedi sehingga justru membawa kita mundur? Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam kurang dari 1500 kata.
Beberapa punchline memang terasa cukup berisiko. Dalam satu adegan, Rispo ditanya nomor ponsel seorang LC di klub. Dengan percaya diri, ia menjawab bahwa ia ingat—namun justru menyebut ukuran bra. Beberapa orang mungkin menganggap lelucon ini misoginis. Namun dari perspektif komedi, saya melihat bahwa korban dari lelucon ini adalah Rispo sendiri, yang terlihat berpikiran kotor.
Konsultan komedi seharusnya tidak hanya memikirkan apakah sesuatu lucu, tapi juga mempertimbangkan apakah lelucon tersebut terlalu melampaui batas. Pada akhirnya, pembuat film memikul beban moral untuk menghasilkan film yang bukan hanya sukses secara komersial, tetapi juga berkontribusi secara budaya dan mencerminkan nilai masyarakat kita.
Penulis: Reza Mardian
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id