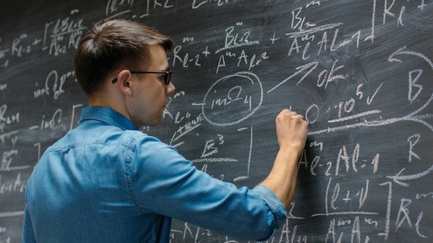tirto.id - Dengan berbagai cara, penguasa kerap kali mencoba menghentikan keberlanjutan aksi massa dengan mengaburkan tuntutan utama demonstrasi, termasuk di antaranya lewat narasi "demonstrasi rusuh" dan "massa rusuh".
Padahal, ada banyak contoh kejadian yang membuktikan adanya provokator di dalam massa demonstran. Lihat salah satu misalnya dalam kasus pembakaran Halte Sarinah di tengah demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada 2020. Alih-alih melakukan penelusuran dan investigasi lebih dalam, instansi pemerintahan kerap kali mengambil jalan pintas: mencari kambing hitam.
Banyak kejadian yang mempertontonkan bahwa provokator sudah membaur dengan massa aksi, tetapi dengan mengusung tujuan berbeda. Keberadaannya sering kali berhasil membajak emosi massa dan membenturkannya dengan aparat, yang kemudian berujung pada perusakan dan pembakaran.
Teranyar, dalam kerusuhan demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada Agustus 2025 lalu, muncul dugaan keterlibatan aparat yang kemudian dipergoki oleh polisi. Namun, kecurigaan yang diperkuat oleh rekaman video itu kemudian dibantah oleh pihak aparat keamanan.
Yang jelas, banyak titik demonstrasi sepanjang linimasa yang disusupi provokator, dengan tujuan utama memecah-belah tujuan awal massa aksi. Lalu, mengapa strategi penguasa dalam mengerahkan provokator di tengah massa aksi kerap kali efektif?
Penguasa Tahu Cara Memainkan Emosi Kolektif
Berada dalam kerumunan demonstrasi dapat melahirkan sensasi yang campur aduk. Marah, geram, dan jengkel, bercampur dengan rasa takut serta khawatir mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kekerasan aparat keamanan, seperti gas air mata, meriam air, pentungan, membuat massa aksi menjadi was-was.
Di sisi lain, berada di tengah massa juga dapat memicu keberanian tersendiri karena terbawa emosi kolektif. Victor Chung dan kolega, dalam artikel jurnal berjudul "Collective emotion: A framework for experimental research" (2023), menyebut bahwa emosi kolektif berkaitan dengan konvergensi dan sinkronisasi respons emosional antar-individu, minimal, melalui pengaruh bersama. Jikapun awalnya muncul rasa takut, perasaan itu akan segera hilang setelah melihat keberanian orang-orang di sekitarnya.
Bahkan, individu juga berisiko kehilangan jati diri sesaat karena telah melebur dengan orang-orang di sekitar. Ia dengan bangga akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok.
Lewat artikel "Self-esteem, ingroup favoritism, and outgroup evaluations: A meta-analysis" (2024), Luis M. Rivera dan kolega menerangkan bahwa rasa bangga itu bisa diidentifikasi melalui teori identitas sosial. Kekhasan positif in-group berfungsi sebagai sumber harga diri, yang pada gilirannya mendorong individu menyukai in-group daripada out-group.
Emosi kolektif juga mempunyai karakteristik unik yang sangat berbeda dari emosi individual. Victor Chung dan kolega menjelaskan tiga karakteristik utama dari emosi kolektif.
Pertama, emotional alignment (keselarasan emosi). Individu dalam suatu kelompok akan saling memengaruhi sehingga dalam suatu titik tertentu mereka mempunyai emosi yang sama.
Kedua, feeling of togetherness (rasa kebersamaan). Pada fase ini individu tidak hanya merasakan kesamaan emosi, tapi juga merasa dibersamai. Mereka merasa gembira dan bangga berada di antara orang-orang yang mempunyai kesamaan dengannya.
Ketiga, mutual awareness (kesadaran bersama). Individu yang terlibat dalam emosi kolektif saling menyadari antara satu dan lainnya. Di sini, muncul sebuah kesadaran bersama sebagai bentuk representasi keadaan mental antar-individu yang saling berinteraksi dalam suatu kelompok.

Dalam konteks demonstrasi, emosi kolektif bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, hal itu membuat demonstrasi menjadi kekuatan besar yang bisa memperlantang suara aspirasi. Mereka tidak mudah ditakut-takuti dalam bentuk apa pun karena telah merasa aman berada dalam kelompok besar. Namun di sisi lain, emosi kolektif bisa menjadi bumerang ketika seseorang di dalam kelompok itu malah terbawa oleh hasutan provokator, yang pada gilirannya memengaruhi massa lainnya.
Ekspresi kemarahan yang dibuat-buat oleh provokator bisa dengan cepat menarik perhatian dan menyulut demonstran lainnya.
Menurut Irina Pitica dan kolega, dalam artikelnya di jurnal Procedia: Social and Behavioral Sciences (2013), kemarahan merupakan sinyal ancaman menonjol yang memunculkan alokasi perhatian istimewa berdasarkan modul ketakutan yang berevolusi.
Dibandingkan dengan ekspresi emosi lainnya, kemarahan lebih menarik perhatian. Oleh sebab itu, ia sangat memengaruhi emosi massa, sesedikit apa pun pemantiknya.
Ekspresi kemarahan dari satu anggota kelompok bisa dianggap sebagai sinyal kemunculan ancaman bagi kelompok demonstran, yang harus segera direspons dengan eskalasi emosi lebih tinggi lagi. Ekspresi dari kemarahan itu bisa hanya berupa ekspresi saja, tapi juga bisa menjadi perilaku ofensif, seperti pelemparan dan pembakaran.

Riset termutakhir menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan kerumunan kerap dipicu oleh pergeseran batas "siapa kami" dan "apa yang wajar dilakukan". Dalam kerangka Elaborated Social Identity Model (ESIM), identitas dan norma kelompok bisa bergeser ketika tindakan aparat keamanan aparat makin represif—dalam kasus terbaru, misalnya, kepolisian melindas Affan Kurniawan dengan mobil rantis hingga tewas, meskipun ia bahkan bukan bagian dari massa aksi.
Hal itulah yang menurut John Drury, dalam artikel "Recent developments in the psychology of crowds and collective behaviour" (2020), membuat massa aksi merasa berhak membalas sehingga menguatkan norma konfrontatif.
Di sinilah provokator memainkan perannya: mengompori dengan cara memancing kontak keras dan menyebarkan framing.
Menurut artikel "Crowd Psychology, Features of Preventing Mass Riots" (2024), provokator memegang peran kunci dalam upaya meniup rumor yang sukar dibantah. Bahkan, mereka kerap kali memberi stimulasi tambahan, entah itu melempar batu, meneriakkan provokasi, ataupun isyarat target perusakan. Tujuannya adalah agar lingkaran emosi dan resonansinya menyebar dengan cepat.
Dalam studi yang terbit di jurnal Psychological Reports (1996), kita dalam merangkum beberapa pancingan kecil yang kerap membuat provokator berhasil.
Pertama, menaikkan tensi dengan cara meneriakkan hasutan, lemparan batu, dan sebagainya, sehingga keputusan massa aksi menjadi impulsif. Kedua, memanfaatkan kontrol internal yang lemah. Ketiga, memantik emotional contagion, yakni kondisi ketika satu aksi ofensif terlihat "aman", orang lain akan dengan cepat menirunya. Keempat, oportunisme, yakni situasi ketika atmosfer kerumunan membuka peluang gratifikasi cepat, misalnya memprovokasi penjarahan dan balas dendam. Kelima, anonimitas dalam kerumunan dianggap menurunkan risiko personal sehingga pelanggaran norma dinormalisasi.
Begitu bentrok lokal terjadi, kericuhan mudah menyebar. Provokator mengeksploitasi momentum itu dengan menggemakan gaung kerusuhan serta "anjuran" balas dendam lewat penjarahan.
Pada gilirannya, ketika para provokator berhasil melancarkan misinya dalam suatu demonstrasi, penguasa dapat menjustifikasi tindakannya: menginstruksikan aparat represif untuk melakukan kekerasan lainnya, penangkapan semena-mena, serta mencapnya sebagai "kegilaan massa". Mirisnya, "bahan bakar" hal itu pada gilirannya disulut pula oleh media massa, termasuk dengan melabeli demonstrasi itu sebagai "aksi anarkis".
Pemerintah, di banyak belahan Bumi, memang lebih suka menganggap kerusuhan sebagai ekses massa aksi. Sebab, penyelidikan mendalam dapat menyebabkan terkuaknya jawaban yang tak diinginkan.
Sebagaimana disebut oleh Dan Hancox dalam sebuah artikel populer yang terbit di The Guardian:
"Ketika mereka yang berkuasa berbicara tentang kerumunan, selalu ada upaya terencana untuk mengurangi beragamnya niat, perilaku, dan kepribadian para anggota demonstran."
Penulis: Kukuh Basuki Rahmat
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id