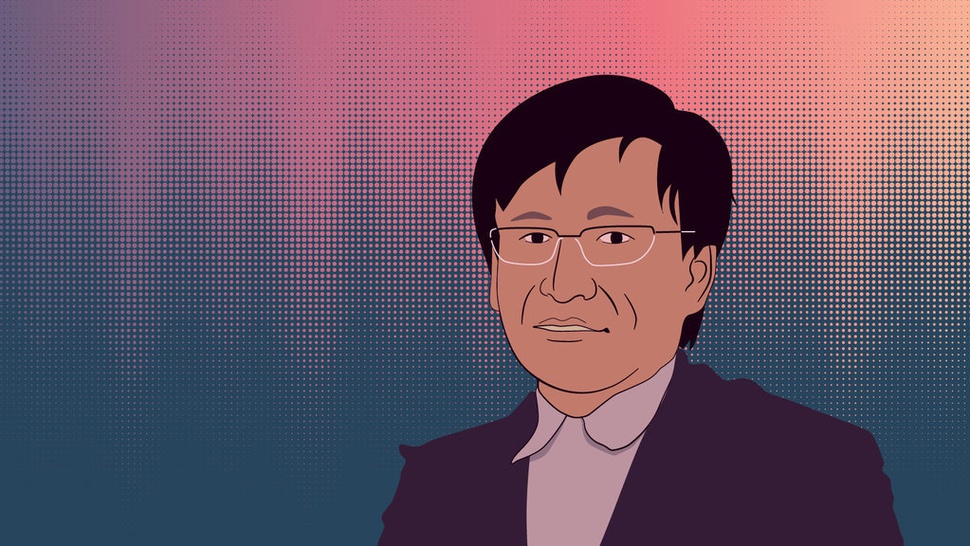tirto.id - Hoaks sudah menjadi langganan menjelang tahun politik. Sejak Pemilu 2014, banyak hoaks yang disebar lewat pelbagai platform media, yang paling banter adalah media sosial. Hokky Situngkir, peneliti media sosial dari Bandung Fe Institute, mewaspadai gejolak hoaks tahun politik kali ini akan lebih dahsyat.
Penyebabnya perang yang dulu dilakukan lewat akun bot atau robot kini sudah beralih dengan pasukan siber masing-masing pasangan capres-cawapres. Perubahan ini dipantik pula oleh perubahan sistem keamanan dan kebijakan media sosial.
“Mereka sudah mengembangkan dan memperbaiki sistem algoritma. Misalnya, Facebook secara rutin melakukan perubahan security, pembobolan akun sangat susah, pembuatan akun pun susah,” kata Situngkir kepada Tirto pada 3 Oktober 2018.
Perubahan ini mengubah juga pola bisnis. Bila dulu bisnisnya adalah pembuatan akun bot, kini jual beli akun yang bisa digunakan untuk menyebar hoaks. Harga per akun dari Rp2.000 hingga Rp25 ribu. Selain itu, persebaran hoaks lewat pasukan siber berpotensi membuat konflik di dunia nyata.
“Ada persuasi yang bisa dilakukan. Bahkan mereka bisa bertemu secara offline untuk merencanakan sesuatu bersama,” ujarnya.
Bagaimana perubahan strategi dan potensi konflik pada Pemilu dan Pilpres 2019? Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana perbandingan persebaran hoaks pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019?
Sebenarnya yang paling anti dengan hoaks itu bukan hanya pelaku politik, bukan politikus di tahun politik, tetapi media sosial juga dirugikan. Jadi dalam setahun, platform media sosial sudah sangat keras memerangi hoaks. Mereka sudah mengembangkan sistem mereka, algoritma yang mereka gunakan.
Kebijakan ini mengubah pola pelaku hoaks dalam menyebarkan konten. Mereka sekarang mengubah strategi.
Perubahan strategi seperti apa?
Dulu mereka pakai bot, pakai AI (kecerdasan buatan) biasa, sekarang sudah tidak lagi. Sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Cara yang mungkin dan sudah dilakukan, cara yang paling gampang, adalah membuat komunitas siber. Jadi komunitas online ini yang dipakai untuk menyebarkan hoaks.
Ini sudah mulai sejak tiga atau empat bulan lalu. Kami mendeteksi banyak akun palsu. Sebenarnya, enggak palsu juga karena ada registrasi nomor telepon, alamat email. Untuk membuat akun medsos sudah tidak semudah dulu. Butuh email. Email sekarang butuh nomor handphone.
Jadi sejak beberapa bulan lalu, sudah banyak akun-akun yang dibuat dengan nomor handphone yang tidak jelas siapa pemiliknya. Nomor kartu keluarganya juga tidak tahu dapat dari mana. Mereka bisa mengakali karena ketidakberesan administrasi di Indonesia. Itu mereka membuat akun dan kemudian diperjualbelikan.
Jadi akun itu dijual dari Rp2.000 sampai Rp25 ribu. Akun sudah diperjualbelikan dengan nomor telepon dan email kloningan itu. Sudah marak sekali jual beli akun yang kami temukan.
Dan supaya Facebook, Twitter, dan Instagram tidak memblokir akun itu, mereka sudah berinvestasi dulu. "Investasi" dalam tanda kutip. Jadi, mereka memposting hal yang biasa, postingan normal, kemudian dijual. Itu sebabnya, kalau cek, akun-akun itupunya timeline beda sekali. Waktu awal dibuat isinya apa, begitu dijual, isinya jauh sekali berbeda.
Yang saya temukan ini sudah berafiliasi dengan salah satu kandidat.
Sudah sampai itu?
Penjualan akun-akun ini terkait dengan urgensi mengapa pemerintah membuat kebijakan harus mendaftarkan nomor telepon. Jadi pemerintah butuh semua terdaftar, mengantisipasi penipuan dan lainnya. Tapi, di sisi lain, provider butuh untuk menjual nomor SIM baru. Nah, para pelaku ini berada di antara keduanya. Mereka memanfaatkan registrasi kartu yang belum rapi dan kebutuhan provider untuk menjual kartu.
Apa untungnya kalau dijual cuma Rp2.000?
Kalau dihitung masih sangat menguntungkan. Borongan. Registrasi menggunakan ketidakberesan administrasi. Bikin nomor KTP dan Kartu Keluarga palsu, setelah itu bisa punya akun email. Dari satu akun email, sudah bisa bikin Twitter, Instagram, Facebook. Ini dijualbelikan. Ini modus baru. Pada 2014, hal ini belum ada.
Perubahan pola persebaran hoaks bagaimana?
Persebarannya sama. Justru perubahan dari bot ke cyber army yang berbahaya. Ada kok kedua belah pihak, dari capres satu dan lainnya ada. Entah itu dari relawan, yang saling berebut panggung di media sosial. Soal topik atau isu bisa jadi sangat berbeda, tapi yang mereka usung sama.
Sekarang juga sudah ada platform. Aplikasi yang memungkinkan orang mengontrol beberapa akun sekaligus.
Itu dijual?
Enggak dijual bebas. Ini dibuat oleh programer-programer. Sudah ada alatnya. Sudah ada mesinnya.
Apa yang paling membedakan gerakan bot dan pasukan siber?
Kalau dampak sama saja. Cuma yang lebih berbahaya pasukan siber dari bot. Kalau bot, hanya digerakkan 1 atau 2 orang. Tapi, kalau pasukan siber ada orangnya asli. Secara biaya juga pasti lebih besar. Tapi yang paling ngeri adalah upaya mereka untuk menggerakkan orang di dunia nyata jadi semakin besar.
Mereka bisa menanamkan pengaruh besar. Ada persuasi yang bisa dilakukan. Bahkan mereka bisa bertemu secara offline untuk merencanakan sesuatu bersama. Ini ada proyek penggalangan offline yang mendukung agitasi online. Ketegangan ini bukan cuma online tapi juga offline karena sentimennya sudah masuk ke orang-orang.
Sekarang terlalu dini untuk mengatakan bahaya. Tapi potensi itu ada.
Apakah pola ini hanya ada di media sosial atau sudah ke platform seperti WhatsApp?
Konten itu sekarang dua arah. Dari media sosial ke WhatsApp, sebaliknya juga. Persebaran semakin masif.
Soal kontrol pemerintah, apa yang mungkin bisa dilakukan?
Satu hal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengedukasi pengguna media sosial. Karena kalau soal program, soal security, itu pasti nanti ada celahnya. Tapi pencegahan itu harus lakukan karena kalau terlalu banyak hoaks, nanti akan muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Ini sangat mungkin menimbulkan chaos. Katakanlah nanti Pilpres siapa pun yang menang, nanti akan muncul ketidakpercayaan kepada pemenang. Kepercayaan orang menjadi sangat rendah. Ini tidak baik.
Dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet, misalnya, justru yang terpapar hoaks adalah politikus, dan orang-orang berpendidikan—katakanlah begitu. Kalau yang pintar saja begini, bagaimana cara mengedukasinya?
Justru pemimpinan adalah cerminan masyarakatnya. Kalau ada banyak pemimpin yang begitu, lantas bagaimana dengan rakyatnya? Artinya ada banyak juga masyarakat yang tidak punya filter terhadap hoaks. Nah, generasi tua ini lebih mudah terpapar hoaks ketimbang generasi Milenial.
Bagaimana kecenderungan glorifikasi yang dibuat oleh para pendukung Jokowi? Ini berbeda dari hoaks.
Punya tipe masing-masing. Kalau cyber army sudah ada pembagian tugasnya. Siapa yang memuji. Siapa yang menjelekkan kubu sebelah.
Lama-lama pola ini menjadi organik dari para influencer. Kalau diperhatikan, penggunaan tagar itu juga berbeda-beda. Artinya sudah sangat cair dan organik.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam