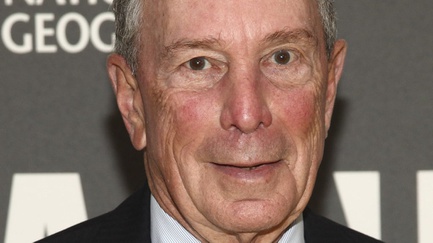tirto.id - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menutup konferensi pers di Istana Negara, Minggu malam, 31 Agustus 2025, dengan dua kata yang pernah jadi mantra pembangunan Orde Baru: stabilitas dan ekonomi. "Kebangkitan ekonomi kita," ujarnya, perlu terus diperjuangkan "dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama."
Usai berucap, bekas Pangdam Jaya yang pernah diperiksa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan 1998 itu bergegas meninggalkan lokasi tanpa mau melayani pertanyaan wartawan.
Pernyataan Sjafrie menjadi perhatian karena datang di tengah usaha pemerintah meredam demonstrasi massal yang meledak di berbagai daerah. Aksi yang berujung kerusuhan, perusakan, dan penjarahan itu memaksa Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elite partai dan pimpinan ormas keagamaan setelah eskalasi mencapai puncaknya pada 29-30 Agustus 2025.
Persoalannya, gelombang kemarahan publik itu dinilai bukan reaksi spontan atas isu politik semata, melainkan akumulasi kekecewaan panjang terhadap kondisi ekonomi yang kian menghimpit. Dus, pernyataan Sjafrie terdengar seperti silogisme terbalik: seolah stabilitas melahirkan ekonomi, padahal justru keresahan ekonomi kini yang menggerus stabilitas.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut keresahan ini berakar pada keadilan ekonomi yang tak kunjung terwujud. "Ini menjadi api dalam sekam yang mudah menyulut emosi masyarakat jika ditunggangi tindakan provokatif," kata Faisal dalam diskusi daring bertajuk Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi, Senin (1/9/2025).
Tentu, faktor politik dalam mobilisasi massa tak bisa dinihilkan. Namun, akar permasalahan sesungguhnya jelas urusan penghidupan dan kesejahteraan. Ia mendedahkan data jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang—kendati turun menjadi 24 juta per Maret 2025—sangat menghawatirkan.
Hingga kini, jelas Faisal, lebih dari sepertiga atau sekitar 100 juta orang Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah Rp1 juta per kapita per bulan. "Ini belum termasuk kelas menengah yang daya belinya pun saat terus mengalami," ucapnya.
Belum lagi soal kerentanan masyarakat di pasar kerja, di mana hampir 60 persen buruh Indonesia masih bergelut di sektor informal. Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur pun melonjak seiring dengan peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada periode Januari hingga Juli 2025, misalnya, lebih dari 43.500 orang terkena PHK—naik 150 persen dibanding periode sama tahun lalu.
"Ini baru kementerian tenaga kerja. Belum kita melihat lagi catatan PHK yang di-record oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) untuk periode yang lebih pendek. Januari-April saja, tahun ini, sudah 52.850. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) lebih tinggi lagi. Dia mencatatkan 73.992 orang untuk Januari-April," jelasnya.
Upah riil buruh pun tak bergerak: pada Februari 2025, pertumbuhannya hanya 1,9 persen secara tahunan, bahkan anjlok 4,8 persen dibanding Agustus 2024. Sementara di rumah tangga, tekanan ekonomi terlihat dari data perbankan yang mencatat saldo di bawah Rp100 juta hanya menyimpan rata-rata Rp1,1 juta. Padahal, proporsi tabung dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 99 persen dari total tabungan.
Sebaliknya, rekening di atas Rp2 miliar yang proporsinya di bawah 1 persen dari total pemilik tabungan justru makin tambun. "Jadi ada pelebaran ketimpangan di sini," ungkapnya. "Pada saat yang sama, pinjaman konsumtif lewat peer-to-peer lending kian marak," ujar Faisal.
Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan nasional yang tergambar dalam rasio gini memang mengalami penurunan dari 0,381 pada September 2024 menjadi 0,375 pada Maret 2025. Tapi jika diurai, gap antara si kaya dan si miskin justru menganga di perkotaan. Rasio gini di kota mencapai 0,395, jauh di atas pedesaan yang 0,299. Tak hanya itu, indeks kedalaman kemiskinan kota bahkan naik menjadi 1,061, sedangkan di desa menurun ke 1,811.
Karena itu lah, Faisal mendesak pemerintah agar mengoreksi arah kebijakan ekonominya ke depan. Misalnya, dengan meninjau ulang pajak yang membebani kelas menengah bawah, menghentikan belanja negara tak produktif, dan mengarahkan fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Terlebih, dalam beberapa waktu mendatang, tantangan kian tak mudah di mana tarif resiprokal dengan Amerika Serikat berisiko membanjiri pasar domestik dengan impor dan memperparah tekanan kepada sektor produksi dalam negeri. "Sehingga sangat mungkin ini akan memperparah tekanan ekonomi," jelasnya.
Pandangan senada datang dari Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie. Ia menilai lonjakan pemutusan hubungan kerja dalam tiga tahun terakhir telah memperparah kerentanan pekerja. Walaupun pemerintah kerap mengklaim tingkat pengangguran turun, kualitas pekerjaan yang tersedia justru stagnan, bahkan didominasi sektor informal.
"Kalau dilihat dari data Januari 2025, jumlah angkatan kerja di sektor informal meningkat dibanding 2024, mencapai sekitar 60 juta orang. Sementara pertumbuhan pekerja formal bisa dibilang mandek dalam empat sampai lima tahun terakhir," ujarnya, sembari menekankan bahwa klaim penurunan pengangguran kehilangan makna karena lapangan kerja yang tersedia cenderung rapuh dan minim perlindungan.
Roby mengaitkan situasi ini dengan tragedi yang menimpa Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas saat demonstrasi berujung ricuh akhir Agustus. Menurut riset The Prakarsa, 60 persen dari 213 responden yang disurvei menganggap profesi ojek daring sebagai pekerjaan utama. Namun, 26 persen di antaranya bekerja lebih dari 48 jam per minggu—kategori kerja eksesif menurut standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Ironisnya, pendapatan pekerja platform justru menurun. Jika sebelum pandemi, periode 2018–2019, rata rata penghasilan harian pengemudi ojol mencapai Rp309 ribu, kini pascapandemi turun menjadi Rp175 ribu. Perlindungan sosial pun amat minim. Dari sekitar 4,6 juta pekerja platform, hanya 12 persen yang terdaftar di BPJS Kesehatan. "Padahal, definisi kerja layak menurut ILO mencakup bukan hanya upah adil, tapi juga keselamatan kerja, jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta kebebasan berserikat," ujar Roby.
Tragedi Affan, lanjutnya, memperlihatkan betapa sektor informal telah lama menjadi penyangga ekonomi perkotaan tanpa disertai jaring pengaman sosial yang memadai. Pertanyaan besarnya: mengapa pekerja informal terus meningkat? Roby menyebut proses deindustrialisasi sebagai pemicu utama.
"Dalam sepuluh tahun terakhir, tren industri pengolahan terus menurun. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja di manufaktur juga melemah," katanya. Perlambatan itu merembet ke hampir semua sektor, menekan penciptaan lapangan kerja formal dan mendorong masyarakat bertahan di sektor informal.
Roby menegaskan, masalahnya bukan sekadar absennya lapangan kerja berkualitas, melainkan juga lemahnya kebijakan perlindungan sosial yang berkeadilan. Pemerintah, menurutnya, lebih sibuk menyalurkan bantuan sosial ketimbang memastikan jaminan sosial yang menyeluruh. "Active labor market policies di Indonesia masih punya gap besar. Akses ke pekerjaan yang layak sangat terbatas," tuturnya.Karena itu, ia mendesak pemerintah mengembangkan kerangka kerja layak—yang mencakup upah dan jam kerja wajar, keselamatan kerja, hingga jaminan sosial bagi pekerja informal. Tanpa perbaikan fundamental itu, krisis pekerjaan layak akan terus menjadi bara dalam sekam, siap menyulut keresahan sosial kapan saja.
Esther Sri Astuti dari INDEF menambahkan bahwa persoalan ketimpangan juga berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan standar kesejahteraan pejabat negara. Ia menyinggung pajak bumi bangunan yang naik drastis dan besarnya tunjangan anggota DPR, kontras dengan kondisi buruh yang tidak mendapat perlindungan layak.
"Ini masalah perut. Pajak bumi bangunan naik drastis, sementara di sisi lain tunjangan anggota DPR luar biasa. Upah minimum tenaga kerja rata-rata Rp5 juta, tapi gaji anggota DPR bisa 25 kali lipatnya," ujarnya.
Menurut Esther, disparitas itu menimbulkan dampak luas, termasuk pada stabilitas moneter dan pasar modal. Rupiah terhadap dolar AS melemah, sementara indeks harga saham gabungan (IHSG) juga mengalami penurunan. "Riset menunjukkan kondisi politik ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar dan IHSG. Seperti ketika ada aksi terorisme yang berdampak pada saham dan nilai tukar," jelasnya.
Ia mencontohkan krisis 1998 ketika rupiah terdepresiasi tajam saat Soeharto lengser, hingga masa transisi SBY ke Jokowi yang membuat kurs melemah ke kisaran Rp12 ribu. IHSG pun mencerminkan reaksi pasar serupa, termasuk ketika ada kebijakan luar negeri yang memicu ketidakpastian.
"Ketika launching Danantara pada 24 Maret, IHSG turun. Kemudian pengumuman tarif Trump pada 11 April menyebabkan IHSG juga bereaksi karena ada kekhawatiran perang dagang," kata Esther.
Bagi Esther, akumulasi tekanan dari kebijakan fiskal yang tidak berpihak, lemahnya perlindungan ketenagakerjaan, dan ketidakpastian politik bisa memperburuk kondisi ekonomi. Karena itu lah, ia meminta pemerintah untuk fokus memangkas gap ketimpangan melalui berbagai instrumen kebijakan. Misalnya, melalui moratorium berbagai bentuk penambahan beban pajak serta penerapan pajak kekayaan.
Pajak kekayaan sendiri menjadi salah satu alternatif sumber penerimaan negara yang dinilai cukup efektif. Center of Economic and Law Studies (Celios), misalnya, pernah mengusulkan pemberlakuan pajak ini terhadap 50 orang terkaya di Indonesia. Dengan asumsi kekayaan terendah di kelompok ini sebesar Rp15 triliun dan rata-rata mencapai Rp159 triliun, tarif pajak kekayaan 2 persen saja bisa menghasilkan Rp81,35 triliun per tahun.
Perlu dipahami, pajak kekayaan (wealth tax) adalah pajak progresif atas total kekayaan bersih individu, mencakup aset tanah, properti, saham, kendaraan, karya seni, dan simpanan rekening. Konsep ini dimaksudkan sebagai kontribusi dari mereka yang paling diuntungkan oleh sistem ekonomi kepada masyarakat luas, sekaligus untuk meredam ketimpangan ekstrem.
Meski demikian, instrumen pajak ini belum hadir dalam bentuk yang komprehensif di Indonesia, melainkan hanya berupa pungutan parsial seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak barang mewah (PPnBM), dan PPh final atas dividen—semuanya belum menyasar keseluruhan aset bersih individu.
"Untuk kelompok yang superkaya. Jadi subsidi silang. Yang kaya bayar pajak lebih mahal, untuk memperbanyak fasilitas publik untuk yang tidak mampu," tutur Esther.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id